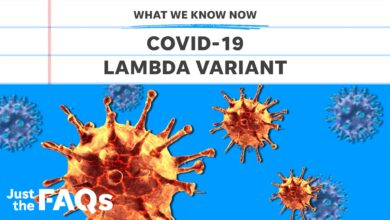Bukan Hannibal Sang Penakluk Roma, Tapi Corona*

Di Italia, sepak bola jauh lebih dari agama. Sepak bola itu suci; menolak akses penggemar ke pertandingan itu adalah sinyal yang lebih drastis daripada menutup sementara Katedral Milan untuk wisatawan dan umat
Dua pekan lalu saya mengirim e-mail dari Roma, tempat saya menikmati satu semester penelitian dan penulisan, kepada seorang teman Cina yang tinggal di salah satu kota kecil berpenduduk lima atau enam juta penduduk. Letaknya sangat jauh dari Wuhan, pusat epidemi virus corona.
Saya mengatakan, saya yakin dia aman, jauh dari krisis saat ini. Dia menjawab dengan sopan dan mengatakan senang bahwa saya mengalami cuti panjang yang begitu indah. Akan tetapi, meskipun kesehatannya baik, hidup dan kehidupan semua orang di sekitar dirinya kini kacau balau. Jalanan di kotanya kosong; semua tempat kerja ditutup; dia dan keluarganya dikurung di rumah. Salah satu dari mereka mungkin menerima izin untuk pergi keluar, bertopeng untuk berbelanja makanan dan persediaan. Semua orang hidup dalam ketakutan. Saya merasa malu dengan e-mail saya yang konyol, tetapi pada saat itu saya tidak sepenuhnya memahami tingkat kebodohan saya.

Saya mengerti sekarang, berkat apa yang tengah berlangsung di Italia. Laporan awal wabah, di beberapa kota di utara negara itu, telah cukup mengkhawatirkan. Tetapi tetap saja berita datang dari jauh. Dengan kecepatan yang mencengangkan, situasinya memburuk: dengan suksesi yang kecepatannya tak terbayangkan, seluruh komunitas dikarantina; sekolah dan gereja menutup pintu mereka; museum, galeri, dan istana ditutup; konser dibatalkan.
Jika ada orang yang tidak memahami situasi ini, dua kejadian lebih lanjut membuatnya sangat jelas: bagian dari Milan Fashion Week, mahkota dari salah satu keberhasilan ekonomi terbesar Italia, ditutup untuk umum. Yang lebih mengerikan lagi, pertandingan sepak bola antara Inter Milan dan saingannya dimainkan di stadion yang sangat kosong. Seperti diketahui semua orang, di Italia sepak bola jauh lebih dari sekadar agama. Sepak bola itu suci; menolak akses penggemar ke pertandingan itu adalah sinyal yang bahkan lebih drastis daripada menutup sementara Katedral Milan untuk wisatawan dan umat beriman.
Di Roma, virus belum muncul. Ada sangat sedikit alarm, selain pembersih tangan. Tetapi, ketika laporan konstan di surat kabar dan di televisi menumpuk, suasana hati berubah. Berita dari utara, kami mulai berkata satu sama lain, menyerupai bunyi tembakan artileri yang meledak dalam pertempuran di suatu tempat di seberang gunung, tidak terlihat tetapi tidak lagi jauh sehingga terdengar kuat. Kemudian musuh terus bergerak melintasi Lombardy dan Veneto, ke Tuscany dan Umbria. Di mana para pembela kami? Jika kita melanjutkan metafora militer, kami harus mengakui bahwa Venesia sangat terancam, kemudian Bergamo, lalu Florence. Roma akan segera jatuh.
Tetapi, ketika percakapan kami tentang virus terus berlanjut — dan semakin tidak mungkin untuk membicarakan hal lain — citra pasukan yang mendekat memberi jalan kepada upaya lain untuk memahami apa yang sedang terjadi. Tentu saja, bahkan di media massa, tidak ada akhir dari artikel epidemiologis. Seringkali artikel yang cukup serius dan terperinci yang ditulis para ahli bersama dengan daftar saran yang sudah mulai membosankan: cuci tangan, jangan menyentuh wajah Anda, bersihkan semua permukaan, terus cuci tangan, menjauh dari orang-orang yang batuk, hindari keramaian, cobalah untuk menjaga jarak setidaknya satu meter dari orang lain. Tetapi, betapapun informatif semua ini — dan kami menghabiskannya dalam beberapa hari saja — dalam situasi stres, seperti biasa, literatur yang menawarkan cara paling ampuh untuk memahami apa yang sedang terjadi atau mungkin akan terjadi. Lulus, bukan dalam arti biologis yang tepat tetapi dalam narasi yang berlangsung.

Jadi percakapan kami beralih ke “Blindness“-nya Saramago, “The Plague” karya Camus, “A Journal of the Plague”-nya Daniel Defoe, karya Manzoni,”The Betrothed”, dan, di atas semua itu — penggambaran fiksi terhebat ini — bab pembuka dari Boccaccio, “Decameron”.
Masalahnya adalah, secemerlang apa pun catatan-catatan ini, mereka menggambarkan budaya dalam cengkeraman penyakit epidemi runtuh ke dalam kekacauan, kekerasan, dan pecahnya ikatan sosial. Tapi ini sama sekali bukan apa yang kita baca di koran atau alami sendiri.
Di Cina, jika akunnya akurat, ada yang sebaliknya: intensifikasi tatanan sosial yang luar biasa, yang terdapat dalam perangkat lunak yang digunakan pemerintah melacak kesehatan dan pergerakan banyak warga negara. Di Italia, tidak ada intensifikasi yang sebanding— terlepas dari teknologinya, kendali semacam itu sangat asing bagi karakter nasional. Tetapi sebaliknya kehadiran yang ditandai dari kehangatan dan kebaikan yang membuat kehidupan sehari-hari di sini begitu menyenangkan, meskipun disfungsi politik terjadi di negara itu. Seolah-olah orang secara naluriah merasakan, bahkan ketika tingkat kecemasan mereka meningkat dan ekonomi mereka tenggelam, versi tatanan sosial mereka bersandar pada humor yang baik, kesabaran, penemuan, dan fleksibilitas.
Ibu dan anak lelaki yang mengelola kios buah dan sayur di pasar, si jenius lokal yang membuat rasa gelato yang sangat tidak masuk akal, pegawai di gym terdekat yang entah bagaimana mengingat (atau pura-pura mengingat) bahwa saya memiliki keanggotaan sementara empat tahun lalu dan melepaskan biaya inisiasi — semuanya, di bawah tekanan krisis, entah bagaimana mencoba memberikan hal-hal manis dari dalam jiwa mereka.
Ini adalah narasi yang berbeda — dan model sastra yang berbeda — yang membantu menjelaskan mengapa saya menulis paragraf-paragraf ini bukan di Roma tetapi di pesawat saat kembali ke Amerika Serikat. Tinggal di puncak bukit yang tinggi, di lingkungan yang tidak sering dikunjungi oleh wisatawan, pada awalnya saya tidak melihat sesuatu yang aneh, tetapi kemudian saya berjalan melewati tempat bersejarah itu.
Dan itu mengejutkan saya: dalam beberapa minggu terakhir, ketika virus menyebar, kota dikosongkan. Kerumunan yang berbaris untuk memasuki Colosseum atau mengunjungi Forum telah menipis; massa yang melempar koin di Trevi Fountain atau memanjat Tangga Spanyol semuanya telah lenyap; restoran dan bar yang biasanya dipenuhi pengunjung hampir kosong. Sudah menjadi kebiasaan, tentu saja, untuk meratapi fenomena pariwisata massal di Italia; bahkan para turis sendiri menggerutu dan bermimpi (seperti halnya saya) tentang betapa menyenangkannya mengunjungi Kapel Sistine dengan kemegahannya itu.
Tetapi efek aktual dari pengosongan, setidaknya untuk alasan saat ini, jelas menakutkan. Tiga malam yang lalu, pergi ke rumah seorang teman untuk makan malam pukul 8 malam, kami berjalan melalui Piazza Navona, alun-alun terindah di dunia, dan kami benar-benar merasa sendirian.
Model sastra di sini bukanlah “Decameron”, dengan para portir yang membawa papan bertumpuk tinggi dengan mayat dan orang-orang yang selamat terbelah antara mengurung diri mereka di rumah-rumah tertutup atau memanjakan diri dalam kerusuhan berlebihan. Alih-alih, itu adalah “Death in Venice” karya Thomas Mann, dengan pahlawan yang terkutuk, jatuh cinta akan bocah cantik, gagal menyadari bahwa semua tamu lain di hotel telah melarikan diri dari wabah kolera.
Tentu saja, penduduk setempat yang menjalankan hotel tidak lari; itu adalah kota mereka, dan mereka tidak punya pilihan selain tinggal. Tapi Aschenbach yang malang—tokoh dalam “Death in Venice”—redaksi Jernih, bisa pulang. Mungkin wabah akan mengikutinya ke sana, tetapi setidaknya dia akan mengubah dunianya sendiri, seperti yang akan saya lakukan ketika pesawat saya mendarat.
[Stephen Greenblatt/The New Yorker, judul diubah redaksi Jernih]
**Stephen Greenblatt, profesor kemanusiaan pada John Cogan University at Harvard.