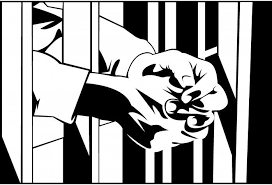Membangkitkan Kembali Kharisma Pesantren

Tapi sejak masa pemilihan umum tahun 1971, ajengan dan pesantren mulai dihadapkan kepada tuntutan-tuntutan informal. Yaitu tuntutan politik bagi kepentingan rezim yang sedang berkuasa, serta “penyetaraan” dengan pendidikan umum
Oleh : Usep Romli HM*
Agama Islam yang sudah tersebar di Nusantara, sejak awal abad 13. Diajarkan di masjid-masjid atau di rumah-rumah kediaman para tokoh ulama yang tersebar di mana-mana, sejak di kota-kota, hingga ke pelosok-pelosok desa.
Namun sejak kedatangan kaum kolonialis-imperialis, terutama Belanda abad 16, sistem pengajaran dan penyebaran agama Islam mengalami perubahan. Para tokoh ulama yang menolak kehadiran kaum penjajah, banyak yang menyingkir ke tempat-tempat terpencil. Mendirikan lembaga pendidikan formal yang dinamakan pesantren. Yaitu tempat menampung para santri dalam mempelajari ilmu-ilmu keislaman.
Sebagai lembaga pendidikan dan lembaga panutan umat, pesantren sangat fokus terhadap penjagaan kelestarian ajaran Islam. Sekaligus menyebarkannya kepada umat. Pesantren berperan sebagai pengibar panji-panji “Izzul Islam wal Muslimin (ketinggian Islam dan umat Islam), sekaligus menunjukkan “Al Islamu ya’lu wa la yu’la alaihi”, Islam itu unggul dan tak terungguli oleh yang lain-lain. Melalui pendidikan, menghasilkan sumber daya yang memiliki keteguhan akidah tauhid, kekhusyuan beribadah, kemulian ahlak, dan banyak melakukan amal saleh.
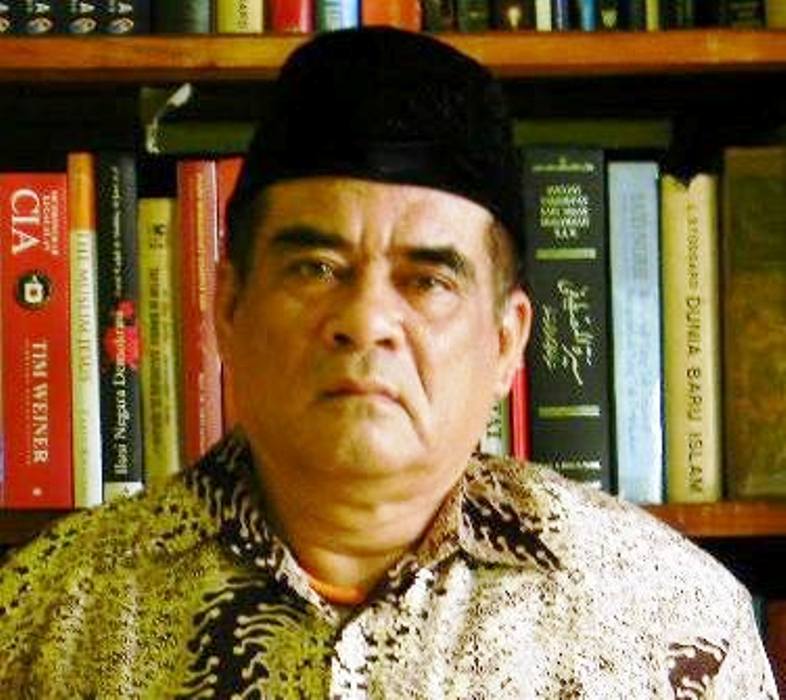
Ajengan atau Kiyai, sebagai sesepuh sekaligus pengelola pesantren, memegang kokoh prinsip dasar kepesantrenan, berupa idealisme yang sarat dengan aspek-aspek rohaniah. Hampir semua ajengan generasi awal pesantrren, menjalankan peran dan fungsi pesantren dengan prinsip “tafwidh”. Penyerahan diri kepada Allah SWT, dan menerima segala kehendak serta izinNya. Para Ajengan tidak pernah bersikap “tadbir”, merancang atau menetapkan segala sesuatu hanya sesuai dengan kehendak (ambisi) diri sendiri secara pasti, sehingga mengabaikan “tafwidh”.
Termasuk dalam urusan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sebagai ahli ibadah, yang sudah dilatihkan (riyadhoh) sejak belasan tahun menjadi santri, para ajengan rata-rata sudah “tajrid”. Menurut Syekh Athaillah asy-Syakandari, penulis kitab tasawuf “Al Hikam” (abad 12), “tajrid” adalah mencapai tingkat hidup dan kehidupan yang mantap dan mapan, baik secara jasmaniah maupun rohaniah. Segala kebutuhan (jasmaniah) dalam batas-batas wajar, sudah terpenuhi. Sehingga tidak ada lagi hal-hal elementer yang mendesak dirinya dengan kesibukan-kesibukan lain, selain beribadah kepada Allah SWT melalui ritual (salat, wirid, doa) dan sosial (mengajarkan ilmu, membantu orang lain sekemampuannya).
Dalam urusan rejeki, memegang teguh pendapat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang menyatakan “ar rizqu rizqani, rizqun yatlubuka, wa rizqun tatlubuha”. Rizki ada dua macam : yang mencarimu, dan yang harus engkau cari. Para ajengan yang sudah berada dalam posisi “tajrid” adalah sosok yang didatangi rizqi tanpa harus mencarinya bersusah payah.
Berkat figur para ajengan yang sudah mampu membersihkan hati dari segala yang rendah dan hina (at takhalli minar raza-il), menghiasi hati dengan segala yang utama dan terpuji (at takhalli bil fadha-il), serta memurnikan hati dari apa saja, selain Allah (at tabarri amma siwalahi), kharisma pesantren menjulang di tengah kehidupan masyarakat. Menjadi tujuan para pencari ilmu. Menjadi tempat “curhat” orang-orang yang membutuhkan jalan ke luar dari berbagai permasalahan.
Termasuk pesantren yang kemudian mendapat keperayaan khalayak dalam mengatasi penyakit ketergantungan obat-obat terlarang, sakit jiwa akut, atau sekedar stres dan drepresi ringan. Semua itu bertolak dari keikhlasan para ajengan dalam menjalankan mu’amalah (peran sosial) pesantren. Menjalankan pola perjuangan dakwah Kangjeng Nabi Muhammad Saw.
Pada periode Mekkah, selama 13 tahun kenabian, Rasulullah Saw hanya mengajarkan aqidah, ibadah dan ahlak mulia, di lingkungan terbatas. Setelah hijrah ke Madinah, selama sepuluh tahun kenabian, Rasulullah berhasil menerapkan praktik sosial. Menjalankan ekonomi, politik, kebudayaan, pertahanan keamanan, dan lain sebagainya. Sehingga terwujudlah “ash shumuluyatul Islam”, kelengkapsempurnaan Islam.
Dengan pondasi akidah tauhid, dan tiang-tiang ibadah (syahadatain, salat, zakat, haji dan puasa), dihiasi ahlak mulai serta praktek muamalah di tengah kehidupan sehari-hari, yang saling berjalin berkelindan dengan akidah, ibadah dan ahlak mulia, terbentuklah masyarakat yang “marhamah”. Saling kasih mengasihi. Itulah inti masyarakat “madani” yang akan menjadi soko guru “baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ”bangsa dan negara indah permai, aman sentosa kertaraharja, penuh ampunan Allah SWT (Q.s. Saba : 15).
Tapi sejak masa pemilihan umum tahun 1971, ajengan dan pesantren mulai dihadapkan kepada tuntutan-tuntutan informal. Yaitu tuntutan politik bagi kepentingan rezim yang sedang berkuasa, serta “penyetaraan” dengan pendidikan umum. Banyak pesantren dan ajengan tak mampu menghindar akibat berbagai faktor. Antara lain intimidasi fisik dan mental, serta iming-iming kemajuan.
Pesantren dan Ajengan yang tidak tunduk pada ajakan mendukung kekuatan politik penguasa, akan dicap sebagai anti pembangunan, anti Pancasila, bahkan kemungkinan dikaitkan dengan gerakan-gerakan “Negara Islam”, dan sebagainya. Pesantren yang tidak mau menerima “penyetaraan” corak dan model pendidikan, akan menjadikan para santrinya terkucil dari sistem pendidikan yang menjadikan ijazah sebagai bukti nilai intelektualitas.
Sehingga, sejak saat itu, banyak ajengan yang–terpaksa atau tidak, memasuki kotak-kotak ciptaan pemerintah Orde Baru. Menjadi “kyai pemerintah” alias “kyai pembangunan” yang loyal kepada Pancasila dan UUD 45 serta Orde Baru, dan tabu akan politik praktis, atau menjadi “kyai oposisi” karena tetap setia kepada parpol-parpol berorientasi ideologi tertentu.
Berkat reformasi Mei 1998, segala ikatan dan keharusan manipulatif itu, terlepas. Banyak kiyai dan pesantren mulai kembali menemukan jati diri masing-masing, sebagai figur dan lembaga yang betul-betul independen, baik dalam niat maupun dalam tujuan. Hanya saja kharisma ajengan dan pesantren, yang nyaris larut tergerus politik rezim pada masa Orde Baru dan politik pragmatis pada masa Orde Reformasi, perlu direvitalisasi. Agar pesantren kembali kepada jati diri awal sebagai lembaga pendidikan Islam formal yang “tidak ke mana-mana, tapi ada di mana-mana”. [ ]
* Pengasuh Pesantren Budaya Raksa Sarakan, Garut