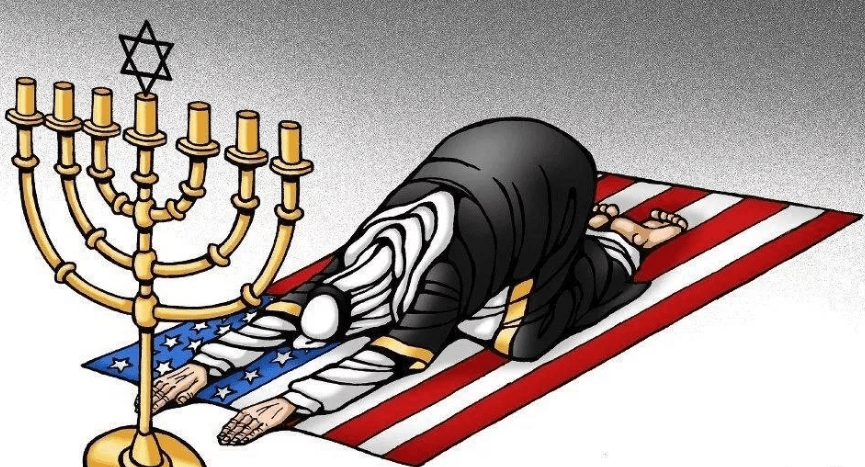Negara-negara Arab tak lagi memegang teguh “Tiga Tidak”, yakni tidak ada perdamaian dengan Israel, tidak ada pengakuan atas Israel, dan tidak ada negosiasi dengan negara Zionis itu…
Oleh : Dov S. Zakheim*
JERNIH– Hampir empat puluh tahun yang lalu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Alexander Haig berambisi menciptakan “konsensus strategis” antara Arab Saudi, Yordania, Israel, Turki, Pakistan, dan Irak, melawan musuh bersama mereka saat itu, Uni Soviet.
Haig boleh punya rencana, tapi semua ambyar. Negara-negara Arab yang menjadi tumpuan program itu, terus memegang teguh “Tiga Tidak” yang diumumkan Liga Arab di Khartoum, segera setelah Perang Enam Hari di 1967. Tiga Tidak” itu meliputi: tidak ada perdamaian dengan Israel, tidak ada pengakuan atas Israel, tidak ada negosiasi dengan negara Zionis itu. Ketika Presiden Mesir saat itu, Anwar Sadat, berdamai dengan Israel pada 1979, Liga Arab mencoret Mesir.
Selama beberapa dekade, terutama setelah Perjanjian Oslo 1993 antara Israel dan Otoritas Palestina, para ahli Timur Tengah berpendapat dunia Arab akan terus mematuhi “Tiga Tidak” itu sampai ada kesepakatan dua negara yang akan mengembalikan Tepi Barat, Gaza, dan Yerusalem Timur untuk Palestina. Tidak akan ada solusi “luar-dalam” seiring versi terbaru dari munculnya strategi konsensus Haig.
Hal itu tetap menjadi pandangan yang disepakati para ahli, bahkan ketika Mesir diterima kembali di Liga Arab pada 1989. Juga ketika Liga Arab diam tidak mengambil tindakan apa pun terhadap Yordania, yang pada 1994 menandatangani perjanjian damai dengan Israel setelah Perjanjian Oslo.
Kebenaran yang diterima di antara para ahli Timur Tengah adalah para penguasa Arab takut jika mereka berdamai dengan “entitas Zionis”, massa akan bangkit melawan mereka. Namun, massa memberontak terhadap para penguasanya karena alasan ekonomi, bukan karena intifada Palestina, atau aneksasi Israel atas Tepi Barat!
Pemberontakan bisa menjungkirbalikkan pemerintah sekuler kuat seperti Ben Ali dari Tunisia dan Ali Abdullah Saleh dari Yaman, atau menyebabkan perang saudara yang berlanjut di Yaman dan Suriah. Namun pemberontakan tersebut tidak menggantikan monarki Arab yang telah mengembangkan hubungan dengan Israel. Massa di negara-negara tersebut tetap diam.
Waktu telah berubah sejak visi Haig tentang front persatuan melawan Soviet gagal. Di awal 2000-an, front persatuan tumbuh antara Israel dan Teluk Arab melawan Iran–ancaman yang dianggap lebih berbahaya dan secara geografis lebih dekat daripada Rusia. Jangkauan pemerintahan Obama ke Iran mempererat pelukan Arab-Israel, seperti halnya perpecahan negara-negara Teluk dengan Qatar dan meningkatnya perselisihan dengan Turki, yang keduanya mendukung Ikhwanul Muslimin.
Menurut Zakheim, para ahli yang telah lama memusatkan perhatian pada konflik Israel-Palestina sebagai krisis sentral di Timur Tengah, tidak mengakui bahwa kecaman Liga Arab tahun 2017 terhadap sekutu Iran Hizbullah sebagai organisasi teroris menandai perubahan dalam hubungan Arab-Israel. Mereka yang terobsesi dengan konflik itu menolak untuk melihat kondisi untuk strategi “luar-dalam” menjadi jauh lebih baik.
Hebatnya, mengingat kesalahan penanganannya terhadap sebagian besar masalah kebijakan luar negeri, justru pemerintahan Trump, bukan ‘ahli-ahli’ yang pertama kali menyadari bahwa ‘warga Arab’ adalah khayalan seperti Arab Spring, dan kasus Palestina hampir diturunkan dari teater pertunjukan Timur Tengah.
Hanya ada sedikit reaksi perlawanan datang dari warga Arab terhadap pengakuan Amerika atas aneksasi Israel di Dataran Tinggi Golan. Kekhawatiran yang disuarakan oleh pemerintah Arab terhadap pengakuan Amerika atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel juga sedikit. Massa juga tidak tumpah ruah ke jalanan saat UEA menandatangani perjanjian normalisasi dengan Israel; ketika Liga Arab menolak permohonan Palestina untuk mengutuk UEA atas perjanjian itu; ketika Arab Saudi secara terbuka mengizinkan pesawat El Al melintasi wilayah udaranya; juga ketika Bahrain mengumumkan akan melakukan hal yang sama.
Sekarang tampaknya dukungan terkuat untuk penolakan Palestina tidak berasal dari dunia Arab, melainkan dari elemen sayap kiri di Barat, khususnya para intelektual dan akademisi. Menerapkan teori yang meragukan tentang “interseksionalitas”, penentangan keras mereka terhadap Israel telah membuat mereka menargetkan institusi Yahudi dan melecehkan mahasiswa Yahudi di kampus bahkan ketika negara-negara Arab mempertimbangkan interaksi yang lebih terbuka dengan Israel, atau bahkan pengakuan langsung.
Jalan menuju solusi dua negara yang sebenarnya tidak melalui akademisi Amerika dan Eropa. Yang ada, para pemimpin Palestina harus menyadari zaman telah berubah. Mereka tidak dapat lagi mengandalkan negara-negara Arab maupun ‘warga Arab’ untuk memaksakan konsesi dengan Israel. Jika mereka benar-benar serius untuk membangun sebuah negara bagi rakyatnya, mereka harus memasuki perundingan tatap muka serius dan berkepala dingin dengan Israel. [The National Interest]
Dov S. Zakheim, wakil menteri pertahanan Amerika Serikat (2001-2004)