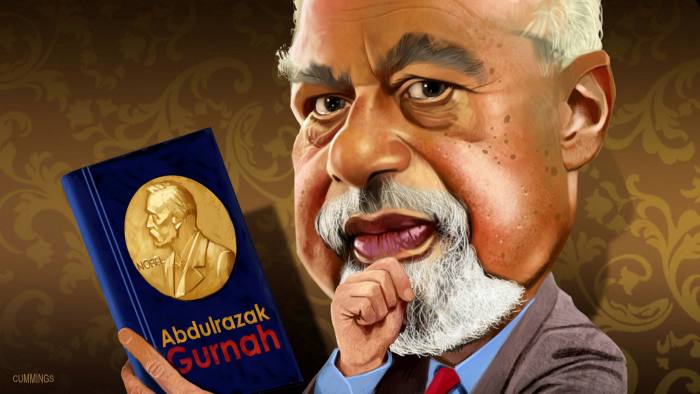Setiap tahun, Komite Nobel mengambil seorang penulis tunggal dari arus besar kesusastraan dunia dan, dengan mengurapinya, secara implisit mengangkat penulis itu di atas segalanya, dengan cara yang jelas-jelas menyesatkan. Ada terlalu banyak penulis, terlalu banyak ‘register’, dengan terlalu banyak perbedaan penting di antara mereka—dan tidak ada metrik tunggal yang dapat digunakan untuk membandingkan semua penulis secara bermakna.
Oleh : Kristen Roupenian
JERNIH– Pertama kali saya bertemu dengan karya peraih Nobel Sastra 2021, Abdulrazak Gurnah, terjadi ketika saya belajar untuk ujian lapangan dalam sastra pasca-kolonial, pada 2009 lalu. Yang paling saya ingat adalah gaya tulisannya mampu mengurangi respons analitis saya yang pedas, yang akhir-akhir ini telah berkembang dalam proporsi mengerikan.
Saat itu, dalam karir pascasarjana saya, saya tidak bisa melewati halaman fiksi tanpa mencoret-coretkan tanda tanya dan tanda seru, beserta komentar gila di pinggir halaman buku. Tapi saya bisa ditenggelam “Paradise,”novel sejarah yang ditulis Gurnah tentang kolonisasi di Afrika Timur, yang diterbitkan pada tahun 1994. Saya saat itu membaca laiknya orang yang masih membaca buat kesenangan. Buku itu mampu memukau saya dengan kekayaan indranya, kilatan erotismenya, dan lamunan interioritas sang protagonisnya. Novel itu bicara tentang kebangkitan jaringan komunitas multibahasa yang terancam oleh monokultur colonial. Lain dari biasa, saat itu pena saya tak banyak menuliskan kata-kata pedas di pinggiran buku.
Beberapa tahun kemudian, ketika saya harus mengajar di kelas sastra pasca-kolonial, saya memakai novel keenam Gurnah,“By the Sea”. Buku yang menggambarkan hubungan penuh antara dua pria Zanzibar yang bersatu kembali di Inggris bertahun-tahun setelah pertemuan pertama mereka itu sangat cocok dengan tema pengajaran yang saya ampu. “By the Sea” novel panjang dan mendalam, yang berfokus pada karakter-karakternya itu, menurut saya adalah novel yang meminta untuk dialami daripada diperdebatkan.
Manakala Kamis lalu Gurnah terpilih memenangkan Hadiah Nobel Sastra, saya tengah menyelesaikan bacaan atas novelnya yang terbit pada 2017, “Gravel Heart“. Novel itu saya pilih karena beberapa opsi; a) saya memang belum membacanya; b) saya penasaran dengan judulnya yang ‘khas’; dan c) buku itu tersedia di Kindle, dan saya tak ingin dibayang-bayangi rasa kepenasaran akan Gurnah, yang beberapa copy karyanya masih terpampang di etalase Strand bookstore di Broadway.
Saya merekomendasikan “Gravel Heart” yang ditulis secara melankolis, menggugah, dan kadang-kadang sangat lucu, untuk menghabiskan sore musim gugur. Meskipun saya pikir Komite Nobel telah tepat untuk menyebut “Paradise” sebagai karya utama Gurnah.
“Gravel Heart” dimulai dengan tulisan yang menawan, namun agak menipu: “Ayahku tidak menginginkanku,” kata si narator, Salim, di kalimat pertama novel itu. Alasan di balik hilangnya cinta ayah yang dirasakan Salim diisyaratkan dalam sebuah narasi yang berjalan mundur dan maju dalam waktu, dan buku itu sering kali tampaknya mengembara jauh dari apa yang seolah-olah menjadi misteri utamanya.
Kemudian ayah Salim kembali di sepertiga akhir novel untuk menyatukan untaian kisah yang diceritakan. Dalam gaya khas Gurnah, narasi dijalin dengan apa yang bisa terasa seperti penyimpangan: meditasi pada foto, surat, dan artefak lainnya; kilas balik sensorik, anekdot, hipotetis—semua aide-mémoire tersebar yang diandalkan oleh mereka yang mengungsi. Kisah ayah Salim, sementara itu, diceritakan dengan keterburu-buruan yang menarik. Cerita di novel ini adalah jenis kisah yang digerakkan oleh plot bersih yang dibuat oleh orang-orang yang telah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk memoles jawaban atas pertanyaan yang pada dasarnya tidak dapat dijawab: Mengapa ini terjadi pada saya?
Salim meninggalkan Afrika sebagai remaja, untuk tinggal di Inggris, di mana ia memutuskan–dalam menghadapi tentangan kuat keluarganya–untuk belajar sastra, dan ia tetap di sana untuk sebagian besar novel, pulang dan menghadapi ayahnya hanya setelah sia-sia merenungkan retaknya kehidupan dari jauh selama bertahun-tahun.
Menjelang akhir buku, setelah ayah Salim mengakhiri penjelasannya, Salim bertanya kepadanya,“Apakah Anda pernah membaca ‘Measure for Measure’?” Ketika ayahnya mengatakan dia tidak pernah sepenuhnya memahami Shakespeare (“Saya tidak bisa melewati Zounds dan Exeunts dan Harks dan mencari-cari di prolog sana”), Salim meluncurkan ke ringkasan plot yang lengkap. Intinya, bahwa tragedi keluarga mereka tercermin dalam peristiwa yang ada pada “Measure for Measure“, namun peran ayahnya dalam cerita mereka sendiri sangat kecil, sehingga dia tidak memiliki kesetaraan dengan personel lain dalam drama Shakespeare itu.
Ayah Salim, seperti yang bisa dibayangkan, tampaknya tidak tertarik merespons kritis intelektual putranya terhadap pelepasan beban emosionalnya. “Saya tidak akan repot-repot membacanya,” katanya, “jika tidak ada bagian untuk saya.”
Orang mungkin berargumen bahwa pertukaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana bobot budaya yang tidak proporsional dari kanon sastra Barat akhirnya membuat cerita-cerita lain tidak ada, bahkan ketika mencoba untuk merangkulnya—atau, mungkin, betapa mengasingkan untuk terus mencari diri sendiri dalam tradisi yang gagal untuk mengakui pengalaman Anda sebagai nyata. Kedua interpretasi menunjukkan bahwa Gurnah, seperti banyak penulis lain yang memilih untuk menulis dalam bahasa Inggris meskipun bukan bahasa pertama mereka, telah memikirkan secara mendalam tentang pertanyaan seputar tradisi, pengaruh, dan kanon.
Dalam esai yang ditulisnya pada 2004, “Writing and Place,” Gurnah mencatat, “Saya percaya bahwa penulis datang untuk menulis melalui membaca, bahwa semua itu keluar dari proses akumulasi dan kontinuitas penambahan, dari gema dan pengulangan, bahwa mereka membuat register yang memungkinkan mereka terus menulis.”
Dia melanjutkan untuk melacak evolusi bacaan yang memungkinkan daftarnya sendiri: aksesnya yang terbatas, tumbuh di Zanzibar, tautan kepada sastra yang ditulis dalam bahasa pertamanya, Kiswahili; pendidikan kolonial Inggris yang mengasingkan yang diterimanya di sana; pembelajaran Alquran yang berlangsung di masjid setempat; dan bacaannya sendiri dalam bahasa Inggris, setelah ia meninggalkan Zanzibar, pergi ke Inggris sebagai pengungsi muda.
Karena saya percaya pada studi sastra, saya percaya bahwa untuk menghargai karya Abdulrazak Gurnah, atau penulis mana pun, kita harus memiliki pengetahuan tentang tradisi yang dimiliki penulis—membaca beberapa buku yang memunculkan ‘register’nya. Kalau tidak, bagaimana kita bisa memahami apa yang ingin dicapai oleh penulis, suara-suara yang dia bicarakan, kiasan dan intertekstualitasnya? Karena dominasi budaya yang luar biasa dari bahasa Inggris, penutur bahasa Inggris hampir selalu memiliki akses ke setidaknya beberapa bagian dari tradisi yang telah membentuk tulisan yang memenangkan Hadiah Nobel.
Bahkan penulis yang tidak menulis dalam bahasa Inggris akan membaca setidaknya beberapa karya klasik berbahasa Inggris, walau hanya dalam terjemahan. Hal ini membuat lebih mudah untuk melupakan semua aliran pengaruh lainnya: puisi Kiswahili, kisah-kisah Islam, bahkan buku sekolah kolonial Inggris yang membentuk generasi penulis di seluruh dunia.
Setiap tahun, Komite Nobel mengambil seorang penulis tunggal dari arus besar kesusastraan dunia dan, dengan mengurapinya, secara implisit mengangkat penulis itu di atas segalanya, dengan cara yang jelas-jelas menyesatkan. Ada terlalu banyak penulis, terlalu banyak ‘register’, dengan terlalu banyak perbedaan penting di antara mereka—dan tidak ada metrik tunggal yang dapat digunakan untuk membandingkan semua penulis secara bermakna.
Tetapi, dengan mengklaim otoritas untuk membangun kanon dunia, panitia mengundang kita untuk melihat lebih dekat tradisi kita sendiri yang dibangun secara individual, bacaan yang telah membangun catatan kita, apakah kita menganggap diri kita sebagai penulis atau bukan.
Kita belajar banyak tentang diri kita pada saat pemenang Hadiah Nobel diumumkan. Saat itu, kita mendapati diri kita berpikir,”Ah, seharusnya si X yang menang.”
Dan ketika kita berada di Strand, berdesak-desakan dengan calon pembaca lain untuk mendapatkan salinan terakhir dari “Paradise” (atau memesan salinan “By the Sea” di Amazon yang saat ini dijual seharga974 dolar AS), kita dapat menggunakan kesempatan itu untuk mengambil satu atau dua buku lain yang mungkin memperdalam apresiasi kita terhadap daftar karya Gurnah. Mungkin kumpulan puisi Kiswahili atau narasi perjalanan, atau “Kisah Seribu Satu Malam,” atau sebuah novel karya penulis besar Afrika Timur lainnya, Ngũgĩ wa Thiong’o . . . atau bahkan “Measure for Measure” karya Shakespeare, yang harus saya akui belum pernah saya baca. [The New Yorker]