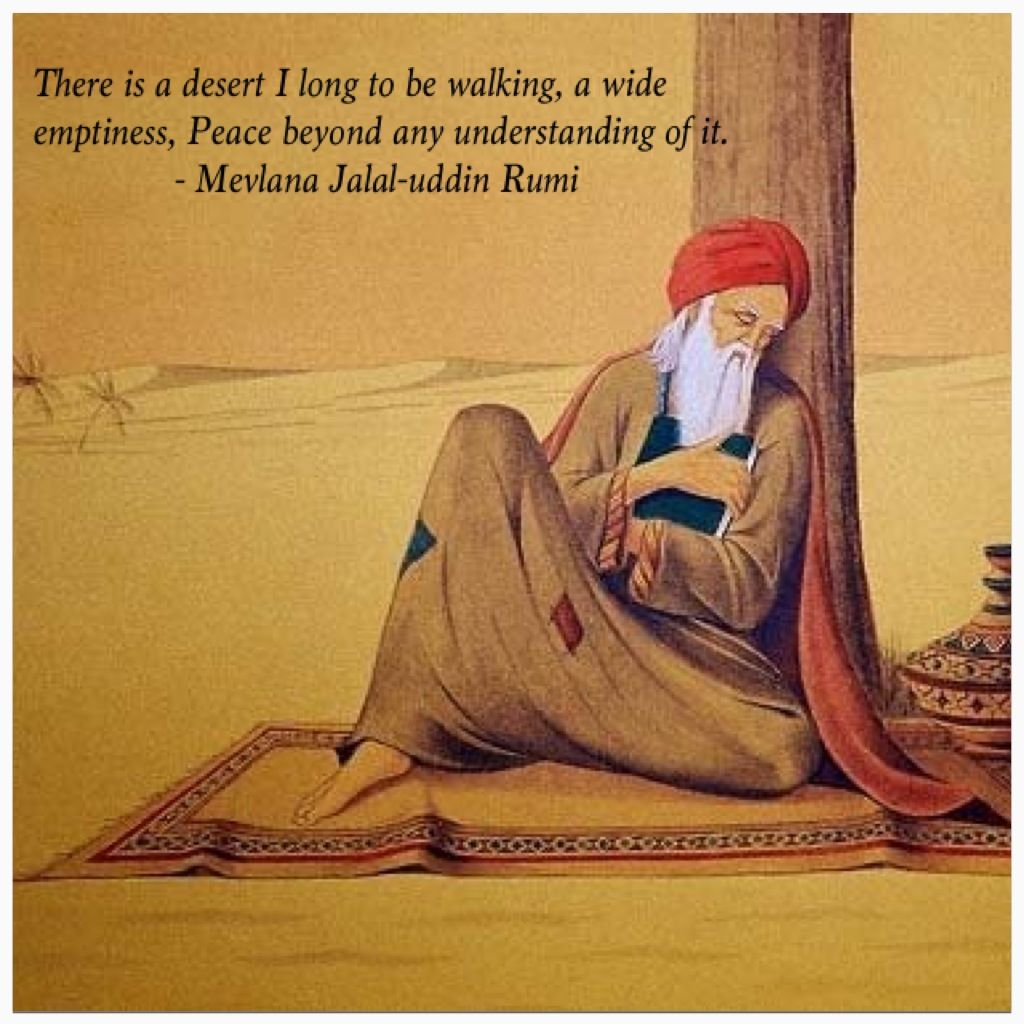“Ya Allah!” seru Malik, “Sebiji korma pun belum sempat kumakan dan Engkau menyebutku Yahudi melalui lidah seorang anak tak berdosa. Seandainya korma-korma ini sempat termakan olehku, niscaya Engkau akan menyatakan diriku sebagai seorang kafir.
JERNIH—Bertahun-tahun lamanya wali sufi Malik bin Dinar tidak mengecap makanan yang manis maupun yang asam segar. Bertahun-tahun ia melakukan hal yang nyaris menjadi ritual rutinnya, setiap malam pergi ke tukang roti, membeli dua potong roti untuk berbuka puasa.
Sesekali roti yang dibelinya itu masih terasa hangat; dan itu membuat hatinya terhibur senang, menganggap hal itu sebagai perangsang selera makannya.
Pada suatu hari Malik bin Dinar jatuh sakit dan ia sangat ingin memakan daging. Sepuluh hari lamanya ia terbaring, menindas keinginan tersebut dalam sakit. Waktu dirinya merasa tidak dapat lebih lama lagi bertahan, pergilah ia ke toko makanan untuk membeli dua tiga potong kaki domba. Disenyembunyikannya kaki-kaki domba tersebut di lengan bajunya.
Si pemilik toko yang mengenal siapa pembelinya itu menyuruh seorang pelayannya membuntuti Malik untuk menyelidiki apa yang hendak ia lakukan. Tidak berapa lama kemudian si pelayan kembali dengan air mata berlinang.
Si pelayan memberikan laporan. “Dari sini ia pergi ke sebuah tempat sepi. Di tempat itu dikeluarkannya kaki-kaki domba itu, dicium-ciumnya dan ia berkata kepada dirinya sendiri. “Lebih dari pada ini bukanlah hakmu.”
Kemudian diberikannya roti dan kaki-kaki domba tersebut kepada seorang pengemis. Kemudian ia berkata pula kepada dirinya sendiri : “Wahai jasmani yang lemah, jangan kau sangka bahwa aku menyakitimu karena benci kepadamu. Hal ini kulakukan agar pada Hari Berbangkit nanti, engkau tidak dibakar dalam api neraka. Bersabarlah beberapa hari lagi, karena pada saat itu godaan ini mungkin telah berhenti dan engkau pun mendapatkan kebahagiaan yang abadi.”
**
Suatu ketika Malik bin Dinar berkata : “Aku tidak mengerti apa maksud ucapan : “Bila seseorang tidak memakan daging selama empat puluh hari maka kecerdasan akalnya akan berkurang!” Aku sendiri tidak pernah makan daging selama dua puluh tahun, tetapi kian lama kecerdasan akalku justru makin bertambah.”
Selama empat puluh tahun Malik tinggal di kota Bashrah dan selama itu pula ia tidak pernah memakan buah korma yang segar. Apabila musim korma tiba, ia berkata,”Wahai penduduk kota Bashrah, saksikanlah betapa perutku tidak menjadi kempis karena tidak memakan buah korma dan betapa perut kalian tidak gembung karena setiap hari memakan buah korma.”
Namun setelah empat puluh tahun lamanya, batinnya diserang kegelisahan. Betapa pun ia berusaha menahan, namun keinginannya untuk memakan buah korma segar tidak dapat ditahannya lagi. Akhirnya setelah beberapa hari berlalu, keinginan tersebut kian menjadi-jadi dan Malik pun merasa tak berdaya untuk menolak desakan nafsunya itu.
Namun tetap berusaha menyangkal keinginannya itu. “Aku tidak mau memakan buah korma. Lebih baik aku mati.”
Malam itu, dalam upayanya bertahan, Malik mendengar sebuah suara berkata: “Engkau harus memakan buah korma. Bebaskan jasmanimu dari kungkungan dirimu sendiri.”
Mendengar suara ini tubuhnya yang merasa memperoleh kesempatan itu mulai menjerit-jerit. “Jika engkau menginginkan buah kurma,” kata Malik menyentak, “Berpuasalah terus-menerus selama satu minggu dan shalatlah sepanjang malam, setelah itu barulah akan kuberikan buah kurma kepadamu.”
Ucapan Malik itu membuat tubuhnya senang. Seminggu penuh ia mendirikan shalat sepanjang malam dan berpuasa setiap hari. Setelah itu ia pergi ke pasar, membeli beberapa buah korma segar, kemudian pergi ke masjid untuk memakan buah korma tersebut.
Belum juga ia memasuki halaman masjid, dari loteng sebuah rumah, seorang bocah berseru, “Ayah! Seorang Yahudi membeli korma dan hendak memakannya di dalam masjid.”
“Apa pula yang hendak dilakukan Yahudi itu di dalam masjid?” kata ayah anak tersebut menggerutu dan bergegas untuk melihat siapakah Yahudi yang dimaksud anaknya itu. Tetapi begitu melihat Malik, ia lantas berlutut.
“Apakah artinya kata-kata yang diucapkan anak itu?”kata Malik mendesak.
“Maafkanlah ia guru,”ujar Si Ayah memohon. “Ia masih anak-anak dan tidak mengerti. Di sekitar ini banyak orang Yahudi. Kami selalu berpuasa dan anak-anak kami menyaksikan beberapa orang-orang Yahudi makan di siang hari. Karena itu mereka berpendapat bahwa setiap orang yang makan di siang hari adalah seorang Yahudi. Apa pun yang telah diucapkannya adalah karena kebodohannya. Maafkanlah dia.”
Mendengar penjelasan tersebut Malik sangat menyesal. Ia menyadari bahwa anak itu telah didorong Allah mengucapkan kata-kata itu.
“Ya Allah!” seru Malik, “Sebiji korma pun belum sempat kumakan dan Engkau menyebutku Yahudi melalui lidah seorang anak tak berdosa. Seandainya korma-korma ini sempat termakan olehku, niscaya Engkau akan menyatakan diriku sebagai seorang kafir. Demi kebesaran-Mu aku bersumpah tidak akan memakan buah korma untuk selama-lamanya.”
**
Suatu hari Gubernur Bashrah lewat bersama rombongan dan tentaranya. Malik berseru mengkritik rombongan yang tidak efisien itu. Para pembantu Gubernur marah dan mengancam Malik. Namun Sang Gubernur buru-buru mencegah, lalu berkata pada Malik,” Ya Fulan, apakah engkau tidak mengenalku?”
“Siapa yang lebih tahu tentang dirimu daripada aku? Awalmu hanya tetesan mani yang menjijikan. Akhirmu adalah jenazah yang hina. Sekarang engkau berada di antara dua kondisi itu, membawa-bawa kotoran.”
Sang Gubernur terperanjat dan menundukkan wajahnya. Ia meminta rombongannya segera meninggalkan tempat itu, sembari pelan,”Sungguh engkau telah mengetahui siapa diriku.”
Itulah Malik bin Dinar, seorang zuhud dalam segala hal. Ia berani kepada semua makhluk dan hanya takut kepada Allah. Ia meninggal dunia sebelum wabah Tha’un (kolera) melanda Bashrah pada 131 Hijriyah. [ ]
Dari “Muslim Saints and Mistics” Fariduddin Aththar, terjemahan Pustaka Zahra, 2005