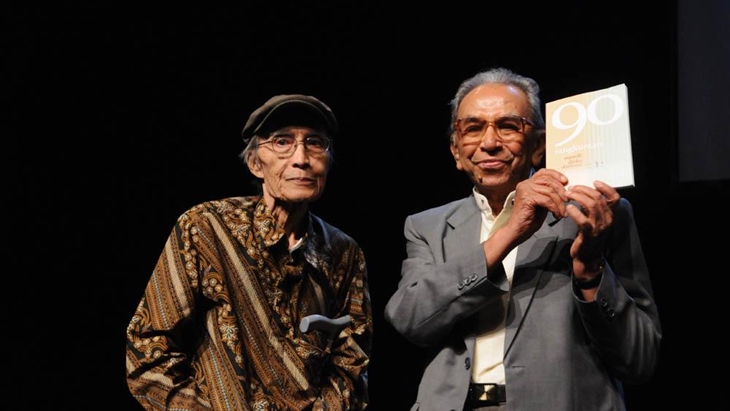Itu salah satu sebab saya sepakat kalau sosok ini kita anggap sebagai legenda–ia adalah dongeng yang tidak pernah merasa jadi jagoan dalam segala hal, tetapi masih memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan tugas yang–menurut saya––ia sendiri pun pasti mampu melaksanakannya.
Oleh : Sapardi Djoko Damono
JERNIH– Ternyata tidak mudah menerjemahkan sosok Ali Audah ke dalam sebuah tulisan ringkas. Menerjemahkan tidak lain berarti mengubah, menciptakan sesuatu yang baru;dan mengubah Ali Audah menjadi sebuah tulisan ringkas kali ini merupakan masalah pelik bagi saya.
Baru kali ini saya merasa bahwa memang ada yang tidak bisa diterjemahkan: Ali Audah mungkin sekali tidak hadir untuk saya pahami tetapi untuk saya hayati. Tidak keliru kalau banyak orang memberinya label legenda, yang dalam bahasa kita tak lain berarti dongeng, sebab latar belakang pendidikan, pencapaian, dan sikapnya terhadap orang lain rasanya akan lama bertahan dalam kenangan kita.
Rasa hormat saya kepadanya dan sikapnya selama ini kepada saya adalah inti penghayatan itu, yang sedikit demi sedikit tumbuh sejak saya mengenalnya di akhir tahun 1970-an. Baik, saya mulai upaya menerjemahkannya ke dalam tulisan ringkas ini yang moga-moga bisa menyinggung serba sedikit pengalaman saya ketika berurusan dengannya dalam kegiatan kami sebagai penerjemah.
Sebermula adalah Amak Baldjun, sahabat yang rasa-rasanya juga tidak begitu mudah diterjemahkan. Almarhum menemui saya pada suatu hari baik bulan baik di akhir tahun 1980 atau awal tahun 1990-an, menyampaikan pesan yang ‘sederhana’ dari Ali Audah, yakni ajakan untuk membantunya menerjemahkan Tafsir Qur’an Abdullah Yusuf Ali, “The Holy Qur’an. Text, Translation and Commentary”.
Untuk meredakan rasa kaget saya, Amak mengajak saya menemui penerjemah itu di Bogor. Rasa kaget itu memang benar-benar rasa kaget sebab saya sama sekali tidak memahami bahasa Qur’an, di samping kenyataan bahwa setiap upaya menerjemahkan Kitab Suci itu ke dalam bahasa Indonesia (dan juga bahasa lain) selalu menuai masalah –tambahan lagi: tafsir Yusuf Ali telah juga menerima kritik pedas dari pihak yang tampaknya berseberangan pandangan dengannya tentang penerjemahan Qur’an.
Mungkin hal itu berkaitan dengan sikap sektarian yang tidak baik kalau saya jelaskan karena memang tidak begitu saya pahami. Amak Baljun kemudian menyerahkan tafsir ulama Pakistan yang konon paling banyak pembacanya dalam masyarakat berbahasa Inggris di seluruh duniaitu. Rasa kaget saya itu sedikit reda ketika Ali Audah menjelaskan bahwa perekrutan saya itu tidak berkaitan langsung dengan teks Qur’an tetapi ‘hanya’ berurusan dengan sejumlah sajak yang mula-mula saya anggap sebagai ‘sisipan’ yang disertakan juru tafsir agung itu untuk menekankan hal-hal penting dalam tafsirnya.
Begini: mahakarya Yusuf Ali itu memuat tiga bagian penting yakni teks Qur’an, terjemahannya ke dalam bahasa Inggris, dan sejenis ‘sisipan’ yang oleh Yusuf Ali disebut “Commentary”.
Tafsir ini unik, di samping menulis tafsir atas surah dan ayat Qur’an, Yusuf Ali menyertakan atau menyisipkan “Commentary” juga atas sejumlah surah dan ayat yang ditafsirkannya. Dalam benak saya muncul pengertian bahwa ada tafsir dan ada komentar, keduanya bisa dibedakan–-karena memang berbeda.
Namun, istilah ‘komentar’ ternyata tidak begitu tepat untuk pengertian yang dimaksudkan Yusuf Ali. Mula-mula lebih sreg jika saya menyebut “Commentary” sebagai sisipan sebab letaknya memang disisipkan di sela-sela teks terjemahannya, tidak terpisah. Namun, dalam pembicaraan Ali Audah dan saya akhirnya diputuskan bahwa yang disebut “Commentary” oleh Yusuf Ali, kami terjemahkan saja menjadi Rangkuman.
Tampilan visual buku Yusuf Ali kira-kira begini: setiap halaman dibagi menjadi dua, yakni atas dan bawah, dibatasi oleh garis horisontal. Bagian atas dibagi dua, dibatasi garis vertikal: sebelah kanan adalah teks Qur’an dalam huruf Arab, sebelah kiri adalah terjemahan dalam bahasa Inggris. Yang disebut “Commentary” disisipkan di sela-sela teks asli dan terjemahan, menerjang garis pembatas vertikal. Masing-masing rangkuman diberi nomor dimulai dengan huruf “C”, maksudnya “Commentary”, tentu saja.
Dalam terjemahannya, huruf “C” diganti dengan “R”. Jumlah sisipan adalah 300, mulai dari C.1 sampai dengan C.300. Perlu diketahui bahwa istilah sisipan memang juga sebenarnya tidak terlalu tepat sebab banyak “Commentary” yang tidak disisipkan tetapi berdiri sendiri, biasanya mengawali ayat seperti yang mengawali keseluruhan tafsir dan mengawali surah 1 (fatiha), atau yang ditaruh di belakang sebagai sejenis penutup.
Rangkuman yang kadang-kadang mengawali surah atau ayat dan kadang disisipkan di antara surah dan ayat itu disebutnya “running Commentary”. Yusuf Ali rupanya sangat memperhatikan aspek kelisanan teks Qur’an. Tentang istilah itu dikatakan dalam prakata bukunya,“The rhythm, music, and exalted tone of the original should be reflected in the English Interpretation.”
Pernyataan ini membuat saya kembali merasa ciut dan kaget dan selanjutnya bertanya-tanya, meragukan kemampuan saya dalam mengalihkan semua itu ke dalam bahasa Indonesia. Rupanya ia sepenuhnya yakin akan dahsyatnya kekuatan dan makna Qur’an kalau dilisankan, yang baginya hanya mungkin disampaikan dalam rangkaian sajak dalam bahasa Inggris yang diharapkan bisa mewakili irama bahasa aslinya.
Ia juga menjelaskan bahwa terjemahan itumerupakan “not a mere substitution of one word for another.” Ujud visual seperti yang sudah saya coba gambarkan itu selanjutnya dijelaskan olehnya bahwa teks terjemahan dicetak dengan huruf yang font-nya lebih besar dibanding dengan rangkumannya. Namun, lebih kecilnya ukuran font ternyata tidak berbanding lurus dengan posisinya dalam tafsirnya.
Katanya, “The text in English is printed in larger type than in the running Commentary, in order to distinguish, at a glance, the substance from the shadow.” Jadi, “Commentary” dianggapnya sebagai bayang-bayang substansi, yakni terjemahannya atau bahkan teks aslinya.
Pada titik inilah saya benar-benar merasa dihargai oleh Ali Audah karena tentu dianggapnya memiliki kemampuan menerjemahkan bayang-bayang substansi terjemahan dan teks Qur’an. Belum pernah selama hidup, dalam kapasitas saya sebagai penulis puisi dan penerjemah, dihargai setinggi itu.
Itu salah satu sebab saya sepakat kalau sosok ini kita anggap sebagai legenda–ia adalah dongeng yang tidak pernah merasa jadi jagoan dalam segala hal, tetapi masih memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan tugas yang–menurut saya––ia sendiri pun pasti mampu melaksanakannya.
Sejumlah karangan Ali Audah yang pernah saya baca membuktikan betapa tinggi taraf kemampuannya dalam berbahasa. Dalam padangan saya, penguasaan atas bahasa sasaran adalah syarat yang mutlak bagi penerjemah. Setelah menerima mahakarya Yusuf Ali dan membacanya beberapa halaman, segera saya merasa ‘akrab’ dengan terjemahannya–lebih akrab dibanding dengan terjemahan ke dalam bahasa Inggris yang dilakukan oleh pakar atau ulama lain, misalnya Muhammad Marmaduke William Pickthall.
Mungkin itu juga salah satu alasan mengapa karya Yusuf Ali adalah salah satu tafsir berbahasa Inggris yang paling banyak dibaca oleh masyarakat yang memahami bahasa itu. Belakangan baru saya ketahui bahwa Yusuf Ali adalah seorang pembaca tekun dan peneliti sastra Inggris, yang konon menguasai bahasa itu sama tarafnya dengan penguasaannya atas bahasa Arab.
Dalam pengantar bukunya, ia mengutip sajak Inggris dan menyebut nama-nama peyairnya. Pengantarnya menjelaskan, “Every earnest and reverent student of the Qur-an, as he proceeds with his study, will find, with an inward joy difficult to describe, how this general meaning also enlarges as his own capacity for understanding increases”.
Sesudah menjelaskan hal itu Yusuf Ali kemudian mengutip sebuah sajak penyair romantik Inggris, John Keats, yang menulis sajak sehabis membaca penjelasan Chapman tentang karya Homerus. Sajak Keats yang dikutipnya itu kira-kira memberi gambaran bahwa semakin tinggi pengalaman orang, semakin luas pandangannya.
Diikutinya larik-larik sajak Keats yang dikutipnya itu dengan pernyataan lugas, “How much greater is the joy and sense of wonder and miracle when the Qur-an opens our spiritual eyes!”
Kutip-mengutip yang dilakukan Yusuf Ali ini saya anggap sebagai ujud kesadaran bahwa ketika menerjemahkan ia menghadapi khalayak yang berbeda, yang berasal dari kebudayaan yang telah menghasilkan karya sastra yang ia kutip.
Pengalaman saya belajar kesusastraan Inggris ketika menempuh tahap pertama pendidikan tinggi tampaknya berkaitan erat dengan rasa ‘akrab’ ketika sekilas membaca terjemahan Yusuf Ali. Juru tafsir itu ternyata suka menulis puisi dalam bahasa Inggris dan saya curiga alasan itulah yang mendorong Ali Audah meminta saya menerjemahkan Rangkuman dalam tafsir tersebut.
Saya yakin, ia mampu melakukan terjemahan sisipan itu sendiri tetapi tentu kerendahhatian telah mendorongnya untuk menugasi saya melakukannya. Sikap itulah antara lain yang sulit saya terjemahkan ke dalamtulisan ringkas ini. Dalam hal ini Amak Baljun, yang semoga sabar menunggu saya di Sana, tentu punya andil juga.
Waktu kami mengerjakan terjemahan, Amak Baljun yang memegang peran utama dalam komunikasi antara Ali Audah dan saya. Maka mulailah saya menerjemahkan 300 Commentary seiring dengan proses penerjemahan teks dan tafsir Qur’an yang dilakukan Ali Audah.
Seingat saya, penerjemah karya agung Haekal tentang “Sejarah Nabi” itu mengusulkan beberapa perbaikan terjemahan saya, sikap yang harus ditafsirkan sebagai bukti bahwa ia memperhatikan apa yang telah saya lakukan.
Bahkan pernah terbit pikiran Amak pada waktu itu untuk memisahkan kumpulan Rangkuman itu dan menerbitkannya tersendiri, tetapi saya lupa alasannya mengapa akhirnya usul yang jitu itu tidak jadi dilaksanakan.
Sebenarnya saya sudah siap-siap memperbaiki terjemahan saya agar lebih utuh kalau tampil sebagai buku tersendiri, sebagai pendamping tafsir Yusuf Ali, atau sebagai tafsir saya atas Rangkuman karyaYusuf Ali. Saya ingat benar, Ali Audah menekankan agar Rangkuman itu diperlakukan sebagai puisi yang kebetulan ada kaitannya dengan tafsir ulama agung Pakistan itu.
Itu saya artikan sebagai sikap yang tidak mencampuradukkan terjemahan Ali Audah dan terjemahan puisi Yusuf Ali. Namun, justru sikap demikian itu menyebabkan saya berusaha sehati-hati mungkin mengalihkan ‘pesan’ yang tersurat dan tersirat dalam Rangkuman tersebut–suatu hal yang jarang saya lakukan kalau menerjemahkan puisi yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan teks lain.
Seperti yang selalu terjadi pada proses penerjemahan puisi oleh siapa pun, penerjemah memiliki kebebasan untuk menciptakan puisi baru yang ‘moga-moga saja’ masih ada kaitannya dengan puisi dalam bahasa sumbernya. Seandainya pun ternyata tidak ada, ya mau apa lagi. Menerjemahkan, menurut keyakinan saya,adalah menciptakan benda budaya ‘baru’ yang, disukai atau tidak,tentu berbeda dengan aslinya.
Itu sebabnya penerjemahan sering dianggap sebagai creative treason–‘pengkhianatan kreatif.’ Dan itu pula sebabnya senantiasa terjadi ribut-ribut bila ada usaha menerjemahkan kitab-kitab yang pada hakikatnya memang tidak bisa diterjemahkan seperti Qur’an, meskipun kita juga sepenuhnya sadar bahwa tujuan menerjemahkan adalah menyediakan pemahaman dan penghayatan atas sesuatu yang maha berharga bagi ummat yang perlu dan pantas mendapatkannya tetapi yang karena perbedaan bahasa tidak bisa mencapainya.
Dan di dalam Islam, kedua hal itu telah dilaksanakan dengan semestinya: ada terjemahan di samping upaya untuk menghafalkan sepenuhnya di dalam bahasa aslinya untuk mengurangi penyimpangan.
Untuk tidak melenceng ke sana ke mari, baik saya kutip saja terjemahan Ali Audah atas teks Qur’an dan terjemahan saya atas Rangkuman yang dianggap Yusuf Ali sebagai “bayang-bayang” substansinya. Kutipan ini bersumber pada Qur’an Terjemahan dan Tafsirnya (Jilid 1). Juz I s/d XV.
Saya kutip terjemahan Ali Audah atas Surah Ali Imran ayat 29, 30 dan ayat 31 yang disisipi terjemahan saya atas R.56.
29. Katakanlah, “Baik kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau menyatakannya, Allah mengetahui semua itu: dan Allah mengetahui segala yang ada di langit, dan yang di bumi, dan Allah berkuasa atas segalanya.
30. Pada suatu hari tatkala setiap orang akan dihadapkan pada segala yang baik yang pernah diperbuatnya dan pada yang buruk yang pernah diperbuatnya, ia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dirinya dan perbuatannya yang buruk tapi Allah memperingatkan kamu terhadap-Nya dan Mahakasih terhadap hamba-bamba-Nya.
R.56
Kebenaran Tuhan berkelanjutan, dan rasul-rasul-Nya
Semenjak Adam sampai Nuh dan Ibrahim,
Sampai ke Rasul terakhir, Muhammad,
Membentuk suatu persaudaraan. Dari keturunan
Imran, ayah Musa dan Harun,
Lahirlah seorang wanita, yang mempersembahkan
Putranya yang belum lahir kepada Allah.
Wanita itu adalah Maryam ibunda Isa.
Sepupunya adalah istri Pendeta
Zakaria yang mengasuh Maryam.
Dalam usianya yang tua, Zakaria mempunyai
Seorang putra, Yahya:
Yahya inilah yang mengetahui kedatangan Isa
Putra Maria, dan ia dikenal sebagai
Yahya pembabtis. Isa
Putra seorang perawan,
Dan mempertunjukkan berbagai mukjizat.
Tetapi bangsanya sendiri malah menolaknya
Sebagai Rasul, bahkan merencanakan untuk membunuhnya.
Rencana itu gagal, sebab rencana Allah
Selalu mengatasi rencana manusia. Dan begitulah
Dengan Islam, Kebenaran dari segenap Keabadian.
31. Katakanlah: “Kalau kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Allah akan mencintai kamu dan mengampuni segala dosamu. Allah Maha Pengampun Maha Pengasih.”
Terjemahan yang dilakukan Ali Audah itu dengan jelas menunjukkan bahwa penguasaannya atas bahasa sasaran sangat tinggi tarafnya, suatu kualitas yang menghasilkan taraf keterbacaan yang tinggi pula. Pengalaman menunjukkan bahwa kebanyakan terjemahan teks dan tafsir Qur’an dalam bahasa Indonesia merupakan hasil kerja penerjemah yang tidak begitu menguasai bahasa sasaran, meskipun mungkin saja penguasaan atas bahasa sumber boleh diacungi dua jempol. Masalah penerjemahan tidak terutama terletak pada bahasa sumber tetapi pada bahasa sasaran.
Demikianlah, maka saya menerjemahkan semua Rangkuman yang jumlahnya 300 itu yang ada di sela-sela atau mengawali surah dan ayat yang diterjemahkan Ali Audah. Tidak pernah terbayangkan oleh saya sebelumnya hal semacam itu akan terjadi, dan ternyata memang terjadi hanya karena ada sosok yang sudah menjadi dongeng yang bernama Ali Audah.
Di samping belum pernah menerjemahkan 300 sajak sekaligus, saya juga belum pernah – dan tidak akan pernah – membayangkan hal serupa akan terjadi lagi.
Saya ingin menutup tulisan ringkas ini dengan mengutip dua R lagi, yakni R.30 dan R.300.
R.30
“Iqra!” – yang kalau ditafsirkan bisa menjadi
“Baca!” atau “Umumkan!” atau “Nyanyikan!”
Rasul yang ummi itu pun bingung:
Ia tidak bisa membaca. Malaikat itu serasa
Mendekapnya di dada dalam pelukan ketat,
Dan suaranya nyaring terdengar “Iqra!”
Begitulah sampai tiga kali; sampai
Pesona yang tadi menguasainya membuatnya
Mampu memahami kata-kata yang menjelaskan
Pesan-Nya; Pengarangnya, Allah Sang Pencipta,
Isinya, Manusia, karya cipta Allah yang mengagumkan,
Yang mampu, dengan anugerah-Nya, naik ke ketinggian mulia;
Dan alat pesan itu, Kalam Suci,
Dan Bacaan Suci, Anugerah Allah,
Yang oleh manusia dibaca, atau ditulis, atau dipelajari,
Atau disimpan dalam jiwanya.
R.300
Begitulah kita harus melaksanakan tugas Persaudaraan,-
Dengan berjalan rendah hati, berdampingan,
Di Jalan Allah,
Saling membantu,
Dan berdoa sepenuh hati,
Serta bertindak,
Sehingga maksud baik Allah
Bisa terlaksana
Dalam diri kita semua!
Apa pun hasil yang saya capai dalam upaya menerjemahkan Ali Audah ke dalam tulisan moga-moga dianggap tidak saja sebagai ungkapan rasa terima kasih yang tulus terhadap keindahan dan ketulusan jiwanya, tetapi juga sebagai pengakuan bahwa sosok itu memang dongeng yang pantas menjadi teladan bagi siapa pun yang mempunyai niat untuk menjadi manusia sebenar-benar manusia. Aamiin. [ ]
Almarhum Sapardi Djoko Damono, semasa hidup di samping mengajar di beberapa sekolah pascasarjana, pensiunan Guru Besar UI ini menghabiskan waktunya dengan menulis buku puisi, fiksi, dan esai.