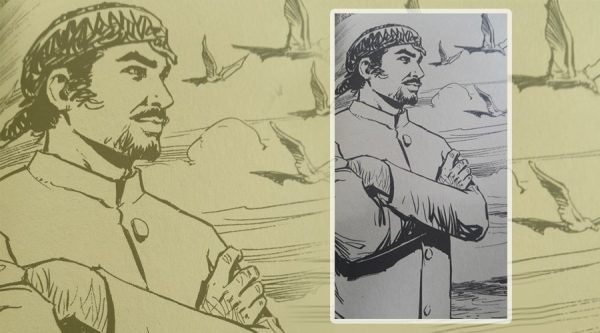“Camkan wahai prajurit Sunda, leluhur kita yang perlaya di Tanah Bubat adalah nenek moyang yang memegang teguh amanah, yang menjaga nama baik Sunda. Jadi, kita semua berangkat maju jurit untuk menegakkan kebenaran. Kita maju jurit karena percaya bahwa menjaga martabat diri dan kedaulatan negeri adalah salah satu titah Ilahi!”
Oleh : Darmawan Sepriyossa
Pengantar:
Setelah jatuhnya Kerajaan Majapahit, ratusan tahun kemudian kerajaan-kerajaan taklukan di seluruh Nusantara bangkit memupuk kekuatan. Yang paling mencorong adalah Kerajaan Mataram, pengklaim pewaris kekuasaan Majapahit. Sementara kekuatan asing yakni Portugis, Belanda dan Inggris, mulai pula datang menancapkan kuku kekuasaan mereka. Masing-masing dengan kerakusan dan kekejamannya sendiri. Pada saat itu, di Tanah Sunda muncul kekuatan yang mencoba menolak penjajahan, dipimpin seorang bernama Dipati Ukur.—
Episode-18
Tumenggung Bahureksa baru mendapatkan posisi baik dalam tata hirarki keraton setelah sukses melaksanakan perintah Mataram sebelumnya untuk membuat bendungan Kali Sambong dan membuka hutan Gambiran yang teramat lebat menjadi pedukuhan yang ramai. Dukuh itu kemudian diberi nama Pekalongan, dari kata ‘tapa kalong’ yang ia lakukan seiring melaksanakan tugas tersebut.
“Ki Mangunrejo!” teriaknya memanggil orang kepercayaannya. “Cari 30 perahu lagi. Cari juga orang-orang. Rekrut mereka, kasih senjata. Kita memerlukan banyak orang untuk tugas ini, atau kepalaku dan kepalamu yang jadi taruhannya.”
“Sendika, Gusti,” kata orang yang dipanggil Mangunrejo itu, khidmat. “Izinkan hamba melaporkan persedian bahan makanan yang bisa kita bawa.”
“Ya, monggo.”
Ki Mangunrejo langsung melaporkan bahwa meski kapal belum cukup, perbekalan untuk serangan ke Batavia sudah mampu mencukupi keperluan dapur umum.
“Di gudang telah ada 130 ekor kerbau dan kambing, 3.600 liter beras, 10.600 ikat padi, 26 ribu butir kelapa dan 5.900 batang gula merah, Gusti.”
“Bagus, kerjamu,” kata Tumenggung Bahureksa. “Kini tinggal dengan cara apa pun kau cari perahu. Kalau pemiliknya menolak, kau takut-takutilah. Bikin dia takut seperti ketakutan yang terus berada di punggungmu karena ancaman potong kepala dari Kanjeng Sinuhun.”
“Sendika, Gusti Tumenggung!” kata Mangunrejo. Kini dia merasa bulat sudah. Kalau para tengkulak di pelabuhan itu menolak meminjamkan perahu mereka, apa boleh buat. Dia tak ingin kepalanya sendiri menggelinding ke jalanan hanya karena dianggap gagal menjalankan perintah Kanjeng Sultan.
***
Untuk penyerangan itu Dipati Ukur memerintahkan mobilisasi umum di seluruh Tatar Ukur dan Kawedanan Sumedang. Dimintanya Ki Somahita menambah wadya bala Sindangkasih. Meski tak semengerikan tabiat Sultan Agung saat menggerakkan perang, Ukur mengancam akan menghukum Ki Somahita bila pada kedatangan pimpinan perangnya nanti hanya membawa tambahan beberapa ratus prajurit. Ki Somahita memang dilarangnya pulang, urusan menambah pasukan dibebankannya langsung kepada orang kepercayaan pimpinan Umbul Sindangkasih itu.
“Tinimbang hulu aing nu ngagulutuk, mending beuheung sia ku aing disapatkeun ayeuna-ayeuna. Daripada kepalaku yang menggelinding karena gagal, mendingan lehermu yang kutebas saat ini juga,” kata Ukur. Ki Somahita terlihat sangat ketakutan dengan teguran keras itu.
Sepekan kemudian pasukan tambahan dari Sindangkasih pun tiba. Hanya memberi waktu sehari untuk istirahat pasukan terakhir itu, esoknya pasukan Ukur-Sumedang pun dikumpulkan untuk segera berangkat menuju Karawang.
“Wahai wadya bala Sunda, camkan oleh kalian semua!” seru Ukur dari atas Si Sembrani, kuda yang sangat ia kasihi.
“Kita berangkat ke medan jurit, menyerang Batavia, bukan karena urusan dendam. Aku ingin setiap kalian para prajurit paham, kita prajurit Sunda, terah Pajajaran, selalu siap bertempur untuk menegakkan kewibawaan dan harga diri kita. Kita akan terus membuktikan bahwa putra-putra Pajajaran adalah laki-laki yang bisa dipercaya, para pria yang teguh memegang amanah. Kita tak mundur untuk berjalan jauh dan bertempur pada saatnya, bukan hanya karena kita bawahan Sinuhun Wetan. Kita bertempur bahu membahu, saling bantu dengan saudara di kiri-kanan kita karena dua hal: kita ingin menegakkan amanah dan kepercayaan yang ada di pundak kita para prajurit Sunda. Selain itu, menyingkirkan musuh-musuh kafir yang merongrong keamanan negara adalah tugas Allah Subhanahu wa Taala!”
Sorak-sorai para prajurit Sumedang-Ukur yang ribuan banyaknya itu membahana, memecah keheningan pagi Dayeuh Ukur yang serta merta ramai meski subuh baru saja beranjak pergi.
“Camkan wahai prajurit Sunda, kewibawaan seorang prajurit adalah menjaga nama baik leluhurnya. Leluhur kita yang perlaya di Tanah Bubat adalah nenek moyang kita yang memegang teguh amanah, yang menjaga nama baik Sunda. Jadi kalian para prajuritku sekalian, kalian tak pergi bertempur ke Batavia untuk kewibawaanku. Tak juga untuk kewibawaan Sultan Agung Raja Tatar Wetan. Kita semua berangkat maju jurit untuk menegakkan kebenaran, untuk mengusir para kafir yang jumawa menginjak-injak harga diri kita. Kita berangkat maju jurit karena percaya bahwa menjaga martabat diri dan kedaulatan negeri adalah salah satu titah Ilahi!”
Sorak-sorai kembali mengguntur, memecah pagi. Setiap komandan dan prajurit Sunda menanggapi perintah berangkat itu dengan semangat berkobar-kobar di dada.
Pada tanggal 4 bulan Agustus 1628, hampir delapan ribu prajurit gabungan Tatar Ukur-Sumedang bergerak meninggalkan Dayeuh Ukur. Kedelapan ribu prajurit itu berjalan beriringan, ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut, ngembat-ngembat nyatang pinang alias berkelompok-kelompok dalam jumlah ribuan. Barisan itu berjalan dengan gemilang, laiknya gambaran yang Ukur baca pada lontar-lontar dari risalah kuno.
Sepanjang jalan pasukan itu bertambah dengan bergabungnya para pemuda desa yang iri melihat kawan-kawannya dari desa dan kaumbulan lain berbaris bersama, maju jurit melawan Kompeni Walanda. Sampai dua ratusan orang pemuda yang bergabung di awal-awal masih kebagian tombak dan tameng. Tetapi setelah itu mereka benar-benar mengandalkan tombak dan golok yang mereka bawa sendiri dari rumah.
Ribuan pasukan Sumedang-Ukur itu berbaris empat-empat, mengular meliuk-liuk seiring topografi Tatar Sunda yang bergunung-gunung. Panjang barisan tersebut hingga mencapai kilometer, merawankan perasaan orang-orang yang melihatnya sepanjang jalan.
Tepat sebelum maghrib di hari kedua, mereka sudah melewati dataran tinggi Tangkuban Parahu, siap untuk berjalan menuruni pegunungan itu hingga Purwakarta. Di tempat itu Ukur menghentikan pasukannya. Tenda-tenda segera dibentang, para prajurit dapur umum sigap memasak nasi dan hidangan. Menu hari itu adalah nasi beras huma dan dendeng kijang yang digoreng dengan minyak kepala dari Galuh. Bergantian mereka melaksanakan shalat, dijamak langsung dengan shalat isya. Setelah itu baru para prajurit bergantian makan, menikmati ransum yang diberikan.
“Bermalam di atas gunung selalu memberiku kesan betapa kecilnya aku sebagai manusia,” kata Ukur. Ia berbicara kepada Ngabei Tarogong, teman yang selalu setia menemaninya. Malam itu mereka berdua ditemani serombongan kecil prajurit memeriksa kondisi para prajurit. Benar tadi selepas magrib para senapati datang dan melaporkan kondisi pasukan masing-masing.
Tetapi pimpinan yang baik tak bisa hanya menerima laporan tanpa mengeceknya kemudian. Itulah yang tengah Ukur lakukan, sekalian juga memompa semangat para prajurit yang ia tahu tak semua akan kembali ke rumah masing-masing bila perang memang terjadi.
Ukur tahu, kecil kemungkinan Sultan Agung akan menarik pasukan tanpa lebih dulu melancarkan peperangan. Sementara para serdadu kompeni yang berbekal peralatan perang lebih baik, kecil pula kemungkinan akan menyerah dan mempersembahkan kepala mereka tanpa perlawanan hingga titik darah terakhir.
“Iya, Rakanda. Sama seperti manakala kita mengarungi ombak, menebas samudera luas. Yang ada tak lain hanya rasa kecil dibanding kekuasaan Allah Sang Maha Pencipta Alam,” kata Ngabei Tarogong. “Mungkin untuk selalu sadar itu, kita harus sering-sering bermalam di gunung atau melayari samudera dan tidur dalam belai ombak.”
Ukur tersenyum. “Apa nama gunung kecil ini, Rayi? Kalau Tangkuban Parahu sih siapa yang tak tahu,” kata Ukur tersenyum. Cahaya unggun menerpa gigi geliginya, memperlihatkan susunan geligi yang tak hanya teratur rapi namun juga bersih berkilat. Ukur rajin menggunakan serabut oyong kering untuk menggosok giginya. Ia selalu terganggu dengan gigi geligi kuning kotor, disertai bau tak sedap yang selalu meruap dari mulut orang-orang wetan.
Tak semua memang, karena banyak bangsawan wetan dan para putrinya yang ia ketahui sangat berseka[1], bersih, wangi, tak jarang menggoda kelelakiannya. Keraton Mataram, menurut Ukur, adalah salah satu tempat dimana putri-putri cantik bertutur kata halus banyak berdiam. Sayang, yang terbaik selalu saja harus terlebih dulu dipetik penguasa tertinggi di sana.
“Seingat Rayi, gunung kecil ini belum punya nama, Rakanda,” jawab Ngabei Tarogong.
“Hm..sayang sekali tempat seindah ini dibiarkan tanpa nama,” kata Ukur, seolah humandeuar, mengeluh dalam monolog. “Elokkah kiranya kalau gunung kecil ini Kanda beri nama?” Ia kemudian bertanya.
“Tentu saja, Rakanda,” Sigap Ngabei Tarogong menjawab. “Nama adalah pemberian yang sangat berarti bagi setiap makhluk. Bohong bila ia tanpa arti. Katakanlah hal-hal yang buruk kepada hewan peliharaan kita, maka mereka akan bersedih, mungkin bisa sakit lalu mati. Sebaiknya, tutur kata kita yang halus akan membuat binatang ternak kita sehat, selalu bergembira dan memberikan bakti dengan apa yang mereka bisa.”
“Wah, benarkah itu Rayi?” tanya Ukur tertarik.
“Sepengalaman Rayi yang juga petani dan peternak ini, begitulah adanya, Rakanda.”
“Hm, Kanda akan ingat-ingat itu. Mungkin bila ada usia, Kanda ingin menerapkan ilmu itu kepada para petani dan peternak di wewengkon[2] Kanda. Oh ya, kembali ke soal gunung kecil ini, Kanda punya satu nama,” kata Ukur.
“Boleh Rayi tahu?” tanya Ngabei Tarogong penasaran.
“Ini juga sekadar usul. Coba Rayi pikirkan. Kanda ingin memberi nama gunung kecil ini Jayagiri. Giri artinya kita tahu, gunung. Jaya, artinya kejayaan, kegemilangan. Kanda ingin orang-orang memandang gunung ini pertanda kejayaan yang akan menyinari Tatar Sunda.”
“Duh, nama sekaligus harapan yang bagus Rakanda. Rayi setuju, dan tampaknya akan begitu pula pra prajurit semua. Bagaimana kalau nama itu Rayi umumkan?” tanya Ngabei Tarogong. Ukur hanya tersenyum sambil mengangkat tangan terbuka, menyilakan. Ngabei Tarogong langsung meminta peniup terompet membunyikan terompet, meminta perhatian semua.
Pada malam itulah gunung kecil di dekat Tangkuban Parahu itu punya nama. Jayagiri, menandai kehendak Ukur dan pasukan Sumedang-Ukur kepada Sang Pencipta, untuk senanrtiasa memberikan rahmat dan kebaikan kepada Tatar Sunda.
Pagi berikutnya, pasukan Sumedang-Ukur kembali bergerak. Dari Jayagiri mereka turun ke Subang, membelok ke kiri mengarah Purwakarta. Tepat tengah hari pada tiga hari berikutnya rombongan delapan ribu prajurit itu telah berada di tepian Dermaga Cimanuk, tempat kapal-kapal bertambat di Karawang.
Di situlah titik pertemuan pasukan Sumedang-Ukur yang dipimpin Dipati Ukur dengan pasukan Mataram. Pasukan yang lewat laut akan dipimpin Tumenggung Bahureksa. Sementara sebagaimana yang Ukur ketahui, ada pula ribuan pasukan darat dari Mataram yang juga direncanakan bergabung di sini. Ukur belum mendengar siapa yang akan memimpin pasukan darat. Yang pasti, komando tertinggi pasukan Mataram berada di tangan Tumenggung Bahureksa.
Persoalannya, siapa yang lebih tinggi dalam komando penyerangan itu di antara dia dan Bahureksa? Tak ada satu penjelasan pun dalam surat yang diterimanya tentang hal itu. Menilik pangkat, Tumenggung Bahureksa adalah Bupati Kendal, seorang bupati. Sementara dirinya saat ini adalah seorang wedana, pejabat yang mengatur beberapa bupati yang membawahi kabupaten.
Dengan kata lain, dari jenjang kepangkatan, Ukur lebih tinggi dari Bahureksa. Persoalannya, tentu saja tak setiap pangkat yang lebih tinggi harus selalu menjadi komando tertinggi di dalam peperangan. Hanya tentu saja, bila ada keterangan tertulis soal itu, itu jauh-jauh lebih baik daripada terjadinya kesimpangsiuran seperti yang tengah dihadapi Dipati Ukur.
“Dirikan
tenda, kita berkemah di sini, menunggu sampai para wadya bala Mataram datang.
Baru setelah itu kita menggempur Batavia bersama-sama,” kata Ukur kepada para
senapatinya. [bersambung]
[1] Mementingkan kebersihan (Kamus Sunda-Indonesia)
[2] wilayah