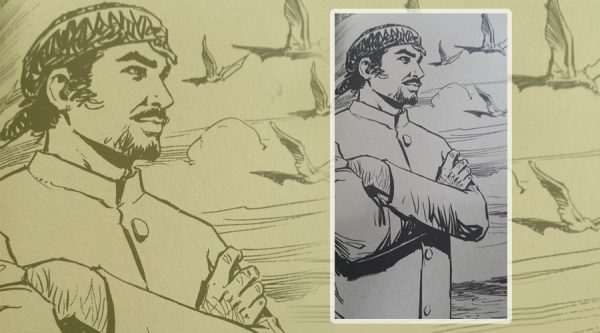Mahmuddin segera sadar, tak syak lagi, orang-orang Kompeni sudah mengetahui apa yang telah terjadi. Kepala pemimpin tertinggi mereka telah dipotong dan dicuri!
Oleh : Darmawan Sepriyossa
Pengantar:
Setelah jatuhnya Kerajaan Majapahit, ratusan tahun kemudian kerajaan-kerajaan taklukan di seluruh Nusantara bangkit memupuk kekuatan. Yang paling mencorong adalah Kerajaan Mataram, pengklaim pewaris kekuasaan Majapahit. Sementara kekuatan asing yakni Portugis, Belanda dan Inggris, mulai pula datang menancapkan kuku kekuasaan mereka. Masing-masing dengan kerakusan dan kekejamannya sendiri. Pada saat itu, di Tanah Sunda muncul kekuatan yang mencoba menolak penjajahan, dipimpin seorang bernama Dipati Ukur.—
Episode-33
Nyimas Utari segera meraih keranjang rotan yang biasa dipakai Eva Ment untuk berbelanja. Ukurannya cukup besar. Lalu dari tumpukan kain hasil seterikaan yang ada di kamar itu dengan tergesa diambilnya dua lembar kain jarit. Kanjut kundang berisi kepala Jenderal Coen itu dibungkus lagi dengan dua lembar kain jarit sebelum dimasukkan ke dalam keranjang. Setidaknya kini kanjut kundang itu tak lagi menetes-neteskan darah.
“Mari Nyai, kita tak punya banyak waktu!” kata Mahmuddin. Ditariknya lengan istrinya agar segera menyingkir dari kamar, dari rumah besar Gubernur Jenderal Coen, dan dari Benteng Batavia itu. Nyimas Utari segera menyambar keranjang, membawanya setenang dan seelegan mungkin, sebelum keluar kamar.
Di pintu kamar, kedua suami-istri itu hanya melempar senyum kepada kedua orang serdadu yang menjaga.
“Nyonya Besar minta tidak diganggu dulu barang satu jam,” katanya. “Nyonya sangat sedih.”
Cepat dirogohnya lima kepeng perak dari balik kebayanya, dan memberikannya kepada salah seorang penjaga. Wajah serdadu itu terlihat bungah melihat kepeng-kepeng perak yang segera berpindah ke tangannya. Tak hentinya ia mengucapkan terima kasih.
“Buat berdua, ya!” katanya, sambil berharap para penjaga itu tak menaruh perhatian kepada keranjang yang dibawa serta tidak rapinya kain yang ia kenakan. Kain itu memang sengaja dipakai begitu rupa, agar bila terjadi apa-apa dengan gampang ditarik ke atas untuk dibelitkan melingkari pinggang. Nyimas Utari sendiri sudah memakai seruwal setinggi betis kakinya di balik kain jarit yang ia kenakan.
Kedua suami-istri itu masih mendengar ucapan terima kasih kedua serdadu penjaga tersebut saat mereka berada di ruang tamu, untuk kemudian mencapai pintu masuk. Saat Mahmuddin membuka pintu keluar, segera dilihatnya dua serdadu penjaga pintu masuk melakukan sikap sempurna.
“Kami akan kembali pada saat Tuan Besar dikebumikan,”kata Nyimas Utari kepada penjaga. Di sini ia juga mengobral kepeng peraknya. Selalu Nyimas Utari yang menyapa penjaga dan para penghuni benteng lainnya, karena memang dia yang lebih dikenal para penghuni benteng. Sebagaimana penjaga pintu kamar, kedua serdadu penjaga pintu masuk itu pun tak hanya sekali mengucapkan terima kasih mereka.
Kini keduanya telah berada di halaman, mencari kereta kuda yang mereka pergunakan pada saat datang.
“Celaka, Nyai,” kata Mahmuddin berbisik. “Delman kita tampaknya dibawa ke istal, karena mereka tahu kita akan berlama-lama berkunjung.” Suara Mahmuddin terdengar berat, penuh kekhawatiran. Saat datang memang ia mengendarai sendiri kereta kuda itu, sengaja tak membawa sais agar tak merepotkan bila terjadi sesuatu. Kini yang terjadi bahkan sebaliknya, tak membawa saislah yang justru menjadi penyebab delman mereka dibawa ke istal. Ada kemungkinan perangkat kudanya pun dibuka dan kedua kuda itu dikandangkan. Jelas tak mungkin mereka memakaikan dulu perangkat kuda itu.
“Ambil saja kudanya, kita kendarai seorang satu,” kata Mahmuddin. “Atau kalau terpaksa, ambil saja kuda mana pun yang sudah siap ditunggangi.”
Nyimas Utari melirik suaminya. Sebagai seorang telik sandi, ia tahu kekuatiran serta apa yang terlintas di benak suaminya. Ia hanya mengangguk.
Di istal kebetulan yang dijumpai Nyimas Utari adalah perawat kuda yang telah dikenalnya dengan baik. Bukanlah seorang telik sandi bila Nyimas Utari tak mampu mengarang cerita yang intinya mereka berdua meminjam kuda karena harus segera pulang ke rumah, membawa keperluan untuk pemakaman Gubernur Jenderal Coen.
“Kuda yang mana saja, Yat, asalkan kuat dan segar,”jawab Nyimas Utari manakala Dayat, perawat kuda itu, bertanya.
Karena diminta cepat, Dayat pun segera membawa seekor kuda tinggi besar berbulu hitam mengkilat. Tampaknya hasil pengembangbiakan kuda lokal dengan kuda luar yang dibawa kapal-kapal Kompeni dari negeri-negeri tempat mereka ‘berdagang’.
“Satunya nyang onoh, Nyimas!” katanya sambil menunjuk seekor kuda serupa, hanya warnanya cokelat kekuningan. Mahmuddin dengan sigap mendatangi kuda tersebut.
Nyimas Utari masih sempat memberi perawat kuda itu dua keeping mata uang perak, saat Dayat melihat keranjang yang dibawa Utari dan memperhatikannya dengan seksama.
“Apa se itu, Nyimas?” katanya heran. “Emang Nyonyah Besar ngasih daging ya, sampai netes-netes begitu …”
Dasar orang yang merasa berdosa. Padahal keingintahuan Dayat itu gampang saja dijawab asal dan seenaknya oleh Nyimas Utari. Bahkan, diiyakan pun pengurus kuda itu sudah akan puas. Tetapi kondisi kejiwaan seorang yang melakukan perbuatan tercela tetap saja tak senormal keadaan biasa. Ucapan Dayat dirasa Nyimas Utari membuka perbuatan yang mereka lakukan, sekaligus membongkar kedok penyamaran keduanya.
Alhasil, baru saja mulut penjaga kuda sok mau tahu itu terkatup, sebuah pukulan telak menghajar pelipisnya, membuat Dayat segera pingsan tak sadarkan diri.
“Ayo, Kakanda!” teriak Nyimas Utari. Sejurus kemudian, dengan satu lompatan dirinya sudah berada di punggung kuda. Kini keranjang itu tak lagi dibawanya. Kanjut kundang berisikan kepala Jenderal Coen itu sudah terikat erat oleh kain jarit yang digunakan untuk membungkus karung tersebut di pinggang Nyimas Utari. Dengan sebuah sentakan pada kendali, kuda yang ditungganginya melompat berlari meninggalkan istal.
Mahmuddin tak punya pilihan lain kecuali segera mencongklang kuda cokelat kekuningan tersebut. Kuda itu sempat menolak. Namun saat itu Mahmuddin menunjukkan kualitasnya sebagai telik sandi pilihan. Dipeluknya leher kuda tersebut, dielus-elusnya surainya, sambil dirayunya untuk segera berlari cepat. Berhasil, kuda itu segera lari mengejar Nyimas Utari yang sudah terlihat jauh meninggalkan mereka menuju pintu benteng.
Pada saat Mahmuddin meninggalkan pintu kandang, dilihatnya beberapa serdadu berlarian masuk ke dalam rumah besar Gubernur Jenderal. Mahmuddin segera sadar, tak syak lagi, orang-orang Kompeni sudah mengetahui apa yang telah terjadi. Kepala pemimpin tertinggi mereka telah dipotong dan dicuri! Mereka pun pasti tahu, dia dan istrinya yang paling mungkin melakukan itu.
“Godverdomme!”
“Kejar suami-istri keparat itu!”
“Tembak mereka!”
Terdengar banyak teriakan di belakang langkah kuda Mahmuddin yang menderap cepat menuju gerbang benteng. Mahmuddin tahu, ia harus sudah keluar gerbang benteng sebelum satu pun bedil atau pistol para serdadu Kompeni itu meletus. Atau lengking terompet tanda kesiap-siagaan dibunyikan. Letusan senjata api dalam benteng akan membuat penjaga gerbang curiga dan waspada. Sementara bunyi terompet jelas-jelas pengumuman adanya suatu kejadian terjadi dalam benteng. Besar kemungkinan gerbang benteng tak akan dibuka. Kalau itu terjadi, ia dan istrinya akan mati sia-sia di sini!
Sambil tetap memacu kudanya sekencang mungkin, Mahmuddin melihat istrinya sudah berada di muka gerbang, tengah berbicara kepada dua orang penjaga. Seorang di antaranya sedang membuka gerbang, yang mulai mengeluarkan suara berderit panjang. Dari jarak sekitar 20-an meter ia melihat resep terbaik istrinya kembali dilakukan: membagikan kepeng perak untuk penjaga gerbang tersebut. Ah, syukurlah, ia melihat kuda istrinya sudah setengah badan keluar dari gerbang benteng.
Mahmuddin belum melakukan apa pun untuk mengendorkan lari kudanya. Ia masih berpacu dengan bunyi letusan senjata api yang lepaskan, atau lengking terompet yang mungkin ditiup serdadu Kompeni penjaga rumah besar Gubernur Jenderal untuk meminta perhatian seluruh penghuni benteng. Benar, saat pantat kuda istrinya sudah tak lagi terlihat, terhalang gerbang yang dibuka seperempat normal, pada jarak sekitar 10 meter dari gerbang, Mahmuddin mendengar suara terompet melengking panjang. Ia tahu, dan bahkan melihat, penjaga gerbang tersentak. Kedua orang itu siap untuk menutup gerbang secepatnya, apa pun yang terjadi di dalam benteng. Itulah aturan baku yang mereka tahu. Terompet kewaspadaan artinya menutup gerbang, apa pun yang terjadi, akan mereka ketahui nanti.
Refleks tangan kanan Mahmuddin mencabut keris yang terselip di pinggangnya. Tangan kirinya erat memegang tali kendali. Kaget dengan kedatangan Mahmuddin yang kini tinggal berada dua meter dari mereka, kedua penjaga gerbang melepaskan tangan mereka dari pintu gerbang benteng. Seorang cepat meraih tombak yang tersandar di dinding benteng, sementara seorang lain menarik flintlock dari pinggang dan segera memasukkan mesiu ke dalamnya dengan tergesa.
Mahmuddin tak kalah tergesa, tak kalah kuatir, bahkan nyaris ketakutan. Teriakan para serdadu sekitar 100-an meter di belakangnya mulai ramai terdengar, disusul bunyi letusan bedil yang untung saja luput mengenai dirinya. Peluru itu menghajar pintu gerbang benteng di depannya. Entahlah kalau nanti ada tembakan kedua, ketiga dan seterusnya, dilepaskan seorang serdadu yang lebih tenang, mengokang dengan rileks tak tergesa, tidak dalam posisi berlari mengejarnya, melainkan setengah berjongkok dengan satu lutut bertumpu ke tanah sementara kaki lain menapak wajar, memberikan peluang bidikan yang kukuh tanpa goyang.
Menghindari kemungkinan besar menubruk gerbang, Mahmuddin menyentak tali kekang, membuat kudanya mengurangi kecepatan. Namun tak lama, hanya dua tiga langkah kemudian, dengan cepat disentaknya lagi tali kekang, kali ini untuk menerjang kedua penjaga yang bersiap untuk menyerangnya. Dengan kaki kiri disepaknya penjaga yang memegang tombak sampai terjengkang. Punggung serdadu itu keras membentur tembok benteng dan membuatnya mengaduh kesakitan. Tombak yang dipegangnya terlepas, sementara tubuhnya menggelosoh di tanah.
Mahmuddin tak punya waktu untuk memperhatikan lebih lanjut nasib serdadu tersebut. Lirikan matanya menyaksikan serdadu berpistol flintlock di sebelah kanannya nyaris selesai memadatkan butiran peluru dengan kawat besi kecil, siap untuk membidikkan pistol itu ke arahnya. Sebelum picu pistol yang kini terarah ke dadanya itu ditarik, dengan menjatuhkan badan ke arah kanan namun kedua kaki erat bertumpu di sanggurdi, Mahmuddin menyabetkan kerisnya membabat leher si serdadu. Terdengar suara mengorok diiringi semburan darah yang memancar kuat dari leher yang tersobek itu.
Kini Mahmuddin harus membuat kudanya berjalan lebih pelan, keluar dari celah gerbang. Saat keluar di lihatnya istrinya sekitar 50 meter di depan, menunggu di punggung kudanya. Tampak kekuatiran membayang kuat di wajahnya.
“Lari! Cepat keluar dari jarak tembak bedil dan meriam!” teriak Mahmuddin, sambil memacu kudanya mengejar Nyimas Utari. Istrinya yang tampak bahagia melihat Mahmuddin sudah berada di luar benteng, segera ikut memacu kudanya, menjauh dari benteng.
“Serong kiri, kita harus menuju pasukan Tumenggung Surotani. Yang lain bisa mengira kita bagian dari pasukan Kompeni!” teriak Mahmuddin.
Nyimas Utari tampaknya jelas mendengar perintahnya, karena kudanya kemudian berlari menyerong ke arah yang diminta Mahmuddin.
“Tar!”
“Tar!”
Terdengar beberapa tembakan dari arah pungggung kedua suami-istri itu. Tampaknya para serdadu Kompeni yang berlarian mengejar mereka sudah sampai di gerbang benteng, keluar dan menghujani mereka dengan tembakan bedil.
Kedua suami istri itu makin mempercepat lari kuda-kuda mereka. Tak sampai dua puluh menit kemudian keduanya sudah sampai di basis pertahanan pasukan Mataram. Saat turun dari kuda, keduanya sudah dikepung pasukan Mataram. Sekian banyak moncong bedil tertuju kepada mereka, demikian pula mata-mata tombak.
“Kami ingin bertemu Kanjeng Tumenggung Surotani. Kami berdua telik sandi anggota ‘Dom Sumuruping Mbanyu’,” kata Mahmuddin. Dikeluarkannya sebilah logam berukir dengan gambar relief tertentu, lalu diacungkannya tinggi-tinggi. Meski mungkin tak banyak yang mengerti arti bilah logam tersebut, hal itu membuat wadya pasukan Mataram terdiam. Baru sejurus kemudian seseorang berteriak agar memberitahukan hal itu kepada Tumenggung Surotani.
Posisi dikepung itu berlangsung beberapa saat, sebelum kemudian dari arah pasukan datang seseorang yang membuat para pengepung tersibak. Tumenggung Surotani sendiri yang datang.
“Oooh, Wong Agung Aceh dan Nyimas Utari,” katanya dengan wajah sumringah. “Senang melihat kalian berdua.” Kedua tangannya terkembang, mengisyaratkan penerimaan.
Namun, baru saja Mahmuddin hendak menyalami, tiba-tiba istrinya terjatuh dalam posisi telungkup. Segera terlihat bahwa pundak kanannya berlubang dengan darah berceceran. Entah mengapa, hal itu tadi luput dari perhatian Mahmuddin.
“Ya Allah!” kata Mahmuddin, kaget. Segera diraihnya tubuh Nyimas Utari, diletakkannya kepala sang istri di pangkuannya. Sementara para prajurit segera berlari dan membawakan mereka seorang tabib.
“Saya tak menyangka Nyimas kena tembakan musuh…” kata Mahmuddin, tercekat. Istrinya tak menjawab, hanya tersenyum. Artinya, sebagai seorang wanita ia wanita yang hebat, mampu tetap sadar dalam kondisi luka seperti itu.
“Rayi Wong Agung, biarlah istrimu dirawat oleh Ki Tabib. Insya Allah, semoga saja pelurunya tak terlalu dalam agar bisa dikeluarkan. Kalau pelurunya bisa diambil, seharusnya istri Rayi akan baik-baik saja. Tinggal sabar dalam perawatan,” kata Tumenggung Surotani.
Mahmuddin sadar, memang itulah yang terbaik. Kepala Jenderal Coen kemudian diberikannya kepada Tumenggung Surotani, untuk diserahkan kepada mertuanya, Bagus Wonoboyo. Pimpinan Dom itu sendiri ternyata sudah berada di sebuah gorap di sebuah dermaga tersembunyi di salah satu pantai Jakatra. Konon, manakala kepala itu ia terima, dimintanya anak buahnya merebus air garam pekat dan sebuah guci besar. Setelah dingin, kepala itu pun dimasukkan ke dalamnya, dibawa lewat laut untuk diberikan kepada Susuhunan Kanjeng Sultan Agung di Kartasura. Itulah yang membuat kepala itu tak hanya utuh sampai ke tangan Sultan Agung, melainkan sudah tak lagi berbau.
Nyimas Utari dan suami tak lama berada di basis pertahanan Mataram. Tumenggung Surotani mengizinkan tabibnya itu ikut kedua suami istri itu pulang ke Kampung Keramat, suatu tempat jauh di selatan Jakatra. Konon, lebih ke selatan lagi tempat itu dekat dengan bekas ibukota kerajaan lama Padjadjaran. Perlu satu setengah hari perjalanan kereta kuda—lebih karena kereta itu bermuatan seorang yang sakit parah, untuk sampai di Kampung Keramat. Esoknya, tabib membuka balutan luka yang ditutupnya dengan borehan berbagai daun dan akar itu. Borehan yang memungkinkan Nyimas Utari tak menderita gangrene yang parah akibat lukanya. Dengan keahlian tabib tersebut, dan keberanian dan kekuatan Nyimas Utari untuk menahan sakit yang teramat sangat, peluru itu pun bisa dikeluarkan. Bentuknya logam bulat berbahan timah, yang begitu menembus tubuh ia terpecah. Tabib itu punya kebiasaan yang diyakininya harus dilakukan usai membedah tubuh orang. Setelah peluru dikeluarkan dan luka dibersihkan dengan air hangat-hangat kuku yang sebelumnya direbus hingga mendidih, sang tabib membaluri luka dan sekelilingnya dengan minyak jarak. Lalu, setelah meminta Nyimas Utari menahan sakit, dibakarnya minyak jarak itu sehingga membakar luka dan sekelingnya seketika. Ia membiarkan api berkobar beberapa lama sebelum memadamkannya. Baru setelah itu luka itu diberinya borehan lain dari kaar dan daun, sebelum kembali membalutnya. Dua pekan kemudian, Nyimas Utari pun sembuh, meski pundaknya kini memiliki semacam cap, sisa-sisa luka akibat tembakan Kompeni.
Kepala Jenderal Coen ternyata punya khasiat juga. Setidaknya kepala yang lepas dari lehernya itu bisa membuat kangjeng Sultan mendengar kata-kata Ki Juru Mertani untuk menyudahi serangan.
Pada tanggal 2 Oktober 1629, Kompeni mencatat sebagai saat-saat pertama pasukan Mataram membongkar perlengkapan. Meriam, peralatan-peralatan bantuan perang pun mereka bereskan. Secara bergiliran, selama enam hari, pasukan Mataram pun pulang kembali ke Kartasura. Orang-orang Mataram terlihat senang, meski kondisi mereka menyedihkan karena terlalu banyak orang yang sakit, meninggal atau kelaparan. Sebagian anggota pasukan malah sudah melakukan desersi, kabur sejak beberapa pekan sebelumnya akibat kelaparan.
Pada
7 Oktober 1629, Kompeni mencatat seluruh wadya bala Mataram sudah meninggalkan
Jakatra[1].
[bersambung]
[1] Dagh Register 15 Desember 1629