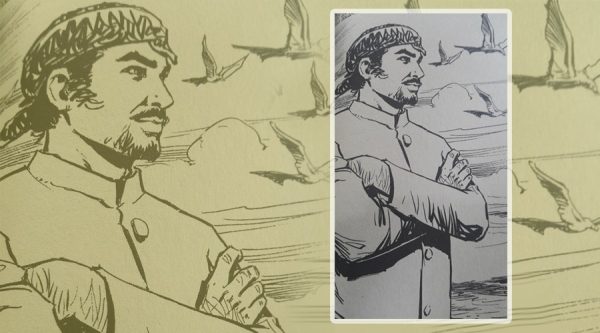Ingin rasanya ia beradu kekuatan mata dengan raja Mataram itu. Tak cukup banyak rasa hormat yang membuatnya bisa menghargai raja tersebut. Di matanya Sultan Agung hanyalah semacam anak kecil yang setiap permintaannya harus diluluskan, tak penting berapa ongkos harus dibayar untuk itu, bahkan bila ongkos itu artinya ribuan kepala lepas dari lehernya, alias sekian banyak darah dan kematian.
Oleh : Darmawan Sepriyossa
Pengantar:
Setelah jatuhnya Kerajaan Majapahit, ratusan tahun kemudian kerajaan-kerajaan taklukan di seluruh Nusantara bangkit memupuk kekuatan. Yang paling mencorong adalah Kerajaan Mataram, pengklaim pewaris kekuasaan Majapahit. Sementara kekuatan asing yakni Portugis, Belanda dan Inggris, mulai pula datang menancapkan kuku kekuasaan mereka. Masing-masing dengan kerakusan dan kekejamannya sendiri. Pada saat itu, di Tanah Sunda muncul kekuatan yang mencoba menolak penjajahan, dipimpin seorang bernama Dipati Ukur.—
Episode-7
Ia sempat sarapan sedikit nasi yang digoreng dengan minyak kelapa. Ada sejumput bubuk rebon yang diletakkan emban dapur di sisi piring gerabahnya, selain sepotong besar daging kerbau. Si emban bilang itu adalah daging kerbau yang ia taklukan kemarin dulu. Sempat Ukur tak hendak memakan daging itu. Tapi ia sadar, memakan dagingnya mungkin justru merupakan penghargaan tersendiri buat kerbau yang jiwanya kini telah berada di alam baka itu.
Di Balairung Ukur duduk menekur dengan khidmad, menunggu kedatangan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Sang Narendra Agung Mataram. Di sebelahnya duduk dengan posisi sama penguasa Sumedang Larang yang sebentar lagi hatur sembah bongkokan, Raden Aria Suradiwangsa.
Tadi keduanya sempat bertegur sapa dengan basa Sunda, membuat sebagian hulubalang menoleh ke arah mereka dengan pandangan tak suka. Ukur seolah tak tahu aturan, tak mengacuhkan mereka. Tapi obrolannya memang bukan pembicaraan yang dalam, hanya basa basi biasa.
Ia juga melihat roman muka Sang Pangeran Sumedang itu tak terlalu berag. Sepertinya ada beban besar yang menghimpit dadanya. Ukur mengerti, tentu susah juga anak muda seperti dia datang menyerah kalah dan melupakan harkat serta wibawa. Ia merasa pikirannya semalam tentang Aria Suradiwangsa salah.
Tiba-tiba berteriaklah Abdi Dalem Keparak Kiwa, menyatakan bahwa Sinuhun segera memasuki Balairung. Dua orang abdi dalem dari kesatuan tersebut segera mendekati Dhampar Palenggahan Dalem atau singgasana raja, memastikan tempat itu bersih, dan terutama aman. Mereka segera kembali ke tempat masing-masing setelah semua kelar.
Lalu masuklah Sang Narendra ke bangsal besar itu. Ia memakai pakaian kebesaran berwarna hitam dan berkain batik motif Garuda Ageng yang hanya boleh dipakai dirinya sebagai raja, putra mahkota dan permaisuri.
Celana serawal hitam yang serasi dengan baju dan kain itu, memperlihatkan mata kakinya. Selop kulit berhiaskan manik-manik yang gemerlap dengan warna emas dan perak menutup kedua kakinya. Meski di dalam Balairung, seorang abdi setia mengikutinya dengan membentang payung.
“Oooh, inikah Raja Mataram dalam pakaian kebesarannya itu?” kata Ukur membatin. Meski cenderung tunduk sebagaimana tata krama keraton, ia masih menyempatkan diri menolehkan matanya kanan-kiri, menyaksikan pemandangan yang baru dialaminya. Diam-diam Ukur merasa dirinya memang seorang udik. Urang kampung bau lisung.
Kini Ukur mengerti betapa rakyat Mataram sangat mengkultuskan orang yang tengah lewat di hadapannya menuju singgasana itu. Raja ini disebut-sebut sakti mandraguna, totosaning bojana kulit, ganti sukma kandange dewa. Ora tedhas tapak palu ning pandhe pula, alias kebal senjata.
Raja ini disebut-sebut setiap subuh selalu berolah raga loncat dari gunung ke gunung. Dari Gunung Lawu ia meloncat ke Gunung Merapi, lalu lompat ke Gunung Mahameru untuk melihat kondisi rakyatnya di sana. Baru setelah itu ia menuju keraton menemui keluarga atau para tetamunya.
Ukur juga mendengar sang Sultan kadang-kadang meloncat ke negeri Cina untuk makan bebek panggang di siang hari. Sorenya ia terbang ke Turki karena ingin makan lokum alias kue-kue manis dari Turki. “Mungkin juga ia datang ke Koryo hanya untuk mencicip kimchi,” kembali Ukur membatin. Sempat ia sendiri tersenyum dengan pikirannya itu, tapi segera sadar sebelum tawanya ikut bunyi.
Ukur memang mendengar semacam dongeng yang akrab di antara warga Mataram bahwa Sultan sempat bertemu Sunan Kalijaga. Oh ya, bahkan dengan Imam Syafii juga. Pertemuan dengan Sunan Kalijaga kabarnya terjadi di Gunung Muria, sementara dengan Imam Syafii langsung di Mekkah manakala Sultan bersembahyang Jumat di sana.
Tentu saja Ukur nyaris tertawa mendengarnya. Kalau tidak karena pertimbangan sopan santun, ingin rasanya ia terbahak. Bagaimana tidak. Kalau menilik usia, tak mungkin Sultan yang masih hidup pada tahun ini, 1620, bisa bertemu Sang Sunan yang lahir pada sekitar 1450 tahun Masehi, alias berjarak 170 tahun itu. Apalah lagi ia bertemu dengan Imam Syafii yang hidup di tahun-tahun awal abad ke-8 Masehi!
Kini Sultan Agung sudah duduk di singgasananya. Sebelum berbicara, ia layangkan pandangannya menyapu seluruh ruangan. Pas giliran pandangannya tertumbuk pada Ukur dan Pangeran Aria Suradiwangsa, ia berhenti agak lama.
Ukur sempat bertatap mata dengan Sultan. Ingin rasanya ia beradu kekuatan mata dengan raja Mataram itu. Tak cukup banyak rasa hormat yang membuatnya bisa menghargai raja tersebut. Di matanya Sultan Agung hanyalah semacam anak kecil yang setiap permintaannya harus diluluskan, tak penting berapa ongkos harus dibayar untuk itu, bahkan bila ongkos itu artinya ribuan kepala lepas dari lehernya, alias sekian banyak darah dan kematian.
Sayang, sekian banyak kepentingan membuat Ukur sadar ia harus tunduk, paling tidak menundukkan kepala kepada Sinuhun.
“Hm, Kau Bekel Ukur, kan?” kata Sinuhun. “Apa kabarmu? Sudah kerasankah tinggal di keraton Mataram ini?”
Senyum mengembang di bibirnya. Ah, andai saja raja ini lebih banyak tersenyum dibanding memberi perintah perang, Ukur merasa dirinya layak, bahkan wajib berbakti hingga mengorbankan nyawanya sendiri untuk raja ini. Sayangnya, raja ini lebih suka memperluas wilayah, melebarkan kekuasaan yang lebih sering justru tak hanya membuat rakyat wilayah jajahannya sengsara, tetapi begitu juga dengan rakyatnya sendiri. Memangnya perang tak banyak makan biaya?
“Sendika, Gusti Prabu. Bekel Ukur sehat, tambah gemuk dan nyaman tinggal di sini. Tentu itu hanya mungkin bila hamba kerasan, Tuanku,” Ukur menjawab setelah sebelumnya bersikap sembah.
“Ho ho, baguslah. Kau harus kerasan, karena ke depan aku akan banyak mengandalkan dirimu, Ukur,” kata Sultan.
“Hinggih, Gusti Prabu.”
Lalu Sultan Agung memulai pembicaraan serius dan resmi. Tampaknya pembicaraan awal soal penyerahan diri Kerajaan Sumedang Larang sudah dibicarakan sebelumnya. Semalam atau mungkin lebih awal lagi. Kini Sultan lebih banyak bicara soal posisi Sumedang Larang dalam kekuasaan Mataram ke depan. Dengan penyerahan diri itu otomatis Sumedang tak lagi sebuah kerajaan sehingga Pangeran Aria Suradiwangsa pun tentu tak lagi berkedudukan sebagai raja.
“Raden Aria, mulai hari ini Adinda kula angkat sebagai wedana Kawedanan Sumedang Larang, mengepalai beberapa bupati di Tanah Sunda. Bupati Sindang Kasih, Bupati Sukabumi, Bupati Bandung, Bupati Cianjur, berada di bawah kendali Adinda,” kata Sultan.
“Sendika, Sinuhun,” kata Pangeran Aria Suradiwangsa, tegas.
“Mulai hari ini Adinda juga kuberi gelar Pangeran Dipati Rangga Gempol Kusumadinata atau Rangga Gempol I,” Sang Sinuhun melanjutkan.
“Beribu terima kasih, Gusti Prabu.”
Kalimat-kalimat itu saja yang diulang-ulang Aria Suradiwangsa, yang kini telah berganti nama menjadi Dipati Rangga Gempol Kusumadinata. Setelah pernyataan takluk itu kini statusnya turun menjadi sekadar Wedana, bukan Raja Kerajaan Sumedang Larang yang kini juga telah hilang. Pernyataan serah bongkokan itu tercatat dilakukan tahun 1620 Masehi[1].
“Sekarang untukmu, Bekel Ukur,” kata Sultan. “Mulai hari ini kau kuangkat sebagai Adipati Tanah Praiangan, mencakup wilayah Sukakerta, Sindangkasih, Indihiang, Bandung, Sukapura, Parakanmuncang, Galuh dan Cianjur,”kata Sultan. Sinuhun diam sejenak, seperti hendak mengetahui apa respons Ukur terhadap karunia yang barusan ia berikan.
Ukur yang sadar akan hal itu langsung bangkit dan berlutut melakukan tepak deku. Satu lutut menyentuh lantai, sementara lutut lainnya sejajar dengan pahanya. Sementara itu kedua telapak tangannya terbuka, bersentuhan satu jari dengan jari tangan lainnya, ia rapatkan ke dahi, layaknya orang memuja.
“Terimakasih banyak, Sinuhun Agung Sultan Agung Hanyokrokusumo. Kula menerima dengan gembira, bungah amarwatasuta bungah kagiri-giri. Perasaan kula laksana kaghunturan madu, kaurugan menyan putih,” kata Ukur. Nadanya meski terdengar menerima, namun tetap saja terdengar tegas.
“Syukurlah kalau Kau senang menerima pemberianku,” kata Sultan. “Hanya sengaja tak akan kuutus caraka untuk membawa suratku kepada Wedana Dayeuh Ukur yang saat ini memerintah. Kau bawa dan serahkan sendiri surat resmiku kepada Bupati Sutapura. Surat pemberhentian dirinya, sekaligus pengangkatanmu menggantikannya, Ukur.”
“Sendika, Gusti Prabu.”
Setelah itu Sultan Agung memberikan masing-masing ksatria Tanah Sunda itu sebilah keris bereluk tujuh. Keris tersebut juga merupakan simbol otoritas yang ia berikan kepada keduanya untuk mengelola wilayah masing-masing. Wilayah yang secara resmi kini hanya menjadi daerah taklukan Mataram.
“Aku minta kalian berdua berangkat besok. Memerintahlah kalian di sana atas namaku. Pada saatnya, aku akan meminta balas terhadap segala karunia yang hari ini kuberikan kepada kalian. Tunggu saja saat itu,” kata Sultan.
Penobatan itu diakhiri dengan makan siang di meja yang begitu panjang, berisikan segala rupa makanan enak. Dari mulai segala jenis ikan yang digoreng, dipindang, dibakar, dibubuy alias ditanam dalam abu panas, sampai diseupan atau dikukus, hingga segala macam daging yang dibakar, digoreng minyak kelapa, digoreng dengan gajih atau lemak kambing, hingga daging yang direbus dan digulai dengan santan kental dan gula nira pilihan.
Buah-buahan? Ada sekitar 10 jenis buah-buahan yang terhidang, mulai dari rambutan, mangga, pepaya, nenas, duku kiriman Kerajaan Palembang, jambu, salak, buah buni, buah kecapi, jamblang, nangka, durian dan sebagainya. Pisang? Ada sekitar 10 jenis pisang yang terhidang.
Ukur sampai pusing memilih apa yang harus ia ambil dan dahulukan masuk memenuhi perutnya. Ukur sering mendengar, para cacah kuricakan alias rakyat kebanyakan meyakini bahwa para menak pemimpin negara itu makan dengan penuh tata krama, juga ancin atau berpura-pura makan hanya sedikit. Ia juga dulu sangat percaya mitos itu, sebelum memasuki lingkungan keraton, baik di Tanah Sunda atau pun di tanah wetan ini.
Yang terjadi sebenarnya justru berlawanan diametral. Para menak justru kebanyakan orang-orang serakah, yang tak hanya makan apapun yang ada di dekatnya, melainkan bisa makan satu,dua atau tiga jenis makanan dalam satu suapan.
Esoknya pagi-pagi sekali, usai menjalankan shalat Subuh Ukur telah berada di punggung kuda. Di sebelahnya Rangga Gempol duduk di kuda yang lain, terkantuk-kantuk mencoba tegak. Tadi, Ukur cukup lama menunggu menak itu bangun sendiri, tapi ternyata tak bisa diharap.
Dibangunkannya setengah paksa, sambil minta maaf dirinya tak bisa menunggu. Sontak menak kebluk alias penidur itu bangun. Ia hanya sempat mencuci muka, entah shalat subuh atau tidak, karena Ukur sendiri sengaja menunggu di punggung kuda.
Di belakang mereka ada 15 orang pengiring sang pangeran yang kini hanya menjabat wedana itu. Mereka tak perlu lagi ke keraton untuk pamitan. Semua sudah mereka lakukan kemarin, kuatir kalau pagi-pagi Sinuhun terganggu.
“Ayo berangkat,” kata Ukur. “Hus! Hus! Jalan, Sambrani!” Ditepuk-tepuknya surai kuda putih yang ditungganginya. Kuda itu segera berjalan, diikuti kuda-kuda lain. Meski secara pangkat Ukur berderajat lebih rendah dibanding Rangga Gempol, dalam perjalanan itu ia mendaulat diri menjadi pimpinan. Dan memang masuk akal, bahkan bisa jadi mesti kalau dilihat dari aturan keprajuritan.
Selain dirinya lebih tua daripada Rangga Gempol, Ukur juga memiliki pengalaman jurit lebih lama dan lebih tinggi dibanding Sang Wedana. Apalagi Ukur sendiri menganggap dalam perjalanan itu dirinya adalah hulubalang penjaga mantan raja terakhir Kerajaan Sumedang Larang. Tanpa harus berpikir lama, Ukur tahu para nenek moyang, karuhunnya di alam sana akan mempertanyakan dirinya bila ia tak bisa menjaga orang yang bisa dianggap raja terakhir Pajajaran itu.
Tiba di tapal batas wilayah keraton, tujuh pengiring memecut kuda mereka melewati Ukur dan Rangga Gempol, lalu berkuda lambat-lambat di depan mereka. Kini formasi penjagaan pun terbentuklah. Tujuh orang di depan mengantisipasi bilamana ada maung ngamuk gajah meta, siku siwulu-wulu alias pengganggu yang datang menghadang. Delapan lainnya di belakang, kalau-kalau ada serangan licik yang dilakukan dari sana.
Di sebuah pertigaan, atas inisiatif Ukur rombongan berbelok ke kanan, mengambil rute tercepat menuju Cirebon. Rute itu memang lebih sepi karena lebih jarang dijalani rombongan para pedagang. Sejak datangnya Kompeni dan maraknya perdagangan di pesisir utara, para pedagang lebih suka memakai jalan pesisir yang lebih ramai.
Jalan pedalaman ini memang sesekali dipakai, namun hanya oleh mereka yang memang memilih tak banyak bertemu manusia. Jalan ini lebih disukai para pertapa, pengelana pencari ilmu, barisan tentara yang ingin segera pulang bertemu keluarga, para juru dakwah Islam atau biksu pengelana. Atau kalau pun pedagang, paling para pedagang dari Sukapura yang terkenal nekat dan jago olah keprajuritan.
Tengah hari, mereka mencari dataran yang agak luas dan bersih. Di sanalah rombongan membuka perbekalan yang tadi pagi diberikan kepala dapur umum. Tak hanya isinya yang membangkitkan selera, lapar karena perjalanan pun membuat semua anggota rombongan makan dengan lahap, tak kecuali Rangga Gempol.
Usai makan dan shalat Dhuhur berjamaah, perjalanan pun berlanjut. Sekitar sepeminuman klembak (rokok dengan bungkus daun jagung dan tembakau bercampur kemenyan) rombongan tiba di mulut sebuah hutan. Alas itu seolah menjadi benteng tersendiri bagi keraton Mataram saking angkernya. Namun tak ada pilihan lain, rimba itu memang harus ditembus bila ingin segera sampai Cirebon.
Hati-hati, rombongan yang hendak pulang ke tanah kulon itu mulai merambah alas. Sejatinya hutan selebat itu memang tak pernah hening. Suara-suara terdengar bersahutan. Kadang terdengar Oa berkoar, berlanjut jerit Surili di kejauhan. Belum lagi kang-kong suara Burung Rangkong, berlanjut geraman macan dahan.
Ada pula bunyi yang tak pernah henti berdenging, koar tonggeret, serangga kecil yang seolah mengikuti perjalanan mereka sejak keluar wilayah keraton Mataram. Jadi hanya ada dua kemungkinan manakala kita mendengar seseorang bilang betapa sunyinya hutan terlarang. Atau dia berbohong, atau dia memang hanya pembual yang sebenarnya belum pernah sekali pun merambah hutan.
Tiba-tiba insting Ukur tergetar. Entah mengapa ia merasa gerak-gerak rombongannya tengah dalam pengintaian. Ada bunyi terinjak, dan telinga Ukur yang terlatih jelas mengatakan itu bukanlah bunyi patahan ranting yang terlindas musang.
“Mangkade, yeuh! Sing iatna.” kata Ukur dalam bahasa Sunda. “Hati-hati, bersiagalah!” Tidak keras sehingga akan membangkitkan kecurigaan lawan yang mungkin tengah siaga, namun juga cukup terdengar semua anggota rombongan sehingga mereka kini waspada. Ukur senang, kelima belas orang yang menjadi pengawal Rangga Gempol itu benar-benar prajurit pilihan. Kesiagaan mereka tampak begitu normal, sehingga tak mencurigakan siapa pun lawan mereka kalau pun itu ada.
Tapi naluri Ukur memang bukan buah ketakutan seorang yang baru pertama kali masuk hutan. Benar saja. Tanpa diawali suara apa pun, sebilah tombak berdesing membelah udara, deras tertuju pada dada Ukur sendiri.
Ukur sekilas melihat arah ujung tombak itu. Benaknya masih cukup waktu untuk mengerti bahwa kalau pun bukan dadanya yang tertembus mata tombak, mungkin saja salah seorang prajurit Sumedang yang justru akan tersatai tombak yang dilemparkan seorang berilmu tinggi itu bila ia mengelak.
Dengan pertimbangan tersebut, Ukur diam tenang di atas punggung kuda, seolah menunggu ajal seiring datangnya tombak. Kesabaran itu berbuah manis, karena saat mata tombak itu tinggal tiga jengkal lagi dari jantungnya, seseorang berteriak keras dari balik rimbunan pohon yang rapat di kanan jalan, seolah girang bukan kepalang.
“Modar Kowe, Ukur!” [bersambung]
[1] tercatat dalam Babad Limbangan