Maret 1959 DI/TII pecah dua. Trio A. Gani, Teungku Amir Hussein Al-Mujahid, dan Hasan Saleh membentuk Dewan Revolusi (DI/TII). Setelah terjadi kup, Al-Mujahid diangkat sebagai “wali negara” NII, menggantikan Daud Beureueh yang berkeras tak mau turun dari gunung untuk berunding
Oleh: Zakaria M Passe*
JERNIH—Pada 21 September 34 tahun yang lalu (70 tahun dihitung saat ini—red Jernih.co). Ada yang sulit dilupakan oleh anak polisi yang masih di kelas III sekolah rakyat ini. Sore itu ia baru usai bermain bola-–tetapi sebelum maghrib ayahnya menyuruh dia dengan ibunya bergegas naik ke sebuah truk peot. Bersama enam keluarga penghuni asrama, di sebelah pos itu, mereka berangkat ke markas resor di Langsa, ibu kota kabupaten.
Ayahnya komandan polisi di Tualangcut, kota kecamatan di Aceh Timur itu. Petugas di pos itu merupakan satu-satunya yang senjata mereka tak dapat dilucuti DI/TII. Padahal, dalam tempo cepat pertempuran sudah berkecamuk di mana-mana.
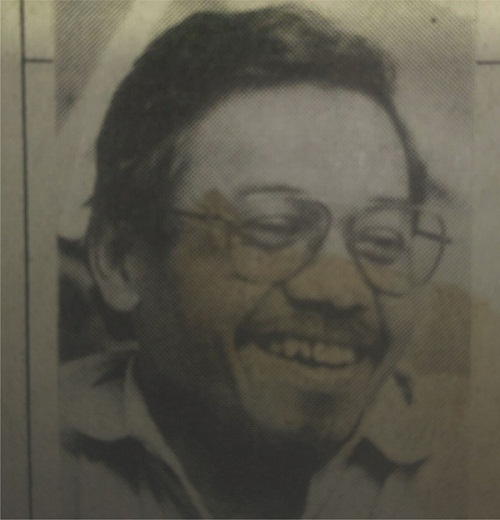
Itu awal 21 September 1953, ketika meletus pemberontakan DI/TII yang dipimpin Teungku Daud Beureueh. Sementara itu, sisa keluarga uleebalang ramai-ramai bereksodus ke Medan dan Jakarta, karena khawatir pembantaian lagi ala Peristiwa Cumbok (1946) di Aceh Pidie.
Dalam pada itu, setiap bangunan milik “pemerintah Pancasila”, termasuk stasiun kereta api dan sekolah, dibakar. Sebaliknya, ada gembong Darul Islam/ Negara Islam Indonesia (NII) yang menyekolahkan anaknya ke luar negeri, hingga meraih gelar master of arts.
Selain itu sejumlah desa berubah jadi ajang bumi hangus. Di Pulot, Cot Jeumpa, dan Leupeueng di Kabupaten Aceh Besar, pada 26 Februari 1955, malah berlangsung pembantaian masal–setelah penduduk di desa-desa itu dipaksa mengaku dirinya anggota DI/TII. Pembunuhan sesama bangsa ini kemudian masuk agenda PBB, di New York.
DI/TII menembak mati kakek
Selama perang saudara, yang memuncak pada 1956-57, anak polisi tadi juga kehilangan seorang kakeknya. Kakek adalah Kepala Kampung Bumlama, di wilayah Rantopanyang, Peureula-– kota minyak terkenal sejak zaman Belanda.
Ayah tiri ibunya itu, suatu malam, bersama seorang tetangganya, diculik. Besok paginya, mayat mereka dijumpai tak jauh dari jalan raya. Sekujur tubuh jenazah penuh lubang bekas peluru.
Kenapa dibunuh, padahal pemimpin DI/TII di wilayah itu juga teman mereka? Karena dua orang ini keras kepala dan tak mau ikut pemberontak? Atau mungkin ini penyebabnya: karena mereka tak mau membayar infak dalam jumlah seperti telah ditetapkan-– sehari sebelum pemimpin DI/TII itu memaksa agar padi dalam lumbung kedua orang tua itu dikosongkan. Tapi si kakek, misalnya, cuma memberi beberapa goni padi.
Tentara Indonesia menembak mati Pak De
Sehabis kakeknya, menyusul dibunuh Pak De-nya. Pak De, putra kandung si kakek tadi, bekas tentara di Medan Area ketika melawan NICA dan sekutu. Setelah pulang dari front, Pak De kemudian terpilih sebagai kepala desa.
Di suatu siang, ketika ia hendak salat Jumat-– setelah menghadiri pesta perkawinan seorang warga desanya-– Pak De dicegat sepasukan alat negara. Ia memang sedang dicari. Di tengah sawah yang baru saja dipanen, ia ditembak. Sebelum dihabisi Pak De dituduh simpatisan pemberontak.
Orang-orang di tempat pestelan melihat bagaimana lelaki itu diberondong delapan peluru sten-gun. Hanya sebutir peluru yang keluar dari tubuhnya. Ia rebah, tewas, bermandi darah. Dan dari jauh-– dalam keadaan tak berdaya-– kakaknya menyaksikan pembantaian itu. Sang kakak tak lain adalah istri bekas komandan polisi di Tualangcut dimaksud.
Bahkan, setelah dua keluarganya itu dibunuh, belakangan bekas komandan polisi itu nyaris mengalaminya juga. Seorang cuak alias “intel swasta” mengatakan-– seperti yang dituduhkan kepada alamarhum iparnya-–dia tak boleh dipercaya, karena “simpatisan DI/TII”.
Karena itu, setiap ia beroperasi ke dalam hutan, polisi itu tetap memilih posisi di belakang pasukan – dengan picu senjatanya siap untuk mendahului daripada didahului. Jika DI/TII memang jelas musuhnya, sebaliknya waktu itu ia tak tahu siapa sebenarnya “musuh” di dalam pasukannya sendiri, antara sesama teman.
DI/TII pecah kongsi dan Daud Beureueh tidak mau berunding
Syahdan, di suatu hari dalam hidup polisi itu-–setelah Kantor Camat di samping rumahya di Langsa dibakar DI/TII-– tanpa diduga datanglah utusan dari gunung menjumpai dia. “Anda sekarang sakit paru-paru. Mari kami obati. Rumah sakit di gunung lebih baik fasilitasnya. Di sana ada dokter Amerika. Anda percuma jadi polisi Pancasila. Anda orang Aceh, lebih baik Anda memilih DI/TII,” begitu rayu utusan itu.
“Tak mungkin saya meninggalkan pasukan saya. Biarlah dirawat di rumah sakit pemerintah RI. Saya ini alat negara RI,” jawab bekas komandan itu. Kurir tersebut pernah dua kali datang lagi, tetapi polisi yang sedang terbaring di rumah sakit itu tetap menolak naik ke gunung.
Maret 1959 DI/TII pecah dua. Trio A. Gani, Teungku Amir Hussein Al-Mujahid, dan Hasan Saleh membentuk Dewan Revolusi (DI/TII). Setelah terjadi kup, Al-Mujahid diangkat sebagai “wali negara” NII, menggantikan Daud Beureueh yang berkeras tak mau turun dari gunung untuk berunding dengan pemerintah.
Trio yang sudah bosan berperang ini menyebut “revolusi sudah selesai”, lalu berunding dengan pemerintah RI yang diwakili Wakil PM-1 Mr. Hardi. Dan sesuai janji pemerintah, 26 Mei 1959 status Aceh dikembalikan lagi menjadi provinsi. Pada 25 Juli 1959 sepertiga dari kekuatan tempur DI/TII kembali ke pangkuan Republik.
Semua anggota eks Tentara Islam Indonesia (TII) kemudian mendapat amnesti dan abolisi dari Presiden RI. Karena mereka mendapat pengampunan umum itu, maka cukup kuat jika sekarang (saat itu—red Jernih) Gubernur Ibrahim Hasan mengikutsertakan eks tokoh DI/TII seperti Hasan Saleh dan Hasan Ali dalam kelompok kerja Pemda Aceh yang dilantik pada 17 September lalu di Banda Aceh. Hasan Saleh sendiri terakhir kolonel TNI, hingga ia pensiun.
Dan suatu hari dalam hidup anak ini, ia ingat kembali ketika Teungku Amir Hussain Al-Mujahid datang ke rumah bekas komandan polisi di pos terpencil itu. Seperti di mana pun kebiasaan dan adat orang Aceh, hari itu Al-Mujahid tampak menyantap hidangan dengan rasa sukacita-– jauh sebelum keduanya berpulang ke alam barzakh.
Sedangkan anak mereka, kini, justru sama-sama menjadi wartawan di sebuah majalah yang sama: semacam bukti bahwa generasi berganti, untuk hidup yang tak usah berkelahi lagi. [ ]
*Almarhum, wartawan majalah TEMPO biro Aceh saat itu.
Sumber : Majalah Tempo, 26 September 1987. Hal: 38.