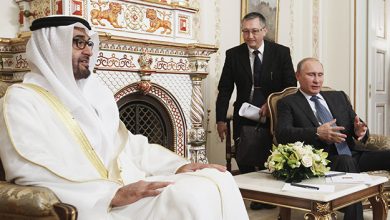Kalabendu yang Mengungkung Kehidupan Kita

Benarkah bencana, sebagaimana ‘Poemesur la desastre de Lisbonne’, sajak tua yang ditulis Voltaire pada 1775, menunjukkan betapa jauhnya jarak Tuhan dengan kita?
Barangkali tidak sepenuhnya benar. Sebab kita pun tahu tidak setiap bencana merupakan azab Tuhan kepada suatu bangsa. Tidak setiap banjir bisa dianggap sama dengan terjangan bah yang diturunkan Tuhan untuk melibas kaum Nabi Nuh AS. Seperti juga tidak semua badai harus dimaknai sebagaimana topan kiriman Tuhan yang menghancurkan kaum Aad dan Tsamud. Tidak setiap bencana itu azab hakikatnya.
Pada sekian banyak korban bencana alam yang jatuh dalam dua bulan ini, yang menurut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letnan Jenderal Doni Monardo, nomor dua terbanyak di dunia, kita barangkali bisa mengatakannya sebagai akibat garis nasib. Sebagai takdir.
Bagaimana pun ini negeri dengan risiko bencana alam terbesar di dunia. Indonesia memiliki 500-an gunung berapi, 127 di antaranya dalam kondisi aktif. Belum lagi ada 295 patahan lempeng bumi di laut dan darat. Bencana alam, dengan fakta itu, menjadi terasa wajar adanya.
Tetapi pada banjir yang nyaris setiap tahun memporak-porandakan kehidupan di utara Jakarta dan kawasan Pantai Utara Jawa umumnya, masihkah kita layak cuci tangan mengatakan semua itu takdir adanya? Seharusnya tidak, karena tangan-tangan manusia menapakkan dampak begitu kuatnya.
Karena itulah, banyak agama yakin, ada hubungan erat antara perilaku manusia dengan alam yang menjadi murka. Tidak sedikit di antara kita percaya, alam yang marah, yang di negeri ini bertubi-tubi unjuk diri, pamer kekuatan melalui bencana, tak lain karena ulah manusia juga. Dunia semakin tua, sementara kelakuan manusia justru tak kunjung dewasa. Kian beradab kita menyebut diri, justru hanya tinggi hati, jumawa dan sikap destruksi yang menjadi ciri.
Ajaran Hindu meyakini apa yang mereka sebut zaman kalabendu. Konon, zaman itu ditandai dengan munculnya dua masalah, yakni murkanya alam semesta dan masyarakat yang mengalami penyimpangan perilaku. Sebagian percaya, zaman itu kini tengah bergulir dan kita alami. Tengoklah alam yang menggeram berkali-kali: langit berlobang menganga, sinar matahari kian panas meranggas, bumi tak henti mengguncang diri, gunung-gunung berapi sebal dan muntah, gelombang ganas di samudera, topan puting beliung, dan sawah-sawah tempat harapan kita pupuk, mati mengering.
Lalu palingkan pandangan kita kepada manusia yang justru kian loba, tamak, rakus dan tega terhadap sesama. Semakin hari, semakin langka kita melihat orang ikhlas berbagi. Kita hidup kian nafsi-nafsi, karena cinta kasih makin lenyap dari hidup sehari-hari. Justru yang semakin sering kita temui di keseharian barangkali tak ubahnya mayat-mayat hidup tanpa Nurani. Persona mati nurani yang lebih layak kita sebut zombie.
Barangkali, inilah zaman yang digambarkan pujangga Ronggowarsito sebagai zaman edan, saat manusia yang ‘ora edan ora keduman’—jika tak ikut gila, maka tak akan kebagian. Era saat para koruptor tak pernah hilang pamor, bahkan dipuji layaknya dermawan yang rajin berbagi. Era manakala pencuri malahan dengan takzim kita hormati.
Inilah zaman ketika keserakahan bahkan menjadi ukuran kesuksesan, manakala orang tak lagi merasa perlu bersalah jika punya 10 Jaguar di tengah kemelaratan hidup berjuta umat.
Putu Setia, mantan wartawan TEMPO yang kini menjadi pandita tinggi Hindu bergelar Mpu Jaya Prema Ananda, sempat menulis tentang Kali Yuga, atau zaman tergelap kehidupan. Putu merinci ciri zaman yang tanda-tandanya akrab kita jumpai saat ini. Namun Putu tak sepakat bila terlalu gampang mengaitkan bencana saat ini dengan Kali Yuga. Ia tak suka zaman dijadikan kambing hitam.
Sikap Putu itu selaras dengan sikap sahabat Nabi SAW, Ali bin AbiThalib. “Manusia terlalu gampang menyalahkan zaman,” kata beliau. “Padahal, dia sendiri yang menghidupkan zaman itu.” Jadi, bukan zaman yang salah, tetapi memang mutu manusia semakin merosot karena kurang pandai menyelaraskan diri dengan alam.
Kita pun tak pernah sadar bahwa hiruk pikuk kita bermain politik—semua memainkan permainan ini, dari para elit pemerintah, anggota DPR-DPD-MPR, sampai peronda di kampung kita–mengalahkan bunyi gunung-gunung yang terus berletusan.
Sejak Juli lalu setidaknya ada empat gunung api yang diberi status siaga oleh Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Fakta itu dengan mudah terhapuskan segala urusan kecil yang dipertontonkan dan ditonton sekian juta mata rakyat di televisi kita, semisal “lisptik warna apa yang dipakai Princes Syahrini kondangan pekan ini?” Gunung-gunung tersebut adalah Gunung Sinabung, Agung, Karangetang, dan Gunung Soputan.
Tampaknya juga tak banyak dari kita yang sadar bahwa selama Juli lalu terdapat 16 gunung api yang berada di level II atau waspada. Gunung-gunung itu antara lain Gunung Anak Krakatau dengan 38 kali erupsi, Gunung Ibu di Halmahera yang mengalami 2.852 kali erupsi, Gunung Dukono empat kali, Semeru 697 kali, serta yang dekat-dekat dan selalu kita pandang jinak, Tangkuban Parahu.
Tentu saja, tak baik bila semua itu menjadikan kita panik. Namun untuk itu tentu perlu koordinasi dan penanganan yang baik dari pemerintah. Berkacalah dari berbagai peristiwa bencana. Jangan seperti yang terjadi saat Sinabung meletus pada 2014. Baru saja para petinggi dari Jakarta pulang meninjau korban Sinabung, justru 15 orang tewas terpanggang. Belum lagi apabila kita menunjuk fakta, manakala saat itu para korban erupsi Sinabung terabaikan tiga bulan di pengungsian, tanpa ada kejelasan.
Yang lebih penting, sebaiknya kita segera berbenah dan mendekatkan diri kepada Sang Khalik. Tidak hanya dengan berperilaku salih yang berdimensi personal antara kita dengan DIA, melainkan lebih penting lagi dengan kesalihan yang berdimensi sosial, hablumminannas.
Selebihnya, segeralah bertawakal dan pasrah. Sikaptersebut penting, sebab sebagaimana dikatakan Ibnu Taymiyah, “Pangkal agama adalah al Islam, penyerahan diri.”
Jika saja setiap kita bisa kembali ke sifat hanif–yang sebenarnya menjadi jati diri setiap manusia itu, rasanya negeri ini tak akan didominasi para pejabat korup, atau para pemimpin yang tak adil di tengah merajalelanya kemunafikan. Sudah terlalu lama kehidupan kita diisi para pemuka agama yang lancung, anak-anak yang durhaka, orang bodoh berotak kosong yang anehnya sombong, atau orang-orang awam tak tahu diri yang gampang kita temui saat ini.
Dan kita memang harus bergegas. Karena ada seorang faqih lain yang melihat bencana justru sebagai obat. “Jika kerusakan sudah menguasai suatu negara,” kata Ibnu Khaldun dalam ‘Al-Muqaddimah’, “maka langkah awal untuk memperbaikinya adalah dengan kekacauan..”
Naudzubillah. [dsy]