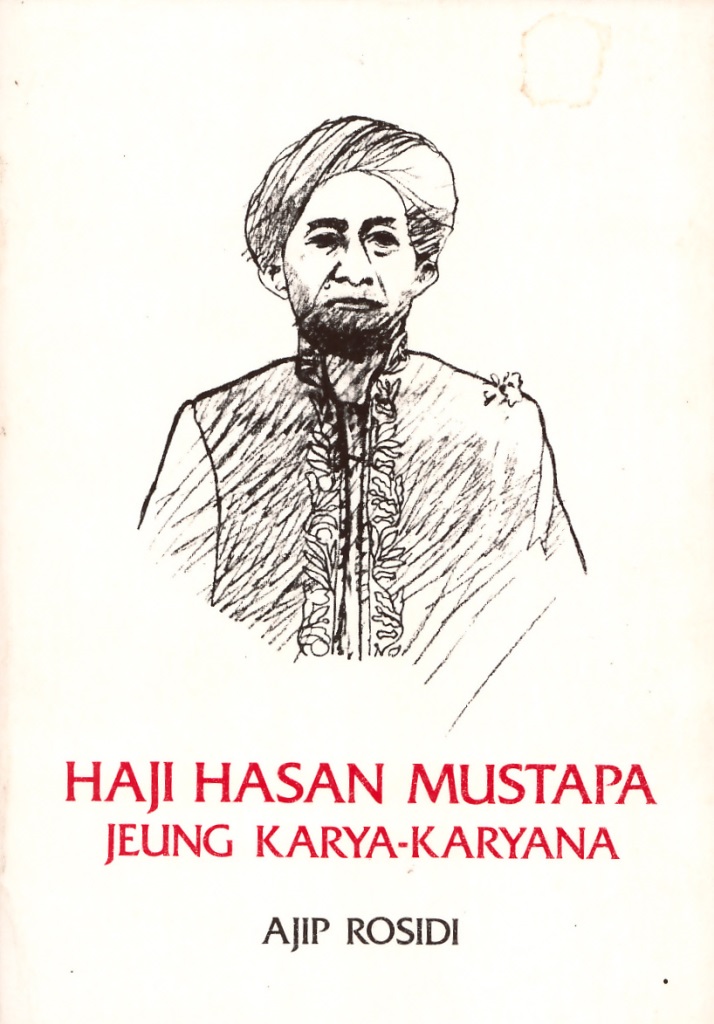Atas usaha Ajip Rosidi, beberapa karya “guguritan” KH Hasan Mustapa, mulai dihimpun berdasarkan “pupuh” yang digunakannya, bersumber dari naskah-naskah yang berada di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Sebagian sudah diterbitkan sejak 2009.
Oleh : H.Usep Romli HM
Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, berfungsi sebagai salah satu benteng pertahanan umat Islam, pusat dakwah dan pusat pengembangan masyarakat Muslim setempat (Ensiklopedi Islam, 1993).
Lingkup pendidikan di pesantren, terdiri dari empat hal pokok. Yaitu aqidah (keimanan kepada Allah Yang Maha Ahad, yang tidak ada sekutu bagiNya), ibadah (meliputi segala aspek ritual, hubungan hamba dengan Allah SWT. Mulai dari sahadat, shalat, zakat, shaum dan haji), ahlak (adab tatakrama, cara bicara, cara berfikir, mencari nafkah, dlsb) serta muamalah (hubungan sosial, mulai dari ekonomi, politik, kebudayaan, pertahanan keamanan, dst).
Keempat hal pokok itu tak terpisahkan satu sama lain. Tetap berjalin berkelindan. Saling mengisi dan memperkuat, dalam kerangka “hablum minallahi wa hamblum minannasi” (Q. S. Ali Imran : 112). Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia.
Tegasnya, inti jiwa pesantren adalah mengaplikasikan perintah Alloh SWT, untuk berbuat baik kepada sesama manusia, sebagaimana Alloh SWT telah berbuat baik pula kepada manusia. Sekaligus meninggalkan laranganNya agar tidak berbuat kerusakan di muka bumi (Q.s.al Qhasash : 77).
Dalam kaitan dengan sastra Sunda, dari lingkungan pesantren, pernah lahir pujangga-pujangga besar. Antara lain KH Hasan Mustapa, yang karya-karyanya hingga saat ini dianggap “grandmaster” sastra Sunda. Lahir di Cikajang, Garut, tahun 1889, KH Hasan Mustapa pernah “nyantri” di beberapa pesantren terkenal di Cirebon, Sumedang, dan Mekkah.
Pernah menjabat “penghulu” di Kutaraja, Aceh, atas ajakan Snouck Hurgronje, kemudian menjadi penghulu besar Bandung hingga wafat tahun 1949.
Karya-karyanya, berupa “guguritan”, masih tercecer di berbagai tempat. Atas usaha Ajip Rosidi, beberapa karya “guguritan” KH Hasan Mustapa, mulai dihimpun berdasarkan “pupuh” yang digunakannya, bersumber dari naskah-naskah yang berada di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Sebagian sudah diterbitkan sejak 2009.
Sastrawan pesantren pendahulu KH Hasan Mustapa, adalah KH Rd.Muhammad Musa. Menulis buku wawacan “Panji Wulung”, “Dongeng-Dongeng Sasakala”, “Mitra Nu Tani”, dll. Ia akrab dengan Karl Federick Holle, pemilik perkebunan teh Waspada, Garut. Antara mereka, terjalin kerja sama yang membuahkan hasil berupa pembaharuan dalam teks dan susunan huruf Latin Sunda. Bahkan merintis percetakan yang mempermudah publikasi tulisan-tulisannya. Hal ini diungkapkan oleh Mikihiro Moriyama, dalam buku “Semangat Baru” (2004) yang menelisik jasa Muhammad Musa bersama KF Holle di bidang pendidikan dan cara memajukan masyarakat Sunda.
Pada masa-masa selanjutnya, pesantren masih menjadi pilihan para sastrawan Sunda, sebagai sarana pencari keseimbangan dan ketenangan jiwa. Novel klasik “Mantri Jero” (1932) karya Rd.Memed Satrahadiprawira, menempatkan pesantren sebagai wahana penempaan mental intelektual tokoh Rd.Yogaswara, yang akan mencari bekal ilmu untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Ditemani tokoh Ki Bulus, Rd.Yogaswara belajar di pesantren asuhan Kiyai Basari. Ternyata kelak terbukti, kiyai itu salah seorang putra Dalem yang mengasingkan diri karena tak mau berebut tahta dengan adik tirinya.
Sastrawan Sunda klasik lainnya, Mohamad Ambri, dalam karyanya “Ngawadalkeun Nyawa” (1935), mengisahkan santri Warliya yang berbuat onar, suka mendebat ulama-ulama sehingga “katulah”. Segala ilmunya hilang lenyap. Ia terpaksa hidup terlunta-lunta dan memohon bantuan seorang Kiyai lain agar mengobatinya. Hingga ilmunya pulih kembali dan selamat dari ancaman kematian dipatuk ular “jin Bagdad”.
Pada karyanya yang lain, novel “Lain Eta”, Ambri menjadikan Neng Eha, gadis anak penghulu Cianjur, sebagai tokoh utama. Konflik perbedaan faham tua-muda dalam urusan perjodohan, membuat Neng Eha “ngalajur napsu”, namun diakhiri kesadaran untuk bertobat.
Sastrawan dari generasi lebih muda, Ki Umbara (1918-2004), juga menjadikan pesantren sebagai sumber kedamaian batin. Mas Sumarna, setelah kalah dalam pilkades yang penuh kecurangan, berangkat ke tempat terpencil. Mendirikan surau dan pondok (“Maju Jurang, Mundur Jungkrang”, 1986). Ki Umbara juga, bersama SA Hikmat, menulis novel “Pahlawan-Pahlawan ti Pasantren” (1970). Mengisahkan perjuangan para santri melawan penjajah, sejak era kolonial hingga revolusi kemerdekaan.
Sedangkan Rahmatulah Ading Afandi (RAF), menulis “Dongeng Enteng ti Pasantren” (1957), berisi anekdote-anekdote tentang kehidupan pesantren tahun 1940, yang sangat berharga sebagai dokumentasi historiografi pesantren di Jawa Barat.
Demikian pula Ahmad Bakri (1917-1989), menulis banyak ceritera yang berlatar belakang pesantren atau mesjid. Antara lain “Ki Merebot” (1984) dan serial kisah “Wa Haji Dulhamid” (2006). Ia layaknya seorang ajengan bertutur petuah kepada para santri mengenai hak dan kewajiban setiap Muslim yang mendambakan kehidupan serba baik di dunia dan akhirat. [ ]