Al-Harits al-Muhasibi: Sufi yang Memberi Pengaruh Besar Kepada Imam al-Ghazali
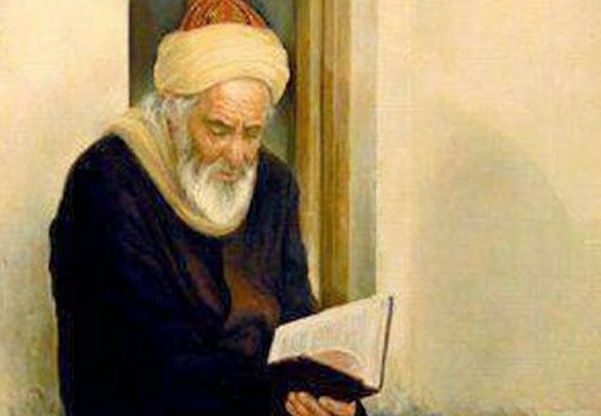
Penilaian banyak sarjana bahwa al-Ghazali adalah sufi pertama yang telah berhasil dengan gemilang mendamaikan tasawuf dan syariat, perlu ditinjau ulang. Sebab, tiga abad sebelum al-Ghazali, Imam al-Haris al-Muhasibi sudah berhasil melakukannya.
JERNIH—Rasanya, hampir tidak ada kaum Muslim yang tidak mengenal Imam al-Ghazali? Sufi abad pertengahan yang namanya dikenal luas melalui karya-karya monumentalnya seperti “Ihya’ Ulumuddin”. Sebaliknya, mungkin hanya sedikit yang paham akan Imam al-Harits al-Muhasibi, padahal dialah tokoh yang dianggap paling berpengaruh terhadap pemikiran tasawuf Imam al-Ghazali.
Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah al-Harits bin Asad bin Ma’qil al-Hamdani al-Muhasibi. Ia lahir di Bashrah dan tinggal di sana selama beberapa tahun, sebelum pindah ke Baghdad pada usia yang masih sangat muda.
Kezuhudan al-Harits mulai tercium sedari kecil. Konon bapaknya adalah seorang kaya-raya yang menganut aliran muktazilah (sebuah madzhab teologi dalam Islam). Ayahnya bukan hanya penganut aliran muktazilah yang pasif, bahkan termasuk salah seorang yang gigih mengampanyekan pemikiran muktazilah. Namun al-Muhasibi ternyata tidak seperti ayahnya, baik dalam masalah teologi maupun dalam sikapnya terhadap harta. Singkat kata, al-Muhasibi boleh dibilang terpisah jauh dari kehidupan sang ayah.
Pengaruh kepada Al-Ghazali
Sejumlah sarjana seperti A.J. Arberry dan Annemarrie Schimmel, menilai bahwa pengantar al-Muhasibi dalam karyanya “Kitab al-Washaya” bersifat otobiografis, dan mungkin dengan baik sekali telah terkandung dalam benak al-Ghazali ketika menulis karya “al-Munqidz min al-Dhalal” yang merupakan otobiografinya.
Dalam pengantar Kitab al-Washaya, Muhasibi menjelaskan pencarian spiritualnya yang dihinggapi banyak keraguan, saat banyak sekte saling mengklaim kebenaran. Hal ini mengingatkan pada kitab “al-Munqidz min ad-Dhalal” karya al-Ghazali. Berikut kutipannya:
Pada zaman kita ini telah terjadi perpecahan umat menjadi tujuh puluh golongan, atau lebih; di antara golongan itu, hanya satu pada jalan keselamatan, dan selebihnya, hanya Allah yang paling mengetahuinya.
Hingga kini, aku tak pernah berhenti, meski hanya sesaat dalam hidupku, memikirkan dengan baik perbedaan-perbedaan yang meruntuhkan umat ini, dan mencari cara yang jelas dan jalan yang benar, dengan tujuan untuk mencari teori dan praktik, dan mengharapkan bimbingan pada jalan menuju dunia yang akan datang di bawah pengarahan para teolog. Lebih dari itu, aku telah mempelajari banyak doktrin tentang Tuhan Yang Maha Agung, dengan interpretasi ahli fikih, dan merenungkan berbagai keadaan umat ini, dan memikirkan doktrin-doktrin dan ucapan mereka yang berbeda-beda.
Di antara semua ini aku memahami yang mesti kupahami: dan saya melihat bahwa perbedaan mereka bagaikan samudera yang begitu dalam, di dalamnya banyak orang tenggelam, dan hanya sekelompok kecil yang berhasil melepaskan diri dari sana; dan aku melihat setiap golongan menyatakan dengan tegas bahwa keselamatan dapat ditemukan jika mengikuti mereka, dan binasalah siapa yang menentang mereka.”
Keterpengaruhan Imam al-Ghazali terhadap Imam al-Harits al-Muhasibi juga diamini Syaikh Zahid al-Kautsari sebagaimana diungkapkan Syaikh Abdul Halim Mahmud, bahwa “Ihya Ulumuddin, karya monumental Imam al-Ghazali, terpengaruh karya Imam al-Harits al-Muhasibi lainnya, “ar-Ri’ayah lihuquqillah Azza wa Jalla”.
Selain keterpengaruhan al-Ghazali terhadap karya-karya al-Harits al-Muhasibi, secara pemikiran tasawuf, sumbangsih al-Haris al-Muhasibi juga cukup kuat dalam membentuk pemikiran tasawufnya al-Ghazali. Jauh sebelum al-Ghazali muncul, al-Haris al-Muhasibi sudah membangun konsep moderatisme tasawuf atau yang biasa dikenal dengan tasawuf sunni. Penilaian banyak sarjana bahwa al-Ghazali adalah sufi pertama yang telah berhasil dengan gemilang mendamaikan tasawuf dan syariat, perlu ditinjau ulang. Sebab, tiga abad sebelum al-Ghazali, Imam al-Haris al-Muhasibi sudah berhasil melakukannya.
Tentang masa-masa belajar al-Muhasibi, banyak sumber menyatakan beliau belajar dari sederet tokoh terkemuka setelah hijrah ke Kota Baghdad. Di bidang fikih, misalnya, ia berguru kepada Imam Syafi’i, Abu Ubaid al-Qasimi bin Salam, dan Qadli Yusuf Abu Yusuf. Sedangkan, ilmu hadis dipelajarinya dari Syuraih bin Yunus, Yazid bin Haran, Abu an-Nadar, dan Suwaid bin Daud.
Cakrawala dan wawasannya yang luas turut menyedot perhatian besar terhadap kondisi dan perkembangan aktual di kawasan Baghdad kala itu, mulai dari dinamika politik dan sosial yang berkembang, hingga diskursus ataupun polemik terkait pemikiran teologi.
Ragam pendapat yang dilontarkan oleh pendapat Mutazilah, Syiah, Khawarij, Jabariyah, dan Qadariyah mengundang rasa keprihatinannya. Berdasarkan pengamatannya atas kelompok itu, dia berkesimpulan, latar belakang yang mendasari sebagian besar kalangan itu bukan akhirat, melainkan kesombongan dan motivasi keduniaan.
Berangkat dari titik tolak ini, al-Muhasibi memutuskan terjun ke dunia tasawuf dan memilih beruzlah dari keprofanan (keduniaan). Berbagai konsep dan teori dalam kajian dan praktik tasawuf banyak ditawarkan oleh al-Muhasibi.
Salah satunya adalah takut (al-khauf) dan pengharapan (raja’). Kedua teori itu merupakan pangkal penting untuk instropeksi. Dan, keduanya dapat dilakukan dengan sempurna bila berpegang teguh kepada Alquran dan sunah, terutama memaknai dan meresapi ayat-ayat yang menegaskan janji dan ancaman.
Karena gemar melakukan introspeksi diri, ia dijuluki Al-Muhasibi (yang suka melakukan muhasabah; perhitungan diri).
Al-Muhasibi memiliki perhatian yang sangat besar terhadap relasi personal dengan jiwanya sendiri, lebih-lebih pada disiplin hati. Bagaimana seharusnya hati dikenali sehingga manusia tahu jati dirinya, kemudian dikelola dan diarahkan ke jalan bahagia. Ini bisa dilacak di sebagian besar karyanya, seperti kalimat di atas yang termaktub dalam kitab “Adaab an-Nufuus” (Adab-adab Jiwa).
Dalam kitab itu beliau menulis, “Jati diri tidak akan diketahui kecuali setelah dites dan diuji”. Sebab itu, menurut beliau,”Jika Engkau ingin mengetahuinya berinteraksilah bersamanya, periksalah tekadnya, dan pertajamlah pengawasanmu terhadapnya”.
Al-Muhasibi menawarkan supaya dalam melakukan “uji diri” ini, kita sebaiknya mengenali satu persatu sifat-sifat baik yang terkandung dalam diri, seperti kesabaran, ketulusan, ketawadukan, dan sebagainya. Seberapa kuat kadar sifat itu melekat pada diri kita, atau jangan-jangan itu hanyalah atribut-atribut yang bermasalah dan perlahan menggerogoti jiwa kita.
Jiwa manusia itu dinamis dan memiliki ketergantungan terhadap kondisi yang menyelimutinya. Berpulang pada hal itu, Al-Muhasibi mengajak kita agar mengidentifikasi dan menguji itu semua berhadapan dengan keadaan-keadaan yang berbeda, bahkan yang paling ekstrem sekalipun, seperti yang diajukan oleh Al-Muhasibi berikut ini:
“Kenalilah ketawadluanmu saat Engkau tidak dikasari oleh orang kasar dan dihormati oleh orang yang terhormat, sesungguhnya di dalam keduanya terkandung godaan. Seorang hamba bisa saja mempertontonkan kerendahan hatinya ketika dihormati orang lain hanya karena ingin penghormatan itu bertambah dan bisa saja mempertontonkan kerendahan hatinya ketika diintimidasi orang lain hanya karena ingin distatuskan sebagai orang yang rendah hati di antara manusia. Maka, periksalah niatmu!”
“Kenalilah sikap diammu ketika engkau takut akan jatuhnya kehormatanmu di hadapan orang-orang yang menganggapmu orang terhormat.”
“Kenalilah kejujuranmu pada situasi banyak orang membaik-baikkan diri dan berpura-pura.”
“Kenalilah ketulusanmu ketika engkau mencintai dirimu sendiri, kawanmu, dan musuhmu sampai engkau tahu apakah engkau mencintai orang lain seperti engkau mencintai dirimu sendiri, atau tidak?”
“Kenalilah kesabaranmu ketika engkau meninggalkan godaan yang mampu dikontrol oleh kesabaranmu. Dapatkah engkau melakukannya?”
“Kenalilah kewara’anmu saat engkau berhasil memilikinya. Dapatkah engkau bertahan jika situasi menjadi kacau balau?”
“Kenalilah akalmu ketika meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu di dunia dan tidak pula di akhirat, serta tak ada balasannya di sisi Allah. Mampukah kau mengacuhkannya?”
“Kenalilah integritasmu saat hawa nafsu mulai menggodamu. Dapatkah kau menunaikan amanahmu dengan baik pada saat itu?”
“Kenali pula ambisimu saat menggebu hasratmu. Mungkinkah kau berputus asa pada saat itu?”
Begitulah Al-Muhasibi menyodorkan tamsil tentang uji diri. [ ]







