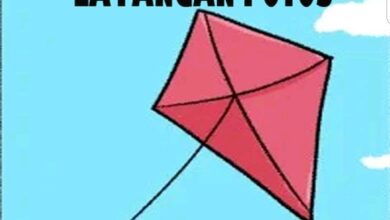Pohon Asam Tanaman Belanda, Masa Kecil dan Lumuran Terasi

Bila dapat Rp 25, artinya uang jajan telah aman untuk lima hari ke depan! Kami tak banyak jajan, lebih terbiasa banyak makan. Sarapan, lalu siangnya ngawadang alias makan siang. Orang Sunda sebenarnya tak punya kebiasaan makan siang, karena ngawadang artinya makan wadang atau nasi sisa!
Oleh : Darmawan Sepriyossa
JERNIH—Dalam perjalanan darat sepulang dari Bali, di beberapa ruas jalan wilayah Kabupaten Probolinggo dan Malang, saya menjumpai satu-dua gerombol pohon asam besar. Melihat bonggol dan batangnya, sekilas pun orang akan tahu bahwa pohon-pohon itu sudah tua.
Segera ingatan saya melayang pada masa kanak-kanak di Kadipaten, Kabupaten Majalengka. Sekitar tahun 1977, masih duduk di kelas satu SD—waktu itu anak-anak masuk SD pada usia tujuh tahun, tanpa melalui Taman Kanak-kanak yang di kecamatan kami pun hanya ada satu-satunya, untuk anak-anak pejabat pabrik gula.

Entah berapa kali sepekan biasanya kami melintas Sungai Cilutung, yang menjadi batas wilayah Kabupaten Majalengka dengan Kabupaten Sumedang. Bila musim kemarau, kami dengan gampang berlari menyeberang sungai yang airnya bahkan hanya semata kaki karena surut. Di luar itu, kami harus membuka baju dan celana, berenang dengan satu tangan teracung membawa buntalan pakaian. Kondisi itu yang membuat kami rata-rata mampu berenang dengan baik, hanya mengandalkan kedua kaki dan satu tangan untuk membuat badan mengambang di arus dan menyeberang.
Tak ada seorang pun dari kami yang memakai celana dalam. Bahagialah anak-anak sekarang, karena generasi saya di kampung saat itu umumnya baru mengenal celana dalam saat SMP. Itu pun rata-rata setelah mengalami pengalaman ‘kepala burung tercekik resluiting celana’.
Di seberang sungai, yang artinya di wilayah kabupaten lain, ada banyak yang bisa kami lakukan untuk bermain-main. Di ‘gunung’ Kancana—yang sebenarnya sebuah bukit saja—kami bisa mengambil satu dua bongkah batu kasungka—semacam padas pejal namun relatif lebih gampang dibentuk. Biasanya untuk dijadikan patung-patung kecil. Dengan batu itu kami juga bisa membuat kelereng, yang meski tak sekuat kelereng marmer yang dijual di pasar, cukuplah untuk modal bermain gundu. Kalau ada tugas prakarya dari sekolah, umumnya kami akan datang ke ‘Gunung Kancana’ dan membuat hasta karya sederhana dari batu padas itu.
Hanya satu kilometer ke arah utara Bukit Kancana, ada sebuah mata air yang airnya begitu jernih, bening dan dingin. Biasanya para pejalan kaki yang berjalan dari Darmaraja rata-rata akan singgah sebentar di sana, menyesap satu dua teguk air dingin dari mata air tersebut. Saat itu kendaraan umum masih jarang, hanya lewat delman, jarang-jarang. Itu pun biasanya sudah sesak oleh penumpang sejak dari Tolengas.
Saya lupa namanya, namun mata air itu merupakan satu dari tujuh mata air yang harus didatangi seseorang yang melakukan ‘laku ngabungbang’—mandi tengah malam di tujuh mata air, bagian dari ritual lama. Ngabungbang itu laku yang lumayan berat, karena untuk menjalaninya orang harus berjalan dari satu ke mata air lain di tengah dini hari buta untuk menyempurnakan prosesi. Sementara, tak hanya dingin, mata air-mata air itu umumnya berada di tempat-tempat sunyi yang dikeramatkan. Tak bisa mandi koboy, karena di setiap mata air itu pun prosesi mandi selalu dimulai dengan segala macam jangjawokan (mantra) yang rata-rata cukup panjang.
Di kaki bukit Kancana itu membentang jalan dari Tolengas ke Darmaraja, yang saat itu pun sudah beraspal. Peninggalan pemerintah kolonialis Hindia Belanda. Di kiri-kanan pinggiran jalan, berderet pohon-pohon Asam Jawa, dengan jarak antara sekitar lima meter. Inilah salah satu tujuan lain kami menyeberang.
Bila pohon-pohon itu tengah berbuah, lebatnya bukan main. Pohon-pohon itu kami panjati, buah-buahnya yang sudah masak kami petik. Beberapa anak kadang lebih suka buah yang belum sepenuhnya masak, masih ‘gunipung’ alias menjelang masak. Kami berebutan memanjat naik, mencari dahan dengan buah terlebat. Lalu di sana sesuka hati memetik asam yang sudah masak, merah terpisah dari cangkangnya. Beberapa terasa pas dengan namanya, kecut asam. Namun tak jarang manis. Apalagi bila dimakan dengan gula pasir yang tak jarang kami bawa. Dibungkus kertas, karena plastik masih sangat jarang kala itu. Sedang untuk pembungkus orang berjualan kopi pun yang dipakai adalah kararas atau daun pisang kering.
Puas berpesta asam Jawa, biasanya tinggal memetik untuk dibawa pulang ke rumah. Untuk diberikan kepada emak masing-masing, sekadar pembeli hati sudah bermain jauh dari rumah. Biasanya asam Jawa itu kami bawa dalam buntalan sarung. Kadang bila sedang beruntung dicegat pemilik warung, kami bisa pulang membawa uang untuk bekal jajan di sekolah selama hari-hari berikutnya. Tak banyak, paling Rp 10 dalam dua keping lima rupiahan bergambar burung. Bukan gambar Keluarga Berencana, yang datang kemudian. Paling untung dapat Rp25, uang logam bergambar burung dara mahkota. Bila dapat Rp 25, artinya uang jajan telah aman untuk lima hari ke depan! Kami tak banyak jajan, lebih terbiasa banyak makan. Sarapan, lalu siangnya ngawadang alias makan siang. Orang Sunda sebenarnya tak punya kebiasaan makan siang, karena ngawadang artinya makan wadang atau nasi sisa!
Sebagai anak kecil, waktu itu saya tak menaruh perhatian pada pohon-pohon asam di pinggir jalan tersebut. Apalagi saya baru keluar kota setelah SMP. Ke Depok, sendirian, menyambangi Uwak. Saya punya riwayat perjalanan jauh justru saat bocah. Keluar kampung halaman tahun 1973, waktu berumur tiga tahun, bersama Bapak yang harus menebang hutan di Sarolangun, Jambi dan sekitarnya, di saat musim Hak Pengusahaan Hutan (HPH) pertama. Kadipaten-Sarolangun saat itu harus ditempuh enam hari dengan bus, karena Jalan Lintas Sumatera pun waktu itu belum lagi ada! Alih-alih tol seperti saat ini.
Baru belakangan saya sadar, menanami pinggiran jalan dengan pohon Asam Jawa sepenuhnya kebiasaan Belanda yang tak lagi diikuti kita. Mungkin karena rasa jumawa untuk tak ikut gaya penjajah, atau apalah.
Kebiasaan itu mulai dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda sejak pembangunan Jalan Raya Pos dari Anyer (ujung barat Jawa) sampai Panarukan yang dibangun atas perintah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. K. Heyne, dalam “De Nuttige Planten van Nederlandsch Indie” yang terbit 1916, bercerita bahwa di sebuah jalanan Jakarta waktu itu, dirinya melihat 30-40 batang pohon Asam Jawa, berbaris rapi di pinggir jalan. “The Batavia heb ik een laan van 30 a 40 oude tamarindeboomen zien rooien voor het verbreeden van den weg,”tulis Heyne dalam buku itu. Pohon-pohon itu telah tua, paling tidak puluhan tahun usianya. Sayang, dalam buku itu pun Heyne tidak menjelaskan kapan pohon-pohon di Jakarta—bukan di jalan raya Pos—ditanam.
Dalam buku itu Heyne mengulas singkat alasan pemerintah Hindia Belanda menanami pinggiran jalan dengan Asam Jawa atau Tamarindus indica itu. Selain cocok untuk iklim tropis seperti Indonesia, Asam Jawa yang bukan tanaman asli Jowo itu sudah welbekende (terkenal) sebagai pohon yang fraaie (indah), sehingga cocok dijadikan hiasan jalanan. Daunnya juga tak akan menyusahkan penyapu jalan, tidak seperti pohon jati, misalnya, yang meski kayunya mahal, guguran daunnya di musim kemarau akan bikin senewen pasukan kuning kebersihan.
Alasan lainnya rasional dan ekonomis. Buahnya bisa dipetik, membantu pemasukan daerah. Di buku itu Heyne menulis adanya pengiriman Asam Jawa dari Bali ke Singapura. Ada pula detil catatan bahwa Pulau Madura, dan Timor pernah mengirimkan 344 ton Asam Jawa ke Sulawesi, hasil panen dari pohon-pohon asam jalanan itu. “Worden in Bangkalan groote voordeden getrokken van de boomen, die daar langs den postweg en eenige binnenwegen zijn aangeplant,” tulis Heyne.
Sayang, setelah merdeka pemerintah Indonesia tidak meneruskan kebiasaan itu. Padahal, selain telah tua, banyak di antara pohon-pohon itu yang mati meranggas karena ulah manusia tak bertanggung jawab. Di antaranya, mungkin beberapa dari kami, anak-anak Kadipaten yang saat itu kurang beradab.
Ternyata, saat main-main di pohon asam itu, tak sedikit dari kami yang bengal. Dengan golok ‘Si Cepot’ khas anak-anak Sunda, yang waktu itu wajar tersandang di pinggang masing-masing, beberapa anak memapas batang asam tua. Dengan ‘paneker’ atau pemantik api tradisional, bagian yang dipapas itu dibakar. Konon, asam tua gampang terbakar, baranya susah padam meski nyalanya tak pernah berkobar-kobar.
Atau dengan cara lain. Beberapa kami yang bengal memapas batang, lalu melumuri bagian kambium pohon Asam Jawa itu dengan terasi yang sengaja dibawa dari rumah. Meranalah pohon itu sebelum meranggas dan mati. Semoga alam dan Tuhan memaafkan kami. [dsy]