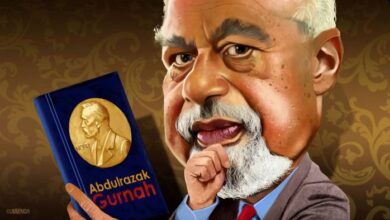Seorang penulis India, Vinay Lal, pernah menulis perihal tidak pernah diliriknya Mohandas Karamchan (Mahatma) Gandhi oleh Akademi Swedia untuk Nabel Perdamaian. Lal mengatakan, “Kita semestinya bangga Gandhi tidak pernah diberikan hadiah itu”. Maksudnya, pertama-tama Gandhi tidak selayaknya dikelompokkan dengan Theodore Roosevelt, Manachem Begin, Henry Kissinger, Simon Peres, Yitzhak Rabin, tetapi lebih-lebih sejatinya karena seseorang tidak memerlukan pengakuan dari Barat untuk menjadi ‘orang besar’.
Oleh : Darmawan Sepriyossa
JERNIH–Pertanyaan tersebut bukan hanya terlontar dari orang-orang Indonesia sendiri. Secetek pengetahuan saya, pertanyaan seperti itu setidaknya juga terlontar dari—setidaknya, karena mereka menuliskannya langsung–dua orang Indonesianis serta cendikiawan terkemuka dunia. Mereka adalah Benedict RO’G Anderson, salah satu pemikir ilmu sosial paling penting di abad 20, yang senantiasa dihubungkan dengan Cornel paper yang fenomenal itu, serta cendikiawan asal Prancis, Henri Chambert Loir. Karena keduanya Indonesianis, baiklah kita sebut saja mereka Ben dan Henri.

Bagi saya, itu artinya sebuah pengakuan dari cendikiawan kelas dunia bahwa sejatinya banyak, atau paling tidak, ada pengarang Indonesia yang karyanya pantas untuk mendapatkan Nobel Sastra.
Ben, misalnya, mempertanyakan mengapa sejak 1901, pemberian pertama Nobel Susastra, tak pernah ada satu pun pemenang dari Asia Tenggara. Semua wilayah di dunia bisa membanggakan sastrawannya pernah menang, hanya Asia Tenggara yang tidak.
Tetapi, baik Ben maupun Henri, masing-masing menjawab sendiri pertanyaan mereka. Menurut Ben, salah satunya karena ‘nasionalisasi bahasa’ yang dilakukan. Negara-negara Asia Tenggara tidak hanya memerdekakan diri secara fisik dari penjajahnya dari Eropa, tapi juga dari sisi bahasa. Vietnam, Kamboja, dan Laos tidak memakai bahasa negara yang menjajah mereka, Prancis. Filipina ogah memakai bahasa Spanyol. Birma, Malaysia, Singapura dan Brunei juga tidak menggunakan bahasa Inggris; dan Indonesia “nehi” memakai bahasa Belanda.
Akibatnya, terputuslah kaitan dengan bahasa-bahasa Eropa, sehingga makin jauhlah sastra Asia Tenggara dari jangkauan hadiah Nobel. Sementara, di sisi lain, hampir semua penerima Nobel Susastra, karyanya menggunakan bahasa kolonial—Inggris dan Prancis. Padahal, kata Ben, tak bisa kita mengklaim bahwa suatu bahasa lebih indah daripada bahasa lain. Seluruh bahasa harus didudukkan secara setara, sehingga memungkinkan karya dengan bahasa lain bisa diterima.
Sementara Henri dalam tulisannya “Hadiah Nobel Sastra Dilihat dari Indonesia” yang diangkatnya dalam dua seminar masing-masing di Kuala Lumpur (2007) dan di Jakarta 2008, mengemukakan berbagai kemungkinan terjadinya hal itu. Pertama, menurut Henri, meski setiap tahun para juri itu membaca 200-an karya sastra, mereka hanya membaca karya sastra yang ditulis dalam bahasa Swedia, Inggris, Prancis dan Jerman. Jadi, karya susastra berbahasa Indonesia hanya mungkin dibaca manakala sudah ada terjemahan dalam setidaknya satu dari empat bahasa tadi.
Kedua, pengarang Indonesia baru akan menarik perhatian Akademi Stockholm—pelaksana Hadiah Nobel—kalau karyanya yang telah diterjemahkan itu berjumlah banyak. Dalam kasus Pramoedya Ananta Toer—penulis Indonesia yang selama beberapa dekade konon selalu disebut-sebut masuk pertimbangan juri–, karya-karyanya yang sudah diterjemahkan ke dalam empat bahasa itu, sangat terbatas. Berdasar data 2008, baru lima karya Pram yang mengalami penerjemahan. Padahal, pencalonan Pram disebut-sebut sudah dimulai pada 1980-an, antara lain dengan dukungan penulis Jerman pemenang Nobel Sastra, Gunter Grass.
Selain Pram, nama-nama pengarang Indonesia yang pernah disebut-sebut dalam kaitannya dengan Nobel Susastra adalah Mochtar Lubis dan YB Mangunwijaya (Romo Mangun). Ketiga nama itu, Pram, Mochtar dan Mangun, telah berpulang.
Apakah dengan tidak adanya pemenang Nobel itu sama artinya dengan miskinnya mutu sastra Indonesia? Henri menolak pandangan tersebut. Sebagaimana Ben, ia melihat hal itu lebih kepada lambannya Akademi Stockholm memperluas konsep sastra mereka keluar dari konsep “sastra Eropa”, yang saat Goethe menciptakan konsep “sastra dunia” (world literature), sejatinya itu terbatas pada konsep sastra yang sangat berciri Eropa itu.
Sementara, dalam surat wasiat yang ditulis Alfred Nobel di Paris pada 1895, menyangkut sastra, surat wasiat itu menyatakan, pertama, ditentukan bahwa Nobel akan diberikan kepada “orang yang, pada tahun sebelumnya, mempersem-bahkan manfaat yang besar kepada umat manusia”. Kedua, pengarang yang diberikan hadiah ialah “yang menghasilkan karva yang paling hebat berpaham idealis”. Ketiga, “kewarganegaraan tidak boleh diperhitungkan; orang terbaiklah yang harus menerima hadiah itu, baik orang Skandinavia atau bukan”.
Ada beberapa hal penting dalam kutipan itu. Hadiah diberikan kepada seorang pengarang untuk keseluruhan karyanya, namun diberikan pada kesempatan terbit sebuah karya penting pada tahun sebelumnya. Karya itu harus bukan saja hebat, tetapi juga “berpaham idealis”. Terjemahan resmi surat wasiat itu dalam bahasa Inggris mengatakan: “the most outstanding work in an ideal direction”. Ungkapan ini tidak begitu jelas. Kata Swedia “idealisk” dapat diterjemahkan sebagai “ideal” atau “idealistic”. Penafsiran kata itu oleh Panitia Nobel pernah berubah dari waktu ke waktu. Mula-mula mempunyai arti umum bernada filosofis, sekarang lebih cenderung ke paham politik.
Jangan salah, mungkin karena Nobel diyakini akan membawa kebanggaan bagi bangsa, di masa lalu selalu gagalnya Pram memunculkan beragam rumors. Misalnya, di masa itu beredar berbagai cerita mengenai peranan para duta besar Indonesia di Eropa, yang katanya ditugaskan rezim Orde Baru agar mencegah Pram mendapat Nobel. Para dubes itu konon juga sangat sibuk melobi pemerintah Swedia agar tidak memberikan Hadiah Nobel kepada Pram.
Tentu saja cerita itu isapan jempol belaka. “Bukan karena Kementerian Luar Negeri saat itu tdak menaruh perhatian perhatian kepada Pram dan Nobel,”kata Henri, “tetapi karena pasti Akademi Stockholm tidak pernah berminat pada ulah dubes tertentu dari negara tertentu.”
Tetapi memang Pram pun punya persoalan khusus dalam urusan Nobel Susastra ini. Salah satu hal yang pasti memberatkan Akademi Stockholm dalam urusan Pram, tulis Henri, memberikan Nobel Sastra kepada Pram tidak hanya berarti mengakui mutu karya sastranya, melainkan juga mengakui kedudukan dan paham politiknya. Pram sebagai figur politik, tak begitu sesuai (untuk Nobel Sastra—penulis). Dia pernah menjadi anggota LEKRA selama beberapa tahun sehingga dekat dengan partai komunis. Orang Stockholm tak suka pada orang Komunis. Satu-satunya komunis yang mendapatkan Nobel Sastra adalah Pablo Neruda, pada 1971.
Apalagi Pram bukan “komunis yang baik”. Perannya dalam kancah sastra Indonesia di awal 1960-an merupakan noda di atas profilnya. Kita bisa melihat itu pada buku ‘lama’ tahun 1990-an, “Prahara Budaya”.
Wajar bila pada 1995, saat Pram menerima anugerah Hadiah Magsaysay, langsung Mochtar Lubis bersama 26 seniman Indonesia lainnya menulis surat protes kepada panitia di Manila. Mereka antara lain menyatakan: “Kami khawatir bahwa pemberian hadiah kepada Pramoedya sekaligus berarti pula bahwa Yayasan Hadiah Magsaysay membayarnya untuk tindakannya menindas kebebasan kreatif sejak awal perte-ngahan 60-an di Indonesia.” “Berarti di negerinya sendiri Pram dianggap tidak patut menerima tanda penghormatan internasional. Dan suara pas terdengar di Stockholm,”tulis Henri.
Menurut Henri ada alasan lain lagi kenapa Pram tidak dianugerahi hadiah Nobel. Alasan itu adalah kebetulan, ketidaktentuan, ketidaktahuan, keterlambatan. Pramoedya juga bukanlah satu-satunya pengarang yang oleh banyak kalangan dianggap pantas menerima Nobel, tetapi oleh Akademi Swedia tidak. Nasib ini juga dialami oleh para pengarang yang amat tersohor seperti Leo Tolstoy, Emile Zola, Thomas Hardy, Rainer Maria Rilke, Henry James, Franz Kafka. Marcel Proust, Loui-Ferdinand Céline, Hendrik Ibsen, Anton Chekov, Yukio Mishima, James Joyce, Vladimir Nabokov, dan banyak lagi nama lain.
Jorge Luis Borges juga satu pengarang ternama yang dilupakan Stockholm. Borges sering mengatakan: “Tidak memberikan Hadiah Nobel kepada saya telah menjadi satu tradisi Scandinavia. Mereka terus tidak memberikannya kepada saya setiap tahun sejak saya lahir”. Sebuah humor yang kelam, tentu.
Tapi Akademi pun tak lepas dari kritik dan hujatan. Setiap tahun, bahkan sejak Nobel Sastra pertama kali diberikan tahun 1901. Pemenangnya adalah penyair Prancis, René François Armand “Sully” Prudhomme. Namanya saja sekarang tak pernah lagi disebut, tertelan waktu. Ketika pilihan itu diumumkan, 42 pengarang Swedia menulis sebuah protes resmi untuk mencela pilihan itu dan mempertanyakan kenapa hadiah tidak diberikan kepada Leo Tolstoy.
Namun Akademi Stockholm juga punya serenceng alasan, kita mengerti atau tidak. Tolstoy dengan sengaja tidak terpilih oleh karena (menurut panitia) dalam karyanya dia menyebarkan paham “anarkisme teoritis dan aliran Kristen mistik”. Thomas Hardy tidak terpilih karena “tokoh-tokoh novelnya kurang memiliki nilai religius dan etika”. Emile Zola dipinggirkan karena karyanya dianggap “sinis dan kasar”. Hendrik Ibsen tidak terpilih karena “pikirannya negatif”, dan sebagainya.
Oh ya, kemauan Alfred Nobel agar hadiah diberikan kepada karya yang “‘berpaham idealis” sangat diindahkan panitia. Meski kata “idealis” itu rupanya semakin diberikan arti politik. Ideologi begitu penting dalam penilaian panitia, sehingga ada empat orang pernah terpilih meski bukan pengarang. Keempat orang itu adalah Theodof Mommsen (1902), Henri Bergson (1927), Bertrand Russell (1950), dan Winston Churchill (1953).
Mungkin saja ke depan, peluang Nobel Sastra diraih orang Indonesia itu masih ada. Setidaknya kalau melihat upaya Goenawan Mohamad menerjemahkan banyak karyanya, yang selama 50-an tahun lebih berkiprah di dunia kepenulisan, ke dalam banyak bahasa dunia.
Tetapi sebenarnya ada yang menarik dari wacana penganugerahan Nobel (Sastra) ini. Seorang penulis India, Vinay Lal, pernah menulis perihal tidak pernah diliriknya Mohandas Karamchan (Mahatma) Gandhi oleh Akademi Swedia untuk Nabel Perdamaian. Lal mengatakan, “Kita semestinya bangga Gandhi tidak pernah diberikan hadiah itu”. Maksudnya, pertama-tama Gandhi tidak selayaknya dikelompokkan dengan Theodore Roosevelt, Manachem Begin, Henry Kissinger, Simon Peres, Yitzhak Rabin, tetapi lebih-lebih sejatinya karena seseorang tidak memerlukan pengakuan dari Barat untuk menjadi ‘orang besar’.
Vinay Lal mengecam apa disebutnya “penjajahan mental” yang menurut dia “Lebih dahsyat akibatnya dibanding penjajahan ekonomi atau pendudukan politik”.
Padahal, kata Lal, “…suatu yang diam-diam dan menyeluruh dari penjajahan itu ialah bahwa kita, seperti juga orang-orang lain dalam dunia ‘berkembang’, terus saja merasa harus memandang ke Barat untuk membenarkan dan mengartikan kehidupan kita.” Obsesi kita, kata dia, dengan Hadiah Nobel Perdamaian yang tidak pernah diberikan kepada Gandhi sebagian hasil rasa marah karena beliau diremehkan. Tetapi sejatinya, kata Lal, itu lebih-lebih disebabkan oleh pikiran bahwa kehidupan kita tidak lengkap jika tidak diakui oleh Barat.” [INILAH.COM]