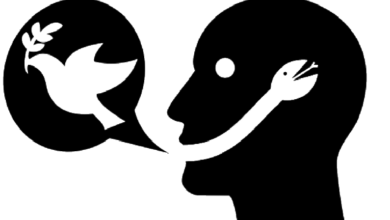Dedy menggunakan beberapa kerangka akademik, seperti teori komunikasi krisis W.T. Coombs, teori perdamaian Johan Galtung, hingga konsep tindakan komunikatif dari Jürgen Habermas. Ia menilai bahwa sejumlah langkah diplomasi Indonesia menunjukkan upaya mendorong multilateralisme dan mengurangi ketegangan, misalnya melalui tawaran kontribusi 20.000 pasukan perdamaian pada forum PBB.
JERNIH– Seorang mahasiswa Magister Komunikasi Krisis, Dedy Wijaya, merilis kajian berjudul “Kritik Komunikasi Krisis dan Jurnalisme Damai dalam Narasi Diplomasi Prabowo Subianto di Konflik Perdamaian Dunia”. Kajian tersebut membedah pola komunikasi Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai aktivitas diplomasi internasional sepanjang 2024–2025, serta menilai peluang dan tantangan strategi Indonesia dalam isu perdamaian global.
Kajian ini mengumpulkan sejumlah peristiwa diplomatik yang dilakukan Presiden Prabowo, mulai dari pidato di Sidang Majelis Umum PBB ke-80 pada September 2025, pernyataan terkait solusi dua negara untuk Palestina, hingga pertemuan dengan pemimpin Brasil, Rusia, Amerika Serikat, dan Malaysia. Penulis memetakan seluruh momen tersebut sebagai “data primer” untuk melihat konsistensi posisi Indonesia dalam navigasi geopolitik yang semakin tegang.
Dalam catatannya, Dedy menilai bahwa komunikasi diplomatik seorang kepala negara pada masa krisis global berfungsi jauh melampaui pernyataan politik. Ia menilai setiap pidato dan pertemuan internasional merupakan “intervensi strategis” yang dapat memengaruhi stabilitas regional maupun global. Karena itu, kajian tersebut menggunakan sejumlah teori komunikasi untuk membaca pesan, risiko, dan konsekuensi diplomasi Indonesia.
Pemaknaan Teoretis dan Tantangan Komunikasi
Dalam kajian itu, Dedy menggunakan beberapa kerangka akademik, seperti teori komunikasi krisis W.T. Coombs, teori perdamaian Johan Galtung, hingga konsep tindakan komunikatif dari Jürgen Habermas. Ia menilai bahwa sejumlah langkah diplomasi Indonesia menunjukkan upaya mendorong multilateralisme dan mengurangi ketegangan, misalnya melalui tawaran kontribusi 20.000 pasukan perdamaian pada forum PBB.
Namun, ia juga menilai ada tantangan struktural. Tawaran Indonesia itu, misalnya, tetap bergantung pada mekanisme Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto negara besar. Kondisi ini, menurut penulis, membuat berbagai langkah diplomasi berpotensi dipersepsikan sebagai retorika apabila tidak mendapat dukungan sistem internasional yang memadai.
Pada isu Palestina, kajian tersebut menyebut bahwa sikap Indonesia yang mendukung solusi dua negara dengan syarat keamanan tertentu bagi Israel dapat memunculkan reaksi pro dan kontra di dalam negeri. Penulis menilai bahwa komunikasi pemerintah perlu lebih menonjolkan diferensiasi antara dukungan kemanusiaan untuk Palestina dan aspek politis yang terkait pengakuan diplomatik.
Selain itu, keterlibatan Indonesia dalam BRICS dipandang sebagai ruang diplomasi baru yang menuntut keseimbangan posisi antara prinsip Bebas Aktif dan kedekatan dengan aliansi global tertentu. Menurut penulis, ketidakseimbangan pesan diplomatik dapat menimbulkan persepsi publik mengenai erosi otonomi kebijakan luar negeri.
Identifikasi Risiko dan Rekomendasi
Dalam bagian kritik, kajian ini memetakan beberapa risiko komunikasi, antara lain:
-tawaran pasukan perdamaian yang bisa dianggap retoris bila tidak diikuti langkah konsensus internasional,
-risiko reaksi balik terhadap gagasan pengakuan Israel bersyarat,
-potensi kesalahpahaman publik mengenai kedekatan Indonesia dengan AS maupun BRICS,
-serta kemungkinan erosi citra Bebas Aktif bila komunikasi antar-forum internasional tidak konsisten.
Penulis kemudian mengajukan sejumlah rekomendasi, seperti perlunya konsolidasi diplomatik sebelum pengajuan proposal perdamaian, peningkatan transparansi dalam isu Palestina, serta konsistensi pesan Indonesia di forum multilateral. Ia juga menyarankan penggunaan komunikasi yang lebih dialogis untuk menjaga posisi Indonesia sebagai mediator yang kredibel.
Kesimpulan Kajian
Kajian tersebut menutup dengan penilaian bahwa Indonesia berupaya memosisikan diri sebagai aktor perdamaian melalui komunikasi diplomatik yang proaktif. Namun, efektivitas strategi itu sangat bergantung pada keselarasan antara pernyataan dan tindakan, serta kemampuan pemerintah mengelola persepsi di tingkat domestik dan global.
Penulis menyebut bahwa diplomasi perdamaian membutuhkan konsistensi, kesiapan struktural, dan kemampuan membaca dinamika geopolitik yang cepat berubah. Tanpa hal tersebut, pesan perdamaian Indonesia berisiko dianggap sebagai retorika dan tidak menghasilkan dampak konkret di arena internasional. [ ]