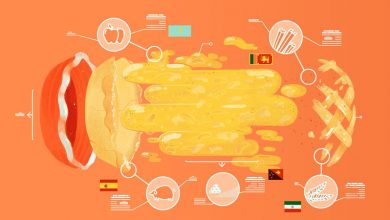Tulah Baliung, Makanan Khas Lemah Sugih yang Orang Majalengka Pun Lupa
MAJALENGKA– Tatar sunda selain terkenal karena keindahannya juga kaya dengan keragaman kulinernya. Namun terdapat beberapa kuliner yang dikenal luas masyarakat saat ini. Salah satunya adalah baliung yang merupakan makanan khas yang hanya terdapat di beberapa tempat saja.
Nama Baliung sebagian makanan khas hanya terdapat di majalengka, namun padanan dari makanan ini terdapat juga di Sumedang dan Lebak dengan nama laksa.
Baliung atau laksa tidak saja makanan khas namun merupakan makanan kuno yang tidak saban wayah didapatkan karena hanya dibuat dan diajikan dalam waktu tertentu saja.
Di Majalengka, baliung hanya dapat dinikmati setahun sekali dalam tradisi Buku Taun yang masih diselenggarakan di beberapa desa. Wajar jika cukup sulit untuk mendapatkan baliung karena tempat dan waktu pembuatannya yang terbatas. Tiga desa di Majalengka yang masih mengolah baliung di antaranya Desa Cipasung dan Desa Borogojol di Kecamatan Lemah Sugih dan Desa Suniabaru di Kecamatan Banjaran.
Di tiga desa tersebut tradisi Buku Taun masih diselenggarakan sebagai tanda syukur masyarakat atas berkah dari yang Maha Kuasa di setiap akhir tahun, sekaligus menyambut datangnya bulan Muharam dalam tahun baru Islam.
Proses untuk membuat baliung disebut ngalaksa. Sedangkan ngalaksa itu sendiri merupakan bagian dari tradisi di tatar sunda yang dilaksanakan di tempat lainnya seperti di Kanekes (Baduy) Kabupaten Lebak, Banten dan Rancakalong, Sumedang. Di dua tempat tersebut laksa adalah nama makanan yang dibuat untuk kepentingan acara adat. Warga Kanekes membuat laksa sebagai ungkapan syukur setelah melaksanakan ritual Kawalu, sedangkan di Rancakalong sebagai syukuran panen padi dan penghormatan terhadap Dewi Sri. Maka hubungan antara baliung dan laksa adalah eta-eta keneh.
Prosesi ngalaksa merupakan tradisi ritual yang sarat dengan nilai kearifan lokal yang di dalamnya selalu menghadirkan proses pembuatan makanan dari bahan tepung beras yang diolah secara tradisional. Di Rancakalong maupun di Cipasung proses pembuatannya sama. Di Cipasung pembuatan baliung dikerjakan beberapa hari sebelum puncak acara Tutup Taun yang diselenggarakan di pelataran tanah tepian Situs Cikencong yang berada di kawasan situs sejarah Gunung Ageung.
Menjelang tutup Buku Taun di Cipasung, kaum dapuran, yakni para emak-emak dan mojang, akan disibukan membuat baliung di dapurnya masing-masing. Dari mencari daun congkok untuk bungkus baliung, memeram beras yang sudah dicuci bersih lantas dipermentasi dengan cara ditutup dengan daun sejenis talas selama beberapa hari, sampai kemudian dibuat tepung dan siap menjadi Baliung. Pembuatan tersebut tidak menggunakan bumbu apa pun dan wanita yang mengolah baliung tidak boleh dalam keadaan haid.
Tanda bahwa baliung tengah diolah dapat dicirikan tanpa mesti menggeruduk masuk dapur, karena aroma baliung yang khas akan tercium sampai keluar rumah. Di gang, di pekarangan sampai ke jalan akan tercium aroma baliung yang sangat menyengat. Kata yang umum untuk menyebut aroma tersebut sesungguhnya adalah bau. Bau yang mendekati busuk.
Namun uniknya warga Cipasung tidak berani mengatakan bau busuk, namun bau tersebut harus disebut wangi.
Rupanya ada kepercayaan tentang aroma baliung yang tidak lajim itu, bahwa barang siapa yang mengolok-olok aroma tersebut, maka akan katulah menjadi penikmat baliung. Dan itu bukan omong kosong. Fakta di masyarakat pendukung baliung menunjukan bahwa banyak para penikmat baliung awalnya terjerumus karena menghina baunya. Dari sanalah muncul istilah ‘dipoyok dilebok’ atau kalau dalam Bahasa Inggris, sudah dihina, digares pula.
Tulah itulah yang menimpa keluarga Hamdan Hidayatuloh alias Ki Balung Karuhun, penggiat budaya dan sejarah dari Talaga. Dulu ia dan istrinya selalu moyok bau baliung, kini mereka menjadi pemburu baliung di setiap Tutup Taun. Ki Balung mengatakan bahwa baliung bisa awet sampai dua bulan dan baunya pun akan semakin ‘harum’ seiring lama disimpan.
Baliung yang telah bulukan, menurut dia, bahkan terasa muaknyus untuk menemani minum kopi. Caranya, Baliung yang sudah agak keras itu diiris-iris tipis kemudian digoreng dan disantap sambil ngopi.
Puncak tradisi Ngalaksa dalam Buku Taun di Cipasung menampilkan prosesi pembuatan baliung yang unik dan melibatkan banyak orang. Sehari sebelum acara digelar panitia telah menyiapkan berbagai sarana untuk ngalaksa. Alat-alat untuk ngalaksa yang paling penting adalah cacadan yaitu alat yang terbuat dari kayu dan berbentuk belincong yang di bagian tengahnya terdapat lobang selongsong berdiameter 12 cm dan tembus ke bawah cacadan. Fungsinya untuk memeras adonan tepung beras sampai merecet keluar. Cret! Bagian pangkal lobang tersebut dililit kuat dengan rotan.
Alat untuk menekan tepung beras yang matang dalam cacadan tersebut sejenis alu yang panjangnya sekitar 35 cm dan diameternya masuk ke dalam lubang cacadan tersebut.
Alu tersebut nantinya digencet oleh batang pohon yang diatur melintang dan panjangnya lebih dari 5 meter. Salah satu ujung batang pohon tersebut dikaitkan di tanah. Sedangkan ujung lainnya digunakan sebagai pengungkit untuk ditekan ke bawah beramai-ramai oleh kaum lelaki.
Pada gencetan pertama, adonan baliung yang merecet tersebut berbentuk seperti lembaran mie akan dipotong oleh seorang gadis perawan. Proses menggencet adonan baliung terus dilakukan berulang-ulang dengan kegembiraan, sampai adonan tersebut habis. Setiap adonan yang telah digencet kemudian dibungkus oleh daun congkok dan dibagikan kepada masyarakat yang sudah berkumpul menunggu jatah baliung.
Kegiatan ngalaksa di Cipasung awalnya dilaksanakan di suatu tempat bernama Panglaksaan kemudian pindah ke Nyatuh. Terakhir dilaksanakan di tepi Situ Cikencong. Tradisi tersebut telah dilestarikan turun temurun. Tujuh generasi sebelumnya yang menurunkan tradisi tersebut sampai generasi terakhir adalah Buyut Moja Laksabuana, Buyut Salur,Buyut Ipang, Aki Satria, Aki Arja dan saat ini dilanjutkan oleh Abah Enceng Obing. Sedangkan pemangku adat yang menjadi sesepuh ngalaksa di Cipasung adalah Abah Jeje Miharja.
Kata ngalaksa, terdapat pada teks naskah kuna ‘Swawarcinta’ yang berbunyi “na kancra dilaksa-laksa“. Kalimat tersebut berkaitan dengan Teknik memasak Sunda kuna yang sejauh ini belum dapat dipastikan bagaimana praktiknya.
Namun dari cara tradisi ngalaksa di Cipasung, dapat diperkirakan bahwa “dilaksa-laksa” bisa saja merupakan proses bahan makanan yang telah menjadi tepung beras kemudian diseupan (dikukus) lantas digenjet sampai merecet. Hasilnya dibungkus dalam jumlah banyak untuk dibagikan kepada masyarakat.
Adanya tradisi ngalaksa yang sarat dengan kekunoan tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah di Cipasung, yaitu dengan keberadaan Situs Gunung Ageung yang banyak menyimpan peninggalan arkeologis berupa tradisi megaliitik yang berwatak Hindu-Buddha di dalamnya. Maka dapat dikatakan bahwa tradisi Ngalaksa merupakan artefak budaya dari masa pra-Islam yang masih lestari sampai masa kini. [pdr]