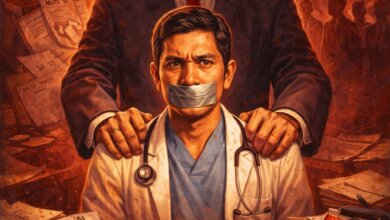Bencana yang meluluhlantakkan Sumatera bukan hanya datang dari langit. Ia juga lahir dari tanah yang dilukai, hutan yang ditebang, dan pemerintah yang terlalu sering menunda—hingga alam sendiri yang membalas.
JERNIH – Akhir November 2025 seharusnya menjadi alarm besar bagi pemerintah daerah se-Sumatera. BMKG telah memperingatkan bahwa bibit siklon 95B di Selat Malaka berkembang menjadi Siklon Tropis Senyar, bergerak menuju Aceh dan Sumatera Utara dengan membawa ancaman hujan ekstrem, angin kencang, dan gelombang tinggi.
Dalam 24–48 jam ke depan, risiko banjir bandang, longsor, dan gelombang besar diproyeksikan melanda Aceh, Sumut, Sumbar, hingga Riau. Namun peringatan itu pada akhirnya menghantam daratan yang sudah lama rapuh, sebuah wilayah yang selama bertahun-tahun diabaikan dari sisi ekologinya.
Dampaknya kini tampak terang benderang: Sumatra utara dan barat mengalami salah satu bencana hidrometeorologi terbesar dalam sejarahnya. Di Aceh, ribuan rumah terendam dan lebih dari 5.900 orang mengungsi. Kondisi di Sumatera Utara dan Sumatera Barat bahkan lebih tragis: lebih dari 105 korban jiwa ditemukan—mayoritas di Tapanuli Tengah dan Sibolga—sementara 81 orang masih hilang.
Total pengungsi mencapai 29.000 jiwa, dan sistem kelistrikan lumpuh setelah lima tower SUTT 150 KV tumbang. Jembatan ambruk, jalan lintas Sumatra terputus di berbagai titik, dan banyak daerah terisolasi sepenuhnya. Itu data yang terhimpun sampai 28 November 2025 sore.
Senyar bukan badai biasa. Ia diperkuat oleh Gelombang Rossby Ekuator dan kondisi geografis Sumatra yang berbukit, membuat tanah cepat jenuh dan sangat rentan longsor. Namun satu kenyataan tak bisa dielakkan: curah hujan ekstrem itu menghantam lahan dan hutan yang sudah lama kehilangan ketahanan ekologisnya.
Fenomena siklon dekat khatulistiwa memang jarang, tetapi bukan mustahil. Senyar terbentuk di sekitar 5° LU—cukup untuk gaya Coriolis menciptakan pusaran—sementara laut hangat Selat Malaka menyediakan energi uap air yang besar. Ketika hujan turun, curahannya tidak sekadar deras, melainkan brutal. Yang membuatnya mematikan bukan Senyar semata, melainkan daratan yang telah kehilangan kemampuan alaminya untuk menahan air, mengatur limpasan, dan meredam bencana.
Daerah aliran sungai (DAS) di Sumatera kini bekerja melampaui kapasitasnya. Hutan yang menyusut, permukaan tanah yang tertutup beton, serta drainase perkotaan yang tidak dirancang menghadapi curah hujan ekstrem membuat air langsung berubah menjadi aliran permukaan—cepat, besar, dan tak terkendali.
Di kawasan hulu, hutan yang dulu rimbun telah berubah menjadi area perkebunan, lahan tebangan, atau tanah terdegradasi. Tanpa akar pohon, tanah menjadi rapuh, dan hujan ekstrem membuatnya jenuh dalam hitungan jam sebelum runtuh sebagai longsor besar yang mengubur rumah dan penduduk. Penelitian global telah lama menegaskan bahwa kehilangan hutan meningkatkan frekuensi dan keparahan banjir, bahkan saat curah hujan tidak ekstrem.
Bukti paling telanjang dari degradasi hutan muncul melalui kayu-kayu log besar yang terseret banjir bandang, bukan ranting kecil atau pohon tumbang belaka. Potongan-potongan kayu itu membentuk bendungan sementara di sungai dan alur air; ketika jebol, gelombang air dan debris menghantam permukiman dengan daya rusak berkali lipat. Di sinilah tampak jelas bahwa bencana alam sering kali memperlihatkan luka ekologis yang sudah terjadi jauh sebelum badai datang.
Organisasi lingkungan seperti Walhi dan Greenpeace sudah lama memperingatkan bahwa bencana semacam ini bukan murni peristiwa alam, tetapi akumulasi kesalahan manusia.
“Banjir dan longsor bukan hanya akibat hujan deras — ini adalah krisis ekologi yang panjang, buah dari perusakan hutan dan alam kita,” tegas Walhi dalam pernyataannya. Greenpeace juga berulang kali menyoroti lemahnya perlindungan kawasan hutan dan tata ruang, yang membuat Indonesia seperti terus membuka pintu bagi bencana.
Ilmu hidrologi sejak awal abad ke-20 pun telah menunjukkan korelasi kuat antara deforestasi, perubahan tata guna lahan, dan peningkatan risiko banjir besar. Ketika tanah kehilangan vegetasi, ia kehilangan kemampuan menyerap air—dan banjir menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan.
Teori “Perubahan Penggunaan Lahan Memperkuat Risiko Banjir” menegaskan bahwa campur tangan manusia pada lanskap secara radikal mengubah cara daerah aliran sungai (DAS) merespons hujan. Ketika permukaan alami yang mampu menyerap air diganti oleh beton, aspal, dan bangunan, kemampuan tanah untuk meresapkan air (infiltrasi) menurun drastis.
Urbanisasi menciptakan permukaan kedap air yang membuat air hujan langsung mengalir sebagai limpasan permukaan, membebani drainase kota dan meningkatkan debit sungai secara tiba-tiba. Dalam kondisi hujan ekstrem, sistem buatan yang semula dirancang untuk mengalirkan air dengan cepat justru mempercepat terjadinya banjir di hilir.
Di wilayah hulu, deforestasi memperburuk keadaan. Hutan yang semula berfungsi mengintersepsi air hujan, memperlambat alirannya, dan membantu tanah menyerap air kini hilang digantikan perkebunan atau lahan terbuka. Tanpa akar pohon, tanah menjadi padat sehingga kapasitas infiltrasi merosot tajam.
Akibatnya, hujan lebat yang seharusnya diserap sebagian oleh tanah berubah hampir seluruhnya menjadi limpasan permukaan yang bergerak cepat dan dalam volume besar. Debit puncak (peak flow) sungai meningkat berkali lipat, membuat banjir lebih sering dan lebih destruktif dibandingkan ketika hutan masih utuh.
Pada saat yang sama, perubahan pada alur sungai—meluruskan, membeton, atau menormalisasi saluran—menciptakan efek domino. Meski dimaksudkan untuk mengurangi banjir lokal, tindakan ini justru meningkatkan kecepatan aliran air, menghilangkan kesempatan sungai untuk meluap secara alami ke dataran banjirnya.
Dampaknya, wilayah hilir menerima limpasan dalam jumlah besar secara mendadak, sehingga banjir besar lebih mudah terjadi dan merusak area yang jauh lebih luas serta lebih padat penduduk. Dalam kombinasi, urbanisasi, deforestasi, dan modifikasi saluran sungai membentuk mekanisme yang menegaskan satu kesimpulan: perubahan penggunaan lahan secara sistematis memperkuat risiko banjir jauh melampaui sekadar faktor cuaca.
Karena itu, tanggung jawab pemerintah sejatinya bukan lagi opsional, tetapi wajib dan mendesak. Pemerintah tidak bisa hanya hadir ketika bencana sudah terjadi. Respon darurat memang penting, tetapi pencegahan struktural jauh lebih penting dan lebih murah biayanya, baik finansial maupun kemanusiaan.
Pemerintah harus menghentikan deforestasi dan melindungi kawasan hulu yang menjadi penopang keselamatan DAS, menegakkan aturan tata ruang yang selama ini mudah diabaikan, mengembangkan sistem peringatan dini yang terintegrasi hingga ke desa-desa rawan, serta merehabilitasi hutan dan lahan kritis melalui reboisasi dan restorasi ekosistem.
Selain itu, kesiapsiagaan masyarakat harus dibangun secara serius, bukan hanya mengandalkan infrastruktur fisik yang sering kali rentan. Izin industri ekstraktif juga harus diawasi dengan ketat, karena banyak di antaranya menjadi pemicu utama kerusakan ekologis.
Fakta paling menyakitkan ini tidak dapat disangkal: Senyar memang membawa hujan ekstrem, tetapi manusialah yang menyiapkan panggung bagi kehancurannya. Jika pemerintah hanya sibuk memadamkan krisis tanpa pernah memperbaiki akar masalahnya, tragedi serupa—atau bahkan lebih besar—bukan hanya mungkin, tetapi pasti akan datang kembali.(*)
BACA JUGA: Siklon Tropis Senyar, Badai Langka di Selat Malaka