
Padahal, dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, gagasan brilian dapat lahir dari mana saja, bahkan dari daerah yang selama ini dianggap pinggiran. Justru di tempat seperti itulah inovasi sering muncul karena kedekatan dengan persoalan nyata rakyat. Ketika kebijakan yang efektif dan membumi seperti milik Dedi tidak segera ditiru, yang dirugikan bukan hanya rakyat Jawa Barat, tapi juga masyarakat di daerah lain yang membutuhkan pendekatan serupa.
Oleh : Kemal H. Simanjuntak*
JERNIH—Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi adalah sosok yang unik dalam lanskap politik Indonesia. Ia menolak pendekatan elitis dan tampil apa adanya: sederhana, bersahaja, dan dekat dengan masyarakat kecil.
Kebijakannya—mulai dari revitalisasi pasar tradisional, pelestarian budaya lokal, hingga reformasi birokrasi berbasis pelayanan langsung—mendapat sambutan hangat dari rakyat. Namun, anehnya, penerimaan yang positif di level akar rumput itu tidak diikuti oleh sikap serupa dari kalangan elit politik di provinsi lain. Jakarta dan Jawa Tengah, dua wilayah strategis dengan pengaruh politik besar, tampak enggan meniru langkah-langkah Dedi. Padahal substansi kebijakannya terbukti efektif dan relevan. Ini bukan soal isi kebijakan, melainkan soal siapa yang membuatnya.
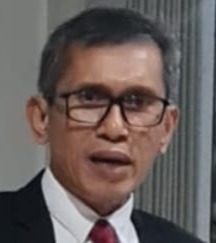
Lingkungan politik Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh logika hierarkis dan simbolik. Politik nasional kita belum sepenuhnya terbebas dari warisan feodalisme modern, di mana ukuran kepemimpinan lebih sering ditentukan oleh gelar, latar belakang militer, partai besar, atau pengalaman panjang di lingkar kekuasaan pusat. Tokoh-tokoh seperti Pramono Anung, yang pernah menjadi menteri sekretaris kabinet, dan Ahmad Luthfi, mantan Kapolda yang kini menjadi gubernur Jawa Tengah, berasal dari jalur kekuasaan yang dianggap mapan. Mereka memiliki modal simbolik yang tinggi—status, koneksi, dan citra nasional—yang membuat mereka terbiasa menjadi panutan, bukan pengikut.
Dalam konteks ini, mereka sangat mungkin merasa canggung, bahkan terancam secara simbolik, jika harus mengakui keberhasilan seseorang seperti Dedi Mulyadi yang datang dari pinggiran dan tidak memiliki “trah” kekuasaan.
Padahal, dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, gagasan brilian dapat lahir dari mana saja, bahkan dari daerah yang selama ini dianggap pinggiran. Justru di tempat seperti itulah inovasi sering muncul karena kedekatan dengan persoalan nyata rakyat. Ketika kebijakan yang efektif dan membumi seperti milik Dedi tidak segera ditiru, yang dirugikan bukan hanya rakyat Jawa Barat, tapi juga masyarakat di daerah lain yang membutuhkan pendekatan serupa.
Pierre Bourdieu menjelaskan dalam teori medan kekuasaan bahwa legitimasi sering kali ditentukan bukan oleh efektivitas gagasan, melainkan oleh siapa yang menyampaikan. Dedi, sebagai mantan bupati dari Purwakarta, tidak dianggap berada dalam posisi simbolik yang setara untuk diteladani. Ini adalah bentuk dominasi simbolik yang menjadikan hierarki status lebih menentukan daripada substansi.
Maka, resistensi terhadap kebijakan Dedi bukan semata karena perbedaan politik, tetapi karena tidak ingin mengurangi status diri dengan mengakui keberhasilan orang yang dianggap “tidak satu kelas”.
Dalam kacamata psikologi sosial, ini dapat dijelaskan melalui efek kredibilitas sumber: gagasan yang datang dari luar lingkaran “ingroup” akan cenderung diabaikan atau diragukan. Apalagi jika sumbernya tidak memiliki status sosial yang tinggi di mata sesama elit. Dalam situasi seperti itu, yang terjadi bukan evaluasi objektif terhadap substansi kebijakan, melainkan reaksi emosional untuk mempertahankan status dan eksklusivitas.
Namun, politik seharusnya tidak semata menjadi panggung pertarungan gengsi. Pemimpin daerah, apalagi di era digital dan keterbukaan informasi seperti sekarang, harus mulai menumbuhkan keberanian untuk belajar dari siapa pun. Keberhasilan Dedi dalam membangun narasi dan kebijakan berbasis nilai-nilai lokal serta pelayanan langsung pada masyarakat seharusnya menjadi inspirasi bersama. Bahwa gaya komunikasi rakyat, simbol-simbol budaya, dan pendekatan populis yang berakar bisa efektif justru karena menghidupkan kembali relevansi negara bagi warga biasa.
Sayangnya, kita masih hidup dalam iklim politik di mana pencitraan dan pengelompokan identitas jauh lebih diperhitungkan daripada evaluasi dampak nyata kebijakan. Politik meritokrasi yang seharusnya tumbuh dari semangat otonomi daerah justru sering terkubur oleh politik status dan gengsi sosial. Tak sedikit birokrat dan politisi daerah yang sebenarnya kagum terhadap cara Dedi memimpin, namun memilih bungkam karena khawatir dianggap “tidak setia” pada pola pusat atau “menurun” karena belajar dari yang tidak setara.
Ironisnya, situasi ini menghambat persebaran praktik baik lintas daerah. Padahal banyak tantangan yang dihadapi daerah bersifat serupa: ketimpangan pelayanan publik, budaya birokrasi yang lambat, hilangnya identitas lokal dalam pembangunan, hingga makin jauhnya hubungan antara pemimpin dan rakyat. Dalam tantangan-tantangan itu, pendekatan berbasis kearifan lokal dan keterlibatan langsung seperti yang dilakukan Dedi bisa menjadi jawaban.
Karena itu, perlu keberanian baru di kalangan pemimpin daerah lain untuk membuka diri terhadap sumber inspirasi yang mungkin tidak populer secara politik, namun relevan secara sosial. Kita membutuhkan suasana politik yang lebih rendah hati dan kolaboratif, bukan kompetisi simbolik yang menutup kemungkinan belajar dari “yang kecil”. Bahkan dalam ilmu manajemen modern, pembelajaran dari praktik lapangan (bottom-up learning) dianggap sebagai elemen penting dalam inovasi berkelanjutan.
Di titik ini, resistensi terhadap Dedi Mulyadi tidak lagi bisa dianggap wajar. Ia harus dikoreksi dengan kedewasaan politik yang mengedepankan dampak, bukan gengsi. Apalagi, masyarakat hari ini semakin kritis dan lebih peduli pada hasil daripada simbol. Bila pemimpin daerah enggan mengakui keberhasilan koleganya hanya karena persoalan simbolik dan status sosial, maka yang dikhianati bukan Dedi Mulyadi, tapi rakyat mereka sendiri.
Dan… ya, namanya juga manusia. Tapi kalau terus berlindung di balik alasan manusiawi untuk menutupi ketidakmauan belajar, maka yang gagal bukan hanya individu—tapi sistem kepemimpinan kita secara keseluruhan. [ ]
* Dr. Kemal H. Simanjuntak, MBA, GRCE, Konsultan Manajemen, GRC Expert, Asesor LSP Tatakelola, Risiko, Kepatuhan (TRK)







