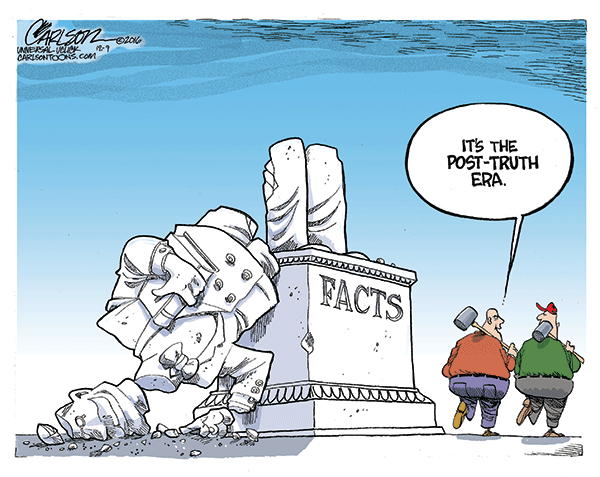Menimbang Demokrasi di Hari Kelahiran Amerika

Kalau pun ada yang menawarkan sistem Islam, itu pun tak luput dari perdebatan yang rumit. Paling tidak di tingkat terminologi atau pengistilahan. Karena selama ini “demokrasi” kadung dianggap sebagai “kekuasaan rakyat” atau kekuasaan yang mengutamakan hak-hak rakyat, maka opsi sistem Islam yang demokratis pun—karena juga datang dengan beragam variannya—oleh banyak kalangan dianggap haruslah disebut “demokrasi Islam”.
Oleh : Darmawan Sepriyossa
JERNIH–Ketika demokrasi di hari-hari ini makin mengecewakan karena dirasa tak banyak membawa angan-angan lama menjadi nyata, tak sedikit di antara kita pun mulai mempertanyakannya. Misalnya, buat apa demokrasi bila apa yang dianggap kekuasaan rakyat sejatinya lebih tepat disebut kekuasaan partai politik? Buat apa demokrasi, bila yang terpilih oleh konon mayoritas rakyat itu justru politisi mentah kemarin sore tanpa rekam jejak politik dan kepedulian yang berarti? Agaimana mungkin nasib rakyat diserahkan kepada politisi yang jauh dari sifat negarawan seperti itu?
Ternyata, fenomena yang sama juga terjadi dan dirasa rakyat Amerika (Serikat). Ketika kemiskinan, angka tuna wisma, kian merangkak baik di kehidupan keseharian AS, warga Abang Sam pun banyak yang memertanyakan peran demokrasi dalam kehidupan mereka. Belum lagi fakta, sementara negara terus menepuk dada sebagai kampiun demokrasi di dunia, penghormatan aparat negara terhadap warga—terutama kulit hitam dan berwarna—masih saja banyak buruknya. Kita bisa menunjuk muncul dan berkembangnya Gerakan “Black Lives Matter” sebagai bukyi otentik, betapa di AS pun hidup demokratis yang dicita-citakan itu masih jauh panggang dari api.
Fluktuasi kehidupan demokrasi
Guru besar sejarah dari Harvard University, Prof. Jill Lepore, pada 2020 lalu menulis sebuah artikel di media terkemuka, The New Yorker, yang sempat memancing derasnya reaksi publik. Pada artikel “The Last Time Democracy Almost Died” itu Lepore menceritakan kembali periode bergejolak di abad ke-20, ketika demokrasi hampir runtuh di seluruh dunia. Juga di AS. Sementara di Eropa, Jerman dan Italia segera memeluk (atau dipeluk) otoritarianisme dan fasisme, AS berhadapan dengan korupsi, monopoli, ketidaksetaraan, kekerasan politik, rasisme, dan pengangguran yang meluas.
Kondisi tersebut menciptakan kekhawatiran bahwa demokrasi mungkin tidak akan bertahan. Godaan untuk berganti beralih ke pemerintahan otoriter pun menanjak, seiring bayang-bayang ‘kemajuan’ yang didapat rezim fasis Mussolini di Italia, dan Adolf Hitler di Jerman.
Selama periode tersebut, banyak warga Amerika beralih ke ideologi ekstrem, baik komunisme maupun fasisme, untuk mencari solusi masalah yang dihadapi negara. Penulis terkenal Sinclair Lewis, menulis novel berjudul “It Can’t Happen Here“, dengan kengerian bahwa fasisme bisa saja terjadi di Amerika. Sampai-sampai ada film seperti “Mr. Smith Goes to Washington”, di mana aktor Jimmy Stewart memohon pada Kongres untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi.
Menurut Prof. Lapore, seperti mitos pengulangan pola sejarah (“le histoire se repete”), di tahun 1990-an, dengan berakhirnya Perang Dingin, banyak negara di seluruh dunia beralih ke demokrasi. Mirip dengan periode setelah Perang Dunia I. Namun, seperti pada tahun 1930-an, banyak dari negara baru demokrasi itu tidak bertahan lama. Di awal 2000-an, angin demokrasi di dunia mulai menurun lagi, dengan naiknya para pemimpin otoriter seperti Vladimir Putin di Rusia, Recep Tayyip Erdoğan di Turki, dan juga di Amerika Serikat dengan naiknya Donald Trump!
Kelebihan dalam kekurangan
Meski penuh kekurangan, seperti telah dirasa sepenjang sejarah, hingga saat ini boleh dibilang belum ada sistem yang memberi opsi sebaik demokrasi dalam kaitannya dengan hak-hak rakyat. Kalau pun ada yang menawarkan sistem Islam, itu pun tak luput dari perdebatan yang rumit. Paling tidak di tingkat terminologi atau pengistilahan. Karena selama ini “demokrasi” kadung dianggap sebagai “kekuasaan rakyat” atau kekuasaan yang mengutamakan hak-hak rakyat, maka opsi sistem Islam yang demokratis pun—karena juga datang dengan beragam variannya—oleh banyak kalangan dianggap haruslah disebut “demokrasi Islam”.
Padanya ada paradigma yang berubah. Keyakinan bahwa kekuasaan tertinggi tetaplah milik Allah, pencipta yang tunggal, dan bukan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Namun mekanismenya tetap mengutamakan suara rakyat, bukan suara mutlak seorang penguasa, apakah namanya raja, kaisar, sultan, atau pun khalifah.
Terma demokrasi Islam dianggap perlu, terutama karena dalam sejarah, demokrasi selalu dipandang datang sebagai antagonis, dan berlawanan diametral dengan kekuasaan absolut orang per orang, baik namanya raja, sultan, kaisar, khalifah, atau apa pun.
Pada sisinya yang memberi ruang humanis bagi peran warga, demokrasi masih paling ok. Apalagi dihadapkan pada fakta sejarah, bahwa tarikh Islam pun mengenal beragam jenis pengangkatan pemimpin tertinggi umat setelah Nabi SAW wafat. Penggantian Nabi ke Abu Bakar, Abu Bakar ke Umar, Umar ke Utsman, dan Utsman kepada Ali bin Abi Thalib, tak satu pun yang sama sejenis. Di sana terangkum baik pemilihan, pengangkatan, pemilihan dengan perwakilan, dan sebagainya sebagaimana analisis banyak ahli politik sepanjang masa.
Perbaikan sepanjang peradaban
Banyak fakta bahwa AS pun tidak selalu memenuhi syarat untuk sebagai negara demokrasi sejati. Paling tidak sampai keluarnya Undang-Undang Hak Sipil tahun 1964 dan Undang-Undang Hak Voting tahun 1965, yang lebih menjamin dan memenuhi syarat untuk kesetaraan politik. Namun, sejak itu pun demokrasi Amerika tidak terus maju, melainkan sering mengalami kemunduran, seperti yang ditunjukkan oleh penurunan peringkat negara dalam Indeks Demokrasi Dunia.
Demikian pula degan demokrasi kita di Indonesia. Sejak 1998, karena ingin “benar-benar menegakkan” demokrasi, pada tahun ke 26 pasca-Reformasi, yang kita temui tetaplah kedegilan politik. Ternyata ada banyak hal lama yang mungkin dalam hal-hal tertentu jauh lebih demokratis dibanding saat ini.
Menurut Lepore, salah satu paradoks dari demokrasi adalah, bahwa cara terbaik untuk mempertahankan demokrasi adalah dengan mengkritiknya. Demokrasi Amerika pada tahun 1930-an memiliki banyak pengkritik, dari sayap kiri dan kanan, yang menuntut banyak perbaikan dari sistem tersebut. W. E. B. Du Bois, seorang pemimpin hak-hak sipil, saat itu memprediksi bahwa Amerika tidak akan bertahan jika tidak memenuhi kewajibannya terhadap martabat dan kesetaraan semua warganya.
Artinya, sebagaimana kita bisa berkata bahwa menjadi Muslim itu sebuah proses harian, mingguan, tahunan dan seterusnya, begitu pula menjadi negara demokratis. Sepanjang itu, warga terus memperbaiki dengan aneka kerja, dengan tujuan terus memperbaiki dan membuat inovasi. Bila Lepore menyoroti orang-orang seperti guru, pustakawan, penyair, aktivis hak-hak sipil, dan reporter investigasi adalah mereka yang bekerja keras untuk mempertahankan demokrasi Amerika, begitu pula kita di sini.
Karena itu, modal dan prasyarat utama untuk itu adalah partisipasi aktif warga, Dalam artikelnya Prof Jill Lepore menekankan bahwa demokrasi tidak pernah dijamin keberlanjutannya. Tapi yang jelas, demokrasi membutuhkan keterlibatan aktif dari warganya untuk bertahan dari ancaman. Melalui kritik yang konstruktif, partisipasi aktif dalam debat publik, dan komitmen untuk keadilan sosial, demokrasi bisa terus hidup dan berkembang.
Mungkin benar bahwa dalam demokrasi Indonesia saat ini partai-partai politik tak lebih dari palasik yang menghisap darah dari tubuh demokrasi? Manakala parlemen, pengadilan, kejaksaan, polisi, bahkan media massa telah nyaris menjadi semacam rumah bordil, di mana kaum kaya bisa membeli sukma dan raga manusia, suara, bahkan nilai-nilai kebenaran.
Namun tetap saja kita akan sepakat dengan apologia Reinhold Niebuhr. Ia berkata, bahwa kapasitas kita untuk berbuat adil, menjadikan demokrasi itu mungkin. Tetapi kecenderungan manusia untuk berbuat curang, menjadikan demokrasi mutak diperlukan. [ ]