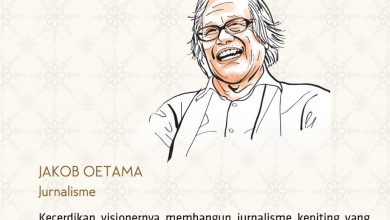Selama masa magang dan kemudian menjadi karyawan tetap itulah hampir setiap pekan saya selalu melihat seorang “anak kecil” yang sering mengetik di luar kelompok meja redaksi, dan kemudian menghilang tanpa sempat bersosialisasi dengan yang lain, kecuali dengan Redaktur Olahraga, Valens Doy.
Oleh : Noorca M Massardi
JERNIH– Pada 1972 – 1976, bersama Tjok Hendro, Dharnoto, Tizar Purbaya (alm), Annie Rai Samoen, Rani Rivai (almh), saya bergabung dengan Grup Teater Lisendra Buana pimpinan Tjok Hendro (meninggal 8 Maret 2018 di Tegal).
Grup Lisendra sebelumnya dikenal dengan nama Lisendra RYC (Remaja Yudha Club) di bawah payung Harian “Berita Yudha,” dan kemudian berganti menjadi Lisendra RIC (Remaja Indonesia Club) di bawah payung Harian “Berita Buana” (karena nama “Berita Yudha” diambil kembali oleh Angkatan Darat).

Baik RYC maupun RIC, wadah kegiatan remaja yang dibentuk oleh dan dalam edisi Minggu (“Yudha Minggu” dan kemudian “Buana Minggu”), itu dipimpin oleh Mas Toto Ariyanto S (1946-2011), penulis tetap kolom “Teenie’s Boy” yang terkenal di “Yudha Minggu” dan “Buana Minggu,” sebelum ia kemudian mendirikan dan memimpin Lembaga Pendidikan InterStudi. Mas Toto AS sendiri memberikan kebebasan sepenuhnya kepada pelbagai kelompok remaja yang bernaung di bawah RYC/RIC itu, baik untuk kegiatan prakarya, kerajinan, tari, teater, bahkan mendaki gunung. Dan, saat itu RYC/RIC merupakan satu-satunya kelompok remaja yang aktif dalam pelbagai kegiatan kreatif dan terkenal di Jakarta dan Indonesia, karena setiap aktivitasnya selalu diliput sendiri dan dipublikasikan di koran edisi Minggu itu.
Setelah sempat berkiprah di Teater Ketjil pimpinan Arifin C. Noer (10 Maret 1941 – 28 Mei 1995) selama beberapa tahun, saya kemudian melanjutkan kiprah di bidang sastra dan teater di C
Atas permintaan pimpinan GRJS Bulungan saat itu, Oyong Karmayudha SH (yang kelak dikenal sebagai tokoh Organisasi Pencak Silat Indonesia), Lisendra diminta menyelenggarakan Festival Teater Remaja se-Jakarta dan kemudian ikut membidani kelahiran Teater Bulungan pimpinan Uki Bayu Sejati, dengan sutradara A.P. Burhan (dari Sanggar Prativi) sebagai “in house” teater di Bulungan. Lalu kami menerbitkan majalah remaja “Sirkuit” (saya sebagai pemimpin redaksi) berisi karya dan kegiatan sastra dan seni pertunjukan GRJS, serta menyelenggarakan pelbagai pementasan dan pelatihan teater, penulisan dan pembacaan puisi, mengadakan pelbagai diskusi tentang sastra, teater dan bahkan cinta, untuk kalangan remaja.
Selama periode itu, GRJS Bulungan pun berhasil menjadi “pusat kesenian remaja” di Jakarta, tidak hanya di Jakarta Selatan, dan bahkan kemudian dianggap sebagai barometer dan pusat kesenian alternatif setelah Pusat Kesenian Jakarta (PKJ) Taman Ismail Marzuki (TIM).
Sehingga, bila para “Seniman senior” Indonesia berkiblat ke TIM, maka para “Seniman junior” Indonesia berkiblat ke Bulungan. Tak aneh bila generasi seniman lapis kedua dan ketiga setelah era Goenawan Mohammad, Subagio Sastrowardoyo dan Sapardi Djoko Damono di bidang sastra, dan era WS Rendra, Arifin C. Noer, Teguh Karya dan Putu Wijaya di bidang teater, kemudian banyak bermunculan dan lahir di GRJS Bulungan, sejumlah remaja pegiat kesenian yang kelak ikut mewarnai perjalanan kesenian dan kebudayaan nasional.
Gairah bersastra dan berteater di Bulungan itu terus berlanjut, kendati saya kemudian pergi ke Paris, Prancis, akhir Maret 1976, untuk “melanjutkan kisah cinta yang (di)putus” karena Rayni dikirimkan orang tuanya ke Paris untuk kuliah Sinematografi di Universite Paris III, Sorbonne Nouvelle, Prancis. Tentu tidak hanya sastra dan teater, Bulungan juga terkenal karena pada saat bersamaan, juga lahir Sanggar Lukis Garajas pimpinan Dimas Praz dan kelompok musik dan folk song pimpinan Henky Parera.
Ketika saya pergi meninggalkan Bulungan, saat itu GRJS sudah memiliki sejumlah nama terkenal secara nasional. Selain Tjok Hendro (alm) dan Dharnoto, juga ada Yudhistira ANM Massardi, saudara kembar saya yang hijrah dari Persada Studi Klub pimpinan Umbu Landu Paranggi (10 Agustus 1943 – 6 April 2021) di Jogjakarta, meninggalkan para sahabat penyair seangkatannya: Emha Ainun Nadjib, Linus Suryadi AG (3 Maret 1951 – 30 Juli 1999), Suwarno Pragola Pati, Sutirman Eka Ardhana, Korrie Layun Rampan (17 Agustus 1953 – 19 November 2015), dan lain-lain.
Selain Yudhis, ada juga Adri Darmadji Woko, yang kerap mengajak Hendrawan Nadesul dan Prijono Tjiptoherijanto, dan sejumlah penyair muda lainnya dari Tegal, untuk datang dan bergiat di Bulungan. Selain Uki Bayu Sejati, Teater Bulungan juga melahirkan primadonna teater Renny Djajoesman, Saraswati Sunindyo, dan Etty Purnamawati (ibundanya komedian/penulis Raditya Dika), Wita Yudarwita, Tari Lestari (kemudian menjadi pengelola Cafe Batujimbar milik keluarga Waworuntu di Sanur, Bali), Tino Saroengallo (10 Juli 1958 – 27 Juli 2018) yang kelak berkiprah di dunia film, dokumenter dan film iklan, serta terlibat di sejumlah produksi film Hollywood yang syuting di Indonesia, sebagai manajer produksi. Lahir pula Teater Gombong pimpinan Tubagus Jody Rawayan Antawijaya yang sebelumnya aktif di Teater Bulungan.
Kembali dari Paris akhir Oktober 1981, setelah menyelesaikan studi di Ecole Superieure de Journalisme (ESJ), Paris, dan sempat menjadi Koresponden Majalah Berita Mingguan “Tempo” untuk Prancis (1978-1981), saya kemudian melamar, dan setelah melalui serangkaian test, kemudian diterima bekerja sebagai pewarta di Harian “Kompas” per 1 Februari 1982.
Pewarta lain yang direkrut bersama saya ketika itu adalah Don Sabdono (Bre Redana), Budiarto Shambazy, Eko Waryono, Diah Marsidi, dan Bambang Sukartiono (kelak sempat menjadi Pemred “Kompas” menggantikan Suryopratomo).
Setelah mengawali tiga kali rotasi magang di desk Nasional, Kebudayaan, dan Luar Negeri, saya kemudian menetap di Desk Luar Negeri di bawah Redaktur Piet Warbung dan bekerja satu tim dengan Rikardus Bagun dan Budiarto Danujaya. Nah, selama masa magang dan kemudian menjadi karyawan tetap itulah hampir setiap pekan saya selalu melihat seorang “anak kecil” yang sering mengetik di luar kelompok meja redaksi, dan kemudian menghilang tanpa sempat bersosialisasi dengan yang lain, kecuali dengan Redaktur Olahraga, Valens Doy.
Walau tempat duduk saya tidak terlalu jauh dengan “anak kecil” itu, saya juga tidak terlalu memberi perhatian, karena ruang kerja redaksi di gedung tua “Kompas” itu terbuka tanpa sekat, dan semua sibuk dengan mesin ketik masing-masing (komputer masih belum lahir waktu itu).
Baru beberapa waktu kemudian saya tahu bahwa “anak kecil” itu bernama Reza Morta Vileni, dan ternyata sering menulis kronik (berita kecil satu kolom ukuran 10 cm) untuk pelbagai rubrik: Kebudayaan, Kota, Kriminal, dan lain-lain dengan inisial (reza). Sementara inisial saya sendiri untuk berita tanpa opini adalah (ncm) yang saya pakai sampai sekarang. Baru beberapa tahun kemudianlah si “anak kecil” Reza Morta Vileni itu kemudian berganti nama dan kelak terkenal sebagai Radhar Panca Dahana (rpd).
Sesuai tradisi “Kompas,” semua pewarta “Kompas” hanya mencantumkan inisial untuk setiap berita, dan baru memakai nama lengkap bila menulis opini/artikel di halaman IV, halaman opini/artikel yang legendaris itu.
Halaman IV menjadi sangat bergengsi secara nasional, karena di situlah lahir para cerdik pandai Indonesia, yang mengungkapkan pelbagai kritik dan gagasannya, meliputi segala aspek kehidupan (politik, ekonomi, hukum, pertahanan, keamanan, diplomasi, urbanisme, filsafat, agama, dan sebagainya). Halaman yang terbatas itu memang sangat selektif dalam memilih para penulisnya, dan karena itu ia menjadi sangat prestisius. Sehingga, tidak sembarang orang bisa menulis di halaman itu, kecuali para pewarta “Kompas” sendiri, yang juga baru bisa dimuat setelah melalui proses seleksi oleh Kepala Desk Opini (Alfons Taryadi, dan J. Widodo), walau tentu dengan “pertimbangan dań dispensasi khusus.” Termasuk saya, tentu saja he he he… [Bersambung]