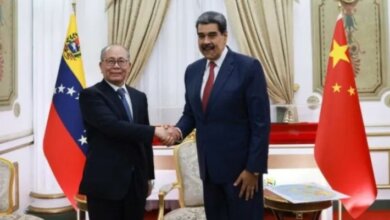Senjata Terbaru untuk Melindas Muslim Assam: Penggusuran Paksa

Dengan kedatangan BJP, konsep ‘pribumi’ semakin diruncingkan untuk menghilangkan hak kaum Muslim dan memberikannya gratis kepada orang Hindu
Oleh: Angshuman Choudhury dan Suraj Gogoi
JAKARTA– Pada Desember 2019, lebih dari 450 keluarga Muslim miskin di distrik Sonitpur di Assam, negara bagian terbesar di India Timur Laut, mendapati diri mereka diusir paksa dari rumah mereka oleh pemerintah distrik yang menerobos masuk dengan buldoser dan personel paramiliter. Awal tahun lalu, 600 keluarga Muslim secara paksa diusir oleh pihak berwenang di Distrik Hojai, yang menyebabkan kematian Kulsuma Begum, yang baru saja melahirkan seorang bayi.
Assam bukanlah korban baru dalam soal penggusuran. Wilayah yang terus diperebutkan India dan Pakistan itu telah dilanda konflik puluhan tahun, banjir musiman, dan bergenerasi-generasi tanpa kepemilikan tanah, negara itu menampung sejumlah besar pengungsi internal (internally displaced persons/IDP). Faktanya, sebuah laporan Asian Centre for Human Rights tahun 2015 mengklaim bahwa wilayah tersebut menampung jumlah terbesar IDP yang disebabkan aneka konflik di dunia. Pihak berwenang secara rutin mengusir para pengungsi ini dengan dalih membersihkan tanah milik pemerintah atau tanah umum dari para ‘perambah’.

Namun, yang sangat mengkhawatirkan adalah kenyataan bahwa penggusuran paksa semacam itu bisa segera menjadi kebijakan negara. Ini akan terjadi dalam konteks ganda–sebuah partai nasionalis Hindu, Partai Bharatiya Janata (BJP), saat ini berkuasa di Assam, dan ada upaya baru untuk memenuhi permintaan penduduk asli yang sudah lama ada di antara konstituensi berbahasa Assam yang dominan di negara itu untuk mengidentifikasi dan mengeluarkan ‘imigran gelap’ dari Bangladesh.
Kombinasi insidental nasionalisme Hindu dan nativisme etno-nasionalis Assam ini menciptakan tatanan institusional yang sangat eksklusif di Assam, yang mengancam keberadaan Muslim miskin dan tidak memiliki tanah, terutama mereka yang melacak nenek moyang mereka sampai ke Benggala Timur (sekarang Bangladesh) dan secara permanen dicurigai orang-orang Assam sebagai ‘Bengali ilegal’,’penyusup’,’bidexis’ (orang asing), dan bahkan ‘rayap’.
Di jantung ‘proyek-proyek’ tersebut terdapat ide yang sangat layak diperdebatkan dari kata ‘pribumi’. Selama beberapa dekade, kelompok nasionalis Assam terus mencoba untuk membangun definisi sempit untuk istilah tersebut, dengan tujuan melindungi kepentingan sosial, politik, ekonomi, dan budaya mereka sendiri seraya menghilangkan hak hidup mereka yang mereka anggap sebagai ‘orang luar’, yakni kaum Muslim dan Hindu asal Bengal). Dengan kedatangan BJP, konsep ‘pribumi’ semakin diruncingkan untuk melindungi kepentingan umat Hindu dan menghilangkan hak kaum Muslim.
Penggusuran baru-baru ini harus dilihat dalam konteks yang berkembang tersebut. Ada dua dokumen kebijakan yang relevan di sini: Laporan Komite Brahma (BC) 2018 dan apa yang disebut “Kebijakan Pertanahan 2019” (untuk selanjutnya disebut sebagai “Kebijakan”).
Baik laporan BC dan Kebijakan bertujuan, antara lain, untuk memindahkan tanah dari “non-pribumi” ke “masyarakat adat Assam.” Sementara Laporan BC dibuat dengan Pemerintah Assam, ‘Kebijakan’ bahkan telah disetujui kabinet negara dan sedang menunggu untuk pengesahan majelis. Keduanya mendorong rezim untuk memecah belah masyarakat Assam dan berupaya melembagakan kekerasan berupa penggusuran paksa.
Laporan Komite Brahma (BC) 2018
Pada Februari 2017, Gubernur Assam membentuk Komite Brahma (BC) untuk menyarankan “perubahan atau modifikasi dalam undang-undang pertanahan dan aturan yang ada” untuk memastikan “perlindungan hak tanah masyarakat adat di Negara Assam.” Komite beranggotakan tujuh orang, yang dipimpin oleh mantan kepala komisi pemilihan India, Hari Sankar Brahma, itu menyerahkan laporan terakhirnya kepada pemerintah Assam pada Januari 2018.
Fitur mendasar dari BC adalah bahwa ia terpaku pada gagasan ‘pribumi’. Segala sesuatu yang lain– data demografis, interpretasi historis, dan proposisi kebijakan, selalu berada di emperan terma ‘pribumi vs non-pribumi’ ini. Untuk menguraikan konsep tersebut, hal itu dimulai dari premis yang cacat, bahwa ‘pribumi’ dapat secara ketat didefinisikan dalam konteks Assam. Bahkan, selanjutnya mengidentifikasi siapa dan apa saja musuh dari mereka yang disebut ‘orang-orang pribumi Assam’ itu, dengan kata-kata yang tak mengenakan.
“Taktik pelaku kejahatan harus diekspos dan kontroversi yang tidak semestinya dibuat sebagai taktik untuk menggagalkan tujuan melindungi hak-hak tanah masyarakat adat Assam, harus diakhiri,” kata BC.

BC juga menetapkan pemahaman nativis yang tak tanggung-tanggung tentang kepemilikan. “Secara alami, tanah yang merupakan hadiah alam yang paling langka dan paling berharga, adalah hak penduduk asli. ‘Putra-putra tanah’ harus memiliki klaim pertama atas tanah Assam,”tulis laporan itu di bagian berjudul “Siapa orang asli Assam?”
Yang lebih mengkhawatirkan, ketika BC mendefinisikan kata ‘pribumi’, ia mendorong garis sejarah, hukum, dan budaya yang ada untuk menetapkan definisi tersempit dari istilah tersebut. Tetapi sebelum menetapkan parameternya sendiri, panitia mengutip empat sumber definisi khusus “penduduk asli Assam” (atau khilonjia), yakni laporan sensus tahun 1951, kamus (baik bahasa Inggris dan Assam), PBB, dan Sanmilita Mahasangha, sebuah organisasi payung yang mengklaim mewakili 49 kelompok masyarakat adat Assam.
Menariknya, ia hanya mengutip definisi dari semua sumber, hampir dengan nada dukungan, kecuali untuk laporan sensus tahun 1951, di mana ia membuat komentar substantif.
Menurut laporan sensus tahun 1951, untuk dihitung sebagai orang “asli” Assam, orang “(i) harus dilahirkan di Assam; dan (ii) ia harus berbicara baik bahasa Assam atau dialek suku/bahasa Assam atau, dalam kasus Cachar, bahasa wilayah (Bengali). Ini adalah definisi teritorial-linguistik yang sulit. Tetapi BC mengeluhkan hal itu.
“Dengan definisi ini, siapa pun yang merupakan warga negara India non-pribumi yang tinggal di Assam juga dapat mengklaim sebagai orang asli Assam asalkan ia telah tinggal di Assam dan tahu bagaimana berbicara salah satu bahasa yang disebutkan di dalamnya. Untuk mengutip sebuah contoh, seorang Bengali atau Bihari atau Punjabi atau Marwari yang tinggal lama di Assam dan berbicara atau bahkan menulis salah satu bahasa negara seperti disebutkan di atas, dapat menjadi orang asli Assam, ” tulis laporan tersebut.
Pada titik ini, jelas panitia ingin membuat pemahaman yang sangat ketat tentang ‘keaslian’ Assam. Dalam pandangan dunia xenofobik alias sikap anti-asing BC, seorang Assam yang dinaturalisasi bukanlah seorang “Assam sejati.”
Definisi yang dikemukakan oleh Sanmilita Mahasangha, yang dikutip BC, juga terkenal, karena melampaui tanggal cut-off 21 Maret 1971 untuk imigrasi yang ditetapkan oleh Assam Accord 1985, sebuah nota kesepahaman yang ditandatangani pemerintah federal India dan kelompok etno-nasionalis di Assam pada akhir Gerakan Anti-Imigran Assam yang berlangsung selama enam tahun (1979-85), dan Pendaftaran Warga National (NRC). NRC diperbarui berdasarkan perintah Mahkamah Agung 2014 dan meminggirkan hampir 1,9 juta orang (kebanyakan Muslim dan Hindu dari Bengal) dalam iterasi terakhirnya yang dirilis Agustus tahun lalu.
Menurut Mahasangha, “…penduduk asli Assam adalah mereka yang telah tinggal di Assam terus menerus sejak 24 Februari 1826, tanggal Perjanjian Yandaboo [sic] dan mereka sendiri harus disebut dan diterima sebagai ‘penduduk asli Assam’”. Mahasangha lebih lanjut mendefinisikan istilah “Assam” adalah: “…mereka yang berbahasa ibu Assam dan telah menggunakan/berbicara/membaca Assam sebagai bahasa asosiasi atau lingua franca, di samping bahasa mereka sendiri/dialek dan sedang berkhotbah dan mempraktikkan budaya mereka sendiri, harus diterima sebagai ‘Assamese'”. Acuan itu menganggap ‘Assamese’ dan ‘pribumi’ sebagai sesuatu yang bisa dipertukarkan alias sinonim.
Ini bahkan definisi yang lebih sempit daripada yang dikemukakan oleh laporan sensus tahun 1951. Ini langsung mengabaikan bahasa yang digunakan dalam bahasa Cachar, yaitu bahasa Bengali. Dengan hanya mengutip definisi dan tidak menantangnya, terbukti bahwa BC menyetujui pemahaman Mahasangha tentang keaslian.

Komite akhirnya menetapkan tujuh parameter khusus untuk memutuskan ketidakmurnian di Assam di bagian “Ciri-Ciri Dasar / Karakteristik yang Menjadikan Seseorang Pribumi.” Namun, “prasyarat” ini tidak hanya abstrak di realitas, mereka juga menyebarkan gagasan xenophobia tentang kepemilikan yang didasarkan pada ketakutan akan “orang luar.” Di atas semua itu, parameternya tidak berada di bawah kerangka kerja legislatif atau hukum India, apalagi konstitusi.
Misalnya, menurut BC, seseorang dapat dianggap “asli” hanya jika “ia percaya bahwa orang-orang kuno klannya telah menjadi atau siap untuk menjadi minoritas di tanahnya sendiri karena migrasi invasi oleh orang luar/orang asing”. Ini benar-benar tidak masuk akal, karena dekat dengan pemolisian pikiran (thought policing). Bagaimana keyakinan individu tentang masalah yang diperdebatkan, seperti migrasi, dapat mendefinisikan sesuatu yang begitu kritis sebagai “asli”?
BC juga memaksakan gambaran totaliter, hitam-putih dari pribumi. Dalam pandangan komite, “seseorang yang merupakan orang pribumi dari negara bagian India lainnya, berbicara dengan bahasa negara tempat asalnya dalam keluarga dan juga mempertahankan budaya aslinya tidak dapat disebut sebagai orang asli Assam.”
Inilah chauvinisme budaya pada puncaknya. Justru karena motif yang begitu populer sehingga minoritas etno-religius di Assam, termasuk “orang daratan” berbahasa non-Assam dari seluruh India, mendapati diri mereka terus-menerus dikesampingkan dan secara langsung menjadi sasaran etno-nasionalis di negara bagian tersebut. Ini juga persis mengapa Muslim asal Bengal yang berani menulis dalam dialek “Miyah” mereka sendiri, dengan demikian mempertahankan hubungan dengan “budaya asli” mereka, menemukan diri mereka difitnah oleh sebagian besar elit yang berbahasa Assam.
BC juga menyebarkan bahasa administrator kolonial Inggris untuk mengkarakterisasi orang-orang di Assam dan menegaskan satu poin: bahwa negara sedang menghadapi ancaman dari imigran ilegal.
Ini label “pribumi” sebagai “malas,” karakter dan psikologi yang dikaitkan Inggris kepada koloninya. Kompleks “pribumi” yang sedemikian malas juga merupakan kasus serius yang salah dalam mengkarakterisasi sebagian orang. Laporan ini juga konsisten dalam karakterisasi kolonial para petani dari dulu Benggala Timur sebagai “petani miskin yang bekerja keras,” yang dapat ditemukan dalam laporan kolonial yang ditulis oleh petugas administrasi Inggris, seperti C.S. Mullan.
Tidak mengherankan, BC mengutip laporan sensus tahun 1931 yang menjadi ikon Mullan, di mana ia mengatakan bahwa Assam menghadapi “invasi gerombolan besar imigran Bengali yang lapar tanah; sebagian besar Muslim, dari distrik Benggala Timur ”.
Faktanya adalah, mayoritas mereka berasal dari daerah yang luas dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ada beberapa kabupaten lain seperti Barpeta, Bongaigaon, Darrang, Dhubri, Goalpara, Hailakandi, Karimganj, Morigaon dan Nagaon yang juga paling terkena dampak serius dan telah berkontribusi besar untuk mengubah pola demografi Assam.
BC juga menarik laporan 1997 tentang imigrasi ilegal yang ditulis oleh mantan Gubernur Assam Letnan Jenderal SK Sinha kepada presiden untuk membuktikan hal yang sama. Misalnya, Assam menghadapi “agresi eksternal” karena migrasi lintas batas terus-menerus dari Bangladesh. Salah satu dari kami sebelumnya berpendapat, melalui analisis ekstensif dari bahan utama, bahwa memo Sinha 1997 dipenuhi dengan kontradiksi yang serius, inkonsistensi, kesalahan faktual, dan interpretasi data ekstrapolatif. Yang sangat penting, penggusuran yang baru-baru ini dilakukan di Assam dilatarbelakangi laporan BC, yang tampaknya telah menjadi tulang punggung kebijakan pertanahan yang baru.
Kebijakan pertanahan baru yang memecah belah
Assam telah memiliki empat kebijakan pertanahan sejauh ini, mulai dari Peraturan Pertanahan dan Pendapatan Assam 1886. Namun kebijakan baru, yang disiapkan oleh Departemen Manajemen Pendapatan dan Bencana pemerintah Assam, adalah yang pertama kalinya menegaskan ‘pribumi vs non-pribumi’. Dengan demikian, setelah disahkan dalam majelis, semua itu akan menjadi hukum yang paling luas dari jenisnya di negara bagian.
Meskipun jauh lebih bersih dalam bahasa, ‘Kebijakan’ meminjam banyak dari laporan BC. Tetapi tidak seperti laporan BC, kebijakan itu secara langsung mengusulkan penjatahan tanah untuk “pembudidaya yang tidak memiliki tanah adat” tanpa mendefinisikan “tanah adat”. Pemerintah dapat dengan mudah mempersenjatai ambiguitas konseptual ini untuk menghilangkan hak kepemilikan dan menggusur beberapa orang yang paling terpinggirkan di Assam, seperti Muslim asal Bengal yang tinggal di daerah char (pulau-pulau sungai temporer) di sepanjang Sungai Brahmaputra. Jelas bahwa hak-hak seperti itu di chars hanya akan diberikan kepada “masyarakat adat”, atau tegasnya orang-prang Hindu.
Jika otoritas pelaksana Kebijakan, seperti yang melakukan penggusuran (dalam hal ini komisioner distrik), memutuskan untuk mengikuti definisi “asli” yang ditetapkan oleh BC, maka kita akan menyaksikan pemindahan paksa yang dilakukan secara paksa di area char. Padahal, orang-orang yang tinggal di daerah pinggiran Assam ini sudah terhuyung-huyung di bawah tekanan ekstrem akibat NRC. ‘Kebijakan’ hanya akan datang sebagai gempa susulan yang menghancurkan.
Kebijakan ini mengambil karakter yang lebih mengancam ketika berada dalam konteks rezim BJP saat ini. Sejak berkuasa di Assam tahun 2016, partai tersebut telah mencoba untuk menghiasi identitas Assam dan memainkan konsensus dominan terhadap Muslim Assam yang berasal dari Bengal, yang secara kasar dianggap sebagai ilegal oleh kaum nasionalis Assam. Menteri dalam negeri India saat ini, Amit Shah, sebelumnya menyebut Muslim ‘rayap’, dengan hati-hati membedakan mereka dari apa yang disebut “pengungsi,” yaitu umat Hindu Bengali dari Bangladesh.
Dalam konteks ini, kebijakan pertanahan yang baru bisa menjadi instrumen masuk rezim untuk merampok Muslim Bengali dari tanah mereka, dan dengan demikian, secara permanen memindahkan mereka. Pendekatan semacam itu cocok dengan segmen dominan nasionalis Assam yang tidak puas dengan angka pengucilan NRC terakhir sebesar 1,9 juta. Kebijakan, dengan demikian, merupakan jalan pintas untuk mencapai tujuan yang sama, yakni untuk membersihkan ‘orang asli Assam’ atas bidexis (orang asing). Untuk minoritas etno-agama, banyak dari mereka yang sudah berjuang sejak zaman dulu, ini adalah prospek yang mengerikan. [The Diplomat]
Angshuman Choudhury adalah Peneliti Senior di Institut Studi Perdamaian dan Konflik, New Delhi.
Suraj Gogoi adalah peserta program doktoral dalam sosiologi di National University of Singapore (NUS).