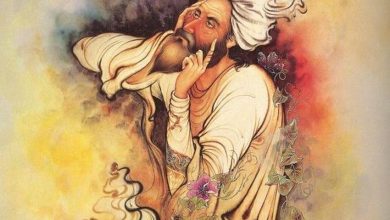Junaid Al-Baghdadi, Sarri As-Saqati, dan Kedermawanan Allah yang Memberi Kemiskinan

“Ayah menangis karena ayah telah mencurahkan seluruh hidup ayah untuk dapat menyisihkan uang lima dirham ini, namun ternyata uang ini tidak memenuhi syarat untuk dapat diterima salah seorang sahabat Allah…”
JERNIH—Sejak kecil Junaid Al-Baghdadi telah memiliki kedalam spiritual yang lain disbanding anak-anak lain, bahkan mereka yang lebih tua darinya. Ia telah menjadi seorang pencari Allah yang bersungguh-sungguh, disiplin, bijaksana, cepat mengerti dan memiliki intuisi yang tajam.
Suatu hari, sepulang dari madrasah, Junaid menjumpai ayahnya tengah menangis.
“Ayah, apa yang terjadi?” tanya Junaid kecil.
“Ayah ingin memberikan sedekah kepada pamanmu, Sarri, (Sarri As-Saqati adalah paman dan guru sufi pertama Junaid—redaksi Jernih.co). Namun pamanmu tak mau menerimanya. Ayah menangis karena ayah telah mencurahkan seluruh hidup ayah untuk dapat menyisihkan uang lima dirham ini, namun ternyata uang ini tidak memenuhi syarat untuk dapat diterima salah seorang sahabat Allah,” kata ayahnya.
“Berikan uang itu padaku,” kata Junaid kecil. “Aku akan memberikannya kepada paman Sarri. Mungkin ia akan mau menerimanya.”
Sang ayah memberikan uang lima dirham itu kepada Junaid kecil, dan Junaid pun pergi menemui pamannya, Sarri. Sesampainya di rumah Sarri, Junaid pun mengetuk pintu.
“Siapa itu?” terdengar suara pamannya dari dalam.
“Junaid,” jawab si bocah. ”Bukalah pintu dan terimalah tawaran sedekah ini.”
“Aku tidak akan menerimanya,” teriak Sarri.
“Aku mohon terimalah ini, demi Allah yang telah begitu dermawan kepadamu dan telah begitu adil kepada ayahku,” kata Junaid.
“Junaid,” teriak Sarri dari dalam, “Apa maksudmu bahwa Allah telah begitu dermawan kepadaku dan begitu adil kepada ayahmu?”
Junaid menjawab,”Allah telah begitu dermawan kepadamu karena Dia telah menganugerahimu dengan kemiskinan. Sedangkan kepada ayahku, Allah telah begitu adil dengan telah menyibukkannya dengan urusan-urusan dunia. Engkau memiliki kebebasan untuk menerima atau pun menolak sekehendak hatimu. Sedangkan ayahku, suka atau tidak, harus menyampaikan sedekah—yang dititipkan Allah kepadanya—kepada orang-orang yang berhak.”
Jawaban Junaid itu menyenangkan Sarri. “Anakku, sebelum aku menerima sedekah ini, aku telah lebih dulu menerimamu,” ujar Sarri. Ia pun membukakan pintu dan menerima sedekah itu. Ia menempatkan Junaid di tempat istimewa dalam hatinya.
***
Junaid baru berumur tujuh tahun saat Sarri mengajaknya berhaji. Di masjidil Haram, masalah syukur tengah dibahas oleh 400 syeikh. Masing-masing syeikh mengemukakan pandangannya.
“Utarakan pendapatmu,” kata Sarri kepada Junaid si bocah.
Junaid berkata,”Syukur berarti engkau tidak bermaksiat kepada Allah dengan menggunakan karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu, juga tidak menjadikan karunia-Nya sebagai sumber ketidaktaatan kepada-Nya.”
“Bagus sekali, benar-benar merupakan pelipur lara bagi mukmin sejati,”kata para syeikh tersebut. Keempat ratus syeikh itu sepakat bahwa tidak ada definisi syukur yang lebih baik daripada yang telah dikatakan Junaid.
“Anakku,” ujar Sarri. “Segera tiba saatnya lidahmu menjadi sebuah karunia istimewa dari Allah untukmu.”
Junaid menangis manakal mendengar pamannya berkata seperti itu.
“Dari mana engkau belajar?” tanya Sarri.
“Dari duduk bersamamu,” jawab Junaid.
Junaid lalu kembali ke Baghdad dan menjadi pedagang barang pecah belah. Setiap hari ia pergi ke tokonya, menutup tirai toko, lalu mendirikan shalat 400 rakaat.
Selang beberapa lama, ia akan meninggalkan tokonya dan pergi ke sebuah ruangan di serambi rumah Sarri. Di sana ia menyibukkan diri dengan penjagaan hati. Dia menghamparkan ‘sajadah wara’, sehingga taka da sesuatu pun yang melintas di pikirannya kecuali Allah. [ ]
Dari “Muslim Saints and Mistics” Fariduddin Aththar, Pustaka Zahra, 2005