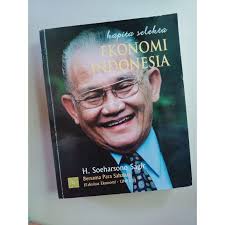
Saat itu pula saya mengerti, mengapa pada zaman Orde Baru itu Pak Sagir berkali-kali berani berkata bahwa hitam adalah hitam, bukan sekadar bukan putih. Pak Sagir yang sempat saya baca saat SMP sebagai mantan dekan yang tak ragu ikut demonstrasi mahasiswa manakala menurutnya apa yang diperjuangkan mahasiswa itu benar adanya.
JERNIH—Hanya tiga hari setelah saya berkesempatan mewawancarai orang yang disebut beliau sebagai “Guru saya yang mengajarkan agarperusahaan besar jangan menjadi enclave di tengah–tengah samudra kemiskinan”—Prof Dr Emil Salim–, pada Sabtu (3/4) malam sekitar pukul 20.00, guru yang membuka mata saya di hari-hari awal saya menjadi mahasiswa itu meninggal. Guru ekonomi yang saya yakini telah membuka mata sekian banyak orang Indonesia, Haji Soeharsono Sagir, harus kita relakan mendului kita, berpulang kembali ke Kampung Halaman.
Saya masih ingat hari-hari di awal “Penataran P4 Pola 100 Jam” yang kami semua ikuti dengan nyaris terpaksa sebagai mahasiswa baru UNPAD hasil Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN) tahun 1990 itu. Semua terasa membosankan karena sejatinya tiga tahun di SMP dan tiga tahun kemudian di SMA telah cukup untuk tak hanya mencerna dan mengendapkan, malah hafal di luar kepala ke-36 “butir Pancasila”.
Hanya dua pengisi materi—pembicara, menurut kami saat itu—yang bukan saja tidak membosankan seperti para pemateri lain, tetapi mampu membuka mata, membentang cakrawala, bahkan menggedor semangat kami, anak-anak mahasiswa baru. Yuddy Chrisnandi yang mewakili mahasiswa senior dan bicara soal kehidupan kemahasiswaan, serta Pak Soeharsono Sagir, yang membedah urusan ilmu ekonomi sebagai ilmu yang sejak itu akan menjadi bahan kajian dan kami pelajari.
Tidak sebagaimana teman-teman lain yang memilih Fakultas Ekonomi UNPAD sebagai pilihan di UMPTN, saya masuk fakultas itu karena fakultas yang saya pilih dan dapatkan tak mungkin menerima saya yang buta warna. Dan tidak sebagaimana saat ini, yakni calon mahasiswa pendaftar diperiksa kesehatan dulu sebelum memilih jurusan dan fakultas, kami waktu itu ikut UMPTN dulu. Baru tes kesehatan dilakukan setelah hasil ujian menegaskan kami diterima. Alhasil, saya baru sadar diri saya buta warna itu setelah diterima di sebuah fakultas yang seringkali cenderung dianggap hanya untuk orang-orang ‘eksakta’.

Pak Sagir-lah yang di awal-awal langkah saya itu bisa menyakinkan, bahwa tak hanya saya jelas tidak salah pilih jurusan—benar-benar memilih sebagaimana dikatakan alm Profesor Lukito Sukahar, pembantu rektor I saat itu,”Ayo, Dik, kamu pilih saja apa yang kamu mau. Asal jangan fakultas eksakta yang ada hubungannya dengan laboratorium. Matematika, Statistika, bolehlah..” Tetapi siapa orangnya yang menghindari hitung-hitungan mau masuk jurusan Matematika atau Statistika? Sementara jurusan manajemen yang saya pilih kemudian pun adalah hasil bertanya,” Kalau jurusan di Fakultas Ekonomi yang paling kurang menghitungnya, apa Prof?”
Mungkin karena kagum sejak awal, meski Pak Sagir hanya mengajar di Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan (ESP), bukan di jurusan saya, Manajemen, setiap beliau mengajar angkatan saya, saya bisa dipastikan hadir. Saya masuk sebagai penyusup dan berusaha hanya menjadi pendengar. Meski tidak memilih bangku paling belakang, alhasil saya menghindari bangku terdepan yang bukan hak saya.
Bukan hanya pada kuliah Pak Sagir saya menjadi penyusup. Saya pun menyusup ke Fikom UNPAD saat fakultas itu masih berada di Sekeloa. Biasanya saya masuk ke mata-mata kuliah yang diampu alm Pak Jalaluddin Rakhmat. Entahlah, selain masih mahasiswa baru yang tak banyak kesibukan, lama-lama sering kelayapan ke jurusan dan bahkan fakultas orang pun rasanya lebih banyak untungnya. Paling tidak, pilihan untuk ‘berkawan’ pun jauh lebih banyak dan variatif.
Belakangan, akhirnya Pak Sagir tahu kalau saya bukan mahasiswa beliau. Awalnya karena secara khusus beliau bertanya dan meminta saya menyebutkan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM). NPM saya yang BIC90199, dan bukan BIA untuk anak-anak ESP membuat beliau bertanya,” Kamu Manajemen?”
Saya mengiyakan. Saya tetap menjawab semampu saya. Pak Sagir pun tak pernah menyoal kehadiran saya sebagai mahasiswa penyusup. Jadi saya tetap melanjutkan kebiasaan saya menghadiri kuliah beliau.
Suatu hari, usai kuliah, Pak Sagir meminta saya menunggu untuk tidak segera keluar ruangan. Yang membuat saya terkejut, beliau menyapa saya dengan nama saya.
“Kamu sering menulis di PR—Pikiran Rakyat—ya?” Saya mengiyakan, dengan sedikit rasa kuatir dan malu. Saya siap untuk menerima kritik atas tulisan-tulisan yang dengan kebanggaan ala mahasiswa tahun pertama mencantumkan diri sebagai mahasiswa FE UNPAD itu.
“Bagus! Teruskan. Kamu tidak harus selesai dulu kuliah atau jadi doktor ekonomi hanya untuk berpendapat dan menyatakan pikiranmu soal ekonomi negara ini,” kata beliau.
Pak Sagir bahkan sempat bertanya di mana saya kost. Beliau sedikit heran manakala saya katakan saya tinggal di Masjid UNPAD.
“Ya sudah,” kata beliau. “Temani saya makan dulu ya..” Saya merasa ada tekanan dalam pernyataan itu. Bukan bertanya, beliau meminta saya untuk ikut makan siang.
Saya lupa nama rumah makan Sunda yang beliau pilih. Jauh dari Kampus Dipati Ukur di utara. Lokasinya di dekat Kampus Universitas Langlang Buana di Jalan Karapitan, Kecamatan Lengkong, yang cenderung di kawasan Bandung selatan.
“Makan yang banyak. Jangan sok malu. Anak muda seusiamu tak mungkin makan sedikit,” kata Pak Sagir tersenyum, saat menyilakan saya memilih lauk pauk yang bertebar aneka rupa.
Selama makan, beliau banyak bercerita, terutama tentang kebiasaan beliau menulis. Saya makan dengan lahap, sesekali menimpali dan menjawab pertanyaan beliau. Usai makan, Pak Sagir menyatakan sesuatu yang sangat membuat saya rikuh. Bagaimana tidak, beliau bilang tak bisa mengantar saya pulang kembali ke Dipati Ukur. Tetapi barangkali—dan belakangan saya yakin—itu cara beliau untuk memaksa saya menerima pemberian yang menurutnya ‘buat ongkos’.

“Lain kali, kita nulis bareng, Wan,” kata beliau sebelum memacu mobil ke arah yang berlawanan dengan tujuan saya.
Lama saya tidak bertemu Pak Sagir setelah itu. Apalagi kemudian saya pun kecanduan aktivisme, baik di HMI atau pun gerakan mahasiswa jalanan yang saat itu bergulung dalam Pemuda Mahasiswa Islam Bandung (PMIB). Saya jadi jarang masuk kuliah, apalagi kuliah sebagai penyusup di mata kuliah lain jurusan.
Baru ketika mahasiswa Bandung bergerak mengkampanyekan gerakan anti-Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB)—program judi lotre nasional saat itu—saya punya ide untuk bikin tulisan, senyampang digagalkannya seminar oleh pihak penguasa saat itu. Saya pikir, alangkah bagusnya bila mahasiswa tak hanya menggelar aksi jalanan, tapi juga menyuarakan usulan.
Ingat kesempatan yang beliau siap berikan, apalagi kemudian saya tahu betapa kerasnya sikap Pak Sagir terhadap SDSB, saya pun mengontak beliau. Saya usulkan agar Pak Sagir menuliskan pandangan beliau soal SDSB.
“Jangan hanya saya,” kata Pak Sagir. “Biar dari saya ide kontennya, kamu yang mengartikulasikan dan menuliskannya sebagai artikel, Wan.” Awalnya saya kaget dan sempat tak percaya diri. Namun Pak Sagir pula yang bisa meyakinkan saya bahwa pada prosesnya saya akan bisa.
Saya lupa di mana kami membicarakan proses pengerjaan artikel nyaris 30 tahun lalu itu. Namun seingat saya, Pak Sagir menyatakan ide beliau, dan saya mencatatnya. Beliau meminta saya mencari data pada beberapa hal, dan bilang ada beberapa data yang bisa beliau berikan. Belum ada SMS atau pesan WA saat itu. Bahkan telepon seluler pun rasanya belum banyak dikenal. Namun yang jelas, saya punya pager berprovider Skytell. Pak Sagir mencatat nomor pager saya, dan akan mengontak saya sesegera menemukan data yang diperlukan.
“Kau ambil ke rumah, Wan,” kata beliau. Saya menyanggupi.
Jadilah kemudian artikel tersebut. Dicatat sebagai ditulis berdua oleh Pak Sagir dan saya. Saya kirim ke Harian Umum Republika dan dimuat pada Sabtu, 2 Oktober 1993. Pada saat wesel honor datang ke Masjid UNPAD, saya sempat mengontak Pak Sagir.
“Kamu pakai sajalah uangnya, Wan,” kata beliau dari seberang pesawat telepon. Suara yang kental dengan kebahagiaan. Ada nada riang karena telah membahagiakan hati orang saat beliau menyatakan itu. Dan memang saat itu saya benar-benar bahagia.
Bukan hanya karena uang honor sekitar Rp 300 ribu yang bisa saya gunakan untuk hal-hal bermanfaat, manakala uang kuliah saya per semester pun saat itu hanya Rp 60 ribu. Tetapi lebih lagi karena tulisan yang dimuat itu juga seolah hasil kolaborasi dengan tokoh yang sejak SMP pun telah saya kenal dan kagumi.
***
Usai membaca pesan di grup WA yang mengabarkan berpulangnya Pak Sagir, ingatan saya kembali ke saat-saat Pak Sagir bicara di ruang D kampus FE UNPAD yang kini tak ada lagi. Saya masih ingat bagaimana Dekan Fakultas Ekonomi UNPAD tahun 1968-1972 itu memompa semangat kami untuk ikut memperbaiki negeri.
“Kalian itu hanya satu persen dari seluruh warga negara. Satu persen yang terpilih dan seharusnya bahagia. Bahagia apa? Bahagia karena di negeri ini ilmu kalian semua tak akan sia-sia. Asal mau dan yakin membaktikannya kembali kepada masyarakat yang telah memberi kalian kesempatan,” kata Pak Sagir saat itu. Tentu saja, tidak mungkin saya ulang dengan verbatim.
Bahkan di awal kami mahasiswa itu, Pak Sagir telah menyatakan kami para mahasiswa baru dengan otak melompong kosong itu sebagai bagian dari cendikiawan.
“Sebab bagi saya, cendekiawan itu adalah manusia yang berani mengingatkan pemimpin yang salah. Yang bisa bertindak cerdas, jujur, arif dan adil melalui lisan, tulisan,teguran atau peringatan keras. Cendikiawan pun tak putus memanjatkan doa, memohon kepada Allah SWT agar Pempimpin dapat kembali pada jalan yang benar. Walau dengan cara itu ia menjalankan fungsi kecendikiawanan yang paling lemah!”
Saat itu pula saya mengerti, mengapa pada zaman Orde Baru itu Pak Sagir berkali-kali berani berkata bahwa hitam adalah hitam, bukan sekadar bukan putih. Pak Sagir yang sempat saya baca saat SMP sebagai mantan dekan yang tak ragu ikut demonstrasi mahasiswa manakala menurutnya apa yang diperjuangkan mahasiswa itu benar adanya.
“Karena saya cendekiawan, maka saya memilih menegur pimpinan yang salah. Menegurnya keras melalui tulisan, karena saya berpendapat bahwa kita harus berani dan percaya diri, asal kita ada di jalan yang benar,” kata Pak Sagir pada sambutan peringatan 75 tahun usia beliau yang digelar para koleganyanya, 2009 lalu.
Sikap yang wajar membuat Presiden Soeharto pernah meminta Menaker Soedomo memecatnya sebagai staf ahli menteri tenaga kerja. ”Pada waktu saya menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja pernah dipanggil Presiden Soeharto—yang karena statement kritik keras Soeharsono Sagir mengenai ekonomi nasional-–meminta kepada saya agar memberhentikan Sdr Soeharsono Sagir sebagai Staf Ahli Menaker. Saya janjikan kepada Presiden, tetapi tidak saya lakukan karena setelah diteliti pendapat Soeharsono Sagir mengandung kebenaran,” tulis Soedomo dalam “Kapita Selekta, Lima Dasawarsa Pengabdian sebagai Guru Ekonomi”, buku yang dicetak 2009 lalu untuk menandai 75 tahun Pak Sagir.
Pak Sagir sendiri tampaknya yakin bahwa kecendikiawanan bukanlah gelar. Ia memilih tidak mengambil pendidikan S2 atau pun S3 yang akan menambahkan gelar-gelar lain padanya kecuali Drs. Ia bahkan beberapa kali menulis ralat—satu di antaranya pada 27 Mei 2009 lalu. Saat itu Pak Sagir meminta PR meralat penyebutan ‘Profesor’ yang ditulis PR dalam tulisan wawancara dengannya.
“Saya bukan profesor (guru besar) Fakultas Ekonomi Unpad, seperti tertulis dalam wawancara tersebut. Saya memasuki masa pensiun sebagai guru ekonomi senior (lektor kepala) pada usia 65 tahun, terhitung mulai 1 Februari 1999,”tulis Pak Sagir yang dimuat utuh dalam PR edisi 27 Mei 2009 itu.
“Baik dalam buku autobiografi saya (70 tahun) maupun buku “Kapita Selekta Ekonomi (75 tahun) H. Soeharsono Sagir”, saya selalu menyebutkan bahwa saya adalah guru ekonomi pada Fakultas Ekonomi Unpad, selama empat dasawarsa (1958-1998) dan lima dasawarsa sebagai guru ekonomi. Saat saya memasuki usia 75 tahun (1958-2008), saya meninggalkan profesi guru ekonomi, terhitung mulai 1 Februari 2009, melalui suatu kuliah kenangan-perpisahan pada 17 Januari 2009, di Aula Gedung Manajemen FE Unpad.”
Baginya, cendekiawan lebih sebagai wakil suara hati nurani masyarakat, dan menjadi juru bicara dari kekuatan moral progresif yang terdapat dalam setiap periode tertentu dalam sejarah kemanusiaan. “Karena itu,” kata Pak Sagir,” cendekiawan, mau tidak mau, suka tidak suka, harus siap dianggap sebagai pengacau yang menjengkelkan para penguasa…” [darmawan sepriyossa]






