UKUR
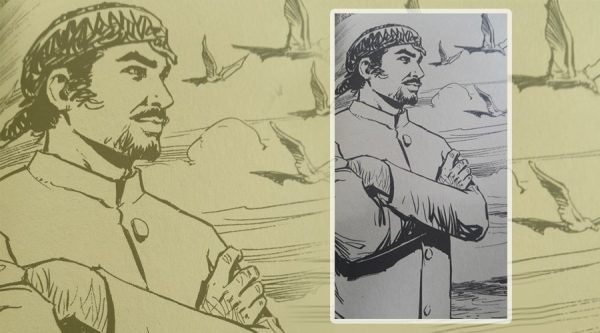
Sejak lama Ukur mencium bau ketidaksetiaan dari Keumbulan Sindangkasih, wilayah timur kekuasaan Ukur yang dipimpin Ki Somahita itu. Pernah Ukur mendapatkan laporan, Ki Somahita banyak bermain mata dengan kekuasaan Kesultanan Cirebon yang dalam geopolitik Sumedang-Ukur tetap harus dipandang sebagai musuh yang harus diwaspadai
Oleh : Darmawan Sepriyossa
Pengantar:
Setelah jatuhnya Kerajaan Majapahit, ratusan tahun kemudian kerajaan-kerajaan taklukan di seluruh Nusantara bangkit memupuk kekuatan. Yang paling mencorong adalah Kerajaan Mataram, pengklaim pewaris kekuasaan Majapahit. Sementara kekuatan asing yakni Portugis, Belanda dan Inggris, mulai pula datang menancapkan kuku kekuasaan mereka. Masing-masing dengan kerakusan dan kekejamannya sendiri. Pada saat itu, di Tanah Sunda muncul kekuatan yang mencoba menolak penjajahan, dipimpin seorang bernama Dipati Ukur.—
Episode-17
“Sendika Gusti!” kata Caraka tersebut. Kepada salah seorang pejabatnya Ukur memerintahkan agar kedua caraka itu diberi bekal uang yang lebih dari cukup untuk perjalanan pulang.
“Sampaikan salam dariku untuk Kanjeng Sultan!” perintah Ukur manakala keduanya telah siap di atas pelana kuda-kuda yang masih segar, siap membawa mereka kembali ke Mataram.
“Sendika, Gusti!” Setelah menyembah, kedua utusan itu segera melompat ke punggung kuda. Mereka berdua mengangguk hormat sebelum kemudian memacu kuda cepat-cepat ke arah wetan.
Kepergian kedua utusan tersebut meninggalkan kepulan debu yang mempercepat hilangnya mereka dari pandangan. Begitu punggung mereka tak lagi terlihat, Ukur segera memanggil seorang hulubalang.
“Senapati, segera pilih 10 orang utusan. Sebar mereka ke 22 wilayah Kandage Lante dan 18 umbul yang ada di wilayah kita. Perintahkan semua umbul dan kandaga lante untuk mengumpulkan pasukan. Sepuluh hari lagi semua harus berkumpul di alun-alun Tatar Ukur, sebelum kita bersama-sama berangkat ke Karawang,” kata Ukur. Perintahnya jelas, membuat hulubalang itu tak harus bertanya lebih jauh.
“Kaula, Nun Gusti, sumangga! Siap!“ katanya. Setelah unjuk sembah, segera ia berlari hendak melakukan tugasnya.
Sore itu, sambil menunggu maghrib, Ukur bersama Nyimas Saribanon menikmati senja. Layung di langit barat tampak megah memulas langit dengan sepuhan warna emas. Burung-burung pulang ke sarang, digantikan kepak sayap kelelawar yang satu persatu tampak keluar beterbangan.
Kelelawar pemangsa serangga saat itu pun sudah bisa mulai berpesta menyambari serangga-serangga yang beterbangan. Capung terutama. Sementara kelelawar buah belum bisa memakan buah-buahan, harus bersabar sementara waktu menunggu datangnya malam.
“Nyai, hari ini datang utusan Mataram, meminta Kakang membantu mereka menyerbu Batavia,” kata Ukur. Diraihnya sepotong pisang yang digoreng dengan minyak kelapa buatan Galuh. Wanginya khas, menunjukkan gorengan itu menggunakan minyak buatan wilayah yang kaya pohon kelapa itu. Lain dengan minyak buatan daerah lain, minyak kelapa Galuh tak pernah membuat gorengan berbau tengik.
“Iya, Dinda melihatnya tadi. Begitu tergesa, hingga setiap orang pun tahu ada persoalan besar yang dibawanya dari Keraton Wetan,” kata Nyimas Saribanon. “Sebenarnya, bisakah seandainya Kakang menolak perintah Sultan?” Nyimas Saribanon bertanya.
Ukur tersenyum. Ia tahu istrinya itu tak menginginkan ia pergi jurit. Apalagi jurit untuk kepentingan Sultan Agung yang terkenal tak pernah mau menerima kegagalan. Tampaknya cerita tentang dipancungnya Adipati Rangga Gempol karena gagal menyerang Kerajaan Madura telah membuatnya trauma.
“Bisa saja, mengapa tidak?” kata Ukur.
“Nah, lalu mengapa Kakang tidak langsung menolak?” Paras muka Nyimas Saribanon berkerut, mempertanyakan sikap suaminya.
Ukur kembali tersenyum. Ia tahu betapa pun istrinya itu istri seorang prajurit, tetap saja ibu rumah tangga yang tak banyak bersentuhan dengan urusan politik dan tata negara.
“Karena itu artinya sama dengan langsung meminta Kanjeng Sultan menyerang dan membunuh kita,” kata Ukur.
“Apalagi yang diminta Kanjeng Sultan juga masuk akal, meminta bantuan untuk menyerang orang-orang Olanda kafir yang watak jahatnya tak kurang dengan sebagian orang-orang Wetan. Belum lagi Kakang pun terikat janji untuk mengabdi. Apa namanya Kakang sebagai prajurit dan nonoman Sunda bila mengabaikan janji yang pernah diucapkan lidah, keluar dari mulut? Kakang harus menepati janji setia. Itu aturan sinatria, Rayi.”
Nyimas Saribanon terdiam. Hatinya gundah. Bagaimana pun ia tahu, perang, apalagi menghadapi senjata bedil yang bisa menjatuhkan musuh jauh lebih dari jangkauan anak panah, bukanlah sebuah kondisi yang bisa memastikan pelakunya selalu dapat kembali pulang. Tak jarang, yang pulang hanya nama, karena jasad telah menjadi mayat, ngababatang[1] di medan juang.
“Jangan sedih, Rayi. Sejak awal kita membangun rumah tangga bukankah kemungkinan ini telah Kakang bicarakan?”
Nyimas Saribanon mengangguk. Ia menghela nafas panjang.
“Semoga saja Allah memberi kemenangan untuk Kakang,” kata dia, setelah sekian lama terdiam.
“Terima kasih, Rayi. Kakang berharap Rayi bisa tegar. Bukan hanya Kakang yang berangkat ke medan perang, melainkan juga seluruh prajurit Ukur dan Sumedang. Bagaimana nanti, bila Rayi, istri Kakang yang akan memimpin jurit para prajurit, justru menunjukkan kesedihan? Yang terbaik adalah selalu sabar, doakan Kakang dalam setiap shalat Rayi,” kata Ukur.
Istrinya mengangguk, meski matanya kini terlihat mulai basah. Nyimas Saribanon menubruk Ukur, menangis di pangkuan suaminya. Dipati Ukur terus membesarkan hatinya sambil tak henti mengelus-ngelus rambut istrinya, hingga adzan maghrib berkumandang.
Sepekan kemudian pasukan Tatar Ukur dan Sumedang sudah terkumpul di Dayeuh Ukur, ibukota Tatar Ukur. Sengaja pengumpulan pasukan tidak dilakukan di Kutamaya, pusat Kawedanaan Sumedang, agar memudahkan beberapa umbul dan kandaga lante. Toh pada saatnya bergerak mereka juga akan memasuki wilayah Sumedang, sebelum bergabung dengan pasukan Tumenggung Bahureksa dari Mataram di Karawang.
Ribuan prajurit dari berbagai kesatuan dan wilayah telah siap siaga untuk berperang. Gobang dan tombak masing-masing sudah terasah tajam, jamparing (anak panah) sudah diperiksa dan tali gondewa (busur) pun telah diganti baru. Begitu pula balati dan keris bila harus bertarung dalam jarak dekat. Tak elok kalau di medan perang nyawa terpisah dari badan hanya gara-gara tali busur putus di tengah peperangan.
“Bagaimana, apakah semua kandaga lante dan umbul sudah datang?” tanya Ukur kepada Ngabei Tarogong. Karena jarak yang tak terlalu jauh dan hubungan persahabatan di antara keduanya, Ngabei Tarogong sudah berada di Dayeuh Ukur sejak sepekan lalu.
“Tinggal pasukan dari Keumbulan Sindang Kasih, Gusti,” jawab Ngabei Tarogong.
“Ah, Kau, gusti-gusti,” kata Ukur. Sudah lama ia meminta teman karibnya itu cukup menyebut namanya. Tetapi jujur saja, ia pun belum bisa memberikan solusi kata apa yang bisa dijadikan ganti. Apalagi ia pun mengerti kesulitan Ngabei Tarogong yang secara kepangkatan resmi berada di bawahnya. Orang akan gampang menyebutnya tak menaruh hormat, atau bahkan membangkang bila seenaknya menyebut nama atasan. Akhirnya Ukur sempat memintanya hanya menyebut ‘rakanda’, namun itu pun tak pernah dilakukan Ngabei Tarogong, kecuali hanya bila keduanya tengah berada berdua, entah di rumah Ngabei di Tarogong, sebuah wilayah di kaki Gunung Papandayan, atau di kediaman Ukur di Dayeuh Ukur.
“Hm, Umbul Sindang Kasih ya..” Ukur berkata lirih. Matanya bertumbuk dengan pandangan Ngabei Tarogong. Keduanya segera tersenyum penuh arti. Sejak lama Ukur dan Ngabei Tarogong memang mencium bau ketidaksetiaan dari wilayah timur kekuasaan Ukur yang dipimpin Ki Somahita itu. Pernah Ukur mendapatkan laporan, Ki Somahita banyak bermain mata dengan kekuasaan Kesultanan Cirebon yang dalam geopolitik Sumedang-Ukur tetap harus dipandang sebagai musuh yang harus diwaspadai.
“Mungkin karena jarak wilayahnya yang berbatasan dengan Kesultanan Cirebon, Ki Somahita memilih mencari cara-cara yang aman,” kata Ngabei Tarogong beberapa waktu lalu. Ukur saat itu hanya mengangguk, meski kemudian mengeluarkan apa yang ia pikirkan.
“Benar. Tapi memang penguasa Sindang Kasih itu wajahnya pun entah mengapa mewakili gambaran seorang pengecut, seorang munafik yang licik. Wajah yang miyuni Sangkuni dalam pewayangan,” kata Ukur.
Ia membayangkan wajah tirus dengan dagu lancip cenderung maju sehingga terkesan cameuh. Semua itu ditambah dengan kumis jarang yang entah mengapa dipelihara pemiliknya dengan rajin dan setia. Semua gambaran wajah yang sukar membuat orang percaya dengan pribadi pemiliknya.
“Tinggal kita waspada permana tingal,” kata Ngabei Tarogong.
“Sumuhun, Rayi. Benar.”
Keduanya masih berbincang-bincang manakala seorang prajurit datang, mengabarkan kedatangan pasukan dari Keumbulan Sindang Kasih.
“Ki Somahita datang dengan seratus prajurit, Gusti,” kata prajurit itu melaporkan.
“Hah? Seratus prajurit?”
Ukur terperanjat. “Apa yang bisa diperbuatnya dengan hanya seratus prajurit? Dia pikir masing-masing prajuritnya itu Gatotkaca atau Raden Antareja? Suruh Si Somahita segera melapor ke sini!” teriak Ukur marah.
Sebelumnya ia berharap sedikitnya Umbul Sindang Kasih membantu dengan tiga ratus prajurit. Sindang Kasih adalah wilayah dengan penduduk tak kurang dari 5.000 umpi. Satu umpi diminta membantu dengan seorang wajib jurit saja sudah 5.000 orang yang bisa ia bawa ke sini. Apa artinya 300 dibanding kemampuannya menyediakan tenaga wajib jurit dengan potensi sebesar itu?
“Rayi, tolong kumpulkan semua pimpinan prajurit. Kita akan berangkat menuju Karawang, besok setelah shalat subuh,” kata Ukur. Ia kemudian berjalan cepat ke arah balairung, menemui Ki Somahita yang dimintanya menghadap.
***
Di Pelabuhan Tegal, Tumenggung Bahureksa sedang gundah. Ia diminta membawa sedikitnya seribu prajurit melalui jalan laut. Sekitar 10 ribu prajurit Mataram, gabungan dari berbagai wilayah taklukan telah berangkat jauh-jauh hari, melalui jalan darat yang akan memakan waktu tak kurang dari tiga bulan lamanya. Namun perahu dan prajurit yang ada kurang dari jumlah yang diminta Sang Susuhunan Mataram.
Yang terkumpul di Pelabuhan Tegal baru 600 orang, masih jauh dari target. Sementara jumlah gorab (perahu berlayar layar ganda khas Jawa) yang dipinjamkan para pedagang pribumi dan para pedagang Tionghoa yang sudah merapat di dermaga tak lebih dari 35 perahu saja.
Jika begini, bagaimana ia bisa sukses merebut Batavia? Jangan-jangan malah kepalanya yang akan menyeringai bertalam nampan di bawa orang ke hadapan Susuhunan. Bukan dirinya yang dengan bangga dan siap menerima tanda jasa melaporkan kemenangan!
Padahal untuk ekspedisi ini ia sudah mengajak anaknya serta, biar nanti anak laki-lakinya itu juga turut mengecap kemenangan dan dilimpahi anugerah Kanjeng Susuhunan. Ia ingin anaknya suatu saat menjadi seorang bupati, menggantikan dan meneruskan jabatan yang saat ini ia sandang dan terbukti banyak memberinya kenikmatan dan kesenangan duniawi.
Sudah 23 tahun ia menjabat posisi itu, terhitung saat dilantik pada 26 Agustus 1605 oleh penguasa Mataram sebelumnya. Syukur-syukur anaknya itu bisa melampaui pencapaiannya di hirarki Keraton Mataram. Menjadi mangkubumi memang sulit, karena juga meniscayakan pertalian darah dan keturunan. Tetapi kalau nasib baik setelah perjuangan yang keras, siapa tahu?
Dirinya pun awalnya hanya putra seorang biasa, Ki Ageng Cempaluk. Nama yang diberikan ayahnya adalah Raden Bahu. Benar, ayahnya itu disebut-sebut punya hubungan pertemanan yang sudah laiknya persaudaraan dengan Ki Ageng Bondan Kejawan alias Lembu Peteng, putra Prabu Brawijaya, raja terakhir Majapahit[2]. Tetapi kenyataannya, dalam keseharian keluarganya hanyalah orang biasa. [bersambung]
[1] Terbujur kaku
[2] Sumbernya hanya dari babad yang penuh mitos, dengan urutan pemberian waktu yang kadang terkesan kacau.






