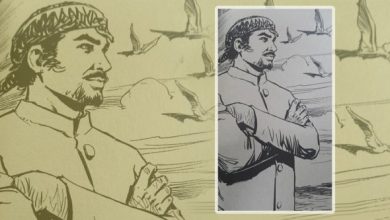UKUR
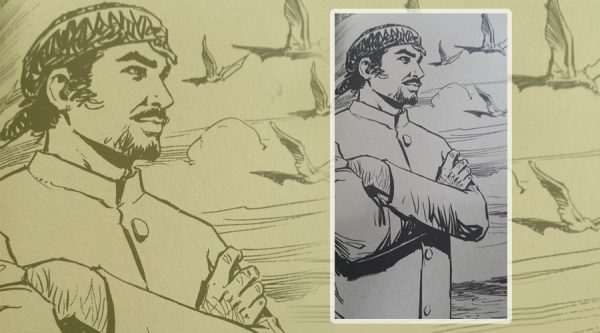
Keraton Mataram memerintahkan Keraton Cirebon untuk bersama-sama Narapaksa kembali menggempur kekuatan Ukur di Gunung Lumbung. Sultan Agung bahkan mengancam penguasa Cirebon, bahwa Mataram akan membunuh setidaknya 100 orang warga Cirebon yang sedang berada di Mataram
Oleh : Darmawan Sepriyossa
Pengantar:
Setelah jatuhnya Kerajaan Majapahit, ratusan tahun kemudian kerajaan-kerajaan taklukan di seluruh Nusantara bangkit memupuk kekuatan. Yang paling mencorong adalah Kerajaan Mataram, pengklaim pewaris kekuasaan Majapahit. Sementara kekuatan asing yakni Portugis, Belanda dan Inggris, mulai pula datang menancapkan kuku kekuasaan mereka. Masing-masing dengan kerakusan dan kekejamannya sendiri. Pada saat itu, di Tanah Sunda muncul kekuatan yang mencoba menolak penjajahan, dipimpin seorang bernama Dipati Ukur.—
Episode—34
Setelah dua kali gagal menaklukan Jakatra, kota yang oleh orang-orang Kompeni Belanda kemudian disebut Batavia, Sultan Agung tak pernah lagi berusaha menyerbu kota itu. Kota itu barangkali tak benar memiliki penjagaan dan kesatuan tentara yang sangat kuat. Namun yang jelas, Kartasura terlalu jauh dari Batavia, sehingga untuk melakukan serbuan, persoalan logistik harus benar-benar dipikirkan. Pada penyerbuan kedua, hal itu sudah direncanakan matang. Yang alpa dilakukan Mataram adalah menjaga gudang-gudang logistic mereka dengan penjagaan yang memadai. Tapi persoalannya, memang Mataram saat itu pun membangun gudang-gudang logitik dengan diam-diam dan rahasia. Mustahil mereka menjaganya dengan sekian pasukan prajurit yang akan segera memancing kecurigaan musuh.
Selain itu, setelah dua kali penyerbuan tersebut Mataram pun segera didera konflik internal di dalam keraton Kartasura sendiri. Kanjeng Susuhunan Sultan Agung dianggap pilih kasih dalam menerapkan hukum. Sementara kepada Adipati Mandurareja, Adipati Upasanta dan Tumenggung Suro Agul agul hukuman dilakukan dengan tegas, dengan membunuh mereka. Bahkan keluarga Suro Agul agul ditumpas kelor, habis dibasmi hingga keturunan yang masih kanak-anak. Sementara, kepada Adipati Jumena, Pangeran Puger, Pangeran Purbaya dan Tumenggung Singaranu, hukuman yang sama tak diberlakukan. Padahal, para pemimpin pasukan tersebut sama-sama pulang membawa kekalahan yang pastinya menurut Sultan Agung sama-sama memalukan.
Bolehlah orang diminta maklum karena Adipati Jumena, Pangeran Purbaya dan Pangeran Puger adalah keluarga langsung Kanjeng Sultan sendiri. Mungkin, sekali lagi mungkin, pihak Keraton menganggap warga Mataram akan memaklumi mengapa mereka tidak menjalani hukuman bunuh, sebagaimana selalu diberlakukan kepada para pimpinan pasukan yang gagal menjalankan tugas, karena hubungan darah yang sangat dekat itu. Tetapi Tumenggung Singaranu?
Wajar bila yang timbul kemudian adalah rumors dan desas-desus. Dan memang semua itu bukan tanpa bukti. Sepulang dari Jakatra, Tumenggung Singaranu tak datang ke Keraton Kartasura. Ia langsung menuju rumahnya tanpa lebih dulu melapor kepada Kanjeng Sultan sebagaimana kebiasaan. Esoknya, seraya menutup diri di rumah besarnya, ia menyerahkan senjatanya dengan menitipkannya kepada putrinya yang cantik yang sudah lepas remaja untuk diserahkan kepada Kanjeng Sultan. Tak hanya itu, ia pun mengirim para selirnya kepada Sihunun Mataram. Semua orang di Mataram tahu, putri Tumenggung Singaranu adalah bunga terindah yang tak ada duanya di Mataram. Belum lagi puluhan selir yang ia dapatkan dari rajinnya melakukan blusukan ke seluruh wilayah kekuasaannya, semata untuk mendapatkan bunga-bunga pilihan yang tak jarang telah menjadi istri orang. Kanjeng Sultan memaafkannya, dan hanya menghukumnya untuk tidak datang ke keraton selama tiga tahun. Hukuman yang enak, karena tak datang ke keratin artinya tak dapat tugas-tugas berat yang potensial menggelindingkan kepalanya[1].
Semua itu membuat rakyat Mataram kecewa. Sejak itu, bisa dikatakan tiada hari tanpa adanya warga yang melakukan pepe, protes kepada Keraton, yang dilakukan dengan cara berjemur di sekitaran Beringin Kembar di alun-alun Keraton, sebagai tanda ketidaksetujuan dan kecewa.
Di Tatar Parahyangan, kepulangan pasukan Mataram dari Jakatra dengan kekalahan yang pahit, kecuali berhasil membawa kepala Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen, sama sekali tak membuat Parahyangan tenang. Mataram gagal paham, bahwa dengan manajemen pra-modern yang berlaku di VOC, kematian Coen tidaklah berarti kematian Kompeni. Hanya ada kesedihan sehari dua atas kematian itu. Tiga hari setelah kematian Coen, pada 24 September 1629, Kompeni segera mengangkat Jacques Specx sebagai gubernur jenderal pengganti. Tak ada yang berubah besar setelah itu. VOC tetap menguasai Batavia, bahkan kian jumawa dengan makin memperbesar tak hanya area, tapi juga berbagai macam regulasi perdagangan yang mereka paksakan.
Geram atas kekalahan yang diderita Mataram, pada 1630 Sultan Agung mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Tumenggung Narapaksa ke basis markas pasukan Ukur di Gunung Pongporang. Pasukan Ukur tentu saja tak memiliki meriam sebagaimana Komepni di benteng mereka. Tetapi benteng kayu dan bambu yang mereka bangun tak gampang dilumpuhkan. Sementara pasukan Narapaksa pun tak membawa meriam, bahkan jenis meriam kecil seperti halve cartouwe yang menggunakan bola besi empat pon sekali pun.
Dengan penguasaan medan laga yang lebih baik,hampir setengah kekuatan pasukan Narapaksa bahkan bisa dihancurkan pasukan Ukur sebelum mereka mencapai area benteng Pongporang. Di sanalah kemudian terjadi pertempuran manjanik alias katepul kedua belah pihak. Sebagian benteng Pongporang musnah terbakar, tetapi pasukan Narapaksa pun kocar-kacir kabur berlarian menuruni gunung, dikejar-kejar wadya bala Ukur yang seolah haus darah.
Akhir tahun 1630 itu Ukur memerintahkan pasukannya untuk pindah ke Gunung Lumbung, wilayah Tatar Ukur[2]. Pertimbangannya, bagaimana pun Pongporang bukanlah wilayah yang sangat dikenalnya dibanding wilayah Tatar Ukur. Bagaimana pun Gunung Lumbung lebih dikenal pasukannya karena dari sekitar itulah dulu mereka lahir dan bertumbuh. Pasokan logistic pun lebih terjaga, karena sekeliling wilayah adalah sawah ladang mereka sendiri yang telah berpuluh-puluh tahun mereka budidayakan. Kelemahannya, lokasi itu terlalu dekat dengan kampung-kampung tempat para istri prajurit berada. Namun Ukur berharap, justru sisi itu akan membuat mereka makin kuat pada saatnya, entah dengan pertimbangan apa.
Tapi Ukur pun bijak. Dimintanya keluarga para prajuritnya untuk berkemas dan melakukan evakuasi ke wilayah Kerajaan Banten. Ribuan warga Tatar Ukur pun, terutama para perempuan dan anak-anak gadis, tahun itu berangkat menuju Banten[3]. Oleh penguasa Banten, atas dasar kemanusiaan, warga Tatar Ukur itu diizinkan tinggal di sebuah area luas, dekat dengan hutan dan sungai, serta lahan yang diizinkan untuk diolah.
Dalam catatan Belanda, terutama Dagh Register, orang-orang Ukur dan Sumedang bahkan sempat mengirimkan utusan kepada Kompeni, meminta diizinkan untuk menetap sementara di sebuah wilayah di Jakatra, guna menghindari serangan Mataram[4]. Tidak ada sumber jelas yang menegaskan apakah permintaan tersebut diluluskan atau tidak.
Tahun itu juga Keraton Mataram memerintahkan Keraton Cirebon untuk bersama-sama Narapaksa kembali menggempur kekuatan Ukur di Gunung Lumbung. Sultan Agung bahkan mengancam penguasa Cirebon, bahwa Mataram akan membunuh setidaknya 100 orang warga Cirebon yang sedang berada di Mataram, bila tugas tersebut tidak dilaksanakan[5]. Akhirnya, Cirebon pun kemudian bergabung bersama Tumenggung Narapaksa, bersama bergerak untuk kembali menggempur pasukan Ukur.
Gunung Lumbung 1632
Sementara malam terus beranjak, binatang-binatang malam saling berkeciap menikmati malam tanpa bulan di keheningan Gunung Lumbung. Tak ada tanda bahwa para penghuninya adalah mereka yang telah siap berperang, siap berjuang mempertahankan nyawa dan harga diri. Malam terasa dingin, tapi tak ada sedikit pun kesuraman di sana. Seolah mengikuti manusia-manusia penghuninya, maka tanah, hutan, ladang, sawah berpengairan sederhana, bahkan udara di sana telah mengikhlaskan diri. Semua tenang, berjalan laiknya suasana normal.
Di tengah rumah paling besar di sebuah dataran luas, Ukur bersila dikelilingi 12 orang kepercayaannya. Sebenarnya yang paling dipercayainya hanya seorang, Ki Mardawa namanya. Sementara 11 lainnya adalah orang-orang yang dipilih dan dipercayai Ki Mardawa. Atas dasar kepercayaannya kepada Ki Mardawa yang telah bertahun-tahun bersamanya, Ukur pun mempercayai semua laki-laki di sekelilingnya.
Usia mereka nyaris sama, di bawah Ki Mardawa. Paling antara 25-33 tahunan. Barangkali juga mereka semua adalah murid-murid kepercayaan Ki Mardawa, yang rela untuk berjuang, bahkan kini bertaruh nyawa untuknya. Untuk Tanah Sunda sebenarnya, karena bila semua perjuangan ini dilakukan hanya untuk diri Ukur, alangkah dangkalnya perjuangan tersebut.
Itulah yang selalu ia upayakan tanam di kepala dan dada para pengikutnya. Berjuanglah, tapi bukan buatku. Aku bukan orang-orang Wetan yang haus kuasa dan puji-puja. Buang jauh-jauh sikap terlalu menerima yang ditanamkan feodalisme orang-orang Wetan itu, yang membuat kalian semua selalu mau menerima apa pun yang mereka minta, yang mereka katakan laksana titah. Tak ada dosa apa pun dengan menolak perintah para menak, seandainya perintah itu picik dan tak masuk akal. Tetaplah berpegang teguh pada aturan baku yang sudah jelas benarnya: aturan agama kita. Berpegang pada aturan itu akan membuat Kalian tak akan linglung kehilangan jalan dan pijakan.
Itu yang selalu Ukur katakan kepada para pengikutnya, di mana pun, pada pengikutnya yang mana pun. Meskipun Ukur sadar, kadang beberapa pengikutnya yang rendah hati dan baik, senantias mengikuti tata aturan lama untuk mengabdi dengan ikhlas kepada para menak, alias bangsawan. Untung kalau para menak itu kebetulan orang baik. Kalau justru para bungaok yang picik dan licik, orang-orang kecil itu biasanya hanya akan menjadi korban kebaikan hati mereka sendiri.
Karena itu Ukur selalu berupaya menanamkan satu keyakinan yang jauh lebih mendasar, bahwa ini adalah perjuangan untuk menegakkan kalam Gusti Allah, yang sejak awal mengharamkan perbudakan manusia oleh manusia lain, pemerasan satu kelompok masyarakat oleh kelompok masyarakat lain, sebagaimana yang terjadi di semua tanah kekuasaan Mataram.
“Ki Sanak semua, benar Ki Sanak sekalian ikhlas berjuang untuk keadilan di Tanah Sunda?” kata Ukur bertanya, membuka percakapan. Pertanyaan itu diiyakan semua yang hadir, menghadirkan semacam dengung yang riuh. Sebentar.
“Sebenarnya Kula di awal-awal sulit untuk diyakinkan oleh Ki Mardawa untuk apa yang sebentar lagi kita lakukan,” kata Ukur. “Kula merasa, mengapa untuk keselamatan Kula, para Ki Sanak semua harus berkorban?” Ukur terdiam, cukup lama. Cukup waktu untuk Ki Mardawa menyelanya.
“Bukan untuk Kanjeng Dipati, kulanun. Lebih untuk Tanah Sunda dan nasib keadilan yang kita perjuangkan,”kata dia. “Kanjeng Dipati adalah pemimpin kami. Sudah menjadi kewajiban dan bagian dari perjuangan kami untuk melindungi Kanjeng Dipati, bahkan dengan mempertaruhkan keselamatan jiwa kami sendiri…”
Ukur menarik nafas panjang, menghembuskannya pelan seolah menunjukan perasaan hatinya yang rawan, membuat semacam uap keluar dari lubang hidungnya, cukup jelas terlihat di malam yang dingin berpenerangan obor-obor berminyak jarak itu.
Seorang pemuda menambahi pernyataan Ki Mardawa, disusul seorang lainnya, seolah berlomba. Semua menyatakan rasa ikhlas, bahkan bangga bisa terpilih oleh Ki Mardawa untuk berperan lebih banyak dibanding paa prajurit Ukur lainnya. Bila Ukur tidak segera menyela, mungkin saja kesebelas laki-laki itu akan bergantian menegaskan ketetapan hati mereka.
“Ya sudah, baiklah,” kata Ukur.
“Perlu Ki Sanak semua ketahui, sejak muda, manakala berlatih dan hidup di rantau Mataram, selain melatih diri dengan tata cara perang, ilmu bela diri dan kanuragan, Kula juga giat belajar agama. Lebih tepat lagi, kula belajar ilmu kebatinan yang sempat diajarkan Syekh Lemah Abang, atau Syekh Siti Jenar.”
Ukur berhenti sebentar, seolah ingin menakar apa yang ada di kepala masing-masing lelaki yang tadi bilang bertekad untuk menjaga dirinya itu.
“Semua untuk ketenangan batin. Untuk mencari karahayuan dalam hidup. Kula tak hanya tenggelam dalam semadhi, ngalenyepan wiridan Syekh Siti Jenar, yang benar-benar ngebrehkeun selang surupna sifat-sifat Gusti Allah, yang menjelaskan susunan sifat-sifat ke-ilahian Gusti Allah,” kata Ukur[6].
“Kula juga menjalankan tirakat untuk beberapa ilmu, yang sebagian belum pernah kula coba. Termasuk yang ini, yang diusulkan Ki Mardawa. Guru kula mengijazahkannya untuk kula jalani, dan telah kula jalani. Hanya belum pernah kula coba. Selalu membuat kula bimbang, apakah yang kula lakukan itu sebuah upaya pura-pura menjadi Gusti Allah atau tidak? Kula tak pernah berpikir menyamai Gusti Allah, bahkan selalu menjaga agar hal itu tak pernah terbersit di kepala kula sedikit pun.”
Ukur memandang sekeliling, bergantian mengamati, kembali menakar niat mereka dari sorot mata yang mereka lontarkan. Sulit untuk meragukan satu pun di antara kedua belas laki-laki itu.
“Baiklah, jika Ki Sanak semua sudah bulat, kita akan memulainya. Kula yakin, Ki Mardawa sudah membicarakan apa yang akan kita lakukan, benarkah?” kata Ukur, berhenti sebentar untuk menunggu penegasan yang sebenarnya tak perlu lagi dari mereka semua. Sebagaimana dikatakannya, ia yakin Ki Mardawa sudah bicara panjang lebar tatkala merekrut mereka.
“Sudah, kanjeng Dipati,“ seseorang menjawab, mewakili mereka semua. “Kami sudah siap.”
“Baiklah,”
kata Ukur. “Inilah ajian Grojog Sewu, semoga saja berhasil..” [bersambung]
[1] HJ De Graaf dalam “Puncak Kekuasaan Mataram” menulis, Tumenggung Singaranu, panglima pasukan Mataram pada serangan kedua, sadar bahwa lehernya sangat rentan dipancung. Sepulang dari Jakarta ia menahan sisa pasukannya yang masih sekitar 10 ribu orang, sebagian besar adalah rakyat Mataram yang dikumpulkan dari berbagai daerah. “Dengan pengikut-pengikutnya,” tulis De Graaf, “ia menarik diri di antara tembok-tembok yang luas dan mengambil sikap mengancam karena melihat kekerasan yang terjadi sebelumnya terhadap panglima-panglima yang dianggap gagal.”
Namun, untuk mendapatkan pengampunan Sultan Agung, Singaranu mengirimkan istri, selir, anak-anak, serta senjatanya sebagai tanda akan tunduk terhadap keputusan raja. “Raja memperlihatkan kemurahan hatinya, lebih-lebih karena putri Singaranu adalah yang paling cantik dan manis dari istri-istri raja, dan istri ini dapat mengetuk hati raja,” tulis De Graaf.
[2] Saat ini loksinya di Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung.
[3] Dalam ”Brieven van Jan Karel Jakob de Jonge (1828-1880) aan Arie Cornelis Kruseman (1818-1894)” LTK 1440, dokumentasi Universitas Leiden, Belanda
[4] Dagh Register mencatat, selama 1629-1636, gelombang eksodus warga Tatar Ukur ke Jakatra dan banten masih terjadi, sekali pun Dipati Ukur pada 1632 disebut-sebut telah ditangkap Mataram.
[5] Dagh Register, Anno 1631-1634, 1898:4
[6] Sebagaimana ditulis Rohendy Sumardinata dan Supis dalam ‘Dipati Ukur’ jilid I hal 48. Bandung: Daya Sunda Pusat. 1959/60.