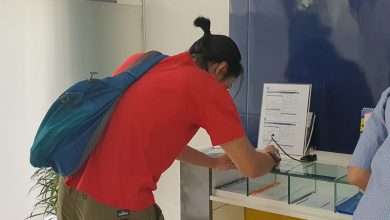Mengabaikan peran Aceh berarti mencabut salah satu akar utama dari pohon kemerdekaan Indonesia. Ini bukan soal nostalgia, apalagi glorifikasi. Ini soal keadilan sejarah. Kita tidak bisa membangun masa depan bangsa tanpa menghormati seluruh elemen yang membentuknya, termasuk mereka yang mungkin tidak berada di pusat kekuasaan atau sorotan media.
Oleh : Iswadi*
JERNIH– Delapan dekade sudah Indonesia mengarungi kemerdekaan. Delapan puluh tahun bukan waktu yang singkat ia adalah rentang sejarah yang penuh dengan perjuangan, pengorbanan, dan semangat kolektif rakyat dari Sabang sampai Merauke.
Namun, dalam euforia memperingati usia kemerdekaan yang ke-80 ini, kita perlu bertanya dengan jujur dan penuh kesadaran: sudahkah kita memberi ruang yang layak dalam ingatan bangsa bagi rakyat Aceh, yang sejak awal turut menyalakan obor kemerdekaan?
Aceh bukan sekadar daerah ujung barat Indonesia. Ia adalah titik awal yang dalam banyak hal menjadi penopang dan pendorong lahirnya republik ini. Dalam sejarah nasional, Aceh dikenal sebagai daerah yang tak pernah tunduk begitu saja pada penjajahan. Perang Aceh melawan kolonial Belanda yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade (1873–1904) adalah salah satu bentuk perlawanan terpanjang dan paling berdarah dalam sejarah kolonialisme di Nusantara.
Namun perjuangan Aceh tak berhenti saat masa penjajahan formal berakhir. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Aceh tidak ragu berdiri di barisan terdepan untuk mendukung republik muda yang masih rapuh. Bahkan ketika Belanda datang kembali dengan agresi militer untuk menjajah kembali Indonesia, Aceh menjadi salah satu wilayah yang tetap merdeka dan menjadi basis penting pertahanan.
Yang paling monumental adalah peran rakyat Aceh dalam mendukung secara logistik dan finansial perjuangan diplomatik Indonesia di mata dunia. Masyarakat Aceh menggalang dana, menyumbangkan emas, dan mendanai pembelian pesawat pertama Republik Indonesia RI 001 dan RI 002 yang digunakan untuk misi diplomasi ke India dan kemudian ke PBB. Para saudagar Aceh, tokoh agama, dan rakyat biasa bahu-membahu demi keberlangsungan republik yang bahkan belum sepenuhnya mapan.
Sumbangan dua pesawat Dakota itu bukan hanya simbol kedermawanan; ia adalah bentuk cinta tulus dan keyakinan rakyat Aceh terhadap republik ini. Namun kisah itu, sayangnya, perlahan mulai tenggelam dalam narasi besar sejarah nasional yang lebih sering terpusat di Jawa.
Kini, dalam momentum 80 tahun Indonesia merdeka, penting untuk kembali merefleksikan: mengapa jasa besar rakyat Aceh cenderung terlupakan dalam narasi utama sejarah nasional? Apakah karena sejarah kita terlalu Jawa sentris? Ataukah karena kita kurang serius dalam merawat ingatan kolektif bangsa?
Mengabaikan peran Aceh berarti mencabut salah satu akar utama dari pohon kemerdekaan Indonesia. Ini bukan soal nostalgia, apalagi glorifikasi. Ini soal keadilan sejarah. Kita tidak bisa membangun masa depan bangsa tanpa menghormati seluruh elemen yang membentuknya, termasuk mereka yang mungkin tidak berada di pusat kekuasaan atau sorotan media.
Dalam konteks pembangunan dan integrasi nasional hari ini, mengakui kembali jasa Aceh bukan hanya soal sejarah, tetapi juga soal rekonsiliasi, penghargaan, dan penguatan rasa keadilan antar daerah. Aceh, dengan segala dinamika dan luka masa lalunya, tetaplah bagian penting dari Republik Indonesia. Ia telah menunjukkan betapa besar semangat persatuan dan pengorbanannya.
Kini, generasi muda Indonesia perlu mengenal lebih dalam siapa Teuku Umar, Cut Nyak Dhien, Tgk. Muhammad Hasan Krueng Kalee, atau tokoh-tokoh seperti Daud Beureueh dan tokoh ulama lain yang tidak hanya berjuang dengan senjata, tapi juga dengan pikiran dan keikhlasan. Mereka bukan hanya pahlawan Aceh mereka adalah pahlawan Indonesia.
Seiring usia republik yang ke-80, mari kita jadikan momen ini bukan hanya untuk merayakan, tetapi juga untuk mengingat. Bukan hanya mengulang slogan-slogan nasionalisme, tetapi juga menggali kembali lapisan-lapisan sejarah yang nyaris dilupakan. Aceh, dengan segala warisannya, adalah cahaya yang ikut menerangi jalan panjang republik ini. Sudah saatnya cahaya itu kita rawat, kita sorot kembali, dan kita tempatkan di tempat yang seharusnya: dalam hati dan ingatan bangsa.
Sebab bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang tahu ke mana ia akan pergi, tetapi juga bangsa yang tidak melupakan dari mana ia berasal. [ ]
*Dr. Iswadi, M.Pd., Dosen Universitas Esa Unggul Jakarta