Agama di Era Kisruhnya Media Massa
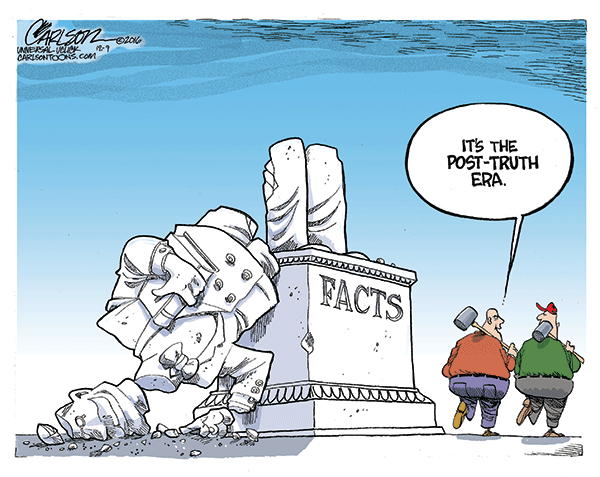
Barangkali, kondisi semihipokrit dalam masyarakat kita juga banyak mendapatkan sebab dari persoalan ini. Merujuk pendapat seorang ahli linguistik, Alfred Korzibsky, penyakit jiwa—personal maupun sosial, timbul karena penggunaan bahasa yang tidak benar. Pertama, mungkin karena terlalu sering menutupi kebenaran dengan kata-kata yang abstrak atau ambigu. Misalnya, gampang menjustifikasi dengan kata-kata ‘tak Pancasilais’, ‘radikal’, dan sebaliknya ‘intoleran’,’dzalim’, dan sebagainya.
Oleh : Darmawan Sepriyossa
JERNIH–“The media’s the most powerful entity on earth. They have the power to make the innocent guilty and to make the guilty innocent, and that’s power. Because they control the minds of the masses” – Malcolm X
Maksud saya menyitir pernyataan alm Malcolm X tak lain bahwa begitu berkuasanya media telah mulai terasa bahkan pada 1960-an itu, saat Malcolm masih berkiprah di dunia. Malcolm mengakui, saat itu pun merah hitam hidup seseorang sudah diarahkan, didikte oleh media massa.
Maka, jika pada era 1960-an saja media telah berperan begitu rupa, bagaimana kondisinya saat ini?

Barangkali kita bisa meneropong, mengira-ngira hal itu dari betapa kuatnya saat ini media massa menempel—‘menaplok’ kata urang Sunda, kalau bukan mencaplok kehidupan kita. Marilah kita membatasinya dengan membicarakan media yang paling dominan dan memiliki pengaruh paling kuat saat ini, yakni televisi.
Sekitar tiga dasawarsa lalu, George Gerbner[1], pakar komunikasi AS, menyebut televisi sebagai agama masyarakat industri. Televisi seolah telah menggeser agama-agama konvensional. ‘Khutbah’nya dalam program dan acara, telah didengar dan disaksikan oleh jamaah yang lebih besar dari jamaah agama manapun. Rumah ibadatnya tersebar di seluruh penjuru bumi, menyuarakan idelogi, menjejalkan pemikiran ke semua manusia yang memirsanya.
Seperti agama, televisi pun bisa memberi legitimasi kepada para ‘raja’. Bila Paus memberkati raja-raja, tv mentahbiskan para penguasa dunia modern, mengangkat orang pada kursi kekuasaan dan jabatan politik. Di sisi lain, tv pun bisa mengorek-orek kesalahan seseorang, membuka dan meniupkannya sebagai berita besar dan menjungkalkannya dari posisi yang sedang diduduki.
Catatan sejarah dengan gampang mengingatkan kita pada momen manakala Barbara Walters bisa mewawancarai presiden AS, Jimmy Carter, sesaat sebelum pelantikannya sebagai presiden pada medio 1970-an dulu. Walters dengan segera menerima pengakuan sebagai ‘paus perempuan dari televisi’—the female pope of television. Ketika Dan Rather dari CNN pada Perang Teluk awal 1990-an lalu berhasil mewawancarai Saddam Hussein, nama Dan pun langsung meroket seolah menjadi dewa pemberitaan dunia. Hal yang sama berlangsung terus dari hari ke hari. Bahkan saat Putra Nababan dari RCTI diberi kesempatan mewawancarai Presiden Barrack Obama, meski hanya dalam ukuran menit dan dengan kualitas pertanyaan ‘begitu-begitu saja’, toh untuk beberapa lama nama Putra seolah identik dengan dunia pemberitaan Indonesia.
Bila agama pernah memegang kekuasaan ekonomi, begitu pula televisi. Bisnis tv bukan saja kuat secara financial, ia juga perkasa dalam memengaruhi kegiatan-kegiatan ekonomi. Lihatlah iklan, khutbah agama bernama televisi itu. Siapa bilang iklan hanya memasarkan produk? Iklan juga merupakan pemasar paling digjaya dari nilai, sikap, perasaan dan gaya hidup. Iklan televisi, kata Christopher Lasch, tidak berkepentingan untuk menunjukkan bagaimana kualitas produk, melainkan memberikan penegasan bagaimana konsumsi barang bisa mengatasi masalah-masalah kehidupan; mengobati kesepian, menaikkan harga diri, menjamin kebahagiaan.[2]
Lihatlah bagaimana Coca Cola, Sprite atau produk minuman ringan pabrikan lainnya menggantikan kata ‘air’ dalam benak manakala kita merasa haus. Bagaimana ayam goring Kentucky, Pizza Hut, dan aneka merek menggantikan bayangan akan makanan konvensional buatan rumah, di saat kita lapar.
Atau, mungkin saja iklan bahkan sempat membuat Anda sempat-sempatnya berpikir bahwa kegagalan Anda dalam pergaulan semata akibat tak punya kebiasaan mengolesi ketiak dengan satu nama deodorant. Dan boleh jadi, manakala seorang istri merawat rambutnya dengan cara membasuhnya dengan samphoo merek tertentu, ia melakukan itu dengan keyakinan bisa merebut kecintaan suaminya.
Yang paling menguatirkan, tv pun mendesakkan ajaran bahwa hidup itu seolah begitu mudahnya. Tentu saja bukan maksud saya mengajak Anda semua menjadi pesimistis menghadapi kehidupan. Saya hanya mengajak Anda untuk tersadar dari mimpi-mimpi yang diantarkan dengan anggun oleh televisi. Mimpi-mimpi yang mengajarkan hidup ini seolah bisa diraih dengan cara-cara yang instan dan sepele, tanpa membutuhkan perjuangan dan keringat.

Lihatlah fenomena yang sudah berlangsung entah berapa dasawarsa lamanya pada dunia sinetron kita. Ada adegan yang saya dengar dari seseorang—karena saya bukan penonton sinetron, di mana seorang gadis SMU yang tengah bersedih dengan gampangnya jatuh ke pelukan teman sekolahnya. Lalu dengan kata-kata berbunga yang tak jelas arahnya, si pemuda tanggung itu mampu mengubah si gadis menjadi sumringah dan seolah hendak melahap hidup dengan gairah. Jangan tanya lagi soal adegan-adegan yang mempertontonkan seorang direktur muda kaya raya yang tak pernah jelas kerjanya, kecuali di kepala kita akan langsung tertera: kaya karena orang tua, dan dia bisa menikmati masa muda dalam foya-foya, masa tua yang aman dalam keadaan kaya raya, lalu karena datang kesadaran sebelum ajal, mungkin saja saat mati pun nanti ia akan masuk sorga.[3]
Di dunia politik dan pemerintahan, hal itu barangkali bisa terlihat lebih vulgar. Bukankah kita hampir setiap saat dicecoki tv dengan videopolitik, yang sering kali kita lihat dengan gampangnya di layar tv? Itu bisa berupa berbagai jenis, entah berupa tayangan berita, pertunjukan bincang-bincang, pernyataan pembawa acara, dsb. Sebagaimana ahli strategi militer abad XIX, Von Clausewitz, pernah berkata bahwa politik adalah merupakan perpanjangan perang dengan cara lain, dengan menambahkan kata ‘video’, maka videopolitik kini telah menjadi perpanjangan perang dengan cara lain. Videopolitik adalah kegiatan melalui televisi untuk mempengaruhi system dan kondisi politik, nasional maupun internasional.
Lihat saja contoh klasik ini. Acara tv ‘ The Great Debate’ tahun 1960, seringkali dijadikan contoh betapa tv bisa mempengaruhi sikap dan pilihan pemilih[4] manakala Kennedy terpilih dan unggul dari Nixon setelah siaran tv itu.
Apa yang sesungguhnya dilakukan tv hingga bisa memberikan dampak sejauh itu? Barangkali, kita bisa merujuk Irving Kristol. Bagi seorang yang di akhir hidupnya dikenal sebagai seorang neokonservatif ini, yang dilakukan tv dengan kekuatan luar biasa itu adalah memobilisasi emosi pemirsa di sekitar gambaran dunia politik yang hidup, disederhanakan dan bersifat melodramatic, dimana pujian dan kutukan menjadi kutub-kutub magnetisnya.
Kristol benar. Paling tidak, kita pun sadar bahwa gambaran di layar tv adalah gambaran yang telah diolah. Ada tangan pertama yang usil, yakni kamera, yang dengannya ditentukan kesan yang ingin dicuatkan dengan cara gerak, ambilan dan sudut kamera (angle). Setelah itu ada penyuntingan alias editing. Dua gambar bisa dipadukan untuk menimbulkan efek yang dimaui. Misalnya, Presiden SBY berpidato, lalu ditampilkan gambaran hadirin yang bertepuk tangan. Itu membuat pemirsa mendapatkan gambaran bahwa pidato itu disambut meriah. Padahal mungkin hadirin yang bertepuk tangan itu lebih sedikit dibanding yang diam.
Begitulah paling tidak peranan media massa dalam kehidupan kita.
Dengan begitu besarnya kekuatan media, maka sesungguhnya besar pula tanggung jawab mereka yang mengelolanya. Mungkin sebagaimana ungkapan klasik, not the gun, but the man behind the gun-lah yang menentukan apakah kebaikan atau keburukan yang dibuat media dengan kekuasaannya yang besar itu.
Bukan sesuatu yang langka menemukan betapa pengelola ataupun penguasa media menyalahgunakaan kekuasaannya itu untuk berlaku sewenang-wenang. Kita tidak harus membakar kemenyan dan mengundang arwah Edward Said bersaksi di sini. Dalam bukunya ‘Blaming The Victims’, Edward Said secara jitu mengungkapkan bagaimana media massa Amerika menciptakan gambaran negatif bangsa Palestina[5].
Itu menurutnya berhubungan dengan fakta, sekitar 25 persenwartawan di Washington dan New York adalah Yahudi. Sebaliknya (saat itu) hampir tidak ada koran atau tv Amerika terkemuka yang mempunyai wartawan Arab atau Muslim.
Lebih jauh, saat menulis ‘Covering Islam’ Edward Said menunjukkan bagaimana penggambaran umum media massa Barat dalam merepresentasikan Islam[6]. Berbagai citra negatif melekat dalam penggambaran media barat mengenai Islam. Agama itu kemudian dibuat identik dengan teroris. Sebaliknya, teroris identik dengan Arab dan Islam. Media barat telah membentuk citra tentang Islam yang identik dengan kekerasan, terorisme, fundamentalisme. “Sebuah generalisasi yang tidak bisa diterima, tidak bertanggung jawab, dan tidak dapat diterapkan pada kelompok-kelompok agama, budaya, atau demografi lainnya di dunia,” kata Edward dalam pengantar buku tersebut.
Jangan pernah berpikir hal itu hanya dilakukan media massa-media massa ‘cetek’ yang memiliki jurnalis kelas tiga. Wartawan senior koran sekaliber New York Times pun ternyata tidak kebal dari kebodohan semacam itu. Saat mengomentari buku Islamic Government karya Ayatullah Khomeini, misalnya, George Capozi,Jr, wartawan koran tersebut menuliskan catatannya dengan judul ‘Ayatollah Khomeini’s Mein Kampf’. Dalam tulisan itu, selain dengan lucu menyatakan bahwa Imam Khomeini seorang Arab dan Islam telah dimulai sejak abad ke-5 sebelum Masehi, ia juga menulis:
Seperti Adolf Hitler pada masa yang lain, Ayatullah Ruhullah Khomeini adalah seorang tiran, pembenci, pemberang, sebuah ancaman bagi tatanan dan kedamaian dunia. Perbedaan utama antara Mein Kampf dengan Islamic Government yang hambar adalah bahwa penulisnya yang satu atheis dan satunya lagi berpura-pura sebagai hamba Tuhan..” [7]
Lebih jauh, berdasarkan riset penuh kesabaran yang dilakukan Noam Chomsky, ternyata media massa melakukan itu bukan tanpa niat. Dalam banyak kasus, semua dilakukan dengan strategi.
Misalnya, Chomsky menunjuk apa yang disebut strategi pengalihan isu—satu terma yang kian akrab di telinga kita sejak Presiden SBY berkuasa. Caranya dengan mengalihkan perhatian publik dari isu-isu penting dan perubahan yang ditentukan oleh elit politik dan ekonomi. Caranya dengan membanjiri public secara terus menerus dengan informasi yang tidak signifikan. Strategi ini penting untuk mencegah minat publik untuk masuk lebih jauh ke dalam info yang merugikan perancang strategi—pemerintah atau pemilik modal, misalnya. Strategi penebaran gangguan sangat penting untuk menjaga agar masyarakat lebih berfokus pada isu-isu ‘kacangan’ sehingga melupakan isu-isu krusial yang berhubungan dengan hidup dan kehidupan rakyat.
Cara lain bisa dilakukan dengan apa yang disebut ‘masalah-reaksi-solusi’. Caranya dengan menciptakan masalah, ‘sebuah situasi’ yang menyebabkan reaksi public. Misalnya, dengan menciptakan masalah yang dapat menyebabkan rakyat ‘mengemis’ memohon pertolongan pemerintah. Lalu pemerintah menjadi sinterklas bagi masalah yang dibuatnya sendiri.
Cara lainnya yakni dengan melakukan strategi bertahap; strategi menunda, yakni senyampang menunggu sesuatu yang menyakitkan datang, terus berusaha melakukan sosialisasi akan harusnya sesuatu itu berlaku. Dengan begitu, manakala kenyataan untuk tibanya sesuatu itu—misalnya naiknya harga BBM, datang, rakyat bisa menerimanya dengan pasrah.
Chomsky juga melihat adanya cara yang disebutnya strategi mendatangi public sebagai anak kecil. Kita melihat hal itu kian sering dilakukan Presiden SBy saat ini. Lihatlah caranya dalam mencari simpati rakyat. Dia selalu muncul seakan-akan figur lemah dan teraniaya, padahal dia sedang menjalankan program peningkatan citra.
Chomsky masih menjabarkan strategi-strategi media itu hingga sekitar 10 jumlahnya.
UNTUNGLAH, kini tayangan-tayangan dan pemberitaan yang sepihak dalam media Barat itu mendapat respons balik yang memperlihatkan fakta sebaliknya. Contoh yang paling menonjol adalah jaringan televisi Al Jazeera (Aljazirah) yang berpusat di Doha, Qatar. Televisi yang kini begitu populer dan disengiti pemerintah Amerika karena sempat dianggap menjadi corong pemerintah Irak itu menjadi alternatif baru bagi sumber berita.
Dalam perang Teluk II, kehebatan dan kegigihan tentara dan para pengikut Saddam, kegagalan-kegagalan tentara koalisi, sekaligus para korban perang yang menyedihkan, justru semakin banyak memenuhi halaman-halaman media. Tak hanya mereka, media- media Eropa pun mulai merasa bosan dengan pemberitaan dan gambar-gambar yang ditayangkan media Amerika yang dianggap banyak menyembunyikan fakta itu.
Inilah kelompok yang oleh Edward Said dikategorikan sebagai kalangan yang berada di luar arus utama (mainstream) yang dominan. Mereka ini disebutnya kelompok antitesis, yang memiliki pandangan berbeda dalam memandang sesuatu. Mereka ini sempat keberadaannya tidak begitu diperhitungkan, hingga kemudian muncul ke permukaan dan mengagetkan.
Kalangan inilah—yang direpresentasikan koran Jerman, Frankfurter Allgemeine Zeitung dalam kasus pembantaian di Houla, Suriah[8], yang menunjukkan betapa negara besar seperti Amerika Serikat, yang menyebut diri paling demokratis di dunia, nyatanya hanya mempertimbangkan segala sesuatunya berdasarkan kepentingan sendiri dan mengabaikan fakta yang merugikan mereka. Menunjukkan bahwa negara yang sok mengagungkan hak asasi manusia itu, sejatinya hanya pembantai ribuan manusia tak berdosa, di Vietnam, Afganistan dan Irak ini. Membuka mata kita bahwa negara dengan teknologi yang sangat canggih itu pun ternyata masih merasa perlu memfitnah, sebagaimana dalam kasus tudingan senjata pemusnah massal sebelum menyerang Irak.
Agama dan Media
Ada petikan dalam Alquran:
“Yang Mahakasih, Mengajarkan Quran,
Mencipta insan, mengajarkan Al Bayan (Qs Ar Rahman, 55: 1-4)
Al Bayan, menurut Al-Syaukani dalam Fath Al-qadir, adalah komunikasi. Dengan kata lain, menyetujui apa yang sempat dikatakan Hajjatul Islam Rafat Bayat, seorang ulama Iran, saya sepakat bahwaIslam adalah agama komunikasi. Dari penjelasan ini,
Hujjatullah Bayat mengambil kesimpulan, demi menyampaikan pesan-pesan transenden Islam, sudah seharusnya umat Islam memanfaatkan semaksimal mungkin media massa demi menyebarkan agama Islam.
Kita tahu, saat ini media massa memainkan peran sangat penting dan tidak dapat dimungkiri mampu menyampaikan pesan lebih cepat dan luas. Semakin maju dunia, peran ini semakin meluas. Pengaruh media semakin menjadi-jadi, berbarengan dengan bergulirnya era televise, dan terakhir, munculnya internet. Satelit kini memancarkan gelombang suara dan gambar ke seluruh dunia, bahkan ke daerah-daerah terpencil sekalipun.
Bagi saya, agama adalah alat untuk menjadikan dunia lebih baik. Jadi, kebaikan public itulah yang menjadi tujuan utama. Maka manakala media massa pun memungkinkan kita mencapai kondisi dunia yang lebih baik, bukan lagi tidak ada salahnya melainkan justru media massa harus diabdikan untuk meraih tujuan yang lebih baik itu.
Mungkin saja, dengan esensi globalitas media itu kaum muslim harus memanfaatkannya untuk menyebarkan ajaran agama. Terlebih lagi dikarenakan pada prinsipnya risalah asli para nabi adalah mendakwahkan agama, spiritual dan menuntun manusia. Keharusan memanfaatkan media massa untuk mendakwahkan agama itu semakin menunjukkan urgensinya saat dihadapkan dengan fakta betapa Barat telah lebih dulu memanfaatkan seluas-luasnya media massa untuk menguasai dunia. Saat ini media-media massa barat menjadi besar dan berpengaruh. Mayoritas media yang dikuasai para pemilik kekuasaan dan modal itu digunakan demi menjamin berlanjutnya keserakahan politik dan ekonomi mereka. Manakala media bisa dimuati faham materialistik, seks bebas, kekerasan dan pelbagai kebejatan moral, maka ia bisa pula dimanfaatkan guna menyebarkan spiritualitas, moral dan penyembahan kepada Allah demi mengantarkan manusia kepada kesempurnaan.
Tapi kalau pun tidak seluhur itu, media massa seharusnya menaati satu hal besar yang secara genuine ia pikul: taat kepada kebenaran.
Barangkali karena itu, maka Bill Kovach pernah berkata bahwa agama yang dianutnya adalah jurnalisme. Kovach melihat ada kekuatan dalam jurnalisme yang mampu membangun masyarakat yang lebih baik. Kovach percaya, semakin bermutu jurnalisme di dalam masyarakat, makin bermutu pula informasi yang didapat masyarakat bersangkutan. Terusannya, makin bermutu pula keputusan yang akan dibuat. Saya sendiri termasuk orang yang percaya, kalau saja jurnalisme di Indonesia bermutu maka kehidupan masyarakat kita pun akan makin bermutu.
Persoalannya, di Indonesia kebanyakan media massa memiliki mutu yang berada di bawah standar mutu jurnalisme internasional. Itulah yang membuat jurnalisme kita seringkali tak lebih dari ‘talking news’. Para wartawan kita sudah merasa memiliki berita untuk disiarkan, hanya manakala mereka mendengar seseorang bicara. Alih-alih menggali fakta, bahkan biasanya benar-tidaknya isi pembicaraan itu pun luput atau mungkin malas untuk diverifikasi.

BAGAIMANA HUBUNGAN agama dengan media massa? Bagi saya, meskipun tak harus berarti mengabdi, nilai-nilai moral agama seharusnya bisa menjadi pegangan bagi para (pelaku) media.
Jadi, bagai saya, manakala pelaku media mentaati ajaran moral agamanya–atau kalau pun seorang atheis sekalipun yang pasti memiliki standar moral tertentu, saat itu pula media akan mampu memfungsikan diri sebagai perangkat pencerah. Media bisa menjadi katalisator ke arah kehidupan yang lebih baik tadi.
Paling tidak, dalam Islam yang saya yakini, ada beberapa ajaran moral yang erat berkenaan dengan komunikasi dan media massa.
Misalnya, ada ajaran bahwa dalam berkomunikasi kita harus melakukan qawlan sadidan (QS 4:9) , alias berbicara benar atau jujur. Dengan ajaran itu, seorang jurnalis muslim seharusnyalah mengedepankan kejujuran dalam bekerja. Ia sebagaimana Pickthall menerjemahkannya, haruslah berusaha straight to the point.
Barangkali, kondisi semihipokrit dalam masyarakat kita juga banyak mendapatkan sebab dari persoalan ini. Merujuk pendapat seorang ahli linguistik, Alfred Korzibsky[9], penyakit jiwa—personal maupun sosial, timbul karena penggunaan bahasa yang tidak benar. Pertama, mungkin karena terlalu sering menutupi kebenaran dengan kata-kata yang abstrak atau ambigu. Misalnya, gampang menjustifikasi dengan kata-kata ‘tak Pancasilais’, ‘radikal’, dan sebaliknya ‘intoleran’,’dzalim’, dan sebagainya.
Kedua, seringkali menutupi kebenaran dengan menciptakan istilah. Misalnya ‘kekurangan gizi’ dan rawan pangan untuk mengganti fakta adanya kelaparan; atau pun menggunakan kata ‘diamankan’, ‘disukabumikan’ untuk mengganti ditangkap dan dibunuh.
Ajaran untuk melakukan qawlan baligha, atau berkomunikasi dengan bahasa yang terang, tepat dan efektif, jelas mengharuskan seorang jurnalis muslim untuk selalu berupaya meningkatkan kualifikasi dirinya. Ia akan terus menjadikan dirinya lebih profesional dalam kerjanya. Ia akan menambah sebanyak mungkin perbendaharaan kata, serta kemampuan merangkai kalimat hingga kian jelas, efektif dan efisien. Ia akan menghindari pemakaian kata yang ambigu, tak jelas, bertele-tele seraya menyembunyikan kebenaran.
Selain itu, yang terutama, adanya kisah Al Walid bin Uqbah yang menjadi asbabun nuzul QS Hujurat 7, mengharuskan jurnalis muslim selalu mengedepankan tabayun. Dalam bahasa jurnalistik fatabayannu alias tabayun itu barangkali adalah kerja investigative reporting. Kerja di perpustakaan dan di lapangan untuk menggali sebanyak mungkin fakta dan data, agar terungkap kebenaran yang ada.
Seorang reporter harus berpantang surut dalam mengejar dan mendapatkan berita. Karena setiap kalimat yang diwartakan, setiap gambar yang disiarkan sejatinya adalah kerja keras dan keringat, dan sebagaimana kata Bill Kovach[10], tanggung jawab kepada publik. Jurnalisme karenanya dituntut dirinya sendiri untuk terbuka, dituntut dirinya sendiri untuk tidak culas. Ia diminta tak putus-putusnya untuk meraih apa yang baik dan benar, betapa pun mustahilnya. [11]
Karena itu pula, dengan tanggung jawabnya pada publik, serang jurnalis adalah seorang yang tak pernah bisa dibeli.
Kita tentu tak mengharapkan kondisi jurnalisme di Indonesia sebagaimana judul sebuah buku, ‘Will the Last Reporter Please Turn Out the Light: The Collapse of Journalism and What Can Be Done to Fix It’.[12] Kita tak ingin para jurnalis kita tak sanggup menghadapi tantangan karena memang mereka tak punya kualifikasi yang baik. Dan untuk menolak semua itu menjadi actual, semua harus bermula dari memperbaiki kualifikasi jurnalisnya sendiri.
Jangan lagi terjadi apa yang sempat dialami harian Republika beberapa tahun lalu. Gara-gara kualifikasi buruk seorang reporternya dalam bahasa Inggris, serta keengganan untuk bertabayun—melakukan reportase investigatif, sebuah media yang mengakui diri sebagai media massa Islam menulis bahwa Republika sudah dimiliki yahudi. Benar kemudian reporter dan media ’Islam’ itu meminta maaf setelah kesalahan mereka terkuak. Tetapi satu hal tak bisa dinafikan: sudah ada luka akibat fitnah yang barangkali tanpa sengaja. The damaged has been done. Tak ada cara untuk memperbaikinya, apalagi hanya dengan pernyataan ralat.
Dari sini kemudian kami tahu, bahwa media Islam bukanlah sekadar media yang rajin mengutip ayat-ayat Quran dan petikan hadits seraya tetap membuka peluang untuk menjelekkan dan mencaci tanpa bukti. Media Islam, seharusnya jauh lebih berakhlak daripada itu.
Semoga kita mampu menyuburkan tumbuhnya media-media yang bertanggung jawab seperti itu. [dsy]
—Grand Wijaya, 31 Juli 2012—
[1] Gerbner, G., Gross, L., Morgan, M., & Signorielli, N. (1986). “Living with Television: The Dynamics of the Cultivation Process” dalam J. Bryant & D. Zillman (Eds.), Perspectives on media effects (pp. 17–40). Hilldale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
[2] Lasch: The Culture of Narcissism: American Life in an Age of Diminishing Expectations. W. W. Norton & Company; edisi revisi. 1991
[3] Ungkapan ini sempat begitu meraja di kalangan generasi muda 1980-an, atau generasi si Boy, ‘Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk sorga’.
[4] Debat yang disiarkan langsung televisi itu menunjukkan, betapa layar tv bisa mempengaruhi citra seseorang, mengangkatnya sebagai si hebat. John F Kennedy, seorang senator muda yang belum menunjukkan prestasi apa-apa, setelah debat itu mampu mengalahkan suara Richard Nixon, seorang yang sudah dua kali berada dalam posisi wakil presiden.
[5]Blaming the Victims: Spurious Scholarship and the Palestinian Question.Verso. 2001
[6]Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the World. Vintage Books.1997
[7] Ayatollah Khomeini’s Mein Kampf: Islamic Government by Ayatollah Rohullah Khomeini. New York, Manor Books. 1979
[8] Berbeda dengan yang lain, dalam kasus pembantaian di Houla, Suriah, awal Juni lalu, koran ini dengan tegas menyatakan hal itu tak mungkin dilakukan pasukan Suriah, melainkan pasukan antipemerintah. Salah satu alasan FAZ, penduduk daerah itu secara budaya dan kebiasaan merupakan pendukung pemerintah.
[9] Science and Sanity: An Introduction ton Non-Aristotelian Systems and General Semantic. Institute of General Semantics. 1995.
[10] Bill Kovach dan Tom Rosentiel, Elemen-elemen Jurnalisme. ISAI. 2003
[11] Lihat Goenawan Mohamad, Y.D (1944-2009), Catatan Pinggir 9.2012
[12] Robert W McChesney & Victor Pickard, eds. 2011
[1] Tulisan ini hanya pengubahan sangat kecil dari sebuah makalah yang pernah dipresentasikan di Masjid Salman-ITB, hampir satu dekade silam.







