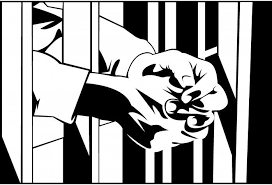Mengapa Prabowo harus merasa “rikuh bin jengah”—istilah buatan yang penulis anggap paling mampu melukiskan kondisi beliau–? Tiga kali bukan kesempatan yang sedikit. Kadang, pada beberapa budaya suku tertentu di Tanah Air, tiga kali sering dianggap pertanda untuk mulai mengambil sikap “menerima”. Di Tanah Pasundan dikenal istilah nista, maja, utama, yang secara sederhana bisa berarti “geus kaleuleuwihi” atau sudah keterlaluan. Bahasa Inggris punya istilah yang khas untuk itu: enough is enough.
Oleh : Darmawan Sepriyossa
JERNIH– Tanpa harus dinyatakan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, bahwa sikap partai untuk mencapreskan kembali Prabowo Subianto sudah final dan tinggal menunggu momentum untuk meresmikannya dalam prosesi deklarasi, sejatinya masyarakat banyak pun sudah mafhum. Ibarat koboy tua William Munny yang diperankan Clint Eastwood dalam “Ünforgiven”, meski sesekali tersedak batuk dan kaki kurang tegar menapak, masyarakat melihat para elit Gerindra masih percaya Prabowo tetap digjaya. Setidaknya, barangkali, untuk menopang kepentingan mereka.

Mudahnya elit Gerindra mengambil sikap seperti itu, sebaliknya belum tentu mudah bagi Prabowo untuk menentukan sikap. Tiga kali kegagalan berturut-turut dalam kontestasi Pilpres, meski tak akan membuatnya trauma, “rikuh bin jengah” sih pasti ada.
Prabowo mulai masuk gelanggang Pilpres saat mendampingi capres Megawati Sukarnoputri pada Pilpres 2009. Hasilnya,kalah. Kedua, saat menjadi capres berpasangan dengan Hatta Rajasa, dengan hasil serupa pada 2014. Ketiga, di 2019 ia kembali tampil ke muka dibantu sekondannya, Sandiaga Uno, dengan hasil kembali dipecundangi.
Mustahil kegagalan tiga kali berturut-turut itu tidak menorehkan bekas di hati beliau. Bagaimana pun, sebelum memutuskan untuk kembali bertarung, Prabowo sebelumnya sudah pasti harus memenangkan dulu pertempuran hebat dalam hatinya. Pergolakan antara rasa “rikuh bin jengah” tersebut dengan antusiasme dan rasa penasaran.
Mengapa Prabowo harus merasa “rikuh bin jengah”—istilah buatan yang penulis anggap paling mampu melukiskan kondisi beliau–? Tiga kali bukan kesempatan yang sedikit. Kadang, pada beberapa budaya suku tertentu di Tanah Air, tiga kali sering dianggap pertanda untuk mulai mengambil sikap “menerima”.
Di Tanah Pasundan dikenal istilah nista, maja, utama. Dalam kamus Sunda-Indonesia susunan Maman Sumantri, dkk (1985), arti nista, maja, dan utama adalah sebagai berikut: nirca atau nista artinya aib; menyimpang dari ajaran agama. Maya atau maja artinya sedang, sementara utama artinya (sudah) cukup. Pemakaiannya dalam kalimat, misalnya: “Lain ukur sakali dua kali manéhna nganyerikeun haté kuring. Geus nista maja utama. Moal diantep ayeuna mah. Bukan sekali dua dia menyakiti hati saya. Sudah nista maja utama. Tak akan lagi saya biarkan.” Dengan kata lain, nista maja utama itu bisa berarti “geus kaleuleuwihi” atau sudah keterlaluan. Bahasa Inggris punya istilah yang khas untuk itu: enough is enough.
Di sisi lain, sukar dinafikan bahwa kondisi saat ini pun memberi banyak peluang bagi Prabowo. Saya sepakat dengan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, yang mengatakan bahwa Pemilu 2024 bisa dijadikan Prabowo sebagai waktu yang tepat untuk unjuk kekuatan. Apalagi sampai saat ini pun belum ada tokoh dominan, sementara beberapa yang menonjol selain dirinya—Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, misalnya—belum punya kepastian diusung partai atau aliansi partai yang memenuhi ambang presidential threshold.
Masuk akal bila hal itu membuat inner cyrcle di sekeliling ngebet agar Prabowo kembali “nyapres”. Dalam terma Wakil Ketua Umum Gerindra, Habiburokhman, saat ini justru merupakan,”Momentum emas Prabowo untuk maju dan menang Pilpres 2024,” kata dia.
Persoalannya, pada Pemilu 2024 nanti usia Prabowo sudah tidak muda lagi: 72 tahun. Artinya, menyilakan Prabowo ikut dalam kontestasi, seolah merestui negeri ini terperosok ke dalam lubang gerontokrasi—negara yang dikendalikan para sepuh. Memang tak ada salahnya, apalagi bila dihadapkan kepada hak asasi orang. Kecuali mungkin akan banyak gerutuan awam di warung kopi,”Memangnya sudah nggak ada lagi orang muda, apa?”
Di sinilah tampaknya usulan Asosiasi Komunikolog Profesional agar Prabowo bersedia menjadi king maker, menemukan alasan kuatnya. Apalagi sebagai king maker, sukses Prabowo tergolong fenomenal. Beliaulah yang pertama kali mengusung Jokowi sebagai calon gubernur DKI Jakarta dan memenangkannya. Beliau pula yang dengan jeli menangkap peluang bersinarnya Ahok, hingga tokoh Belitung itu memutuskan berkiprah di Jakarta. Jangan lupa pula, Prabowo juga yang menggadang-gadang Anies sejak awal, hingga tokoh muda itu terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta, dengan sinar yang kini kian berbinar.
Barangkali, tak ada salahnya beliau mempertimbangkan saran para komunikolog tersebut. Akan halnya “aspirasi” warga Gerindra di daerah, sebagai tokoh sejarah yang langsung berada di pusarannya saat itu, Prabowo tak hanya mafhum, tetapi telah khatam pengalaman mantan mertua beliau, alm Pak Harto. Di 1997 itu, Ketua Golkar mendiang Harmoko mendesak Pak Harto dalam sebuah kebulatan tekad untuk mendukungnya kembali mencalonkan diri sebagai presiden. Saat itu Harmoko membawa-bawa “aspirasi” daerah. Kita tahu, Harmoko pula yang dengan cepat bermanuver di 1998, menyebabkan tak hanya kabinet, melainkan kekuasaan Soeharto pun rontok.
Berkaitan dengan para elit Gerindra, kita semua paham akan ungkapan “a friend in need, is friend indeed”. Mereka adalah para sahabat Prabowo, bukan pemandu sorak atau pun tukang hore-hore. Di sinilah mata, hati, insting dan rasa mereka akan diuji, untuk memberikan bisikan terbaik kepada sahabatnya itu. Sebab bisikan yang jujur, yang tak hanya bertautan dengan kepentingan atau urusan “Asal Babe Senang” itulah yang justru tengah sangat diharapkan Sang Pejuang itu, saat ini.
Akan elok kiranya jika Prabowo meneladani langkah tokoh Anshar, Saád bin Ubadah, dalam kisruh pengangkatan khalifah sepeninggal wafatnya Nabi Muhammad SAW, di Saqifah (Aula) Bani Saidah. Bila di Mekkah ada “Al-Amin”, Nabi sendiri, di Madinah saat itu dikenal “Al-Kamil (yang sempurna)”, Sa’ad, yang dua kali berbaiat kepada Al-Amin, pada dua kesempatan berbeda.
Sa’ad, yang menurut Ibn Asakir dengan mengutip al-Waqidi dalam kitab “al-Maghazi”, pernah dinyatakan Rasulullah sebagai “Sebaik-baiknya manusia pada masa jahiliyah dan adalah sebaik-baiknya manusia pada masa Islam” itu, memilih mengurungkan pencalonan dan menjadi king maker. Kita tahu, pada kisruh kepemimpinan sementara jenazah Nabi pun belum lagi dimakamkan itu, Abu Bakar yang akhirnya terpilih. Sikap yang diambil Sa’ad membuat peluang perseteruan yang sangat mungkin berujung pertumpahan darah itu terhindarkan.
Sikap yang sama diambil Abdurrahman bin Auf dalam pemilihan khalifah setelah pembunuhan Khalifah Umar bin Khattab. Ia yang bersama Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam dan Saád bin Abi Waqhas, dipilih Umar yang bersimbah darah sebagai formatur pemilihan khalifah, sekaligus punya hak dipilih, meletakkan haknya itu. Ia memilih menjadi king maker, yang dikenang hingga hari ini dalam tarikh Islam.
Pada Prabowo potensi untuk itu ada, dan bahkan besar. Sebagaimana Sa’ad dan Bin Auf, Prabowo juga kaya raya dan sangat dermawan. Ketiganya pun para patriot pembela cita-cita luhur yang landasannya demi orang banyak, demi agama. Sangat besar peluang Prabowo mengikuti langkah kedua sahabat Nabi tersebut. Bila itu beliau lakukan, kita bisa berharap dukungan beliau yang amat berpengaruh itu bisa ia berikan kepada calon-calon yang lebih muda. Mungkin buat Ganjar, Puan, atau bisa jadi bagi Anies Baswedan.
Senyampang itu, dengan menjadi king maker, Prabowo pun bisa memberi bukti bahwa para haters yang selama ini mengkritiknya sebagai haus kekuasaan pun, salah besar. Sekaligus dengan sikap itu pula, Prabowo menihilkan keyakinan Nietzsche akan apa yang disebutnya ‘kehendak berkuasa’—The Will to Power—sebagaimana judul buku yang disusun Elizabeth, saudara perempuannya, yang menerbitkannya setelah Nietzsche meninggal.
Nietzsche percaya dunia sebagai “Monster energi, tanpa awal, tanpa akhir… dunia Dionysianku yang menciptakan diri sendiri secara abadi, menghancurkan diri sendiri secara abadi…”
Kepercayaan yang membuat dirinya menyimpulkan: “Dunia ini adalah kehendak untuk berkuasa—dan tidak ada apa-apa selain itu! Dan kau sendiri juga adalah kehendak untuk berkuasa—dan tidak ada apa-apa selain itu!”
“Tidak!”kata Prabowo. Dengan perbuatan, bukan sekadar kata-kata. [dsy]