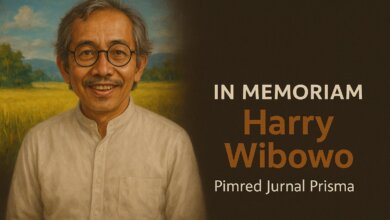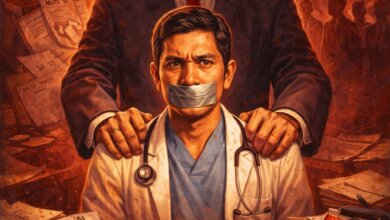Buku ini tidak membedakan Marxisme sebagai kritik ekonomi, sosialisme sebagai teori keadilan distributif, dan komunisme sebagai bentuk pemerintahan satu partai yang represif. Semua dicampur, diratakan, dan ditembak dengan peluru yang sama. Akibatnya, setiap ekspresi keresahan sosial dicurigai sebagai “alat merah.” Padahal sejarah pemikiran Indonesia mencatat bahwa Islam sendiri—agama mayoritas penduduk negeri ini—sering berjalan beriringan dengan gagasan-gagasan sosialistik.
Oleh : Darmawan Sepriyossa
JERNIH– Diskusi ini menyoal sebuah buku yang terbit lebih dari dua dekade lalu, “Mewaspadai Kuda Troya Komunisme di Era Reformasi”, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1999, hanya setahun setelah rezim Orde Baru tumbang. Buku ini segera dicetak ulang dalam beberapa edisi, bahkan masih tersedia dalam versi terbitan tahun 2014 di sejumlah platform jual-beli daring.
Ia hadir bukan sebagai catatan ilmiah yang mengundang dialog, melainkan sebagai alarm—kadang menyerupai sirene yang meraung tanpa henti. Kini, pada tahun 2025, kita diajak kembali membacanya. Pertanyaannya: apa yang hendak dicari dari sebuah bunyi sirene yang tak pernah berganti nadanya?
Buku ini disusun oleh dua nama yang tidak banyak dikenal publik: Dra. Markonina Hartisekar dan Drs. Akrin Isjani Abadi. Pencarian di dunia maya nyaris tak membuahkan profil atau rekam jejak lain dari keduanya, selain keterkaitan mereka dengan buku ini. Tidak ada latar belakang keilmuan yang bisa diakses, tak ada konteks sosial atau institusional yang memberi kita petunjuk tentang kecenderungan atau posisi ideologis mereka. Dan karena buku ini pun tidak menyertakan biografi penulis, maka analisis terhadap isinya nyaris harus semata berdasar teks, bukan konteks. Ini menyulitkan, sekaligus memberi peluang: kita menilai argumen sebagaimana adanya, bukan sebagaimana siapa yang menyusunnya.
Yang kita temukan dalam buku ini adalah daftar panjang kecurigaan. Gerakan mahasiswa, organisasi lingkungan, aktivis LSM, media alternatif, hingga program pelatihan jurnalistik mahasiswa—semuanya disebut sebagai bagian dari skema besar infiltrasi komunisme gaya baru.
Di halaman 5 tertulis: “Komunisme gaya baru tak lagi datang dengan senjata, tapi melalui ide, media, kampanye lingkungan, hingga dunia pendidikan.”
Di bagian lain, penulis menulis: “Jika kita melupakan sejarah kekejaman PKI, sama halnya kita menabur benihnya kembali di tanah yang sama.” (halaman 15). Kutipan ini kuat secara retoris, tapi juga perlu kehati-hatian dalam pembacaan. Karena trauma, jika tidak dibedakan dengan fakta, bisa melahirkan paranoia.
Penulis juga menyoroti tokoh-tokoh muda yang muncul di era 1990-an, termasuk Dita Indah Sari, yang catatan hariannya dikutip untuk menunjukkan bahwa ia mengidentifikasi kelahiran PRD sebagai kebangkitan PKI. Tapi kita tahu, seorang aktivis muda bisa saja menulis hal semacam itu bukan karena ia kader, tapi karena ia sedang dalam fase “pubertas ideologi.” Dita mungkin tergoda oleh narasi besar tentang perlawanan terhadap ketidakadilan dan menemukan dalam PKI sebuah simbol yang baginya heroik, bukan faktual.
Bahkan jika ia berasal dari keluarga eks-PKI sekalipun, itu bukan dosa. Catatan hariannya bukan manifesto. Justru cara buku ini memperlakukannya sebagai dokumen resmi menandakan betapa miskinnya riset lapangan yang dijadikan dasar.
Buku ini tidak membedakan Marxisme sebagai kritik ekonomi, sosialisme sebagai teori keadilan distributif, dan komunisme sebagai bentuk pemerintahan satu partai yang represif. Semua dicampur, diratakan, dan ditembak dengan peluru yang sama. Akibatnya, setiap ekspresi keresahan sosial dicurigai sebagai “alat merah.” Padahal sejarah pemikiran Indonesia mencatat bahwa Islam sendiri—agama mayoritas penduduk negeri ini—sering berjalan beriringan dengan gagasan-gagasan sosialistik.
Lihatlah HOS Tjokroaminoto yang meramu Islam dan keadilan sosial dalam Syarikat Islam. Atau bacalah pemikiran Dr. Kuntowijoyo, yang menegaskan pentingnya Islam sebagai kekuatan kultural yang mampu mendorong transformasi sosial. Bahkan di era 1990-an, muncul arus yang dikenal sebagai “Kiri Islam”, yang mempertemukan nilai-nilai keadilan sosial dalam Islam dengan prinsip-prinsip kesetaraan struktural dari tradisi kiri. Ini semua menunjukkan bahwa garis antara “agama” dan “sosialisme” tidak setegas yang dibayangkan penulis buku ini.
Menariknya, sebagian (besar?) tokoh yang pernah dicurigai sebagai aktivis kiri radikal kini hidup sebagai pebisnis mapan. Salah satu pentolan PRD kabarnya kini menjadi pengembang properti, menjual kavling dan rumah mewah. Apakah ini bentuk transformasi? Atau pembuktian bahwa yang dulu dianggap sebagai revolusioner sejati, sebenarnya hanya anak-anak muda yang sedang mencari jati diri dan kini telah menemukan kenyamanan dalam pelukan kapitalisme?
Buku ini lahir di tengah trauma dan disusun dalam suasana gejolak. Sidang Istimewa MPR 1999, kerusuhan etnis, konflik di Cawang yang terekam dalam dokumentasi visual yang langka, semua menjadi latar belakang yang membentuk semangat penulis. Namun, trauma bukan dalih untuk terus-menerus menabuh genderang kecurigaan. Sejarah seharusnya menjadi ruang refleksi, bukan ladang tuduhan.
Buku ini tetap berguna—jika dibaca dengan nalar kritis. Ia mencerminkan semangat zaman dan ketakutan yang lahir dari kekosongan kepercayaan. Tapi ia juga menunjukkan betapa mudahnya kita menghidupkan kembali retorika musuh bersama demi menutup ruang kritik. Jika semua aktivisme dicurigai sebagai kuda troya, lalu siapa yang berhak menyampaikan keresahan sosial?
Dalam dunia yang kian mengekang, seperti kata Camus, kadang keberadaan kita sendiri adalah bentuk perlawanan. Dan “The only way to deal with an unfree world is to become so absolutely free that your very existence is an act of rebellion.” Di tengah dunia yang penuh tekanan, ketakutan, dan pelabelan semena-mena, barangkali menjadi waras dan berpikir kritis adalah bentuk perlawanan paling mendasar.
Maka keberanian untuk berpikir bebas, untuk tidak ikut panik, dan untuk tetap rasional dalam membaca sejarah, adalah bentuk keberpihakan paling nyata kepada demokrasi. Jika semua yang berbeda kita sebut “kuda troya”, jangan-jangan kita sedang menciptakan benteng yang justru mengurung diri kita sendiri. [ ]
*Disampaikan dalam Diskusi Buku Mewaspadai Kuda Troya Komunisme di Era Reformasi, Bandung, 10 Mei 2025