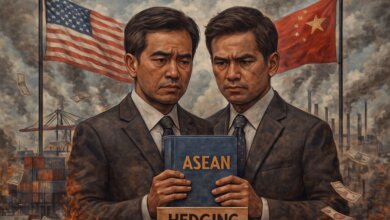Ketika MBG, pos pendukung ini, mengambil porsi terbesar anggaran, sementara alokasi untuk guru, dosen, beasiswa, laboratorium, dan akses perguruan tinggi jauh lebih kecil, terjadi disorientasi serius. Negara-negara dengan capaian pendidikan unggul, seperti Finlandia, Korea Selatan, atau Singapura, memang punya program makan sehat di sekolah. Namun, proporsinya tidak pernah mendominasi anggaran pendidikan. Finlandia menempatkan porsi makan sekolah sekitar 3–5 persen dari belanja pendidikan, sementara 40 persen diarahkan untuk kualitas guru dan 30 persen untuk infrastruktur sekolah.
Oleh : Fahrus Zaman Fadhly*
JERNIH– Pemerintah mengalokasikan Rp757,8 triliun untuk fungsi pendidikan pada APBN 2026, naik 9,8 persen dari tahun 2025 yang sebesar Rp690,1 triliun. Angka ini terlihat besar dan patut diapresiasi, sebab konstitusi mengamanatkan minimal 20 persen APBN untuk pendidikan.
Namun, bila diperhatikan lebih rinci, hampir setengah dari anggaran itu atau Rp335 triliun justru dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Artinya, sekitar 44,2 persen dari seluruh belanja pendidikan dipakai untuk konsumsi harian, bukan inti pendidikan. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah pemerintah benar-benar menempatkan prioritas yang tepat dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia?
Secara filosofis, pendidikan adalah investasi jangka panjang. Fungsinya bukan sekadar menjaga tubuh agar kenyang, melainkan membangun kompetensi literasi, numerasi, keterampilan abad 21, hingga kapasitas inovasi. Program makan gratis memang bisa mendukung dengan menurunkan angka kelaparan siswa, meningkatkan kehadiran, dan memperbaiki konsentrasi belajar. Akan tetapi, ketika pos pendukung ini mengambil porsi terbesar anggaran, sementara alokasi untuk guru, dosen, beasiswa, laboratorium, dan akses perguruan tinggi jauh lebih kecil, terjadi disorientasi serius. Pendidikan akhirnya terjebak pada pemenuhan kebutuhan konsumsi jangka pendek, bukan pada pembangunan daya saing jangka panjang.
Masalah yang kedua adalah biaya peluang. Dengan Rp335 triliun, MBG lebih besar hampir dua kali lipat dari total tunjangan guru, dosen, dan tenaga kependidikan yang hanya Rp178,7 triliun. Ia juga 35 kali lipat lebih besar dibandingkan BOPTN Rp9,4 triliun yang menopang operasional perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Padahal, bila hanya 10 persen saja dari MBG dialihkan ke KIP Kuliah, maka lebih dari 2,7 juta mahasiswa tambahan bisa mendapatkan bantuan kuliah per tahun (dengan asumsi biaya rata-rata Rp12 juta per orang). Itu adalah investasi yang langsung meningkatkan mobilitas sosial generasi muda. Namun, sayangnya alokasi itu tetap kecil: KIP Kuliah hanya Rp17,2 triliun, PIP Rp15,6 triliun, dan beasiswa LPDP Rp25 triliun. Semua jumlah itu, jika digabung sekalipun, tidak sampai seperlima dari anggaran MBG.
Risiko terbesar justru terletak pada tata kelola. Pemerintah merencanakan pembangunan 30 ribu dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari sisi logistik, ini proyek raksasa dengan potensi masalah serius: mark-up pengadaan, kualitas bahan pangan yang tidak merata, standar keamanan pangan yang sulit dijaga, hingga biaya tetap yang akan mengunci fiskal selama bertahun-tahun. Satu saja kasus keracunan massal bisa meruntuhkan legitimasi program. Selain itu, alih-alih memperkuat sekolah sebagai pusat pembelajaran, sekolah bisa terdorong menjadi pusat distribusi konsumsi. Ini akan memperlebar jurang antara fungsi pendidikan sebagai pengembangan ilmu dan keterampilan, dengan peran konsumtif jangka pendek.
Di sisi lain, ambisi Wajar Belajar 13 tahun menjadi semakin sulit dicapai. Pemerintah pernah menyampaikan target memperluas akses pendidikan menengah hingga perguruan tinggi. Namun, dengan struktur anggaran ini, akses kuliah rakyat kecil justru makin menyempit. KIP Kuliah tidak cukup untuk menutup biaya hidup mahasiswa. BOPTN yang kecil membuat kualitas kampus sulit bersaing. Bahkan LPDP, meski terlihat besar Rp25 triliun, sebenarnya sangat terbatas bila dibandingkan kebutuhan nasional.
Jika biaya rata-rata beasiswa mencapai Rp500 juta per orang untuk studi S2/S3 luar negeri, maka hanya sekitar 50 ribu penerima yang bisa dibiayai selama beberapa tahun. Jumlah ini tidak sebanding dengan target membangun tenaga ahli dan peneliti kelas dunia yang dibutuhkan Indonesia untuk masuk jajaran negara maju.
Untuk memperjelas kritik ini, kita bisa menengok praktik internasional. Negara-negara dengan capaian pendidikan unggul, seperti Finlandia, Korea Selatan, atau Singapura, memang punya program makan sehat di sekolah. Namun, proporsinya tidak pernah mendominasi anggaran pendidikan. Finlandia menempatkan porsi makan sekolah sekitar 3–5 persen dari belanja pendidikan, sementara 40 persen diarahkan untuk kualitas guru dan 30 persen untuk infrastruktur sekolah. Korea Selatan bahkan fokus besar pada kurikulum STEM, laboratorium, dan riset, sedangkan program makan lebih diarahkan ke siswa miskin dan bukan massal. Singapura memperkuat subsidi kuliah, beasiswa, dan lifelong learning agar warganya terus bisa meningkatkan keterampilan. Dari contoh ini, terlihat bahwa Indonesia salah dalam skala prioritas: yang seharusnya menjadi program pelengkap justru dijadikan pos utama.
Jika tidak ada koreksi, dampak jangka panjangnya jelas berbahaya. Pertama, kualitas pembelajaran stagnan. Anak-anak mungkin kenyang, tetapi literasi, numerasi, dan keterampilan digital mereka tetap rendah.
Kedua, akses ke perguruan tinggi makin terhambat. Generasi miskin sulit menembus jenjang kuliah karena biaya hidup dan biaya pendidikan tidak terjangkau.
Ketiga, riset dan inovasi makin tertinggal. Kampus kekurangan dana operasional, dosen tidak cukup mendapatkan insentif penelitian, laboratorium usang, dan kolaborasi internasional minim. Akibatnya, target Indonesia Emas 2045 yang bergantung pada produktivitas sumber daya manusia bisa meleset. Bonus demografi justru bisa berubah menjadi beban demografi.
Koreksi arah mutlak dilakukan. Pertama, MBG sebaiknya diposisikan sebagai program sosial-gizi tertarget, bukan massal. Pemerintah bisa fokus pada kantong stunting, daerah tertinggal, dan kelompok rentan. Distribusinya bisa melalui e-voucher, kantin sekolah, atau kerja sama dengan koperasi dan UMKM lokal, bukan membangun birokrasi baru yang mahal.
Kedua, perlu ada realokasi. BOS, KIP Kuliah, dan BOPTN harus dinaikkan secara signifikan. Hanya dengan itu kualitas guru, fasilitas belajar, dan akses kuliah bisa meningkat. Ketiga, tata kelola MBG perlu dibuat ramping dengan mekanisme audit digital, pelaporan transparan, serta partisipasi masyarakat. Dengan begitu, anggaran bisa tetap mendukung gizi siswa, tetapi tidak mengorbankan investasi inti pendidikan.
Di sinilah suara para pendidik, akademisi, dan masyarakat sipil diperlukan. Kritik terhadap kebijakan bukanlah bentuk penolakan terhadap makan bergizi, melainkan upaya meluruskan prioritas. Presiden Prabowo memang punya niat baik untuk memperbaiki gizi anak bangsa, tetapi niat baik harus ditempatkan pada skala yang benar.
Pendidikan bukan soal kenyang hari ini, melainkan tentang kompetensi dan daya saing puluhan tahun mendatang. Tanpa koreksi, amanat konstitusi 20 persen APBN untuk pendidikan hanya akan menjadi formalitas di atas kertas, bukan investasi nyata bagi generasi emas Indonesia.
Sebagai penutup, kita perlu menegaskan bahwa APBN Pendidikan 2026 adalah lonceng peringatan. Bila arah ini tidak diluruskan, Indonesia akan kehilangan momentum. Jalan tengahnya bukan menolak MBG, melainkan menjadikannya proporsional, berbasis bukti, dan tertarget. Porsi terbesar anggaran harus kembali pada jantung pendidikan: guru, beasiswa, kampus, riset, dan infrastruktur belajar. Hanya dengan cara itu cita-cita Indonesia Emas 2045 bisa benar-benar diwujudkan, bukan sekadar slogan. [ ]
* Dosen Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Kuningan