Catatan Politik Kebhinekaan untuk Bang Trisno S. Sutanto
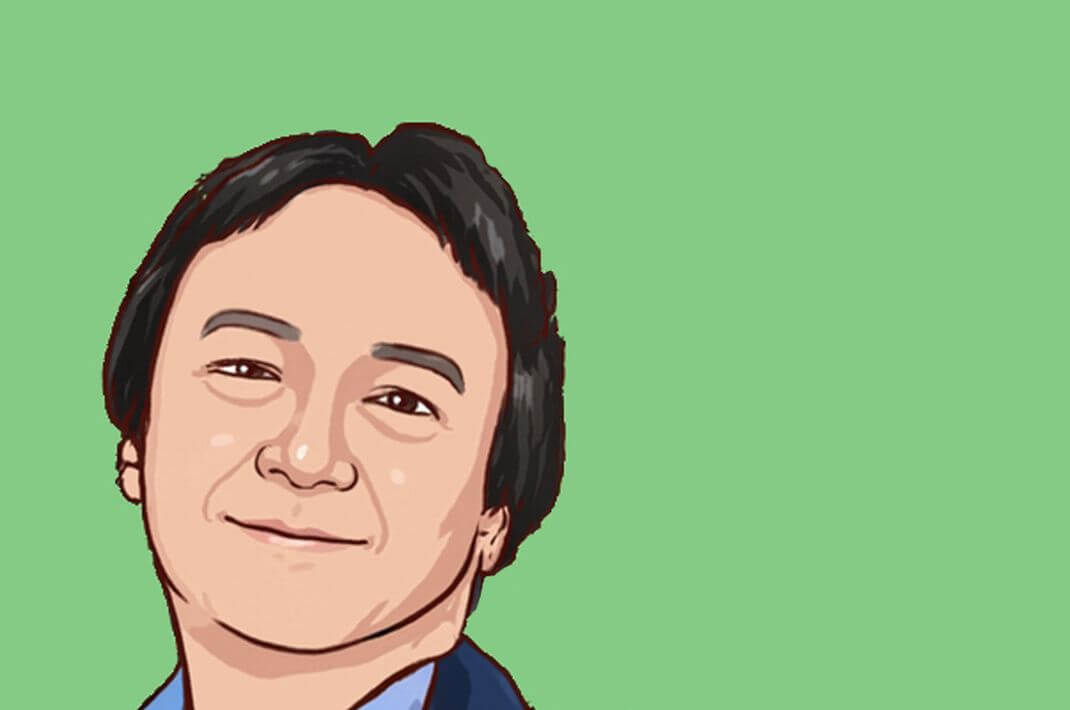
Pulanglah, kawan, pulang! Kita hanyalah anak-anak sang waktu yang mengalir dari titik ke titik persinggahan sementara. Waktu dan ruang bukanlah keabadian. Sekadar labirin tanda tanya yang setiap ujung jeda dan pintunya selalu sisakan misteri. –“Pulang”—Yudi Latif
Oleh : Swary Utami Dewi*
JERNIH–Trisno S. Sutanto. Abang senior yang satu ini nyentrik. Aku mengenalnya sudah puluhan tahun. Seingatku sejak di acara-acara diskusi Paramadina di pertengahan tahun 1990-an. Dari dulu, ia berwatak ceria dan humoris. Tiba-tiba ia suka berpendapat unik saat diskusi dan itu menunjukkan kecerdasannya. Untuk isu kebinekaan dan kebangsaan ia jagonya; sejago sifatnya yang nyentrik.
Aku masih ingat. Dulu di sela-sela diskusi, Bang Trisno terkadang menunjukkan lembaran-lembaran ketikan buah pikirannya. “Hayo, baca ini,” ujarnya. Aku biasanya membaca sekilas lalu memberikan kembali kertas-kertas itu. Tulisannya memang lebih banyak tentang isu kebinekaan, pluralisme, hak asasi manusia (HAM). Seputar itulah.

“Keren, Bang,” ujarku, yang biasanya disambut tawa lepasnya. Bisa jadi tulisan-tulisan itulah yang kemudian menjadi buku Politik Kebinekaan: Esai-Esai Terpilih, yang diterbitkan pada 2020.
Setahuku, Bang Trisno mengagumi pikiran-pikiran Cak Nur dan Gus Dur. Maka tidak heran ia getol menyambangi diskusi-diskusi yang ada dua tokoh ini. Ia menyimak dengan serius dan mencatat. Dan tampaknya, perjumpaan-perjumpaannya dengan para guru bangsa inilah yang membentuk pemikiran Bang Trisno. Ia seakan–dan memang–menemukan cintanya pada isu-isu “serius” tentang pluralisme, kemanu-siaan dan kebangsaan. Bukti baktinya pada isu-isu ini bukan hanya pada kege-marannya hadir di diskusi-diskusi terkait, tapi juga argumen yang cerdas dan bernas dalam narasi lisan dan tulisan–salah satunya tergambar dalam buku tebal di atas tadi.
Bagi Trisno, isu-isu tentang pluralisme dan kebangsaan harus dibicarakan secara terbuka. Dialog menjadi titik penting sebagai pembuka pintu kemajemukan dalam rangka merekatkan bangsa dan mengembangkan kemanusiaan. Tapi Trisno tidak berhenti sampai di sini saja. Ia mengajak kita melanjutkan ke langkah kepedulian. Tidak cukup mengembangkan pluralisme dan kebangsaan, jika masih ada mayoritas masyarakat yang miskin dan terpinggirkan. Maka, Trisno mengetuk hati kemanusiaan kita untuk memikirkan pula cara mengubah struktur sosial ekonomi yang timpang. Tujuannya jelas: untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama.
Di sini aku jadi teringat almarhum Buya Syafii Maarif, yang sering mengingatkan kita, yang lalai menjaga sila kelima Pancasila: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan dan Demokrasii disertai musyawarah hanya akan berarti jika ada keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia–hal yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi negara. Ah, Abang. Bisa jadi, pemikiran Buya Syafii Maarif juga terpatri kuat di hati dan pikiranmu.
Selama beberapa tahun terakhir, aku lebih sering berjumpa dengan Bang Trisno di acara-acara Satupena, Esoterika dan sejenisnya. Beliau seniorku di Satupena, yang jika aku memberikan komen di grup WA, sering ditanggapi dengan respons lucu yang membuatku nyengir.
Aku ingat dua pertemuan terakhir dengannya. Pertama adalah pada diskusi kebangsaan tentang Masa Depan Indonesia, yang digelar di Universitas Paramadina, 4 Maret 2024. Aku yang menggagas acara ini, dengan didukung oleh Prof. Didik J. Rachbini, mengundang puluhan tokoh pemikir. Salah satu yang masuk dalam list-ku tentu saja Trisno S. Sutanto. Aku japri dan ia menanyakan siapa saja yang hadir. “Ah malas, yang itu-itu lagi,” ujarnya bercanda. Nyatanya, ia hadir dan ikut hingga acara hampir berakhir.
Kedua, pada acara buka bersama komunitas Satupena dan Puisi Esai, 15 Maret 2024. Lagi-lagi, Bang Trisno selalu masuk list undangan. Ia hadir dan tampak sumringah, bahkan sempat ngobrol dan berfoto berdua denganku.
“Wah, senang masih ada acara-acara begini,” ujarnya yang dikanjutkan dengan tawa khasnya yang lepas dan ngakak. Aku jawab setuju. Siap, Bang …
Jelang tengah malam, Sabtu, 30 Maret 2024, Bang Trisno dipanggil Yang Kuasa, pada usia 61 tahun. Aku terkejut dan berduka. Bang Trisno wafat di bulan Ramadhan, menjelang Hari Paskah. Ia wafat di bulan baik bagi muslim dan di hari-hari suci bagi umat kristiani. Tuhan bisa jadi memilih memanggilnya pada hari-hari pluralisme ini. Persis seperti jalan pengabdian yang Bang Trisno pilih dalam hidupnya.
Pagi ini aku kembali menangis saat membaca japrian bang Yudi Latif, yang khusus membuatkan puisi untuk sahabatnya, Trisno S. Sutanto.
Pulang (1)
Yudi Latif
Pulanglah, kawan, pulang!
Kita hanyalah anak-anak sang waktu yang mengalir dari titik ke titik persinggahan sementara.
Waktu dan ruang bukanlah keabadian. Sekadar labirin tanda tanya yang setiap ujung jeda dan pintunya selalu sisakan misteri.
Tapi, setiap jejak tidaklah sia-sia. Seperti samudera bermula dari tetes. Setiap kata yang engkau sapakan pulihkan harapan pada kecemasan. Setiap senyum yang engkau sunggingkan tebarkan gairah pada keputusasaan. Setiap darma yang engkau sumbangkan bangkitkan daya pada kelembaman.
Jalan pengembaraan ini telah kau tempuh sepanjang hayat. Kesibukan dan pencarian membuatmu lupa sebagai perantau.
Dalam siuman, setiap pengembara merindukan kepulangan. Fakta keterlemparan manusia dari langit suci dan kebertualangan dari asal tumpah darah membuat sukmanya senantiasa resah-gelisah, merindukan luang berpulang ke rahim Ilahi dan rumah primordial.
Sekarang, dengarlah degup jantung, jeritan hati memanggilmu pulang. Ada saatnya elang petualang balik ke sarang. Dalam mudik, engkau terlahir kembali.
Selamat jalan Bang Trisno, seniorku yang baik dan nyentrik. Kembalilah ke pelukan Yang MahaKasih. [ ]
31 Maret 2024







