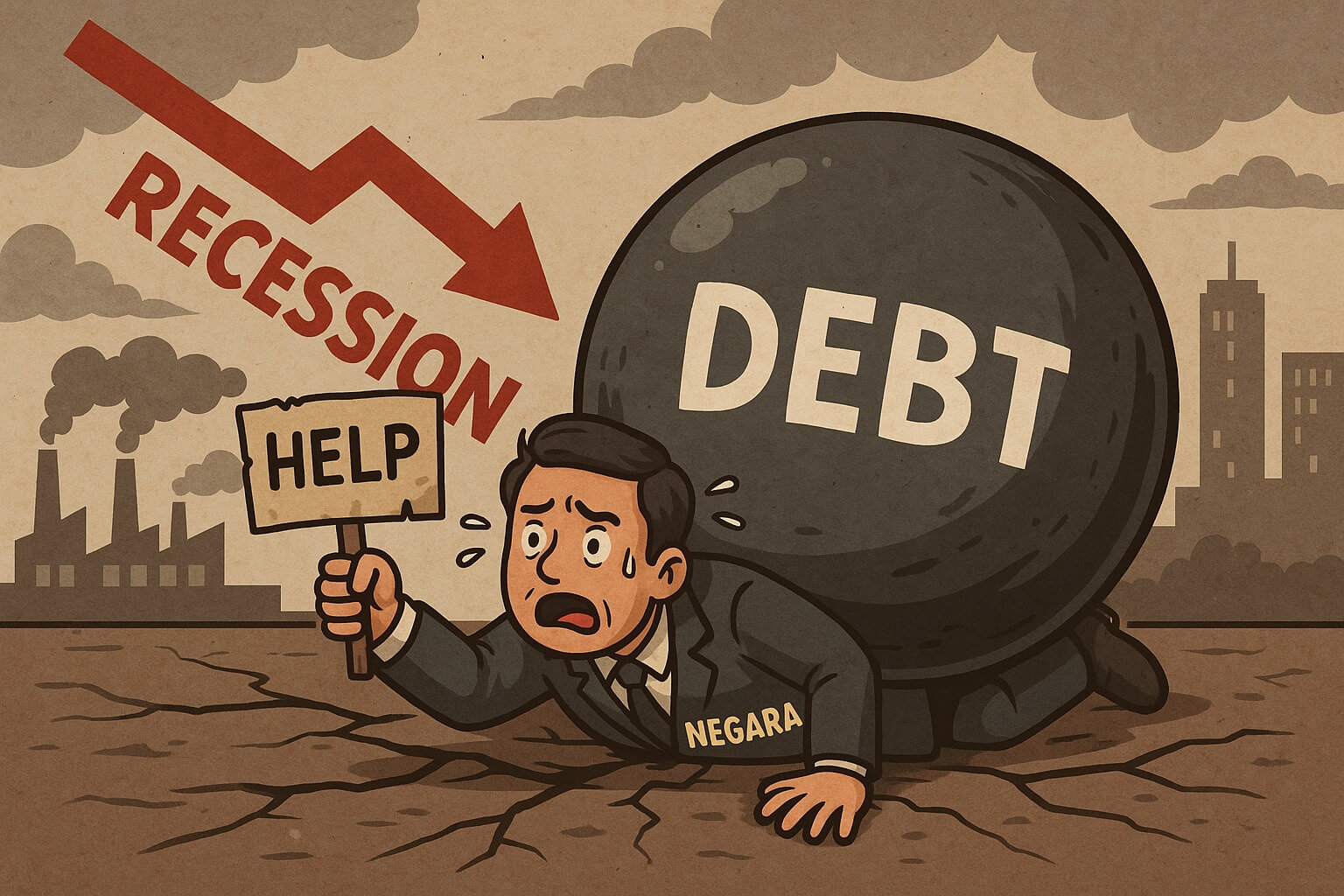
Bayang-bayang kepentingan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggantung berat di atas pemerintahan Prabowo. Demi menjaga kesinambungan politik serta melindungi kepentingan pribadi dan keluarga, Jokowi menciptakan jejaring loyalis dan proyek-proyek strategis yang tak mudah diubah.
Oleh : Yudi Latif
JERNIH– Mohammad Hatta, negarawan yang teguh dalam integritas dan tangguh dalam tata kelola, pernah mengingatkan, ”Pemerintahan yang bersih dan efisien hanya mungkin jika dijiwai oleh semangat melayani, bukan menguasai.”
Pernyataan ini cermin kearifan, sekaligus kompas moral bagi penyelenggaraan kekuasaan yang berpihak pada rakyat. Dengan kompas etis itu, kita bisa menakar kinerja pemerintahan Prabowo yang datang dengan janji yang melambungkan harapan.
Pemerintahan baru yang konon akan tampil efisien, tangkas, dan bebas dari beban-beban birokrasi masa silam. Sebagian publik menyambutnya dengan antusias, seolah menemukan cahaya di ujung terowongan panjang inefisiensi struktural dan pemborosan yang telah menjadi warisan tak terhindarkan.

Namun, seperti yang kerap diajarkan sejarah, janji paling merdu pun bisa berbuah kecewa. Retorika efisiensi yang dielu-elukan, ternyata tak serta-merta menjelma menjadi kebijakan yang ajek, tepat guna, apalagi tepat arah.
Yang terjadi justru sebaliknya: efisiensi itu membuncahkan paradoks—kabinet yang membengkak, prioritas yang kabur, tata kelola yang buruk, dan megaproyek yang menjulang sebagai monumen politik, bukan solusi konkret. Di tengah pusaran kepentingan, kata efisiensi meluruh dari semangat pengabdian menjadi jargon dministrative yang kehilangan jiwa.
Inkonsistensi dan malafungsi
Kontradiksi paling gamblang tampak pada struktur kabinet. Narasi kampanye mengumandangkan perampingan, efisiensi, penyederhanaan. Namun, realitas yang muncul justru sebaliknya: kabinet tambun dengan kualitas semenjana, menampung lebih banyak menteri, wakil menteri, dan beragam jabatan baru dari berbagai spektrum kekuasaan.
Bukan semangat melayani yang menggerakkan roda, melainkan kalkulasi kuasa—upaya mengakomodasi sekutu, menenangkan pesaing, dan menambatkan stabilitas lewat politik bagi-bagi kursi.
Kementerian strategis yang sejatinya menopang kualitas hidup rakyat—pendidikan, sosial, lingkungan hidup—justru dipangkas atau stagnan anggarannya.
Sementara itu, kementerian yang bersentuhan dengan megaproyek dan agenda stabilisasi kekuasaan malah dibanjiri sumber daya. Rasionalisasi anggaran tak lagi berangkat dari kebutuhan rakyat, tetapi dari strategi bertahan dalam pusaran elite yang terus berdansa di atas panggung kekuasaan.
Efisiensi, yang seharusnya menjadi jalan pintas menuju kemaslahatan, berubah menjadi lorong gelap. Kita menyaksikan pembangunan Ibu Kota Negara baru dengan gegap gempita, sementara di banyak pelosok desa, rakyat masih bergelut dengan kekurangan layanan dasar. Proyek lumbung pangan (food estate) yang membabat hutan atas nama ketahanan pangan, berujung kegagalan panen dan kerusakan alam yang tak terpulihkan.
Kebijakan hilirisasi tambang yang konon akan mendongkrak nilai tambah nasional, realisasinya hanya menguntungkan segelintir investor dan tenaga kerja asing, sementara rakyat lokal tetap menjadi buruh miskin di tanah sendiri.
Yang lebih mengkhawatirkan, kini muncul megaproyek baru bernama Danantara—superholding yang merangkul teknologi tinggi, digitalisasi, dan anasir kekuatan militer dalam satu wadah tunggal. Di atas kertas, proyek ini diklaim sebagai langkah strategis untuk transformasi ekonomi dan pertahanan digital.
Jika kebijakan dibiarkan digerakkan intuisi politik semata tanpa koreksi dari pengetahuan, bukti, dan data, yang lahir bukan pemerintahan kuat, sebaliknya rapuh.
Tapi di balik kilau narasinya, tersimpan risiko besar: sentralisasi kekuasaan, kerentanan privasi, kerapuhan akuntabilitas publik. Pembangunan semacam ini bukan sekadar salah sasaran—ia bisa jadi batu loncatan menuju otoritarianisme berdalih kepentingan bangsa.
Jika efisiensi tak menyentuh denyut kebutuhan rakyat dan tak merapikan simpul-simpul keadilan sosial, ia kehilangan maknanya. Kita melihat hal itu, misalnya, dalam program Makan Bergizi Gratis. Sebuah ide mulia yang, dalam praktiknya, dilingkupi karut-marut: distribusi amburadul, mutu makanan meragukan, hingga para penyedia lokal yang tak kunjung dibayar.
Program yang seharusnya jadi simbol keberpihakan pada masa depan anak-anak dan ekonomi kerakyatan, justru menunjukkan betapa negara begitu gagap mengeksekusi niat baiknya sendiri.
Negara tampak berjalan tanpa arah, seolah proyek demi proyek diluncurkan bukan karena panggilan urgensi rakyat, melainkan demi membangun citra kekuasaan. Rakyat, lagi-lagi, hanya jadi penonton dari sebuah panggung pembangunan yang megah di permukaan, tetapi menyimpan kekacauan di balik tirai.
Efisiensi dalam ”state capture”
Malapraktik efisiensi yang kita saksikan hari ini bukan sekadar kesalahan teknis atau kegagalan manajerial. Ia mencerminkan simpul kusut kekuasaan: janji efisiensi sejak awal telah dikandaskan oleh beban kompromi antara presiden terpilih dan kekuasaan lama yang enggan undur diri.
Bayang-bayang kepentingan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggantung berat di atas pemerintahan Prabowo. Demi menjaga kesinambungan politik serta melindungi kepentingan pribadi dan keluarga, Jokowi menciptakan jejaring loyalis dan proyek-proyek strategis yang tak mudah diubah.
Ini membuat Prabowo terpaksa menjalani pemerintahan dengan terlalu banyak kompromi yang tidak saja melemahkan independensinya dalam mengambil kebijakan terbaik, tetapi juga membebani kinerja institusional pemerintah secara keseluruhan.
Dalam keadaan seperti itu, efisiensi kehilangan maknanya sebagai instrumen tata kelola yang sehat. Ia berubah menjadi sekadar modus untuk membiayai transaksi kekuasaan demi ”harmoni” elitis. Selama Prabowo belum mampu menciptakan ruang otonom bagi dirinya untuk membuat pilihan rasional yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak, efisiensi akan terus tertawan oleh bayang-bayang masa lalu.
Setiap langkah yang diambil bukan berdasarkan kebutuhan obyektif atau visi jangka panjang, melainkan atas dasar konsesi kepada kekuatan lama yang masih bercokol. Hal itu bukan sekadar deviasi teknokratik belaka, melainkan menyingkap luka struktural yang lebih membusukkan.
Di balik kebijakan acak, terselip rancangan kekuasaan sistematis: negara dibajak oleh segelintir elite melalui mekanisme state capture—di mana institusi publik terampas untuk melayani kepentingan kuasa raksasa.
Maka, setiap kali ”efisiensi” dilontarkan dari podium kekuasaan, pertanyaannya: untuk siapa? Efisiensi sering kali menjadi kendaraan licin bagi perampasan negara oleh oligarki.
Demokrasi masih berjalan dalam rupa, tetapi jiwanya telah tergadaikan; negara tetap berdiri, tapi telah dikavling dalam paket-paket konsesi.
State capture bukan lagi istilah akademik. Ia menjelma nyata dalam kebijakan yang menguntungkan oligarki, bukan rakyat. Regulasi disusun untuk memanjakan pemodal, sumber daya dikeruk tanpa kendali publik, proyek digerakkan demi dominasi kelompok, bukan kebutuhan warga. Hukum tak lagi menjamin keadilan, melainkan membenarkan status quo.
Demokrasi kehilangan makna substantif. Pemilu tetap digelar, lembaga formal aktif, namun keputusan besar lahir bukan dari suara rakyat, melainkan ruang gelap tanpa akuntabilitas. Parlemen tumpul, hukum melemah, birokrasi lembam. Di baliknya bekerja shadow state: jaringan informal elite politik, pengusaha, dan aparat, tanpa mandat rakyat, tapi memegang kendali bangsa.
Inilah wajah tirani baru di era demokrasi prosedural: kekuasaan bekerja dalam diam, mengatur dari balik layar, dibungkus jargon pembangunan dan efisiensi. Shadow state inilah yang membuat reformasi mandek, korupsi merajalela, dan institusi publik kehilangan nyawa. Dalam lanskap ini, efisiensi menjadi alat depolitisasi—tampak netral, tapi sarat keberpihakan. Rakyat terbius oleh angka dan grafik, sedangkan perampasan berlangsung senyap.
Di tangan shadow state, efisiensi bukan sarana keadilan, melainkan alat penguasaan. Dalam negara bayangan ini, rakyat menjadi asing di negerinya sendiri. Akses dibatasi, suara dibungkam, harapan menguap. Pemilu tak lagi ruang perbaikan, tapi parade yang dikendalikan uang, media, dan algoritma.
Apa makna efisiensi dalam tatanan seperti ini? Ia tak lebih dari etalase. Tata kelola dibenahi di permukaan, tetapi arahnya tetap melayani akumulasi kuasa. Prosedur disederhanakan demi kelancaran akumulasi. Anggaran dipangkas agar sumber daya cepat mengalir ke proyek-proyek mercusuar yang jauh dari denyut rakyat jelata.
Lentera dari akar
Jika negara telah dirampas dan efisiensi kehilangan jiwa, ke mana rakyat mesti berpaling? Jawabannya: kembali ke akar. Di tengah gelap yang menutup jalan dari atas, harapan tetap bisa tumbuh dari bawah—dari komunitas yang saling menopang, dari gerakan yang tumbuh mandiri, dari solidaritas yang menyalakan kesadaran.
Efisiensi sejati bukan perkara memangkas angka dari pusat kekuasaan, melainkan soal ketepatan menyentuh kebutuhan rakyat. Ia hanya hidup jika dikawal masyarakat yang sadar, kritis, dan terorganisasi.
Maka, lentera dari akar itu harus dinyalakan: membangun ekonomi berbasis komunitas, menguatkan koperasi dan jejaring solidaritas lokal, menyebarkan pendidikan politik yang membebaskan, memperluas ruang partisipasi rakyat dalam menentukan nasibnya sendiri.
Di saat yang sama, mereka yang menggenggam kekuasaan pun tak bisa terus berjalan dalam ilusi manipulatif.
Efisiensi bukan sekadar pemadatan struktur, melainkan keberanian menata ulang prioritas demi keadilan. Arah kebijakan harus berpijak pada kebutuhan rakyat, bukan pada ambisi kekuasaan. Transparansi anggaran harus menjadi prinsip, bukan jargon. Eksekusi kebijakan harus bermutu, adil, dan tak merundung mereka yang hendak ditolong.
Pembangunan harus punya arah, bukan sekadar gerak. Di atas segalanya, rakyat harus kembali menjadi pusat dari segala keputusan. Negara tak bisa berjalan tanpa mendengar dan merasa. Karena rakyat bukan penonton panggung kekuasaan—merekalah pemilik panggung itu sendiri.
Efisiensi sejati bukanlah soal angka, melainkan cermin dari keadilan, kebijaksanaan, dan cinta yang memberdayakan rakyat. Selama itu belum tampak, efisiensi tak lebih dari gema kosong di lorong-lorong kekuasaan—jauh dari tanah tempat rakyat berpijak.
Ingatlah pesan Bung Karno, ”Pemimpin sejati adalah dia yang mencintai rakyatnya dan dicintai oleh rakyatnya. Ia bukan yang merasa besar karena kekuasaan, tapi yang merasa kecil di hadapan penderitaan rakyat.” []
*Dimuat atas izin penulisnya.
**Yudi Latif, Cendekiawan, Budayawan







