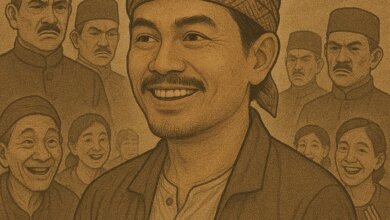Karena dianggap milik mereka, birokrat merasa bisa menggunakan anggaran itu sesuka hati. Ini mungkin terkesan sinis dan dalam dokumen resmi pasti masih dikatakan peruntukannya ditujukan untuk kepentingan rakyat. Akan tetapi dalam praktik, bisa dikatakan sebaliknya. Jika Anda dekat dengan pejabat, Anda bisa membuat usulan kegiatan apa saja selama–dalam dokumen resmi–nomenklaturnya sesuai dengan nomenklatur unit organisasi tsb…
Oleh : Medrial Alamsyah*
JERNIH– Salah satu aksi Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau populer dengan nama KDM (Kang Dedi Mulyadi), yang mencengangkan adalah dia membuat pemerintah, khususnya Pemda Jawa Barat, terlihat punya uang banyak. Sangat bertolak belakang dengan kesan selama ini, bahwa uang pemerintah terbatas. Kita percaya dan memaklumi ketika melihat fasilitas umum dan layanan publik seperti jalan, jembatan, sekolah serba buruk. Tak mengherankan bila seorang sahabat saya, jurnalis senior, dengan terperangah berkata: “Ternyata pemerintah itu banyak duitnya ya.”
Bayangkan, KDM menaikkan anggaran pembangunan kelas baru dan perbaikan dari Rp 70 M menjadi Rp 1,2 triliun (naik 17 kali lipat lebih); menaikkan anggaran jalan dari Rp 600 M menjadi Rp 3,2 triliun (naik 5 kali lipat lebih), anggaran jaringan listrik untuk rakyat miskin dari naik 20 kali lipat lebih; dst. Ketika menertibkan bangunan liar dan melarang tambang beroperasi, tanpa pikir panjang, KDM sebagai Gubernur, dengan mudah memutuskan memeberikan kompensasi pada keluarga terdampak. Seakan uang pemda tidak pernah habis. Bukankah selama ini pemerintah tidak melakukan apa yang dikerjakan KDM itu selalu berkilah “uang pemerintah terbatas”?
KDM tidak melakukan semacam breakthrough, tapi hal sederhana belaka: mencoret banyak kegiatan dan pembiayaan pemda yang tidak jelas, tidak penting, atau mengada-ada seperti biaya perjalanan dinas, studi banding, sosialisasi, monitoring dan evaluasi, mobil dan pakaian dinas, dll. Lalu mengalihkannya untuk pembiayaan infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, jaringan listrik untuk rakyat miskin, dsb.
Belakangan, KDM bergerak lebih maju, membuat kebijakan yang lazim di dunia swasta tapi aneh bagi birokrat. Pertama, karena ada pemotongan TKD (Transfer Keuangan Daerah), agar anggaran lebih banyak banyak untuk infrastruktur, KDM menghilangkan biaya makanan untuk tamu Pemda, hanya ada air minum; penghematan pemakaian listrik, air di kantor, dengan memberlakukan WFH (Work From Home). Kedua, menetapkan standar minimal 7,5% anggaran kabupaten kota harus dialokasikan untuk infrastruktur jalan.
Selama ini uangnya kemana? Pertanyaan logisnya kemudian bagaimana penggunaan anggaran selama ini sehingga KDM bisa melakukan efisiensi anggaran demikian besar tanpa gejolak di masyarakat? Bukankah logisnya, karena ada anggaran dinas/bidang yang hilang dalam jumlah besar ada kelompok masyarakat yang biasa menerima manfaat, sekarang tidak mendapatkan lagi. Memang ada adalah kelompok elit tertentu yang ribut, tetapi kenapa tidak mendapat dukungan dari akar rumput? Artinya anggaran itu selama ini memang tidak terkoneksi dengan kepentingan rakyat banyak. Lalu kemana perginya? Bagaimana mereka membunyikan sehingga terkesan mereka gunakan untuk kepentingan rakyat?
Pertama, uang lebih banyak habis untuk membiayai birokrasi yang gemuk, akibat dari: menggunakan model disain organisasi hirarkhial-fungsional ala Weber, dimana semua fungsi dibagi habis secara hirarkhial seperti sistem assembly line. Disain itu hanya cocok dan efektif pada abad ke-19 (Drucker, 1989) karena pekerjaan pemerintah tidak terlalu rumit. Sekarang pekerjaan pemerintah makin rumit sehingga model assembly line itu banyak melahirkan unit-unit organisasi yang tidak (sepenuhnya) dibutuhkan.
Persoalan menjadi lebih rumit karena penyusunan organisasi birokrasi di Indonesia tidak sepenuhnya rasional seperti diteorikan Weber. Dia tidak disusun berdasarkan kebutuhan pekerjaan semata, tetapi juga untuk mengakomodasi politik dan jumlah ASN pada setiap tingkatan. Jika jumlah ASN dalam eselon 1 dan 2 masing-masing ada 10 dan 30, maka harus diupayakan jumlah struktur/jabatan eselon 1 dan 2 juga 10 dan 30. Demikian seterusnya.
Akibatnya lebih banyak muncul unit-unit organisasi beserta pegawai yang bukan saja tidak diperlukan, tetapi juga tumpeng tindih. Efek berikutnya utilisasi jam kerja mereka sangat rendah. Sebagai gambaran, dalam perhitungan yang pernah penulis lakukan di Inspektorat DKI Jakarta (1999) dan di seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Kabupaten Tapanuli Selatan (2005) utilisasi jam kerja pegawainya hanya sekitar 22,5%. Walaupun itu data lama penulis yakin masih relevan karena, baik struktur organisasi maupun cara kerja birokrasi, tidak banyak berubah.
Kedua, keberadaan unit-unit yang tidak diperlukan itu tidak hanya memakan biaya untuk gaji, tunjangan, ruang dan fasilitas kantor, tetapi juga untuk program, kegiatan dan kebijakan yang diada-adakan. Karena diada-adakan seringkali jadi tumpang tindih. Tapi karena unit-unit organisasi itu eksis secara formal dan nomenklatur anggaran cocok, tetap saja mesti diberi anggaran. Celakanya, bila unit tersebut dipimpin oleh pejabat yang pintar melobi, dia bisa mendapat anggaran lebih banyak. Akhirnya lebih banyak lagi anggaran yang habis untuk sesuatu yang tidak bermanfaat.
Ketiga, secara umum perencanaan program dan kegiatan pemerintah kita lebih bersifat bureaucracy oriented ketimbang public focus, kepentingan birokrasi didahulukan ketimbang kebutuhan publik. Orientasi pada kepentingan birokrasi itu dilindungi oleh asas legalistik, yaitu bahwa semua aktivitas pemerintah harus punya dasar hukum. Masalahnya, mantra suci legalistk ini telah berubah menjadi formalistik. KDM, dalam berbagai kesempatan menyebutnya administratif.
Ada dua aturan formal tempat berlindung dalam penyusunan program, yaitu visi-misi pejabat politik yang dituangkan dalam dokumen RPJM/D (Rencana Pembangunan jangka Menengah/Daerah) dan sistem penganggaran berbasis pagu. RPJM/D biasanya tidak disusun dengan metode yang benar karena dibuat setelah struktur organisasi eksis, sehingga semua unit punya kesempatan untuk memastikan nomenklatur unitnya masuk dalam RPJM/D. Alhasil isinya penuh kalimat-kalimat indah dan mengawang. Bila kita minta pembuatnya menjelaskan, semakin panjang dia menjelaskan, bukan saja kita yang yang jadi bingung, tetapi juga yang menjelaskan.
Pagu anggaran K/L di pusat dan SKPD di daerah ditetapkan melalui proses politik di DPR/D. Sekali pagu ditetapkan maka anggaran itu seakan menjadi milik mereka. Oleh K/L dan SKPD anggaran itu dibagi lagi kepada unit-unit dalam K/L dan SKPD masing-masing, termasuk unit-unit yang tidak diperlukan seperti dijelaskan di atas. Lagi-lagi anggaran yang dibagi-bagi itu, oleh pejabat dan personel di unit tsb., dianggap sebagai miliknya. Bukan milik rakyat.
Karena dianggap milik mereka, birokrat merasa bisa menggunakan anggaran itu sesuka hati. Ini mungkin terkesan sinis dan dalam dokumenresmi pasti masih dikatakan peruntukannya ditujukan untuk kepentingan rakyat. Akan tetapi dalam praktik bisa dikatakan sebaliknya. Jika Anda dekat dengan pejabat, anda bisa membuat usulan kegiatan apa saja selama–dalam dokumen resmi–nomenklaturnya sesuai dengan nomenklatur unit organisasi tsb. dan nomenklatur usulan tercantum dalam RPJM/D, walaupun secara substantif ga nyambung. Kata kepentingan rakyat dan publik kemudian hanya urusan dokumen.
Dengan organisasi dan sistem penganggaran di atas kita akan memahami mengapa kegiatan-kegiatan yang tertera dalam APBN/D, banyak yang gagah dalam judul tapi loyo dalam realitas. Lihat saja anggaran mengatasi stunting paling besar habis untuk workshop dan seminar di hotel; kegiatan studi banding isinya cuma jalan-jalan; keputusan rapat hanya terealisasi dalam dokumen, tidak di lapangan; laporan monitoring dan evaluasi ada tetapi penyimpangan dimana-mana, dst.
Dijadikan Benchmark
Kebijakan dan aksi KDM bukan tanpa kritik, tetapi sejauh ini argumentasi yang digunakan berbasis pada apa yang disebut dalam berbagai literatur New public Management (NPM) sebagai paradigma lama administrasi negara. Contoh, dikatakan tidak menggunakan sistem dan prosedur, tidak ada landasan hukumnya, dst. Kritik seperti itu tidak hanya datang dari “the man in the street” tetapi juga dari dosen kebijakan dan administrasi publik, yang tampaknya kurang mengikuti perkembangan ilmunya sendiri.
Sesungguhnya apa yang dilakukan KDM itu sangat sejalan dengan paradigma baru dalam ilmu administrasi negara yang disebut New Public Management (NPM) atau belakangan disebut Public Management. Ada 7 komponen utama NPM menurut Christopher Hood (1991), yaitu: (1) Manajemen professional yang lebih aktif dan proaktif, (2) Standar Kinerja yang jelas dan terukur, (3) fokus pada control output dan hasil, (4) Pemisahan unit-unit organisasi menjadi lebih kecil dan otonom, (5) Peningkatan kompetisi antara lembaga publik dan swasta, (6) Penerapan gaya manajemen sektor swasta, dan (7) Penekanan pada disiplin dan penghematan dalam penggunaan sumberdaya. Dalam konteks tulisan ini dan dalam batas tertentu, menurut penulis, KDM telah menerapkan komponen nomor 1, 2, 3, 6, dan 7.
Apa yang dipraktikkan oleh KDM ini sangat penting, setidaknya karena: (1) Di tengah teriakan nyaring banyak pejabat pusat dan – terutama daerah – bahwa mereka kekurangan uang, KDM memberikan peta jalan sekaligus bukti bahwa jika kita mau mengulik dan berkorban, uang untuk program-program pokok guna kemasalahatan publik itu bisa diadakan; (2) Peringatan kepada para pengajar di Lembaga Administrasi Negara dan Jurusan Administrasi Publik/Negara, dan para birokrat, yang masih memuja paradigma lama admnistrasi negara, untuk segera insaf dan menyadari bahwa dunia sudah berubah sejak lama dan paradigma lama itu bukan saja sudah tidak berlaku, lebih dari itu penerapannya menimbulkan banyak kerusakan; (3) Cara kerja KDM ini bisa disebut sebagai praktek terbaik (best practice) dan layak dijadikan benchmarking, baik oleh pemerintah daerah lain maupun kementerian dan lembaga (KL) di pusat. [ ]
*Pengamat birokrasi dan kebijakan publik