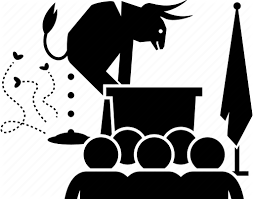Interfaith dan Islamophobia [Selesai]

Peristiwa kembali terulang dan tak akan terlupakan ketika Donald Trump mengeluarkan aturan “Muslim Ban” atau pelarangan orang Islam masuk Amerika di tahun 2018, yang dimulai dari enam negara mayoritas Muslim. Kembali para Rabi di kota New York mendorong kami untuk memimpin rally dengan tema yang sama “Today I am a Muslim too”. Kali ini bahkan menurut perkiraan puluhan ribu non-Muslim memadati salah satu sudut Time Square itu.
Oleh : Imam Shamsi Ali*
JERNIH–Tidak dapat disangkal bahwa kegiatan interfaith dapat berujung ganda, madu atau berujung racun. Kegiatan ini, sebagaimana media sosial misalnya, bisa membawa manfaat besar, atau sebaliknya mendatangkan mudharat yang tidak disangka-sangka.

Itulah barangkali yang menjadi pertimbangan Rasulullah SAW ketika beliau melarang sahabat-sahabatnya membaca kitab suci orang lain di awal kerisalahan. Pastinya ada pertimbangan mudharat saat itu. Belakangan beliau justru menugasi sebagian sahabat, salah satunya Abdullah bin Salam, untuk mendalami Kitab Taurat. Kebetulan memang latar belakang Abdullah bin Salam pernah beragama Yahudi.
Pelarangan dan di sisi lain penugasan (perintah) ini menunjukkan adanya realita mudharat dan manfaat dalam mempelajari kitab suci orang lain. Maka secara langsung atau tidak juga demikian dalam berinteraksi dengan penganut agama lain. Tentu kedua sisi ini harus masuk dalam konsideran kita semua.
Secara umum sebenarnya saya sering sampaikan bahwa kita yang berada di jalan dakwah ini menghadapi dua kemungkinan. Menghadapi kemungkinan tantangan dan sebaliknya menghadapi kemungkinan godaan. Keduanya dapat menjadi lobang kejatuhan bagi da’i di jalannya.
Pada bagian lalu saya telah sampaikan beberapa manfaat dari kegiatan interfaith. Dari interfaith sebagai jalan realisasi rahmah Islam. Hingga kepada pembuktian terbalik dari berbagai tuduhan buruk terhadap Islam.
Adapun mudharatnya tentu akan lebih banyak ditentukan oleh bagaimana cara pandang pelaku interfaith. Dengan interfaith seseorang boleh saja terperangkap dalam pemahaman “unifikasi” atau penyatuan agama-agama. Dengan kata lain interfaith mengantarnya kepada pemahaman jika semua agama itu sama.
Sesungguhnya kekhawatiran sebagian orang dan hal itu memang valid. Sebab memang ada pelaku interfaith yang kemudian hanyut atau terwarnai pemikiran unifikasi agama-agama itu. Padahal tanpa disadari cara pandang seperti itu dengan sendirinya meremehkan makna keragaman (diversity) yang dijunjung tinggi.
Kegiatan interfaith yang kami lakukan di Amerika dan berbagai belahan dunia lainnya tetap dengan konsideran tentang dua kemungkinan itu. Menimbang dengan jeli antara kemungkinan manfaat dan mudharat yang ditimbulkan.
Di tulisan ini saya akan memberikan contoh interfaith yang kami lakukan bersama komunitas Yahudi Amerika. Pemilihan contoh ini karena relasi Islam dan Yahudi barangkali adalah relasi yang paling aneh dan unik. Tentu karena banyak pertimbangan, salah satunya karena konflik Timur Tengah yang klasik itu.
Namun ada satu hal yang kami sadari di Amerika adalah bahwa suara umat Islam, walaupun dengan jumlahnya yang cukup signifikan, masih belum didengar. Hal itu karena umat masih kalah dalam membangun persepsi. Media sebagai alat membangun citra berada dalam genggaman orang lain.
Dan karenanya untuk menyuarakan kepentingan umat, khususnya upaya melawan Islamophobia diperlukan tangan-tangan lain yang kuat. Dan realitanya masyarakat Yahudi di Amerika memilki tangan-tangan kuat itu. Inilah salah satunya yang kemudian menjadi alasan kenapa interfaith dengan komunitas Yahudi ini menjadi intens sejak peristiwa 9/11 di tahun 2001 lalu.
Dalam perjalanan yang cukup panjang itu kami banyak mengakui betapa banyak kesalahpahaman yang terjadi di antara kedua komunitas ini. Padahal dari sekian banyak agama-agama dunia, Islam dan Yudaisme adalah agama yang paling identikal (most identical faiths).
Dari sekian banyak kesalahpahaman, satu hal pasti yang perlu dikoreksi adalah tendensi generalisasi antara satu dengan yang lain. Dan pastinya tendensi ini tidaklah adil pada komunitas masing-masing. Mereka melihat perilaku segelintir umat sebagai wajah umat secara keseluruhan. Demikian pula umat ini selalu melihat bahwa perilaku pemerintan atau Yahudi Israel mewakili semua orang Yahudi dunia.
Pandangan generalisasi seperti ini telah meracuni relasi antara dua komunitas ini. Kecurigaan bahkan permusuhan yang ada di kepala masing-masing cukup dalam. Apalagi dengan teori konspirasi yang mengatakan bahwa Islam hadir untuk menghancurkan Yahudi. Dan Yahudi adalah sumber segala kejahatan dunia.
Ternyata persepsi itu ternyata tidak semuanya benar. Secara umum kami harus akui bahwa sejak terjalin komunikasi intens dengan komunitas Yahudi, mereka kerap berdiri tegap membela hak-hak Muslim di negara ini. Berbagai serangan baik secara fisik atau non fisik (media misalnya) ada saja dari kalangan komunitas Yahudi yang berani bersuara menentang serangan itu dan membela Komunitas Muslim.
Contoh terdekat adalah ketika komunitas Muslim Amerika dilabeli “komunitas radikal” dengan sebuah dengar pendapat (hearing) di Kongress. Tema yang diusung pada dengar pendapat ini adalah “Radicalization of Muslim community in US” yang dikomandoi Peter King, seorang anggota Kongress dari Long Island, New York.
Di momen yang begitu buruk itu, di saat umat digeneralisasi sebagai komunitas radikal, beberapa Rabi Yahudi menawarkan bantuan untuk merespon (menolak) acara dengar pendapat itu. Namun mereka tetap tidak ingin tampil secara terbuka. Maka mereka menginginkan agar respons itu dikomandoi oleh saya sebagai Imam.
Kami pun mengadakan rally atau demo besar di jantung kota New York, Times Square. Sekitar tujuh ribuan orang, mayoritasnya non-Muslim hadir dengan slogan: “Today I am a Muslim too“. Dan saya harus tampil sebagai koordinator yang dihadiri oleh banyak pejabat kota, tokoh agama, hingga beberapa orang Hollywood.
Peristiwa kembali terulang dan tak akan terlupakan ketika Donald Trump mengeluarkan aturan “Muslim Ban” atau pelarangan orang Islam masuk Amerika di tahun 2018, yang dimulai dari enam negara mayoritas Muslim. Kembali para Rabi di kota New York mendorong kami untuk memimpin rally dengan tema yang sama “Today I am a Muslim too”. Kali ini bahkan menurut perkiraan puluhan ribu non-Muslim memadati salah satu sudut Time Square itu.
Dalam perjalanannya, interaksi yang terjadi antara komunitas Muslim dan Yahudi semakin meyakinkan bahwa pada semua komunitas ada unsur-unsur baik dan buruk. Persis pada komunitas Muslim juga. Ada Muslim yang taat dan damai. Tapi ada juga Muslim yang kerjanya mengedepankan pandangan negatif dan kebencian.
Secara khusus saya ingin menyebut seorang rabi Yahudi bernama Marc Schneier, yang saat ini menjadi teman, bahkan menulis buku bersama dengan judul “Sons of Abraham”. Buku kami telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul “Anak-Anak Ibrahim”, dan saat ini dalam proses diterjemahkan ke dalam lima bahasa dunia lainnya.
Rabi Schneier adalah putra dari seorang rabi keturunan Austria. Dalam kehidupannya sejak lahir di Amerika belum pernah bertemu dengan seorang Muslim pun. Tapi setiap harinya membaca berbagai informasi atau misinformasi mengenai Islam dan Muslim. Maka dia pun tumbuh dan menumbuhkan kebencian kepada Islam dan pengikutnya.
Puncak dari kebencian itu terjadi ketika Amerika mengalami musibah dengan serangan teroris 9/11 lalu. Saat itu Rabi Schneier adalah salah seorang dari 50 Rabi Yahudi yang paling berpengaruh di Amerika. Kebencian itu diekspresikan dalam berbagai pernyataan dan wawancaranya.
Akan tetapi di penghujung tahun 2004 itu Allah rupanya ingin melakukan perubahan itu. Saya dipertemukan dengan Rabi schneier dalam sebuah wawancara di TV CBS tentang Paus Yohannes (Pope John II) dari perspektif non-Kristen. Ketika ketemu pertama kali sang Rabi ini bahkan tidak mau salaman dan melihat muka saya.
Sekitar enam bulan kemudian kantor Rabi Schneier menelpon dan menyampaikan jika Rabi itu ingin ketemu. Di pertemuan itulah Marc Shcneier berterus terang bahwa dia tidak mau salaman di studio karena ketika itu dia memang tidak suka Islam dan pemeluknya. Tapi setelah beberapa kali melihat saya di media (khususnya di TV) dia justru ingin kenalan lebih jauh.
Singkat cerita kami pun hanyut dalam dialog hari itu. Ragam pertanyaan kita lemparkan. Dan akhirnya kita sepakat untuk melanjutkan dialog itu pada level yang lebih luas. Satu di antaranya kami berdua menginisiasi pertemuan Imam dan Rabi se-Amerika Utara. Acara itu kami namai “The Summit of Imams and Rabbis in North America” di tahun 2006.
Mungkin tidak berlebihan jika saya katakan bahwa dialog Muslim-Yahudi yang saya dan Rabi Shcneier inisiasi di kota New York itu menjadi cikal bakal tumbuhnya berbagai dialog dan kerja sama antara dua komunitas ini di mana-mana.
Singkatnya Rabi Shcneier saat ini tidak saja berdialog dengan komunitas Muslim. Tapi sudah menjadikan prioritas kerjanya membela komunitas Muslim di saat umat ini mendapat serangan. Maka motto Dialog kami adalah “fighting for one another”.
Misalnya dalam menghadapi Islamophobia dan anti-semitisme kami melihatnya sebagai “the two sides of the same coin”.
Walaupun demikian, kedekatan interaksi pada tataran komunitas di Amerika ini tidak mengurangi komitmen untuk membela hak dan keadilan dalam pandangan kami, khususnya dalam konteks konflik Timur Tengah. Sehingga satu lagi motto kami: “We can agree to disagree without being disagreeable” (kita sepakat untuk berbeda pendapat tanpa harus saling membenci).
Penutup
Dari semua semua apa yang telah disampaikan jelas bahwa baik secara agama, sejarah, maupun berdasarkan realita sosial, interfaith adalah sesuatu yang tidak saja penting, tapi saat ini sudah menjadi kebutuhan dalam upaya mengurangi kesalah pahaman dan kebencian kepada mereka yang dianggap berbeda. Bahkan interfaith sebenarnya dapat menjadi jalan dalam upaya kita membangun dunia yang lebih aman, damai dan berkeadilan. Betapa banyak konflik dunia saat ini yang memakai agama atau sentimen agama sebagai gandengan atau justifikasi. Dan oleh karenanya agama harus dibalik dan dimaksimalkan untuk menyelesaikan konflik serta mewujudkan perdamaian dan kerja sama manusia.
Hanya mereka yang tidak paham atau gagal paham yang melihatnya justru tidak penting. Tapi yang lebih berbahaya lagi adalah ketika penolakan itu didasari oleh perasaan paling beragama. Tanpa disadari terjadi keangkuhan beragama yang sangat berbahaya. Sekali lagi, biasanya penilaian seperti itu terjadi ketika pandangan keagamaan seseorang dibatasi oleh dinding-dinding ritual yang sempit. Wallahu a’lam.
Akhirnya, terima kasih sudah membaca tulisan panjang tentang interfaith ini. Saya akhiri sampai di sini dan salam akhir pekan. Semoga Allah ridhoi kita semua. Aamiin. [ ]
* Presiden Nusantara Foundation