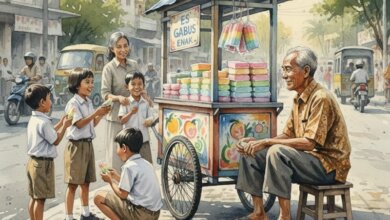Syahganda Nainggolan, direktur eksekutif GREAT Institute yang memoderatori diskusi itu, mengingatkan bahwa langkah Prabowo untuk tetap independen dari tekanan dua kekuatan besar dunia—Amerika dan Tiongkok—merupakan keberanian strategis yang layak dicatat. “Prabowo sudah tepat, karena ingin membahas hubungan dagang ini secara terpisah dan independen antara negara berdaulat, baik terhadap Amerika maupun China,” katanya. Bagi Syahganda, sikap independen dalam politik dagang bukan sekadar pilihan taktis, tapi bagian dari doktrin ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pusat, bukan sebagai angka dalam matriks global.
Oleh : D. Sepriyossa*
JERNIH– Di tengah dunia yang sedang menyusut oleh rasa curiga, proteksionisme bukan lagi sekadar momok, melainkan kebijakan resmi. Sejak Donald Trump menabuh genderang perang tarif pada 2017, apalagi kini ia kembali memerintah Amerika Serikat, tata niaga dunia berubah. Dunia tak lagi berjalan di atas semangat pasar bebas, melainkan di atas meja-meja negosiasi yang sempit, tertutup, dan penuh gertakan. Dalam laporan WTO tahun 2020, hambatan perdagangan meningkat lebih dari 30 persen. Gelombangnya sampai ke Jakarta.
Indonesia pun, negeri yang sejak dulu lebih suka menunggu angin ketimbang membangun layar, tergagap. Data ekspor nonmigas ke Amerika sempat anjlok hampir 13 persen pada 2020, sebagaimana dicatat oleh Badan Pusat Statistik. Tapi yang lebih mengkhawatirkan bukanlah angka, melainkan arah. Ketika peta global menjadi kabur, Indonesia butuh kompas. Pada saat seperti itu, Prabowo Subianto, dengan segala kontroversinya, datang membawa gagasan: Prabowonomics.

Di sebuah diskusi yang digelar GREAT Institute, di Jakarta, pada 24 April 2025, belasan ekonom dan pejabat berkumpul, membedah satu kalimat besar: “negara harus kembali ke desa.” Bukan sebagai slogan, tapi sebagai arah ekonomi. Di podium itu, Wakil Menteri Koperasi, Ferry Joko Juliantono, berkata dengan nada tegas tapi akrab: “Desa selama ini jadi ladang eksploitasi para tengkulak. Sekarang negara kembali hadir.”
Yang ia maksud bukan bansos atau dana desa yang umumnya lenyap begitu saja. Tapi koperasi. Tepatnya 80 ribu Koperasi Merah Putih, yang ingin dibangun di seluruh pelosok tanah air. Lembaga ekonomi lokal yang bukan hanya memberi akses modal, tapi juga menebus martabat. Bersamaan dengan itu, Klinik Desa, Apotek, Toko Sembako, hingga Gudang Desa akan menyusul, membentuk ekosistem baru yang membuat desa tak hanya jadi objek, tapi subjek ekonomi nasional.
Syahganda Nainggolan, direktur eksekutif GREAT Institute yang memoderatori diskusi itu, mengingatkan bahwa langkah Prabowo untuk tetap independen dari tekanan dua kekuatan besar dunia—Amerika dan Tiongkok—merupakan keberanian strategis yang layak dicatat. “Prabowo sudah tepat, karena ingin membahas hubungan dagang ini secara terpisah dan independen antara negara berdaulat, baik terhadap Amerika maupun China,” katanya. Bagi Syahganda, sikap independen dalam politik dagang bukan sekadar pilihan taktis, tapi bagian dari doktrin ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pusat, bukan sebagai angka dalam matriks global.
Di masa lalu, pembangunan selalu bergerak dari pusat ke pinggiran. Dari ibukota ke pelosok. Tapi kini, ada hasrat untuk membalikkan arah. Sebagaimana Gandhi pernah berkata, “India lives in her villages.” Kini Indonesia ingin hidup kembali dari desanya.
Namun, ada yang lebih mendalam dari sekadar koperasi atau apotek. Ekonomi yang dicanangkan Prabowo ini menyentuh simpul-simpul nilai. Prof. Dian Masyita, ekonom syariah, melihat napas Islam dalam kebijakan ini. Ia mengutip Surat Al-Hasyr ayat 7: “Supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” Ayat itu, yang sering terabaikan dalam khutbah maupun kebijakan, kini menemukan pantulannya di meja pemerintahan. Bagi Prof. Dian, Prabowonomics bukan sekadar program—ia adalah bentuk nyata dari semangat distribusi, dari cita-cita ekonomi yang adil.
Pasal 33 UUD 1945, yang lama jadi teks mati dalam debat pembangunan, turut dihidupkan. Bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan dipakai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat—itulah semangat konstitusional yang menurut banyak peserta diskusi, kini kembali punya gaung.
Dari perspektif industri, narasi ini menemukan pijakan praktis. Anthony Budiawan menyampaikan, dalam bahasa yang lebih teknokratis, bahwa pembangunan harus menyentuh dua sisi: forward linkage dan backward linkage. Artinya, selain hilirisasi, Indonesia perlu membangun industri komponen yang menopang produksi dari dalam. Tidak cukup merakit, kita harus mencipta. Dan itu hanya bisa dilakukan jika desa menjadi fondasi baru bagi industri kecil dan menengah.
Apa yang disampaikan Anthony sebenarnya pernah coba dibangun sejak Orde Baru melalui strategi substitusi impor. Tapi kemudian runtuh oleh gelombang liberalisasi yang tak terkendali. Kini, strategi itu kembali dibangkitkan, bukan dalam bentuk isolasi, tapi dalam bentuk kemandirian.
Dalam diskusi yang sama, Prof. Perdana Wahyu Santosa berbicara dengan nada prihatin tentang lemahnya posisi Indonesia dalam negosiasi dagang dengan Amerika. Ia menyarankan agar diplomasi ekonomi tidak lagi terpaku pada pasar lama, tetapi mulai membidik Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan. Data dari International Trade Centre mendukungnya: permintaan produk pertanian dan tekstil dari Indonesia ke kawasan-kawasan itu tumbuh 10–12 persen per tahun.
Syahganda menanggapi pernyataan itu dengan nada reflektif. Ia menyebut bahwa pendekatan ekonomi Prabowo tidak bisa disamakan dengan Deng Xiaoping, sebagaimana pernah disamakan oleh seorang pengamat asing. “Saya kira lebih tepat bila Prabowo dibandingkan dengan Mao Zedong. Mao memperkuat desa untuk mengepung kota. Itu yang sekarang dilakukan Prabowo, dengan konteks yang berbeda tentu saja,” katanya.
Satu hal yang membayangi semua harapan itu adalah komunikasi. Dr. Tito Sulistio menyampaikan, dalam kalimat yang lugas, bahwa terlalu banyak kebijakan baik yang tidak sampai ke publik. Ia mencontohkan program Makan Bergizi Gratis yang, menurutnya, adalah investasi untuk otak rakyat, bukan hanya isi perut. Tapi program ini kurang mendapat tempat dalam wacana publik karena lemahnya narasi yang mendampingi.
Dalam konteks inilah, Prabowonomics tak boleh berhenti pada anggaran dan angka. Ia harus dibumikan dalam cerita, dijelaskan dalam bahasa rakyat, dan diterjemahkan dalam tindakan yang konkret. Sebab rakyat bukan hanya butuh kertas, tapi juga kehadiran. Bukan hanya struktur, tapi juga rasa.
Ketika semua telah dikatakan, pertanyaannya bukan lagi apa itu Prabowonomics, tapi apakah kita mau membawanya ke hidup yang nyata? Dalam dunia yang makin tidak pasti, keadilan bukan sekadar idealisme. Ia adalah infrastruktur peradaban. Dan seperti kata Amartya Sen, “Pembangunan adalah kebebasan.” Maka membebaskan desa dari ketertinggalan bukan sekadar strategi ekonomi. Ia adalah tanggung jawab sejarah. []
*Penulis adalah bagian dari GREAT Institute