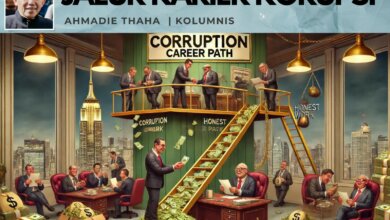Janji “mengejar koruptor sampai ke Antartika” hanya akan bermakna bila diartikan sebagai tekad untuk menghancurkan fondasi korupsi sistemik. Jika tidak, ia akan berakhir sebagai slogan heroik tanpa isi. Maka, pertanyaan terakhir yang perlu kita ajukan kepada Presiden Prabowo adalah ini: Apakah Anda akan menjadi pemburu koruptor, atau pembasmi sistem korupsi dengan menjaga independensi birokrasi dan hukum?
Oleh : Radhar Tribaskoro
JERNIH– Setiap rezim selalu datang dengan janji yang sama: memberantas korupsi. Tetapi kenyataan yang berulang membuktikan, sistemlah yang selalu menang. Baru-baru ini, publik kembali dikejutkan oleh dua peristiwa: OTT terhadap Imanuel Ebenezer, wakil menteri tenaga kerja yang dulu dikenal sebagai aktivis keras, dan vonis 18 bulan penjara untuk Tom Lembong, teknokrat reformis yang selama ini punya citra bersih.
Kasus Noel memperlihatkan betapa cepat seorang pejabat bisa terseret dalam praktik rente begitu ia masuk ke lingkaran kekuasaan. Sistem politik yang menuntut biaya mahal seolah memaksa setiap aktor mencari jalan pintas. Idealismenya sebagai aktivis runtuh, berganti dengan logika transaksional: untuk bertahan, ia harus ikut bermain.
Kasus Tom Lembong bahkan lebih telanjang. Publik luas melihatnya bukan sekadar pejabat yang tergelincir, melainkan korban dari sistem peradilan yang korup—dari polisi, jaksa, hingga hakim—yang menjadikan hukum sebagai komoditas. Vonis 18 bulan itu justru memicu gelombang dukungan, petisi, dan protes di berbagai ruang publik. Akhirnya Presiden Prabowo turun tangan dengan memberikan abolisi, sebuah langkah politik yang mengindikasikan bahwa lembaga hukum tidak lagi dipercaya untuk menegakkan keadilan secara independen.
Dua peristiwa ini menunjukkan wajah asli persoalan di Indonesia: korupsi bukan lagi soal individu yang serakah, melainkan soal sistem yang cacat. Aktivis bisa jatuh, teknokrat bisa dihukum, bahkan rakyat pun bisa menjadi korban, karena seluruh mekanisme politik, birokrasi, dan hukum sudah tertanam dalam logika rente. Inilah bukti paling mutakhir bahwa korupsi kita telah bersifat sistemik.
Di negeri ini, korupsi tidak lagi sekadar perilaku menyimpang. Ia sudah menjadi sistem. Bukan hanya segelintir orang serakah yang menjarah, melainkan seluruh mekanisme kekuasaan yang dirancang agar rente terus mengalir. Korupsi adalah “metabolisme” politik kita: ia mengatur alokasi sumber daya, menentukan siapa yang naik dan siapa yang jatuh, bahkan menjaga stabilitas rezim.
Korupsi Sistemik: Teori dan Fakta
Apa yang kita saksikan melalui kasus Noel dan Tom bukanlah sekadar kebetulan. Ilmuwan politik Susan Rose-Ackerman (1999) sudah lama mengingatkan tentang fenomena korupsi sistemik, yaitu situasi ketika korupsi bukan lagi perilaku menyimpang segelintir orang, melainkan mekanisme alokasi sumber daya dalam birokrasi dan politik. Dalam kondisi ini, sistem itu sendiri memberi insentif agar aktor-aktornya melakukan korupsi, karena tanpa itu mereka justru tidak bisa bertahan.
Michael Johnston (2005) menjelaskan fenomena ini sebagai “syndrome of oligarchs and clans”, sebuah jaringan patronase antara elite politik dan bisnis yang menopang diri melalui rente. Korupsi menjadi equilibrium—keseimbangan yang dihasilkan oleh sistem, bukan kecelakaan. Dengan kata lain, korupsi adalah produk dari proses jual-beli kekuasaan yang berlangsung terus-menerus antara oligarki dan penguasa.
World Bank (1997) menambahkan bahwa korupsi sistemik bersifat “pervasive, embedded in rules, and affecting most transactions”. Ia meluas dan merata karena sudah ditanamkan dalam aturan formal maupun informal. Bahkan, Samuel Huntington (1968) melihat korupsi dalam situasi seperti ini sebagai “pelumas” sistem politik, sesuatu yang justru membantu elite mempertahankan stabilitas di tengah lemahnya institusi.
Maka, dari sisi teori maupun fakta, kita sampai pada kesimpulan pahit: korupsi di Indonesia telah melembaga. Ia bukan lagi “penyakit” yang bisa diobati dengan sekadar menyingkirkan individu-individu serakah, melainkan bagian dari metabolisme politik kita sendiri. Tetapi dari mana korupsi sistemik ini bermula?
Biaya Politik yang Melahirkan Rente
Sejak Pemilu langsung digelar pasca-Reformasi, biaya politik di Indonesia melonjak gila-gilaan. Riset KPK menyebutkan bahwa biaya untuk mencalonkan diri sebagai bupati atau walikota berkisar antara Rp 30–50 miliar, sementara calon gubernur bisa mencapai Rp 100–200 miliar. Untuk Pilpres, nilainya sudah pasti triliunan rupiah.
Dari mana uang sebesar itu datang? Partai dilarang punya usaha, bantuan negara minim. Akhirnya, para calon menggandeng sponsor bisnis. Sponsor itu tidak gratis. Sebagai imbalan, mereka menuntut akses proyek, konsesi tambang, atau izin usaha. Inilah mengapa kepala daerah silih berganti dijerat KPK. Lebih dari 300 kepala daerah terseret kasus korupsi dalam dua dekade terakhir. Ini bukan kebetulan, melainkan sebuah pola: biaya politik mahal → butuh sponsor → rente jadi jalan keluar.
Bagaimana menjelaskan siklus itu? Pertama, kita melihat birokrasi sebagai mesin uang. Korupsi tidak terjadi di panggung politik saja. Birokrasi kita telah dirancang menjadi mesin rente. Perizinan berbelit, layanan publik lambat, dan proyek negara menjadi ladang pungli. Kasus e-KTP hanyalah puncak gunung es: proyek Rp 5,9 triliun dijarah berjemaah oleh anggota DPR, pejabat, dan pengusaha. Itu bukan kasus satu-dua orang. Itu bukti bahwa birokrasi sudah dijadikan mesin penghisap.
Kedua, hukum bisa dinegosiasikan. Jika hukum berfungsi, korupsi akan runtuh. Tetapi hukum di Indonesia sering berubah menjadi komoditas. Kasus bisa diatur, vonis bisa ditawar. Bahkan, mantan napi korupsi bisa kembali duduk di kursi DPR atau maju pilkada. Artinya, korupsi tidak mengakhiri karier politik, malah justru bagian dari karier itu sendiri.
Ketiga, rakyat pun terjebak. Masyarakat juga, mau tak mau, ikut menjadi bagian dari sistem. Politik uang dianggap normal: “kalau tidak menerima sekarang, nanti juga tidak akan dapat apa-apa setelah ia terpilih.”
Pungli dianggap wajar: “bayar sedikit biar cepat.” Inilah normalisasi sosial yang membuat korupsi bertahan. Dan terakhir. nepotisme menguatkan rantai. Anak, menantu, kerabat—semua ikut berebut kursi kekuasaan. Meritokrasi dipinggirkan, patronase dijadikan norma. Nepotisme memperkuat loyalitas, dan loyalitas memperkuat rente. Siklus ini berjalan tanpa henti.
Jadi, korupsi di Indonesia bukanlah “penyakit” yang bisa dioperasi lalu sembuh. Ia adalah equilibrium—keseimbangan yang dipelihara oleh politik, birokrasi, hukum, dan masyarakat itu sendiri. Biaya politik mahal, birokrasi rente, hukum selektif, rakyat permisif, dan nepotisme: semua saling menopang.
Itulah mengapa setiap upaya pemberantasan korupsi terasa seperti menimba air dengan ember bocor. KPK bisa menangkap satu, sepuluh, seratus pejabat, tapi sistem akan melahirkan seribu lainnya.
Hukum Mati Atau Reformasi
Hukuman mati bagi koruptor? Itu solusi jangka pendek, memberi efek takut sesaat, tapi tidak menyentuh akar masalah. Duterte, mantan Presiden Duterte, pernah memberi kuasa tembak di tempat untuk bandar narkoba. Ratusan telah tertembak. Tetapi peredaran narkoba di Pilipina hanya mereda sejenak, sekarang perdagangan barang haram marak kembali.
Demikian juga aturan hukuman mati dalam UU No.35/2009 tidak banyak berpengaruh dalam peredaran narkoba di Indonesi. Hukuman mati dalam kasus korupsi, sebagaimana dicontohkan oleh Cina, Vietnam, atau Arab Saudi menunjukkan bahwa eksekusi hanya jadi “alat politik”, bukan obat struktural.
Bandingkan dengan Singapura, yang tanpa hukuman mati berhasil menekan korupsi hingga level terendah di Asia. Rahasianya sederhana: gaji tinggi untuk pejabat, hukum independen, birokrasi transparan, dan meritokrasi.
Jika Indonesia ingin keluar dari lingkaran setan ini, jalannya bukan sekadar “shock therapy”, melainkan reformasi menyeluruh: pembia-yaan politik yang bersih, birokrasi digital tanpa rente, penegakan hukum yang tak bisa dinegosiasikan, meritokrasi ASN, dan pendidikan publik untuk melawan normalisasi politik uang.
Penutup
Presiden Prabowo pernah berkata lantang: “Kita akan mengejar koruptor sampai ke Antartika.” Sebuah janji yang menggema, penuh simbol keberanian. Tetapi pertanyaan penting tetap harus diajukan: apa sebenarnya maksud dari pernyataan itu? Apakah yang dimaksud hanyalah memburu individu-individu korup, menangkapi mereka satu per satu untuk memberi efek jera? Ataukah yang dimaksud adalah tekad untuk membasmi korupsi sampai ke akar sistemnya?
Pengalaman dua dekade terakhir mengajarkan kita: menangkap koruptor penting, tetapi tidak pernah cukup. KPK telah menahan ratusan pejabat, kepala daerah, menteri, dan anggota DPR. Namun korupsi tetap hidup, bahkan berkembang dengan wajah baru. Ini karena akar masalahnya ada pada korupsi sistemik: biaya politik yang mahal, birokrasi yang rente, hukum yang bisa dinegosiasikan, budaya politik uang yang dinormalisasi, dan nepotisme yang merajalela.
Jika Presiden Prabowo sungguh ingin menepati janjinya, maka yang harus ia kejar bukan hanya individu, melainkan struktur. Ia harus berani membenahi pembiayaan partai politik agar tidak lagi bergantung pada oligarki. Ia harus mendigitalisasi birokrasi untuk menutup celah rente. Dan yang paling penting—ia harus menjaga independensi birokrasi serta aparat hukum. Tanpa birokrasi profesional dan aparat hukum yang tidak bisa diintervensi, semua slogan antikorupsi akan runtuh.
Di sinilah pelajaran dari Singapura menjadi relevan. Negara kota itu tidak menggunakan hukuman mati untuk memberantas korupsi, melainkan memastikan birokrasi dibayar layak, berjalan transparan, dan bebas dari tekanan politik. Aparat hukumnya berdiri independen, sehingga siapapun yang bersalah dapat ditindak tanpa pandang bulu. Itulah yang membuat Singapura berhasil menekan korupsi ke level terendah di Asia, tanpa harus melakukan kampanye seremonial.
Dengan demikian, janji “mengejar koruptor sampai ke Antartika” hanya akan bermakna bila diartikan sebagai tekad untuk menghancurkan fondasi korupsi sistemik. Jika tidak, ia akan berakhir sebagai slogan heroik tanpa isi. Maka, pertanyaan terakhir yang perlu kita ajukan kepada Presiden Prabowo adalah ini: Apakah Anda akan menjadi pemburu koruptor, atau pembasmi sistem korupsi dengan menjaga independensi birokrasi dan hukum?[ ]