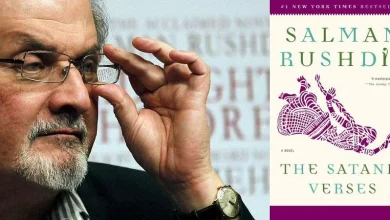Melestarikan (Keterbelakangan) Suku Anak Dalam

Saya sontak melompat dari ranjang besi yang ikut berderit nyaring, menyibak kelambu, berlari mendapati ibu di belakang rumah. Melewati bahu Ibu yang bergetar ketakutan, menerobos pintu kayu yang terkuak lebar, pandangan saya tertumbuk seorang pria bertelanjang dada, berdiri di luar menghadap lubang pintu. Tangan kanannya memegang tombak dengan ujung runcing menghadap tanah, sementara seekor ayam hutan tak berhenti berkepak di tangan kirinya
Oleh : Darmawan Sepriyossa
JERNIH—Saya masih bisa mengingat jerit ketakutan Ibu, manakala di satu pagi membuka pintu belakang, menuju ke dapur yang terpisah dari rumah utama untuk mulai memasak bagi keluarga. Seolah baru kemarin bunyi penuh jeri itu berdengung kuat di membran telinga saya, bocah empat tahunan, padahal itu terjadi lebih di tahun 1975. Ingatan itu pula yang membuat saya tak pernah meng-underestimated kemampuan anak-anak mengingat apa pun, termasuk mengingat perlakuan kita sebagai orang tua mereka.

Saya sontak melompat dari ranjang besi yang ikut berderit nyaring, menyibak kelambu, berlari mendapati ibu di belakang rumah. Melewati bahu Ibu yang bergetar ketakutan, menerobos pintu kayu yang terkuak lebar, pandangan saya tertumbuk seorang pria bertelanjang dada, berdiri di luar menghadap lubang pintu. Tangan kanannya memegang tombak dengan ujung runcing menghadap tanah, sementara seekor ayam hutan tak berhenti berkepak di tangan kirinya. Lelaki itu hanya mengenakan cawat, menutup area paling sakral bagi manusia di peradaban mana pun.
Itulah pertemuan pertama keluarga kami dengan warga Suku Anak Dalam—dulu lazim disebut Suku Kubu. Mereka tengah ‘melangun’—pergi dari tempat asal karena berbagai sebab–dan lewat kamp penebangan kami di pinggiran hutan, di seberang Kampung Muara Ketalo, dipisahkan aliran Sungai Tembesi. Saya ingat, Ibu baru bisa ditenangkan ayah yang berlari tergesa dari jamban umum di pinggir kamp, hanya berlilitkan handuk dari pinggang ke bawah. Sore itu kami makan dengan lauk ayam hutan, yang ditukar ayah dengan dua bongkah garam bata dan selembar kain sarung ayah.
Ingatan tersebut kembali membayang manakala saat ini media massa dipenuhi berita tentang Suku Anak Dalam (SAD). Tentang nasib mereka yang kian bikin miris, soal makin banyaknya warga SAD yang harus mengemis. Untung saja pekan-pekan ini ada berita baik, tentang Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang mau meluangkan waktu menginap di permukiman warga SAD.
Barangkali, itu saja berita baik soal SAD. Lainnya lebih merupakan kabar buruk, terutama berkaitan dengan ruang hidup warga SAD yang kian lenyap seiring musnahnya hutan di Jambi. Berawal dari penerapan Hak Penguasaan Hutan (HPH) oleh sekian banyak perusahaan di 1970-an, program transmigrasi yang memberi setiap keluarga dua hectare lahan, diikuti investasi di sektor perkebunan kelapa sawit pada 1980-an dan 1990-an, deforestasi akibat kebutuhan lahan membuat hutan yang menjadi ruang hidup warga SAD pun kian sempit. Belum lagi belakangan, setelah mengenal uang, warga SAD sendiri yang menebangi hutan secara besar-besaran untuk mereka jadikan perkebunan kelapa sawit dan karet, atau dijual kepada pendatang. Sebelum meniru pendatang, tak pernah warga SAD di masa lalu membuka hutan secara luas. Paling hanya untuk bertanam ubi, yang akan mereka tinggalkan juga pada waktunya untuk kembali menjadi hutan.
Akibatnya, pada 2000-an luas hutan Jambi tercatat hanya tinggal 1,6 juta hektare. Belakangan, pada 2017, dari analisis Citra Satelit tim GIS Komunitas Konservasi Indonesia Warsi, tutupan hutan di Jambi tinggal 930.000 hektare, atau hanya 18 persen dari luas daratan provinsi itu. Kehilangan hutan, sangat berpengaruh pada kehidupan mereka SAD.
Antropolog Universitas Diponegoro, Adi Prasetijo, yang lama bersentuhan dengan komunitas SAD, mengatakan, bagi SAD hutan tidak hanya berfungsi ekonomi tetapi juga mempunyai makna budaya yang sangat tinggi. Perubahan fungsi hutan secara langsung mempengaruhi kualitas hidup warga SAD. Secara perlahan, hilangnya hutan membuat warga SAD kehilangan mata pencaharian dan terpaksa harus menyesuaikan diri dengan lingkungan alam yang baru.
“Kini mereka terpaksa mencari makanan di perkampungan Melayu karena hutan yang menyempit membuat hewan dan tumbuhan yang jadi makanan menipis jumlahnya. Temuan kasus–kasus kelaparan di beberapa kantong pemukiman SAD menjadi makin sering terjadi. Sampai Bank Dunia pun mencatat temuan adanya sekelompok warga SAD yang menjadi pengemis di jalanan dan menggelandang di pemukiman masyarakat kota Jambi karena hilangnya hutan sebagai tumpuan hidup mereka,” kata tokoh yang akrab dipanggil Tijo itu.
Beberapa berita media massa masih dengan serampangan menulis jumlah warga SAD sebanyak 200 ribu orang. Entah data kedaluwarsa dari tahun berapa, karena menurut data statistik Kabupaten Sarolangun tahun 2010, warga SAD di Jambi tinggal 3.198 jiwa, tersebar di beberapa kabupaten atau kota. Ada 858 jiwa di Kabupaten Merangin, 1.095 di Sarolangun, 79 jiwa di Batanghari, 57 jiwa di Tanjung Jabung Barat, 823 orang di Tebo, dan 286 di Bungo.
Dalam sebuah obrolan di Jambi, bulan lalu, seorang tokoh LSM yang intens mengurusi warga SAD mengatakan kepada saya, belum tentu 10 tahun mendatang masih ada SAD yang tersisa. Yang ia maksud adalah warga SAD ‘asli’, dengan karakter SAD yang juga genuine. Bukan warga SAD yang akan bersegera memakai cawat manakala kedatangan pengunjung, untuk kemudian kembali ke penampakan asli saat ini: berbaju-celana sama dengan ‘Orang Terang’ (warga desa atau pendatang), hanya cenderung lebih kumal.
Saya pribadi bukan orang yang mengidealkan lestarinya warga SAD dalam kondisi yang hanya sedikit lebih baik dibanding nenek moyang manusia di zaman perunggu itu. Sebagai sesama manusia dengan kesadaran bahwa setiap individu berhak atas ‘kehidupan yang layak’, saya lebih memilih tak ada lagi orang-orang SAD yang mengembara di hutan, memungut hasil hutan yang sebagaimana lingkungannya yang kian sempit, juga semakin sedikit itu, dibanding tahu bahwa ada komunitas yang hidup melarat di bawah tingkat subsisten karena ruang hidup yang kian memojokkan mereka.
Saya percaya, sebagaimana fakta sebagian kecil India Seminole yang hidup makmur, bahkan memiliki Hard Rock café dan jaringan hotel segala, orang Seminole bisa hidup dengan kualitas kehidupan modern, tanpa membuang sama sekali budaya Indian mereka. Artinya, orang SAD pun bisa keluar hutan, hidup laiknya ‘Orang Terang’, dengan tetap memelihara apa yang mereka pegang sebagai tradisi sejak lama.
Toh, kondisi ‘Rimbo Bungaron Raya’—hutan belantara habitat komunitas SAD sejak lama—yang dulu sangat berlimpah dengan buruan dan hasil hutan, kini keberadaannya pun telah tergantikan pokok-pokok sawit yang dijaga sekian peleton Satuan Pengamanan. Bukan lagi milik bersama, yang meski berada di rombong lain, tinggal uluk salam dan meminta.
Waktu pun bergerak lurus tanpa bisa diputar ke belakang. Apa yang sudah terjadi, hanya mungkin dicarikan solusi. Sedih memang, menyadari rimba Jambi kini tak sebagaimana dulu lagi. Tapi kalau bubur memang mustahil dibikin jadi nasi, mungkin lebih bijaksana bila kita mencari abon sapi dan mulai menikmati. Terserah, bisa menyantapnya dengan diaduk, atau langsung tanpa mengaduk-aduknya dulu.
Direktur KKI Warsi–LSM yang lama melakukan pendampingan kepada SAD—Rudy Syaf, melihat bahwa banyaknya perubahan yang terjadi pada warga SAD memungkinkan program semacam transmigrasi bisa membawa harapan cerah untuk masa depan mereka.
“Kalau pemerintah hari ini mendorong mereka untuk memiliki lahan dan membangunkan rumah, kami sangat setuju,” kata Rudi. Dia mendukung niat pemerintah mendorong warga SAD menetap dalam kawasan terpadu, meski tahu betul bahwa program merumahkan orang Rimba bukanlah ideal. “Idealnya dikasih hutan, tapi itu sudah tidak mungkin. Sebab biaya menyediakan lahan di hutan lebih mahal dibanding merumahkannya,” kata dia kepada situs lingkungan, Mongabay.
Program laiknya transmigrasi sangat tepat karena sangat terpadu. Masyarakat dapat perumahan, jatah hidup, ada penyuluhan, pendampingan, bantuan bibit, dan yang terpenting, lahan garapan. “Buktinya (transmigrasi) Rimbo Bujang, sukses. Bergurulah kepada (program) transmigrasi,” kata Rudi. [ ]