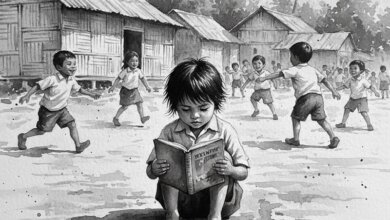Ekonom Richard Musgrave mengingatkan, anggaran negara punya tiga fungsi: efisiensi, redistribusi, dan stabilisasi. Jika pemerintah hanya terpaku pada efisiensi, maka aspek keadilan sosial bisa terabaikan. Efisiensi macam apa yang dibutuhkan?
JERNIH – Efisiensi memang penting, tetapi ia bukanlah tujuan akhir. Seperti dikatakan Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi: “Development is freedom”—pembangunan adalah tentang kebebasan manusia untuk hidup bermartabat. Jika efisiensi mengekang kebebasan itu dengan mengorbankan akses masyarakat miskin pada layanan dasar, maka efisiensi telah kehilangan maknanya.
Bila ditinjau pilihan efisiensi berdasarkan pada beberapa alasan di antaranya keterbatasan fiskal akibat utang dan beban subsidi. Lalu, tuntutan pembangunan yang makin kompleks dengan sumber daya yang terbatas. Juga alasan tekanan global untuk menjaga stabilitas makroekonomi.
Efisiensi dianggap sebagai jalan tengah agar pembangunan tetap berjalan tanpa membebani kas negara secara berlebihan.
Dalam lanskap kebijakan publik Indonesia, isu efisiensi anggaran selalu menjadi tema yang hangat diperbincangkan. Pemerintah, dengan alasan keterbatasan fiskal dan kebutuhan pembangunan, kerap menekankan pentingnya efisiensi. Namun, pertanyaan yang menggelitik adalah: apakah efisiensi benar-benar menghasilkan keadilan dan kesejahteraan, atau justru menjadi “ilusi manis” yang menutupi lemahnya distribusi manfaat anggaran?
GREAT Institute mencermati, mengkritisi, sekaligus memberi rekomendasi atas arah kebijakan fiskal pemerintah. Konsep efisiensi dalam anggaran publik dapat ditarik dari teori klasik ekonomi, yakni pandangan Vilfredo Pareto tentang efisiensi Pareto: “Sebuah kondisi dikatakan efisien bila tidak ada seorang pun yang dapat ditingkatkan kesejahteraannya tanpa mengurangi kesejahteraan orang lain.” Namun, dalam praktik kebijakan publik, efisiensi sering kali berhadapan dengan prinsip equity (keadilan).
Ekonom kebijakan publik, Richard Musgrave, menegaskan bahwa anggaran negara tidak hanya berfungsi untuk efisiensi, tetapi juga untuk redistribusi dan stabilisasi. Dengan kata lain, efisiensi bukanlah satu-satunya kompas; keadilan sosial juga harus menjadi bintang penunjuk.
Efisiensi anggaran kerap dimaknai sebagai pemangkasan belanja atau penghematan. Namun, hemat tidak selalu identik dengan baik. Di sinilah peran analisis kritis diperlukan. GREAT Institute misalnya, menyoroti apakah penghematan justru menurunkan mutu layanan publik. Contoh: jika anggaran kesehatan dipangkas untuk menekan defisit, apakah itu berdampak pada ketersediaan obat di puskesmas atau gaji tenaga medis? Jika iya, efisiensi yang dilakukan justru kontraproduktif karena mengurangi akses masyarakat pada hak dasar.
Analisis kritis berarti menguji trade-off: apakah setiap rupiah yang dihemat masih menghasilkan manfaat sosial yang sepadan. Bukan hanya melihat angka “pengeluaran turun”, tetapi juga menilai apakah kesejahteraan masyarakat ikut naik atau justru merosot.
Merujuk ungkapan ekonom James Buchanan: ““Efisiensi tanpa tanggung jawab adalah ilusi yang berbahaya.”
Pemerintah sering menjadikan efisiensi sebagai jargon politik. “Belanja hemat” terdengar populer, tetapi tanpa kajian, bisa menyesatkan. Maka advokasi kebijakan dari think tank hadir untuk memberikan rekomendasi berbasis data dan riset, misalnya: alih-alih memangkas subsidi kesehatan, lebih baik memperbaiki mekanisme distribusinya agar tepat sasaran.
Daripada mengurangi anggaran pendidikan, bisa dilakukan efisiensi melalui digitalisasi kurikulum atau pengadaan buku elektronik. Menghentikan proyek infrastruktur yang mangkrak, sehingga dana bisa dialihkan ke program produktif lain.
Advokasi semacam ini membuat pemerintah tidak terjebak dalam pemahaman efisiensi yang sempit. Efisiensi seharusnya berarti optimalisasi manfaat, bukan sekadar pemangkasan anggaran.
Tokoh tata kelola publik Mark Bovens menyebutkan bahwa, “Akuntabilitas adalah landasan pemerintahan yang demokratis.” Karenanya efisiensi anggaran tidak akan dipercaya publik tanpa transparansi. GREAT Institute menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat tersebut. Umpamanya dengan mendorong adanya laporan belanja yang bisa diakses publik, audit yang terbuka, serta forum diskusi dengan masyarakat sipil. Dengan begitu, publik dapat menilai apakah efisiensi dilakukan dengan adil, atau hanya menjadi alasan untuk memangkas hak-hak dasar warga.
Kontrol publik ini juga penting untuk mencegah moral hazard birokrasi, di mana efisiensi hanya dijadikan tameng untuk menyembunyikan inefisiensi atau bahkan korupsi.
Tiga aspek ini—analisis kritis, advokasi kebijakan, dan kontrol publik—membentuk satu kesatuan yang menjaga agar efisiensi anggaran tidak menyimpang dari tujuan utama: kesejahteraan rakyat.
Efisiensi memang penting, tetapi harus disertai keadilan, transparansi, dan keberpihakan pada kelompok rentan. Tanpa itu, efisiensi hanya akan menjadi slogan, bukan solusi.

Dalam beberapa kajian, efisiensi anggaran pemerintah dapat berdampak positif sebaliknya juga negatif. Efisiensi akan berdampak positif bila mengacu kepada setidaknya lima faktor.
Faktor perencanaan yang matang di mana efisiensi didesain melalui kajian mendalam, sehingga penghematan dilakukan di pos-pos yang tidak produktif atau rawan pemborosan, bukan pada sektor vital. Contohnya, mngurangi proyek infrastruktur yang mangkrak dan mengalihkan dana ke pendidikan atau kesehatan.
Anggaran harus tepat sasaran. Anggaran diarahkan ke program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Jika subsidi atau bantuan sosial tepat sasaran, maka efisiensi justru meningkatkan keadilan sosial. Hal tersebut mesti dibarengi dengan melakukan inovasi birokrasi. Efisiensi mendorong birokrasi untuk mencari cara kerja baru yang lebih cepat, murah, dan efektif (misalnya digitalisasi layanan publik).
Efisiensi dilakukan dengan transparansi dan akuntabel. Dalam hal ini proses efisiensi terbuka bagi publik, sehingga masyarakat tahu alasan penghematan dilakukan dan bisa ikut mengawasi penggunaannya. Terakhir adalah faktir keseimbangan antara efisiensi dan keadilan, soal penting tetapi selalu gagap di negeri ini. Pemerintah tidak hanya fokus pada angka fiskal, tetapi juga memperhatikan dampaknya pada kelompok rentan.
Namun efisiensi dalam kaca mata GREAT Institute dapat berbalik menjadi bola api bila mengalpakan equity (keadilan sosial). Jika efisiensi hanya menguntungkan kelompok tertentu (misalnya investor atau birokrasi) sementara masyarakat miskin dikorbankan, maka ketimpangan akan meningkat.
Efisiensi dijalankan dengan pemangkasan yang serampangan. Efisiensi hanya dipahami sebagai “mengurangi anggaran” tanpa kajian dampak. Akibatnya, layanan publik menurun (misalnya pengurangan tenaga medis atau guru). Efisiensi demikian juga akan berakibat pada polarisasi si kaya dan si miskin.
Faktor pemicu negatif lainnya adalah birokrasi defensif. Sesuatu yang belakangan muncul di berbagai pemerintahan baik pusat maupun daerah yang terpotret dalam bentuk minimnya serapan anggaran. Aparat lebih takut membelanjakan anggaran daripada mencari cara kreatif, karena khawatir dianggap “boros”. Akhirnya, anggaran tidak terserap optimal.
GREAT Institute juga menyoroti faktor minimnya komunikasi yang membuat minimnya pula partisipasi publik. Efisiensi dilakukan tanpa dialog dengan masyarakat sipil, sehingga publik tidak tahu apa yang dipangkas dan apa dampaknya.
Dan, tentu saja yang paling berbahaya jika semangat efisiensi anggaran semata hanya menjadi jargon politik. Efisiensi dijadikan slogan populer tanpa implementasi nyata, sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah.
Pendek kata efisiensi berdampak positif bila disertai kajian berbasis data, pengawasan publik dan berorientasi pada manfaat sosial. Sebaliknya, efisiensi akan berdampak negatif bila dijalankan hanya untuk “menyelamatkan angka fiskal” tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat.
Seperti pepatah manajemen publik: “What gets measured, gets managed. But what gets mismeasured, gets mismanaged.” Hal-hal yang diukur dengan jelas akan lebih mudah dikelola. Jika pemerintah mengukur kinerja layanan publik (misalnya jumlah pasien yang bisa dilayani rumah sakit), maka layanan itu bisa dikelola dan ditingkatkan. Tanpa ukuran, kita tidak tahu apakah sesuatu berhasil atau gagal.
Sebaliknya, jika pengukuran dilakukan dengan cara yang salah, maka pengelolaannya juga akan salah. Misalnya, efisiensi hanya diukur dari berapa besar penghematan anggaran, bukan dari seberapa besar manfaat sosial. Akibatnya, pemerintah bisa memangkas dana pendidikan atau kesehatan, lalu menganggapnya “efisien”, padahal masyarakat justru dirugikan. Jadi, ukuran yang keliru akan menghasilkan kebijakan yang keliru pula.(*)
BACA JUGA: Populisme dan Tantangan Pemikiran Kritis GREAT Institute