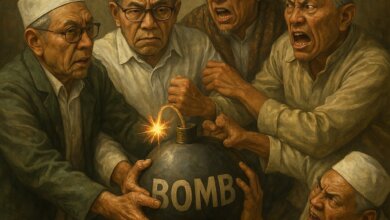Kalau kata Jokowi Whoosh itu investasi sosial yang melibatkan peran negara karena tidak mungkin projek dengan modal masif seperti itu dibiayai swasta, tawaran Jepang untuk menggunakan skema pembiayaan G2G, dengan bunga modal sangat rendah (0,1 persen) dan masa pengembalian utang sangat panjang (40–50 tahun), adalah tawaran yang sangat rasional. Tapi mengapa pemerintah justru memilih skema B2B dengan China—yang memaksa BUMN membiayai proyek dengan utang berbunga komersial sekitar 3–4 persen dan tenor yang jauh lebih pendek? Ketika Indonesia memilih B2B tanpa jaminan fiskal eksplisit, itu bukan hanya langkah yang tidak lazim—itu anomali global.
Oleh : Radhar Tribaskoro*
JERNIH–Pernyataan mantan Presiden Joko Widodo bahwa proyek kereta cepat Whoosh adalah “investasi sosial”—yang ia sampaikan Senin, 27 Oktober 2025, —telah membuka sebuah kotak pandora yang selama ini hanya bergetar pelan di ruang diskusi kebijakan dan ruang-ruang pemikiran publik yang kritis. Ucapan itu, yang tampaknya netral dan berniat merasionalisasi keputusan besar, justru memaksa kita menengok ke dalam kontradiksi mendasar yang menyelimuti perenca-naan proyek ini sejak awal.
Jika Whoosh adalah investasi sosial, logika ekonominya jelas: investasi sosial tidak dibangun untuk mencari laba, tetapi untuk menciptakan manfaat kolektif jangka panjang. Misalnya melalui peningkatan nilai tambah kawasan melalui projek Transit Oriented Development (TOD), mempercepat mobilitas penduduk, memperluas integrasi tenaga kerja, dan membentuk kota-kota yang saling terhubung secara produktif.
Mengetahui hakekat itu, investasi sosial seperti kereta cepat (High Speed Rail, HRS) selalu melibatkan peran negara karena tidak mungkin projek dengan modal masif seperti itu dibiayai swasta. Dengan kata lain, tawaran Jepang untuk menggunakan skema pembiayaan pemerin-tah-ke-pemerintah (G2G), dengan bunga modal sangat rendah (0,1% seperti yang ditawarkan Jepang) dan masa pengembalian utang sangat panjang (40–50 tahun), adalah tawaran yang sangat rasional. Karena sifat dasarnya itulah, tidak ada satu pun negara di dunia yang membangun kereta cepat sebagai program bisnis murni. Jepang, Prancis, Spanyol, Inggris, Tiongkok, Arab Saudi—semuanya membangun dengan jaminan negara, melalui APBN, subsidi eksplisit, atau penjaminan fiskal jangka panjang.
Sehingga risiko fiskal terkendali, beban jangka panjang dapat diatur, dan manfaat publik dapat tumbuh seiring waktu tanpa menekan APBN secara brutal.
Namun yang terjadi adalah kebalikannya. Mengapa pemerintah justru memilih skema B2B dengan China—yang memaksa BUMN membiayai proyek dengan utang berbunga komersial sekitar 3%–4% dan tenor yang jauh lebih pendek. BUMN tidak hanya diposisikan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai penanggung risiko keuangan—sebuah langkah yang bertentangan dengan prinsip dasar pengelolaan infrastruktur publik.
Di sinilah letak jurang yang menganga: argumen investasi sosial tidak sejalan dengan desain pembiayaan. Di dalam jurang itu terdapat selisih biaya puluhan trilyun rupiah. Karena itu kesenjangan antara alasan yang diucapkan dan struktur keputusan yang dipilih tidak dapat dianggap sebagai kebetulan atau kebodohan. Kesenjangan itu mengindikasikan mens rea—sebuah niat tersembunyi, atau kehendak yang tidak diungkap di ruang terang.
Mengapa Infrastruktur Publik Tidak Bisa Mengandalkan Skema B2B
Untuk memahami keganjilan ini, kita perlu kembali ke dasar pengertian infrastruktur. Infrastruktur bukan sekadar benda fisik—rel, kereta, jalan, pelabuhan, bandara. Infrastruktur adalah pondasi material dari aktivitas sosial dan ekonomi. Ia adalah mesin tak terlihat yang membuat seluruh kehidupan modern bergerak.
Karena itu, infrastruktur memiliki tiga karakter utama:
Pertama, biaya investasi awal sangat tinggi. Infrastruktur besar memerlukan modal awal yang tidak bisa dikembalikan dalam waktu singkat. Kedua, manfaatnya bersifat eksternal dan jangka panjang. Infrastruktur menciptakan manfaat tak langsung: kenaikan produktivitas, pengembangan kawasan, penguatan nilai lahan, peningkatan konektivitas. Manfaat ini tidak dapat dimasukkan ke dalam tiket atau tarif. Ketiga, risiko proyek harus ditanggung negara, bukan swasta. Karena manfaat yang muncul bergantung pada dinamika makro—pertumbuhan ekonomi, migrasi tenaga kerja, kebijakan tata ruang, pola permukiman—yang semuanya berada di luar kontrol pelaku usaha.
Maka dalam teori pembangunan infrastruktur dunia, peran negara adalah sentral. Negara memastikan kelangsungan proyek, menjamin pembiayaan, dan menyerap risiko jangka panjang. Karena itu, tidak ada satu pun negara yang membangun kereta cepat dengan skema B2B murni. Tidak di Jepang. Tidak di Prancis. Tidak di China. Tidak di Spanyol. Tidak di Jerman. Tidak di Amerika Serikat ketika mencoba California High-Speed Rail.
Semua proyek ini menyertakan dukungan fiskal negara.
Contoh Internasional dan Pembelajaran Penting
Ketika Jepang membangun Shinkansen pertama pada 1964, proyek itu tidak menguntungkan selama 30 tahun pertama. Namun Jepang menyiapkan integrasi tata ruang kota, mendorong konsentrasi bisnis di stasiun, dan menciptakan model Transit-Oriented Development (TOD) yang kuat. Hari ini, Jepang menuai manfaat ekonomi jangka panjang yang sangat besar—tetapi itu bukan keuntungan tiket, melainkan pertumbuhan nilai kawasan.
Prancis dengan TGV juga menunjukkan pola serupa: negara membiayai konstruksi infrastruktur dasar (rel, terowongan, stasiun). Operator kereta hanya mengelola operasional. Kerugiannya diserap negara sebagai public service obligation.
China sendiri, yang menjadi acuan Whoosh, membiayai kereta cepat melalui BUMN yang dijamin negara. Utang mereka adalah sovereign-backed—artinya tetap ditopang APBN dan kebijakan fiskal pusat. Meski terlihat B2B, pada praktiknya China menjalankan model G2G terselubung dengan kontrol penuh negara atas risiko. Karena itu, ketika Indonesia memilih B2B tanpa jaminan fiskal eksplisit, itu bukan hanya langkah yang tidak lazim—itu anomali global.
Pertanyaan tak Mungkin Diabaikan: Mengapa Tidak Memilih Jepang?
Jika benar Whoosh adalah investasi sosial, maka skema Jepang adalah pilihan yang paling rasional:
– bunga ±0,1%
– tenor 40–50 tahun
– risiko fiskal minimal
– tata kelola sangat transparan
Namun pemerintah justru memilih:
– bunga ±3–4%
– tenor lebih pendek
– risiko pada BUMN
– ruang negosiasi kabur
Di titik ini, jawaban teknis tidak lagi cukup. Kita sedang memasuki wilayah desain kepentingan. Skema Jepang memiliki kontrol audit yang ketat, standar akuntabilitas tinggi, dan meminimalkan ruang untuk rente dan manipulasi biaya. Skema China memberi ruang yang lebih besar untuk mark-up, perubahan kontrak, penilaian ulang biaya, dan struktur pembiayaan yang kabur.
Dengan kata lain:
Skema Jepang lebih menguntungkan negara. Skema China lebih menguntungkan elite. Dan di sinilah mens rea itu bersemayam: Keputusan yang tidak mengikuti logika ekonomi, tetapi logika rente.
Kegagalan Desain-Beban Sepanjang Usia
Hari ini, Whoosh tampak megah. Ia cepat, modern, dan memukau. Tetapi di balik itu:
– biayanya membengkak dari ±80 triliun menjadi ±126 triliun
– konsorsium BUMN kini menanggung utang besar dengan pendapatan yang tidak mampu menutup bunga
– negara harus turun tangan pada akhirnya
Ketika hari itu tiba, pilihan-pilihan politik akan tampak dalam wujud yang paling telanjang:
– subsidi sosial dipotong
– pajak dinaikkan
– belanja kesehatan dan pendidikan dikurangi
– APBN dialihkan menyelamatkan proyek yang sejak awal salah desain
Dan rakyat akan bertanya:”Mengapa tidak ada yang memperingatkan kita? Jawabannya keras: “Sudah banyak yang memperingatkan.” Namun suara mereka dikalahkan oleh ketidak-pedulian penguas dan gemuruh mesin yang meluncur di rel.
Kita Tidak Dikejar Masa Depan, Kita Dihajar Masa Lalu. Lagi dan Lagi.
Whoosh bukan sekadar kereta. Ia adalah simbol bagaimana kekuasaan dapat mengemas keputusan yang tidak rasional menjadi sesuatu yang tampak mulia. Yang gagal bukan teknologinya. Yang gagal adalah kejujurannya.
Kita memang sudah membangun kereta yang melaju 350 km/jam. Tetapi yang tidak kita bangun adalah cara negara berpikir dengan jernih.
Dan sekarang pekerjaan terpenting bukanlah mengoperasikan kereta itu. Tetapi mengungkap motif di balik pilihannya—agar negara tidak lagi berlari tanpa arah di atas rel yang sedang retak.[ ]
*Penulis berijasah asli dari Jurusan Studi Pembangunan FE-Unpad; Anggota Komite Eksekutif KAMI; Ketua Komite Kajian Ilmiah Forum Tanah Air