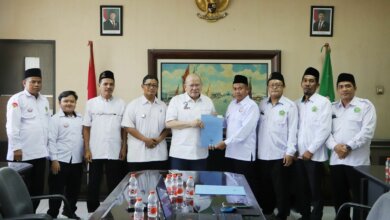Presiden Prabowo mempunya visi dan kemauan besar. Ia berdiri di panggung kebesaran, menebar janji tentang pagi yang lebih cerah setelah malam panjang. Namun, di balik teriakan visi itu, masih membayang wajah-wajah lama: politisi dan birokrat penjaga kemapanan yang tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya berganti seragam, berganti jargon, seperti musim yang datang silih berganti—ramah menyambut pemimpin baru, sambil menata ulang catur kekuasaan dengan kepiawaian lama.
Oleh : Yudi Latif
JERNIH– Lawatan demi lawatan ke berbagai negara, untuk menguatkan simpul diplomasi Indonesia dan muruah kepemimpinannya di panggung global, dengan pidato-pidato hebat yang menuai pujian, sudah cukup menjadi catatan pembuka kepemimpinan Presiden Prabowo. Namun, di balik gemerlap panggung luar negeri itu, rakyat di Tanah Air masih menunggu jawaban atas rundungan persoalan nyata: kebocoran anggaran, keborokan birokrasi, perburuan rente dalam pelayanan publik dan bantuan sosial, pelemahan kualitas penyelenggara negara, hingga biaya hidup yang kian mencekik.
Negeri ini tidak cukup ditopang senyum diplomasi di luar negeri, tetapi menuntut langkah nyata dalam membenahi distorsi dalam tata kelola negara sebagai wahana pengungkit kebajikan dan kebahagiaan publik.
Sinyal ketidakpuasan rakyat mulai menyeruak. Ledakan aksi demonstrasi belakangan ini adalah tanda bahwa arus bawah tidak lagi sabar menunggu, bahwa keresahan sehari-hari mulai mengkristal menjadi energi perlawanan. Bila suara-suara ini terus diabaikan, bukan mustahil Indonesia bisa mengikuti jejak Nepal—di mana kegagalan elite membaca denyut rakyat berujung pada ledakan perubahan yang tak terbendung. Semoga negeri ini tidak sampai ke sana; tetapi tanda-tanda zaman selalu patut dibaca sebelum terlambat.
Memang tak diragukan, Presiden Prabowo mempunya visi dan kemauan besar. Ia berdiri di panggung kebesaran, menebar janji tentang pagi yang lebih cerah setelah malam panjang. Namun, di balik teriakan visi itu, masih membayangi wajah-wajah lama: politisi dan birokrat penjaga kemapanan yang tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya berganti seragam, berganti jargon, seperti musim yang datang silih berganti—ramah menyambut pemimpin baru, sambil menata ulang catur kekuasaan dengan kepiawaian lama.
Begitulah nasib gagasan besar di negeri ini: sering tertahan di meja-meja tua, tersandera kebiasaan usang, menguap dalam rapat yang bertele-tele. Sebelum kebijakan baru sampai ke rakyat, ia sudah layu di perjalanan, berubah menjadi kompromi yang mengerdilkan. Visi dan kemauan itu akhirnya hanya mengaum di atas kertas. The devil is in the detail, kata pepatah. Dan detail itulah yang justru sering kita abaikan.
Kita sudah melihat gejalanya. Pemberitaan viral tentang keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta rekening-rekening bansos fiktif hanyalah puncak dari gunung es. Di kedalaman, ada moral hazard yang menjalar, ada birokrasi gemuk yang berkarat, ada patrimonialisme yang masih menguasai denyut nadi kekuasaan. Birokrasi kita luas cakupannya, tapi lemah daya tegaknya (enforcement) dan buruk kinerjanya. Elite penguasa kita cenderung makin semenjana dalam kualitas, namun makin rakus dalam kepentingan. Aparatur negara kita seperti tubuh tambun yang ringkih: gampang lelah, sulit berlari, gemar menyalahkan keadaan. Negara Indonesia terjebak dalam mesin birokrasi pemerintahan yang rakus anggaran tapi miskin prestasi.
Jika negeri ini ingin benar-benar sehat, kita harus berani melakukan perampingan birokrasi negara secara terukur, menuju sebuah minimalist state—negara dengan postur dan rentang kendali yang lebih susut, namun efektif dengan daya tegak hukum yang kuat. Negara semacam ini tidak tambun oleh pegawai dan biaya rutin, tidak berlimpah dengan keruwetan regulasi, dan tidak larut mengatur perkara-perkara remeh. Sebaliknya, ia hadir dengan ketegasan hukum, kejelasan arah kebijakan, serta kebajikan pelayanan publik yang bersih, adil dan memakmurkan. Singkatnya, negara yang ringkas dalam struktur tetapi tangguh dalam fungsi; sederhana dalam rupa, namun berwibawa dalam daya mengabdi kepada warganya.
Perlu pembedahan besar
Namun, enforcement tidak akan pernah kuat bila rantai terlemah, yakni aparatur penegak hukum, tetap keropos. Di titik inilah kepemimpinan sejati diuji: apakah berani menempuh jalan pembedahan besar, atau hanya menempelkan plester di luka bernanah.
Dunia sudah memberi teladan. Di Georgia, Presiden Mikheil Saakashvili berani membubarkan kepolisian lalu lintas yang terkenal korup, menggantinya dengan aparat baru hasil seleksi ketat. Ukraina pasca-Revolusi Euromaidan pun menempuh langkah serupa setelah kejatuhan Yanukovych. Di Meksiko, reformasi kepolisian dijalankan demi merebut institusi dari cengkeraman kartel narkoba. Polandia pun berani membedah sistem peradilan, karena sadar akar masalahnya bersemayam di sana.
Namun, membongkar bukan sekadar mengganti. Reformasi bukan ajang bagi-bagi kursi, bukan pula rotasi wajah di balik meja birokrasi. Ia harus menyentuh jantung sistem: menegakkan profesionalitas, menjamin transparansi, memastikan akuntabilitas. Jika tidak, reformasi hanya akan jadi arak-arakan kosong—ramai di awal, senyap di hasil. Banyak reformasi gagal karena hanya mengganti orang tanpa membenahi sistem; laksana mengganti sopir tanpa memperbaiki rem mobil yang blong.
Lebih dari itu, pembaruan juga harus menyentuh kultur. Aparatur hukum yang baru tidak akan berarti bila mentalitas lama masih bercokol, bila integritas dianggap barang mewah, bila jabatan dilihat semata ladang rente. Maka, reformasi sejati menuntut ekosistem: pembenahan institusi, pengawasan publik yang efektif, serta kultur masyarakat yang tidak permisif pada pelanggaran hukum.
Dalam ekosistem itu, pers kritis memegang peran penting. Ia menjadi cermin yang memantulkan wajah kekuasaan apa adanya, sumber informasi alternatif di luar lingkaran para pembisik. Tanpa pers yang bebas, presiden hanya akan hidup dalam gema pujian dan laporan yang disaring. Karena itu, penekanan atau ”pengucilan” terhadap pers kritis bukan saja mengkhianati demokrasi, tetapi juga kontraproduktif terhadap agenda reformasi. Sebab, hanya dengan ruang kritik yang sehat, bangsa dapat menegakkan hukum dengan wibawa dan membangun negara yang benar-benar beradab.
Pemberdayaan komunitas dan swasta
Saat postur dan cakupan negara dirampingkan, banyak urusan publik justru dapat ditangani lebih baik dengan memberi ruang partisipasi yang luas bagi komunitas dan dunia usaha. Bermutualismelah dengan swasta, tetapi bukan dalam rupa kolusi dan nepotisme, melainkan melalui pembagian peran yang proporsional dan sehat. Prinsipnya, negara tidak harus selalu hadir dengan tangan yang menguasai, melainkan dengan kebijakan yang mengarahkan, mengatur, dan mengawasi.
Contoh bisa dilihat di Denmark. Pemerintah memang berkewajiban menyediakan angkutan gratis bagi pelajar, tetapi kewajiban itu tidak harus diwujudkan dengan membangun armada angkutan negara sendiri. Negara memberi ruang bagi perusahaan swasta untuk berperan, sementara pemerintah fokus menetapkan standar, memastikan kualitas, dan menjamin aksesibilitas. Dengan begitu, beban negara untuk menggaji pegawai baru dan memelihara armada—yang hanya akan membuat birokrasi dan pembiayaan kian tambun—dapat dihindari.
Hal yang sama bisa diterapkan pada program MBG. Agar tidak tergelincir menjadi bancakan proyek para pemburu rente yang ujungnya melenceng dari tujuan mulia memberi gizi baik bagi para pelajar, pemerintah perlu membuka ruang partisipasi komunitas dan pengusaha lokal. Misalnya, pelibatan komite kesejahteraan sekolah, koperasi lokal, kelompok tani, hingga UMKM penyedia bahan makanan.
Distribusi pemasok makanan pun sebaiknya diarahkan ke komunitas-komunitas terdekat dengan sekolah: satu komunitas melayani satu sekolah. Dengan begitu, rantai pasok menjadi lebih pendek, penanganan lebih terkendali, dan risiko menumpuknya pasokan yang membuat masakan cepat busuk dapat dihindari. Model ini bukan hanya memastikan makanan tetap segar dan sesuai standar gizi, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal dan partisipasi inklusif dengan menghidupkan dapur-dapur masyarakat di sekitar sekolah.
Pemerintah dalam hal ini cukup berperan menetapkan standar gizi, mekanisme pengawasan, serta transparansi anggaran. Eksekusi lapangan dilakukan oleh komunitas yang memang memahami kebutuhan daerah dan lingkungan sekolahnya. Dengan demikian, MBG tidak sekadar program Makan Bergizi Gratis, melainkan juga instrumen untuk memperkuat gizi generasi muda, menggerakkan ekonomi rakyat, serta mempererat ikatan sosial antara sekolah dan komunitasnya.
Atau, jika ingin lebih terkendali, program MBG bisa saja ditangani langsung oleh keluarga. Pemerintah cukup mentransfer bantuan kepada keluarga-keluarga yang betul-betul membutuhkan sehingga orangtua dapat menyiapkan makanan bergizi sesuai selera dan budaya makan anak-anak mereka. Cara ini sekaligus memperkuat peran keluarga sebagai lingkar pertama pendidikan dan kasih sayang.
Bahkan, pemerintah juga bisa menimbang ulang: apakah dana yang begitu besar untuk MBG tidak lebih bermanfaat bila dialihkan untuk menjamin pendidikan gratis setidaknya hingga jenjang sekolah menengah atas, yang sungguh-sungguh ditegakkan—tanpa berbagai ”pungutan liar”. Pendidikan yang benar-benar bebas biaya, dari pintu masuk hingga pintu keluar, akan menjadi jaminan keadilan sosial yang lebih berjangka panjang daripada sekadar sepiring nasi yang cepat habis.
Dengan begitu, pilihan kebijakan tidak sekadar berhenti pada soal ”gratis atau tidak gratis”, melainkan bagaimana memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan negara benar-benar menguatkan masa depan anak-anak bangsa, entah melalui gizi yang sehat, entah melalui akses pendidikan yang terbuka, atau keduanya sekaligus.
Menuju revolusi tata kelola
Dari titik inilah kita tiba pada persoalan yang lebih besar: bagaimana negara menata ulang dirinya agar tetap relevan dengan tantangan zaman. John Micklethwait dan Adrian Wooldridge dalam “The Fourth Revolution” (2014) menjelaskan bahwa sejarah kenegaraan pada dasarnya adalah sejarah perombakan berulang, sebagai respons atas ekses negatif dari watak negara sebelumnya.
Pada abad ke-17, Hobbes membayangkan negara sebagai Leviathan perkasa, dengan kekuasaan absolut untuk meredam kekacauan. Tetapi absolutisme itu melahirkan represi sehingga pada abad ke-18 dan 19 muncul revolusi demokrasi yang menekankan akuntabilitas, meritokrasi, dan kebebasan individu sebagai koreksi.
Lalu, ketika negara liberal melahirkan ketimpangan sosial, abad ke-20 menghadirkan negara kesejahteraan, dengan jaring pengaman untuk melindungi warga dari derita. Namun, proteksi yang semula dimaksudkan sebagai penopang justru menjadi bantalan empuk: memberi rasa nyaman sesaat, tetapi membuat negara tambun, lamban, dan kehilangan kelincahan.
Pada tahap inilah dunia memasuki revolusi keempat yang menuntut negara berhenti menjadi pengasuh serba hadir, dan bertransformasi menjadi mitra yang cerdas. Negara mesti melepaskan beban yang bukan urusannya, menjual aset yang tak perlu dikelola sendiri, memangkas subsidi yang hanya menguntungkan kelompok kaya atau terhubung secara politik, serta menata ulang tunjangan agar benar-benar tepat sasaran bagi yang membutuhkan.
Dengan kata lain, negara perlu bergeser dari janji serba melindungi—yang kerap melenceng menjadi arena korupsi dan perburuan rente—menuju peran baru: regulator yang tangguh, fasilitator yang adil, dan pengawal hak-hak warga yang esensial.
Bagi Indonesia, makna revolusi keempat ini sangat terang: subsidi tidak boleh terus-menerus dikurung dalam pola konsumsi instan yang memelihara ketergantungan dan rente politik. Subsidi harus digeser menjadi insentif produksi yang memberdayakan, mendidik rakyat naik ke kurva belajar yang lebih tinggi, dan menumbuhkan nilai tambah secara berlapis. Dengan cara itu, negara tidak lagi menjadi induk semang yang memanjakan (melemahkan), melainkan pemandu yang memampukan. Hanya dengan transformasi semacam ini, kemakmuran dapat tumbuh lebih luas, inklusif, dan berjangka panjang.
Namun, persoalannya, apakah kita berani melangkah ke sana? Ataukah kita masih betah hidup dalam ilusi negara pengasuh, yang sibuk menyalurkan subsidi konsumtif demi meredam gejolak sesaat, sementara akar masalah dibiarkan mengeras? Kita tahu, terlalu lama bergantung pada ”ibu negara” yang cerewet justru membuat anak-anaknya manja, tidak pernah belajar berjalan sendiri.
Revolusi keempat, sebagaimana ditunjukkan Micklethwait dan Wooldridge, menuntut keberanian untuk menanggalkan jubah usang Leviathan tambun atau sekadar negara liberal yang membiarkan ketimpangan. Yang diperlukan adalah negara pelayan dengan postur yang ramping namun efektif dan cerdas: regulator yang adil, mitra yang memberdayakan, dan pengawal hak-hak dasar warga. Jika tidak, kita hanya akan terjebak dalam arak-arakan reformasi palsu—ramai di retorika, tetapi senyap di hasil—sementara rakyat tetap terperangkap dalam kemiskinan yang dipelihara.
Pada akhirnya, negara yang relevan bukanlah negara yang sibuk mengurus semua hal, tetapi negara yang tahu kapan harus hadir dan kapan memberi ruang bagi warganya untuk tumbuh. Itu bukan sekadar pilihan teknokratis, melainkan ujian kepemimpinan: apakah kita ingin rakyat menjadi subyek yang berdaya, atau terus diperlakukan sebagai obyek yang perlu ditenangkan dengan bantal subsidi.
Kini, Presiden Prabowo berada di persimpangan sejarah. Akankah ia dikenang sebagai pemimpin yang berani melakukan pembedahan besar, atau sekadar menambah catatan panjang janji-janji yang layu di tengah jalan? Tepukan dari luar bukannya tidak penting; ia bisa menghibur sesaat, memberi rasa hangat seperti sorak penonton di tepi jalan.
Namun, derita dan kekacauan di dalam negeri tak mungkin di atasi hanya dengan tepukan. Rakyat tak hidup dari sanjungan, melainkan dari kepastian hukum, keadilan, dan pelayanan publik yang baik. Karena itu, yang ditunggu rakyat bukanlah derai aplaus diplomatik, melainkan langkah konkret yang menyehatkan rumah sendiri.[ ]
Yudi Latif, Cendekiawan dan Budayawan
*Sebelumnya dimuat Kompas, 1 Oktober 2025. Dimuat ulang atas izin penulis.