Stay at Home, Mengenang Suasana Politik 55 Tahun Lampau

Adagium “my loyalty to my party ends, where my loyalty to my country begins” (loyalitasku kepada partaiku selesai tatkala loyalitas kepada negara dimulai), yang sering diucapkan para presiden Amerika Serikat, tidak berlaku di Indonesia
Oleh : Usep Romli HM
Sedang “nyingkrem” di rumah (stay at home), pikiran melayang ke mana-mana. Selain memikirkan bekal sehari-hari yang makin menipis, juga memikirkan situasi dan suasana menegangkan. Maklum ancaman virus Covid-19 tak terdeteksi.
Tiba-tiba ingatan melayang ke suasana 55 tahun lampau. Sama mencemaskan dan menegangkan. Bukan karena ancamam virus penyakit. Melainkan akibat kondisi politik nasional yang terus memanas.
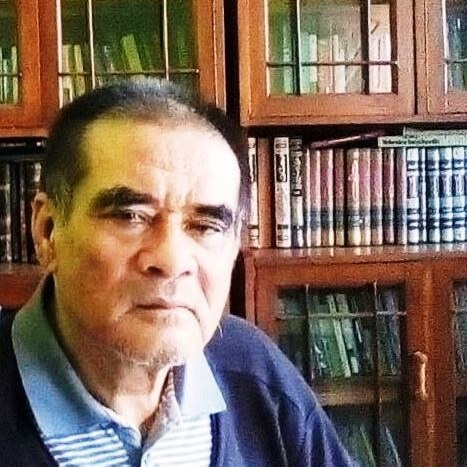
Semua mencapai titik kulminasi tanggal 30 September 1965. Sebuah tragedi politik dan kemanusiaan, meledak. Terkenal dengan sebutan “G-30-S”. Malam itu, di Jakarta, enam jendral dan seorang letnanTNI AD tewas dibunuh segerombolan orang. Partai Komunis Indonesia (PKI) dituding sebagai dalang peristiwa berdarah itu.
Presiden RI, Sukarno, kena imbas. Dikenakan tahanan rumah, hingga wafat tahun 1970. Jendral Suharto duduk di atas tahta kepresidenan, selama 32 tahun. Ia mengundurkan diri akibat tekanan reformasi, Mei 1998.
Peristiwa 55 tahun lalu itu, yang bermula dari “G-30-S”, menimbulkan dampak mengerikan. Para tokoh, anggota dan simpatisan PKI, baik di pusat maupun daerah, banyak yang terbunuh tanpa kubur. Meringkuk belasan tahun di penjara dan pembuangan, tanpa diadili.
Memang, setahun sebelum “G-30-S”, Indonesia dilanda hiruk pikuk politik luar biasa. Sikap Presiden Sukarno yang “anti neokolinialisme”, mendapat dukungan khalayak. Terutama melalui partai partai politik yang sejak 1960, segaris sehaluan dengan presiden. Hitam kata presiden, hitam kata parpol. Kekuatan Presiden Sukarno, yang di-back-up Angkatan Darat, sungguh luar biasa. 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan Dekrit berisi pembubaran Konstituante (MPR) hasil pemilu 1955, dan kembali ke UUD 1945. Rancangan UUD buatan Konstituante selama persidangan dua tahun (1957-1959), diabaikan begitu saja. Padahal, menurut Adnan Buyung Nasution dalam bukunya “Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio Legal atau Konstituante 1956-1959” (1995), Konstituante sebagai majelis pembuat undang-undang dasar merupakan satu bentuk nyata dari puncak perwujudan demokrasi untuk merumuskan, memberi landasan, dan membentuk negara Indonesia dengan pemerintahan yang konstitusional. Constitutonal government adalah konsep pemerintahan yang demokratis dan melindungi rakyat, tulis Buyung (hal.xxvi).
Setahun setelah dekrit, presiden membubarkan dua partai politik terkemuka. Masyumi (partai Islam pemenang pemilu 1955) dan Partai Sosial Indonesia (PSI), tempat para intelektual Indonesia terkenal, seperti Sutan Syahrir, Sumitro Djoyohadikusumo, Sujatmoko, Sutan Takdir Alisyahbana, dan lain-lain, berkiprah di bidang politik.
Dekrit dan pembubaran Masyumi dan PSI menjadikan Presiden Sukarno penguasa tunggal. Semua aparat dan unsur pemerintahan, termasuk parpol di DPR, semua “sumuhun dawuh” alias “yesman” pada Sukarno. Semua mendekat, dan “menjilat” Paduka Yang Mulia (PYM), sebutan resmi untuk Presiden Sukarno kala itu.
Parpol yang paling berhasil mengambil hati presiden, adalah PKI. Hampir semua program dan gagasan PKI disetujui Bung Karno. Antara lain Manipol (Manifesto Politik), Nasakom (Nasional, Agama, Komunis). Kedudukan Manipol dan Nasakom bahkan dianggap melebihi Pancasila dan UUD 1945.
Suasana 1964-1965 begitu gempita oleh kegiatan politik bernada provokatif. Indonesia keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Menyatakan “berdikari” (berdiri di atas kaki sendiri). Mendirikan blok kekuatan baru “Nefos” (New Emerging Forces). Negara-negara Barat dianggap “Oldefos”. Kekuatan tua, pengusung “neokolonialisme-imperialisme” (penjajahan baru). Menentang prakarsa Inggris memisahkan Singapura dengan Malaya, yang menghasilkan negara baru, Malaysia.
Bung Karno didukung semua parpol yang mengaku progresif revolusioner, menyatakan perang kepada “nekolim”, khususnya Malaysia, yang dianggap proyek “nekolim”. Slogan “Ganyang Malaysia” menggema di mana-mana. Pemimpin Malaysia, Tengku Abdurahman, menjadi sasaran ejekan sebagai “antek nekolim”.
Parpol yang mendapat udara bebas, mengklaim sebagai pelaksana “amanat penderitaan rakyat” (Ampera). Para pemimpin parpol mengaku memiliki “ikatan suci” dengan rakyat. Padahal waktu itu, rakyat dalam keadaan sengsara. Susah sandang susah pangan, infrastruktur rusak berat, kesehatan dan kebutuhan hidup layak di bawah standard, dll.
Tapi para elit penguasa dan elit politik tidak peduli. Mereka asyik menikmati fasilitas yang berasal dari pajak. Menyelenggarakan pesta-pesta mewah, membangun proyek “mercusuar” yang tak berkaitan dengan perut rakyat. Keluyuran dengan sedan mewah Impala.
Korupsi merajalela di berbagai sektor. Dilakukan para aparat atas tuntutan parpol. Sebab para aparat itu sebagian besar anggota parpol. Sehingga mereka dibebani kewajiban “setor” mengisi kas parpol. Hampir di semua kementrian terjadi korupsi.
Termasuk di Kementrian Agama. Menteri Agama Wahib Wahab ditangkap Kejaksaan Agung. Setelah kasusnya divonis pengadilan, masih harus menghadapi tuntutan kasus lain. Namun mendapat abolisi (penghapusan hukuman) atas permohonan KH Saifuddin Zuhri, Menteri Agama 1962-1967 (KH Saifuddin Zuhri “Berangkat dari Pesantren”, 1987, hal.530-531).
Kasus-kasus itu terjadi akibat para pejabat negara harus mematuhi “garis partai” yang mencalonkannya. Walaupun sudah menjabat di eksekutif dan legislatif, mereka tetap dianggap “petugas” partai.
Adagium “my loyalty to my party ends, where my loyalty to my country begins” (loyalitasku kepada partaiku selesai tatkala loyalitas kepada negara dimulai), yang sering diucapkan para presiden Amerika Serikat, tidak berlaku di Indonesia. Padahal para pejabat itu sama-sama dicalonkan oleh partai masing-masing. Di AS dicalonkan Partai Demokrat atau Partai Republik. Setelah terpilih(terutama menjadi presiden) mereka tidak lagi “mengabdi” kepada partainya, tapi mengabdi kepada bangsa dan negara.
Begitulah susana, situasi dan kondisi Indonesia pra-G-30-S, didominasi parpol-parpol yang berlomba mencari dana untuk partai, dan melakukan “kultus individu” terhadap presiden. Sementara rakyat yang diaku-aku sebagai simpul “ikatan suci” terabaikan sama sekali. Parpol sibuk berebut kedudukan, berebut fasilitas, mulai dari rumah dinas hingga mobil mewah, tanpa mempedulikan kehidupan rakyat yang “kembang kempis”. Mereka menganggap rakyat cukup digelorkan semangat “revolusi belum selesai”, “ganyang itu ganyang ini” dan lain-lain yang sloganistis bombastis.
Itulah sekedar kenangan atau khayalan di tengah himpitan “stay at home” dan PSSB. Kenangan yang bermutu atau tidak, terserah orang menilai. [ ]







