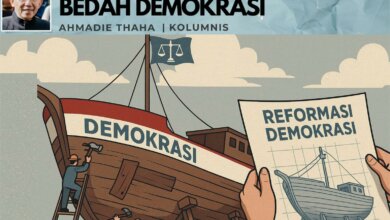Kita mengira, mengubah konstitusi sama artinya dengan mengubah nasib bangsa. Padahal konstitusi adalah wadah, bukan isi. Seperti vas tanpa bunga, teks hukum akan hampa tanpa jiwa hukum. Dan jiwa hukum tidak ditentukan oleh perumusnya, tapi oleh mereka yang menjalaninya. Dulu kita mengira bahwa pembatasan masa jabatan presiden akan mencegah kekuasaan yang rakus. Tapi kini, kekuasaan menemukan jalannya sendiri: melalui putra, menantu, atau pembentukan koalisi superjumbo yang menelan oposisi dalam sekali suap.
Oleh : Radhar Tribaskoro
JERNIH— Ada orang yang percaya pada mantra. Pada susunan kata-kata yang konon bisa menggerakkan dunia. Tapi sejarah tak pernah tunduk kepada bunyi. Ia berjalan dengan kaki—dan kadang, dengan luka.
Kita sudah berkali-kali mengubah konstitusi. Dan setiap kali itu pula kita seolah ingin percaya bahwa perubahan teks akan menyulap bangsa ini menjadi lebih adil, lebih demokratis, lebih beradab.
Tapi kekuasaan, seperti pohon beringin yang akarnya menembus jauh ke bawah tanah, tak goyah oleh ganti pasal. Kita bukan kekurangan kalimat. Kita kekurangan keberanian.
Sejak 1945, kita telah mengalami empat jenis konstitusi: UUD 1945 asli, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, lalu kembali ke UUD 1945 yang diamandemen. Kita juga telah membentuk lebih dari 40 kabinet. Nama-nama berganti. Slogan diperbarui. Struktur dirombak.
Namun ada yang tak pernah berubah: watak kekuasaan. Ia tetap tegak seperti menara tanpa jendela, memandang rakyat dari ketinggian. Di dalamnya, suara-suara dikurung, bahkan yang paling lirih sekali pun.
Bukankah konstitusi bisa menjadi sekadar jubah? Indah secara tekstual, tapi menutupi tubuh yang penuh luka dan dendam. Sejarah kita memperlihatkan itu. Soeharto, misalnya, memerintah selama lebih dari tiga dekade dengan bersandar pada UUD 1945 yang sama. Ia tidak mengganti teks, tapi ia mengubah hidup orang banyak.
Apa gunanya teks jika kekuasaan tidak dituntun oleh nurani? Apa arti pasal-pasal jika hukum berjalan dengan mata tertutup sebelah?
Kita mengira, mengubah konstitusi sama artinya dengan mengubah nasib bangsa. Padahal konstitusi adalah wadah, bukan isi. Seperti vas tanpa bunga, teks hukum akan hampa tanpa jiwa hukum. Dan jiwa hukum tidak ditentukan oleh perumusnya, tapi oleh mereka yang menjalaninya.
Dulu kita mengira bahwa pembatasan masa jabatan presiden akan mencegah kekuasaan yang rakus. Tapi kini, kekuasaan menemukan jalannya sendiri: melalui putra, menantu, atau pembentukan koalisi superjumbo yang menelan oposisi dalam sekali suap.
Dulu kita berpikir bahwa pemilu langsung akan memperkuat suara rakyat. Tapi nyatanya, pemilu yang mahal justru memperkuat suara uang. Partai menjadi pasar, dan rakyat jadi penonton, kadang jadi pelanggan. Jarang sekali jadi pemilik.
Mengapa perubahan tak pernah benar-benar datang? Mungkin karena kita membayangkan perubahan seperti mengganti cat dinding rumah. Hari ini merah, besok hijau, lusa mungkin hitam.
Tapi yang retak bukan warna dindingnya. Yang rapuh adalah fondasi. Dan fondasi itu bernama: kesadaran kolektif.
Ia tidak tercetak di lembar konstitusi. Ia lahir dari pengalaman, dari luka yang dikenang, dari keberanian untuk menolak lupa. Ia tumbuh pelan, kadang ditumbangkan oleh waktu, kadang dikubur hidup-hidup oleh kekuasaan.
Kesadaran kolektif bukanlah kumpulan pidato. Ia adalah ingatan yang tak diamputasi. Ia adalah pertanyaan yang tak berhenti dikemukakan: siapa yang berkuasa, mengapa ia berkuasa, untuk siapa kekuasaan itu bekerja?
Kadang kita lupa: bahwa demokrasi bukanlah sebuah tujuan, tapi proses yang tak pernah selesai. Ia seperti taman yang harus dirawat saban hari. Bukan ditinggalkan lalu diklaim sebagai “sudah jadi”.
Demokrasi bukanlah teks. Ia adalah praktik. Ia adalah bagaimana kekuasaan dikoreksi, bukan disucikan. Ia adalah bagaimana minoritas diberi tempat, bukan disingkirkan. Ia adalah bagaimana rakyat ikut menentukan arah, bukan hanya memilih perwakilan.
Tapi kita hidup dalam zaman yang menyukai representasi tanpa partisipasi. Di mana legitimasi dihitung dari jumlah kursi, bukan dari jumlah suara yang didengar. Di mana lembaga independen bisa dilumpuhkan hanya dengan satu revisi undang-undang.
Ada yang berkata: mari kita kembali ke UUD 1945 asli. Seolah-olah teks awal adalah rumah suci yang bisa menyembuhkan segala dosa politik kita. Tapi bukankah rumah itu pula yang pernah membiarkan kekuasaan tanpa kontrol selama 32 tahun?
Kembali ke UUD 1945 tanpa menumbuhkan budaya politik baru sama seperti kembali ke rumah lama dengan orang yang sama, dengan kebiasaan yang sama, dan dengan kekerasan yang sama. Kita hanya menukar kalender, bukan mengubah hari.
Yang kita perlukan bukan sekadar teks baru. Tapi sistem baru. Bukan dalam arti struktur lembaga, tapi dalam cara berpikir dan bertindak. Kita harus membangun kembali yang hancur: kepercayaan.
Percaya bahwa hukum bisa berpihak pada kebenaran, bukan pada kuasa. Percaya bahwa rakyat bukan beban, tapi sumber energi. Percaya bahwa kritik bukan penghinaan, tapi vitamin bagi kebijakan.
Tapi itu hanya mungkin jika pemimpin berani keluar dari lingkaran perlindungan. Jika rakyat berani menolak janji kosong. Jika sistem komunikasi politik dibuka untuk silang pendapat, bukan hanya siaran sepihak.
Luhmann menyebut sistem politik sebagai sistem komunikasi. Maka siapa yang menguasai struktur komunikasi politik, dialah yang akan memenangi pertarungan kekuasaan.
Tapi pertanyaan berikutnya lebih penting: siapa yang menentukan isi dari komunikasi itu? Jika media sudah dibeli, jika partai dikuasai segelintir elite, jika aparat hanya menjawab pada kekuasaan pusat, maka komunikasi itu tidak lebih dari gema. Bukan dialog.
Dan demokrasi tidak hidup dalam gema. Ia tumbuh dalam perdebatan, dalam kekisruhan yang produktif, dalam kegaduhan yang menjernihkan.
Kita harus menerima satu kenyataan pahit: perubahan tidak datang dari teks. Perubahan datang dari rasa muak yang memuncak, dari keteguhan yang tak bisa lagi dikompromikan. Kadang ia muncul dari orang-orang kecil yang tak pernah tampil di layar. Kadang dari generasi yang tak mau lagi dibohongi. Kadang dari krisis yang membuka kebusukan yang selama ini ditutup rapi.
Teks hanya penting jika dibaca dengan kemauan untuk berubah. Tanpa itu, ia hanya menjadi kitab yang dikeramatkan tapi dilanggar saban hari.
Dalam puisi Chairil Anwar, ada satu baris yang menggugah: “Kami sudah coba apa yang kami bisa, tetapi kerja belum selesai, belum apa-apa.”
Mungkin di situlah kita berdiri hari ini. Di tengah kerja yang belum selesai, dengan tantangan yang justru makin kompleks. Karena itu, marilah kita berhenti percaya pada keajaiban teks. Marilah kita mulai membangun sistem yang hidup. Bukan sistem yang hanya hidup di atas kertas.
Teks memang penting. Tapi ia bukan pusat segalanya. Perubahan, pada akhirnya, bukan soal konstitusi. Perubahan adalah soal keberanian. [ ]
Bekasi, 26 Juli 2025