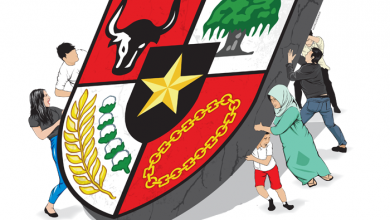“Siapakah Guru Anda? Para Nabi Atau Justru Namrud dan Fir’aun?”tanya Hatim ‘Si Tuli’

Saya tidak ingin hanyut dalam jebakan pertanyaan itu, maka saya cukup menjawabnya, “Saya akan makan kematian, mengenakan kain kafan, dan tinggal di liang lahat.”
JERNIH—Pada suatu ketika, dalam perjalannya sebagai sufi pengelana, Hatim singgah di salah satu kota tempat hidup seorang ulama terkenal bernama Muhammad ibn Muqatil.
Percaya bahwa memandang seorang ulama adalah ibadah, Hatim pun berkunjung ke rumah Ibn Muqatil, ulama tersebut. Ternyata rumahnya megah, luas dan indah. Hatim tercenung. Dia menemukan sang ulama tidur di kamar yang sangat mewah. Seorang pelayan selalu siap untuk mengipasi kepalanya jika Muqatil kepanasan. Hatim kemudian dipersilakan duduk oleh sang ulama, namun Si Tuli itu menolak.
Ibnu Muqatil lalu bertanya,”Apa keperluan tuan kemari?”
“Tuan Syekh,” kata Hatim,” Ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Dari manakah Tuan Syekh memperoleh ilmu ini semua?”
“Tentu saja dari orang-orang yang dapat saya percaya. Mereka mendapat ilmunya dari para sahabat Nabi, kemudian sahabat itu mendapat ilmu dari Rasulullah, dan Rasulullah mendapat ilmunya dari Jibril, dan Jibril dari Allah SWT, Ya Hatim!”
Hatim kembali bertanya,” Apakah dari guru-guru Tuan semua itu, dari para Sahabat, dari Nabi SAW, dari Jibril dan dari Allah tersebut, Tuan mendapatkan pelajaran bahwa memiliki rumah besar dan hidup mewah akan meninggikan derajat manusia di hadapan Allah?”
Sesaat Ibnu Muqatil terkesiap, tetapi ia masih berusaha menjawab. “Tentu tidak, ya Hatim. Bahkan mereka mengajari kita untuk hidup zuhud, mencintai akhirat, menyayangi orang miskin. Dengan itulah orang akan mendapatkan kedudukan tinggi disisi Allah SWT.”
“Bila begitu, Tuan Syekh, siapakah guru Tuan sesungguhnya? Adakah mereka itu Nabi? Para sahabat Nabi? Orang-orang salih? Ataukah justru Fir’aun, Namrud, yang mendirikan gedung-gedung bertatahkan pualam?” kata Hatim.
Konon, sejak pertemuan dengan Hatim itu Muhammad ibn Muqatil jatuh sakit. Penduduk kota yang mengetahui peristiwa itu pun gempar dan mendatangi Hatim yang mereka dapati tengah berada dalam masjid.
Salah satu dari penduduk kota itu berkata kepada Hatim. “Wahai Hatim, datanglah ke Kota Qazwin. Di sana juga ada seorang ulama yang kehidupannya jauh lebih mewah dibanding Ibnu Muqatil. Namanya al-Thanafisi.”
Hatim pun berangkat ke Kota Qazwin, guna menjumpai sang ulama. Ia selalu percaya, memandang wajah seorang ulama adalah kenikmatan dan ibadah. Kepada ulama yang ternyata benar hidup dalam kemewahan itu Hatim minta diajarkan cara berwudhu yang benar, sesuai sunnah Rasulullah.
“Tuan Syaikh, saya akan berwudhu di hadapan Tuan. Mohon perbaiki cara berwudhu saya bila Tuan mendapatkan saya menyalahi sunnah Rasulullah dalam melakukannya,” kata Hatim, memohon dengan sopan.
Hatim pun mulai mengambil air, membasuh muka dan membasuh tangannya masing-masing empat kali.
“Hai!” seru Al Thanafisi,”Mengapa engkau berlebih-lebihan. Engkau tadi membasuh tanganmu empat kali.” Al Thanafisi menegur.
“Subhanallah,” kata Hatim. “Sesauk air Tuan anggap berlebihan. Sekarang bandingkan seluruh kemewahan yang telah Tuan miliki dan nikmati ini dengan contoh Rasulullah SAW. Apakah ini tidak berlebihan?”
Al-Thanafisi tidak menjawab. Kabarnya, ia tidak keluar keluar dari rumahnya selama 40 hari karena malu. Ia sadar tindakannya dalam menikmati hidup selama ini memang telah berlebih-lebihan.
Imam Ahmad bin Hanbal mendengar berita itu. Dia mendatangi Hatim dan minta nasihat. Imam besar ahli hadits yang juga pendiri mazhab Hambali itu tidak segan bertanya kepada Hatim. “Alangkah cerdasnya Hatim,” kata Imam Hambali penuh kekaguman.
**
Hatim pernah bernasihat kepada sahabatnya, dengan nasihat berikut:
-Tiada waktu pagi datang melainkan setan mencercaku dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggoda, “Apa yang akan kamu makan?” Apa yang akan kamu pakai? Di manakah kamu akan tinggal?”
Saya tidak ingin hanyut dalam jebakan pertanyaan itu, maka saya cukup menjawabnya, “Saya akan makan kematian, mengenakan kain kafan, dan tinggal di liang lahat.”
-Pernah suatu hari saya ditanya, “Tidakkah kamu menginginkan sesuatu?” Maka saya jawab, “Saya ingin selalu sehat dari pagi hingga malam hari”. Ditanyakan lagi,“Bukankah kamu sehat selama seharian?”
Saya jawab,“Sehat menurutku adalah tidak menjalankan dosa dari pagi hingga malam.”
-Saya pernah berada dalam suatu pertempuran. Pernah ditangkap oleh seorang tentara musuh, kemudian badan saya ditelentangkan untuk disembelih. Hati saya tidak merasa takut sedikit pun, bahkan saya menunggu keputusan Allah untukku. Ketika prajurit itu menghunus pedangnya untuk menyembelih diriku, tiba-tiba meluncur sebuah anak panah menembusnya sampai mati, sehingga ia terlempar dariku. Saya pun segera berdiri.
-Barang siapa memasuki mazhab kami, hendaklah ia bersedia menerima empat kematian. Mati putih karena lapar, mati hitam karena menanggung penderitaan dari manusia, mati merah karena berbuat ketulusan untuk melawan hawa nafsu, dan mati hijau karena fitnah. [ ]
Dari “Tadzkiratul Auliya”, Fariduddin Aththar