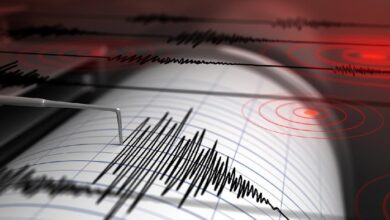Malin Kundang, Mualim Kondang
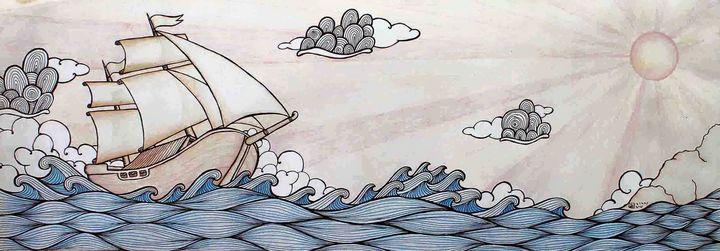
Batu Malin Kundang membawa masyarakat Minangkabau menjadi bermusuhan dengan laut yang membawa kebudayaan asing, berupa lupa pada bundo kanduang. Ia dikutuk oleh ibunya, sehingga tak bisa lagi meminta maaf kepada ibunya dan meminta ampun kepala Allah SWT. Dari namanya, Malin, tentu orang tahu bahwa itu adalah aksara Arab.
Oleh : Indra J Piliang *)
JERNIH–Bagi masyarakat Minangkabau, Pariaman tidak termasuk dalam kategori ranah (luhak). Ada tiga luhak di Minangkabau, yakni Luhak Lima Puluh Kota, Luhak Agam dan Luhak Tanah Datar.
Pariaman hanyalah rantau terdekat dari Luhak Nan Tigo. Kawasan Lembah Anai, misalnya, adalah perbatasan antara Darek dengan Rantau dalam cerita-cerita tambo. Sehingga muncul istilah, ikue darek, kapalo rantau. Kalau pun kini mobil bebas lalu lalang setiap hari, tidak demikian di zaman saisuak. Buktinya, terdapat Bukit Tambun Tulang di sekitar Lembah Anai, yakni kawasan tempat para parewa dan pandeka mempertaruhkan nyawa sebelum memasuki kawasan paling rimba dari bumi Pariaman.

Namun, dalam kaitannya dengan agama Islam, Pariaman adalah wilayah pertama yang ditempati oleh Syech Burhanuddin, ulama asal Aceh yang dipercaya sebagai pembawa agama Islam ke Minangkabau. Makam Syech Burhanuddin bertempat di Ulakan yang kini menjadi bagian dari Kabupaten Padang Pariaman.
Karena itu pula, Pariaman dikenal sebagai pusat dari nama-nama yang terkait dengan Syech Burhanuddin. Ada perguruan tinggi yang membawa nama ini, yakni Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syech Burhanuddin. Selain itu ada juga Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sumatera Barat. Keduanya terletak di Kota Pariaman. Keberadaan nama Syech Burhanuddin itulah yang menempatkan image bahwa masyarakat Pariaman adalah masyarakat relegius, terutama dikaitkan dengan tarekat Syattariyah.
Di masa kecil, saya sering mendengar pembicaraan soal tarekat demi tarekat ini. Tidak jarang orang-orang di Pariaman menuntut ilmu (mengaji) ke tempat-tempat lain. Perdebatan tentang hubungan manusia dengan Allah SWT berlangsung di banyak surau, terutama setelah semua orang tidur. Karena saya tinggal di Kampuang Tangah, Lansano, Sikucur Selatan, tentu ada perasaan bahwa orang yang tinggal di Pariaman jauh lebih maju dari kami. Kemajuan itu dilihat dari peralatan yang dimiliki dan dipakai, seperti kendaraan, telepon, sampai televisi.
Saya semakin mengenal Kota Pariaman ketika masuk SMA 2 Pariaman (1988-1991). Sama sekali tidak ada perasaan minder dari sisi ilmu pengetahuan, selain saya berasal dari keluarga berkekurangan. Jarang saya memiliki baju yang layak untuk dipakai dalam kegiatan non sekolah. Saya memasak sendiri di rumah kos, bersama Sahrul Chaniago, sesama jurusan Fisika yang kini jadi sahabat saya. Pagi ke pasar membeli kentang dan ikan asin, lalu memasaknya. Sepatu hanya satu, itu pun sobek dengan merk Dragon Fly.
Di akhir pekan saya kembali ke Kampuang Tangah, Kecamatan V Koto Kampuang Dalam. Terkadang, sungai banjir, sehingga terpaksa menunggu air surut selama berjam-jam. Tidak ada jembatan penyeberangan. Kalaupun ada ban bekas, itu pun yang memiliki tidak banyak orang. Kampung ibu saya memang baru dimasuki listrik pada tahun 2002 lalu, kemudian memiliki jembatan gantung tahun 2008. Alhamdulillah, sekarang sudah ada jembatan permanen, dibangun atas bantuan Kerajaan Oman pasca-gempa bumi hebat 2009.
*
Studi etnografis dan antropologis bisa saja membawa kita kepada mitos yang negatif. Salah satunya adalah sosok yang bernama Malin Kundang. Yang namanya mitos, hampir tidak ada yang bisa menyebutkan angka tahun kemunculan tokoh ini.
Yang anak-anak tahu–dan kini anak-anak itu sudah berkepala empat juga seperti generasi saya–adalah Malin Kundang Anak Durhaka. Emaknya seorang pencari kayu api. Zaman pencari kayu api belum berakhir sampai kini, terutama di daerah pegunungan. Yang mungkin makin sulit adalah mencari emak-emak yang mencari kayu api di area pesisir.
Dari kisahnya, orang-orang tahu–bahkan hingga Mamah Dedeh dalam satu acara televise-–- betapa Malin Kundang adalah anak yang sama sekali lupa akan ibunya yang miskin dan berkain buruk. Ia datang dengan wajah bak pangeran ke kampung halaman, dengan membawa seorang istri yang cantik, kapal besar, makanan enak, hingga intan permata dan kain sutra.
Ia adalah seorang pedagang yang berhasil. Keberhasilannya itulah yang membuat ayah mertuanya membekalinya dengan kapal besar untuk kembali ke kampung halamannya.
Padahal, ketika memutuskan untuk menjadi anak kapal di usia mudanya, ia perlu membeli baju sederhana dari hasil berjualan kayu emaknya. Emaknya tak tahan melihat anaknya begitu ingin bepergian dengan kapal besar, merantau ke negeri orang.
Ia bisa menyelinap ke dalam kapal. Hampir tak pernah ada kisah antara ia pergi dan ia pulang itu. Bagaimana nasibnya di kapal? Kenapa ia bisa tiba-tiba saja menjadi begitu kaya-raya di zaman yang sudah masuk berkemajuan? Ia juga bukan seorang ahli silat ataupun parewa yang memiliki tubuh tahan panas dan api. Ia pekerja biasa yang bermodalkan kejujuran dan kecekatan. Tak mungkin pula ia “membunuh” seseorang, hingga bisa menjadi orang nomor satu di kapal, yakni menjadi Nahkoda.
Yang orang tahu, Malin Kundang jadi batu, ketika terlalu dekat dengan laut dan menjadi saudagar muda yang memiliki kapal layar besar. Akibat perangainya yang buruk, Malin Kundang tidak hanya menjadi durhaka kepada ibunya, tetapi juga durhaka kepada alam Minangkabau secara luas.
Batu Malin Kundang membawa masyarakat Minangkabau menjadi bermusuhan dengan laut yang membawa kebudayaan asing, berupa lupa pada bundo kanduang. Ia dikutuk oleh ibunya, sehingga tak bisa lagi meminta maaf kepada ibunya dan meminta ampun kepala Allah SWT. Dari namanya, Malin, tentu orang tahu bahwa itu adalah aksara Arab.
Seyogianyalah mitos itu diruntuhkan atau ditafsirkan ulang. Tidak semua laut bisa membawa seseorang menjadi Malin Kundang. Pembangunan area yang berdekatan dengan laut, dengan visi maritim yang jelas, adalah cara untuk memecah batu Malin Kundang yang membebani mentalitas manusia Minangkabau. Yang pasti, Malin Kundang sebelum menjadi nakhoda, tentulah sudah menjadi mualim kapal yang kondang. Saking kondangnya, seorang saudagar phinisi dari Bugis menjadikannya sebagai menantu.
Lagi pula, tidak ada satu ayat pun dalam kitab-kitab suci yang menceritakan bahwa manusia bisa menjadi batu. Betul, ada cerita betapa Nabi Adam terbuat dari tanah liat dan Nabi Isa AS mampu menghidupkan orang mati dengan ekor lembu. Bahkan, ummat nabi-nabi yang membangkang seperti Fir’aun (ummat Nabi Musa AS), atau ummat Nabi Luth, ummat Nabi Nuh, hingga ummat nabi-nabi lainnya, tak pernah berubah menjadi batu, pohon atau yang lain. Mereka mengalami kematian ala manusia, terkena penyakit, diterjang air bah, ataupun tertimbun gempa.
Kalau pun ada yang menjadi batu, tentunya manusia-manusia penghuni Kota Pompeii akibat meletusnya Gunung Vesuvius. Mereka menjadi batu akibat terkena lava cair. Tak mustahil juga, batu di Air Bangis adalah endapan dari letusan gunung berapi di sekitar pantai.
Tapi, endapan dari gunung berapi yang mana? Tidak mungkin juga Plato sampai menulis tentang sebuah negeri yang disebut sebagai Atlantis dengan ciri-ciri yang banyak disebut berada di kepulauan Indonesia. Teori-teori gempa tektonik ataupun letusan gunung berapi lebih masuk akal, ketimbang seseorang bisa dikutuk menjadi batu, beserta seluruh penumpang kapal dan sekaligus kapal-kapalnya. Kutukan sebesar apa yang bisa menjadikan itu?
*
Karena lahir di Kota Pariaman, saya mengetahui kota ini dari ayah saya, Boestami Datuak Nan Sati. Ayah bekerja di kantor Bupati Padang Pariaman (waktu itu masih meliputi Kota Pariaman dan Kabupaten Kepulauan Mentawai). Ayah berasal dari Luhak Tanah Datar, tepatnya Nagari Aie Angek, Kecamatan X Koto. Sebagai pegawai negeri, ayah di mata saya memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Bacaan “Intisari” menjadi makanan wajib kami, begitu juga siaran radio BBC Inggris dan ABC Australia. Pengetahuan saya dibentuk dari apa yang dibaca dan didengar oleh ayah saya.
Kota Pariaman dalam ingatan masa kecil saya masih dipenuhi oleh rimbunnya pohon baguak (Gnetum gnemon, family gnetaceae). Selain itu, pohon ceri (kersen) dan tebu. Halaman rumah masih melewati jembatan kecil melintasi selokan yang berawa dan berair coklat.
Memang sudah ada bioskop Garuda. Ci Ayang dan Ci Elok, dua panggilan tante (etek) dari pihak Datuak Nullah – keluarga sesuku –, mengajak saya menonton di bioskop itu. Sebagai anak kecil, saya tentu ketakutan melihat ada kereta api besar hendak melindas, sehingga saya sembunyi di balik bangku.
Di Pariaman dulu masih banyak kuda bendi, sebagai ciri khas mengangkut orang dari dan ke pasar di dekat tepi laut. Inilah ciri yang mulai hilang di Kota Pariaman. Kuda bendi ini dihiasi dengan beragam bendera, apabila menjelang Tujuh Belasan atau Tabuik Piaman. Dengan kemajuan yang kini ada di Kota Pariaman, kuda bendi ini tidak lagi menjadi sesuatu yang khas, sebagaimana juga terjadi di kota-kota lainnya.
Saya tidak tahu, sejak kapan kuda ini menjadi bagian yang tak bisa dipisahkan dari masyarakat Pariaman, lalu kenapa sekarang malah mulai hilang. Barangkali karena aspek perlindungan atas hewan yang mulai meningkat, tetapi lebih banyak lagi akibat kendaraan bermotor yang jadi pemandangan keseharian.
Laut adalah wilayah yang terasa jauh, bahkan ketika saya lahir di Pariaman dan sekolah di tingkat SMA. Sama sekali tidak ada keakraban antara manusia dengan laut. Sampai sekarang, banyak orang di luar Pariaman masih menganggap Pantai Pariaman sebagai WC terpanjang di dunia. Dulu, Bupati Anas Malik (1980-1990) memberantasnya, dengan cara razia setiap pagi dan senja. Bupati ini juga rajin menangkap hewan ternak yang lepas, lalu membawanya ke halaman kantor bupati.
*
Dengan luas wilayah 73,36 kilometer persegi, Kota Pariaman termasuk sebagai kota kecil di Indonesia. Menurut sensus 2010, jumlah penduduk Kota Pariaman hanya 79.043 jiwa. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki. Keunikan lain, hanya ada 6 (enam) kota di pantai barat Sumatera, yaitu Kota Banda Aceh, Kota Sibolga dan Kota Gunung Sitoli (Sumut), Kota Pariaman dan Kota Padang (Sumbar) dan Kota Bengkulu.
Rantai atau sabuk enam kota di Pantai Barat Sumatera itu menarik dijadikan sebagai panggung Indonesia ke Lautan Hindia. Sebelum Selat Malaka dipenuhi kapal, perjalanan dari Eropa ke Amerika dan Australia melewati pantai barat Sumatera. Bahkan, penulis terkenal Karl May-pun pernah singgah di Teluk Bayur, Padang. Banyak penjelajah dan penulis asing yang singgah di kota-kota pelabuhan di pantai barat Sumatera di abad-abad lampau, termasuk dari Eropa, India, Cina dan Arab.
Merasa jauhnya masyarakat kota, termasuk Kota Pariaman, terhadap laut juga terjadi secara regional, ketika perhatian ke pantai barat Sumatera terlalu minim. Maritim masih dianggap sebagai bukan bagian dari proses modernisasi Indonesia, juga bukan masa depan umat manusia. Visi pembangunan kota dan pantai menjadi penting, apalagi menjadi kota pantai. Semacam waterfront city yang memang jadi tujuan berakhir pekan secara nyaman di pelbagai negara maju di dunia.
Apabila di masa lalu Kota Pariaman masih dikenal sebagai daerah yang memiliki banyak rawa, termasuk lokasi SMA 2 Pariaman di Rawang (rawa), maka kini keadaan itu semakin sedikit. Dengan posisi strategis di pinggir pantai, Pariaman bisa menjadikan laut sebagai teman, termasuk sebagai area transportasi laut ke Kota Padang – apalagi ke Bandara Internasional Minangkabau di Padang Pariaman – ataupun ke Agam dan Pasaman Barat. Sabuk alam yang sudah disusun rapi itu, tinggal dimanfaatkan dan dimaksimalkan bagi kepentingan masyarakat ke depan.
Tak perlu lagi mitos baru dilahirkan, guna mengusik ketenangan masyarakat Pariaman. Yang jelas, dengan pemberhentian Archandra Piliang sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, masyarakat nasional dan internasional sudah tahu betapa Pariaman tak pernah sebetulnya melahirkan Malin Kundang. Hanya saja, ketika masyarakat menerima para perantau yang berhasil dari luar: ia mengalami banyak kendala, sehingga tak mampu lagi menghadapi dengan cara berpikir yang ia terima dari rantau itu. [ ]