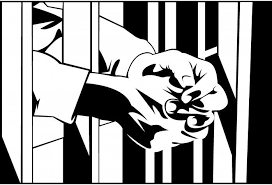
Atau yang ketiga. Para napi lain, jumlahnya tak mungkin dilawan sendirian, akan meminta Herry—atau siapa pun napi perkosaan–menghadap tembok. Lalu mereka akan memaksanya merancap alias onani dengan balsam yang gampang dibeli di warung koperasi Lapas. Bahkan orgasme—yang pasti alangkah susahnya dalam kondisi tertekan begitu—tak menghalangi penyiksaan serupa dilakukan berkali-kali di malam yang sama.
Oleh : Darmawan Sepriyossa
JERNIH—Beberapa hari lalu, saat pertama kali membaca kasus Herry Wirawan, guru agama yang melakukan perkosaan terhadap puluhan santriwati, saya hanya bisa menggeleng. Sekejap saya langsung membayangkan apa saja yang akan, atau bahkan mungkin sudah dialami Herry sejak hari pertama ia ditahan di sel, baik sel tahanan polisi maupun rumah tahanan (Rutan). Apa yang (akan) dialami Herry adalah mimpi buruk di siang bolong, yang mampu membuat narapidana sebengis apa pun menggigil takut.
Apalagi jika para napi lain itu tahu segala aksesoris yang menjadi pernak-pernik perkara Herry. Misalnya, fakta bahwa sembilan di antara korbannya itu telah melahirkan, lalu sejak masih merah pun bayi-bayi suci itu dipaksa merasakan sengat terik matahari, dijadikan penarik iba untuk mendulang recehan di perempatan lampu merah. Saya bahkan berpikir, kalau suatu hari nanti Herry tergantung, entah di WC Rutan atau Lapas, itu sangat rasional dan masuk akal. Dan di zaman semua orang—termasuk penghuni penjara—butuh telepon pintar, paling tidak handphone—tak ada lagi tembok yang bisa menahan berita apa pun masuk sel tahanan, bahkan sel tikus sekali pun.
Pasalnya, hingga setidaknya enam bulan pertama menghuni entah Rutan atau Lapas, hanya perlakuan sangat buruk yang mungkin dialami Herry. Yang menjadi faktor pemberat Herry di mata para napi, justru posisinya sebagai seorang ‘ustadz’. Waktu menghuni Lapas Cipinang saya belajar agama serta ilmu Nahwu dan Shorof pada seorang ustadz. Cing Wawan namanya.
Cing Wawan juga jelas seorang napi, untuk hukuman sekitar 4,5 tahun penjara karena narkoba. Tapi ia tak pernah menutupi kebenciannya terhadap napi kasus perkosaan, apalagi manakala pelakunya seorang ustadz atau pemuka agama.
“Saya benci ustadz-ustadz yang masuk penjara karena urusan setud—istilah penjara untuk perkosaan–,” kata Cing Wawan. “Ngurus burung aja nggak becus, bagaimana mau ngurus umat?”
Pada tahun 2018-2019 itu dia menghitung, dari puluhan napi di Blok Kriminal yang masuk Lapas Cipinang karena ‘nyetud’, 20 di antaranya ustadz atau ahli agama. “Lainnya cuma ada dua pastor. Memalukan saja!” kata Cing Wawan, keras. Dia konsisten untuk kebenciannya itu: di Blok Masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling) ada dua imam yang biasa memimpin shalat Maghrib, Isya dan Subuh. Selain Cing Wawan, seorang lainnya ustadz yang lebih tua, beranjak sepuh. Tak pernah sekali pun saya lihat Cing Wawan memasang wajah ramah, bahkan manakala ada yang harus mereka obrolkan soal mushala. Penyebabnya jelas, ustadz yang lebih sepuh itu masuk penjara karena urusan ‘setud’.
Meski kurang elok, pembaca tak akan bisa membayangkan ngerinya nasib Herry kalau saya menutupi peluang perlakuan buruk yang menanti guru lancung tersebut. Pertama, yang paling buruk, Herry akan dihajar beramai-ramai oleh sesama napi. Jika Anda pernah mendengar atau membaca adanya budaya perpeloncoan di penjara, jangan pernah berpikir itu sama sekali bohong dan mengada-ada. Para napi jelas memerlukan hiburan. Karena norma, kewajaran, dan adab di penjara pun tidak senormal di luar tembok tinggi itu, ‘sense of hiburan’ para napi pun bisa berwujud keinginan memukuli orang. Napi seperti Herry, yang dalam standard penjara pun tergolong keji, biasanya menjadi pilihan bersama.
“Tukang setud itu banci. Beraninya hanya sama perempuan,” itu kalimat yang sering saya dengar di Lapas, sebagai stereotype untuk profiling napi perkosaan di antara komunitas narapidana. Kalimat itu juga yang saya baca dari hasil penelitian Aroma Elmina Martha dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogjakarta, danChandra Khoirunnas dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Keduanya melakukan riset dan menuliskan penelitian berjudul “Penganiayaan Terhadap Narapidana Pelaku Perkosaan yang Mengalami Label Negatif di Lapas (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta)”.
Contoh ekstrem kemungkinan itu dengan gampang bisa dicari di berbagai kliping media massa. Misalnya, matinya narapidana kasus perkosaan, Daeng Massenge alias Ambo Sengeng bin Duntu, yang tewas di Rumah Tahanan Berau, Kalimantan Timur, 2013 lalu. Daeng, kakek 56 tahun itu tewas dianiaya teman-teman sekamarnya, yang benci karena pria itu masuk penjara dua kali untuk kasus yang sama: memperkosa anak kandungnya. Dia tewas di Blok Mapenaling, yang artinya baru masuk kembali ke penjara. Kali ini karena memperkosa anak perempuan lainnya, adik kandung korban sebelumnya. Mayat Daeng sempat dibawa ke keluarganya, namun baik keluarga maupun penduduk kampung tersebut, menolak jasad yang sudah kaku itu.
Atau seperti yang dialami Sugeng Slamet 2019 lalu, yang juga memperkosa anak kandungnya hingga 50-an kali. Sugeng yang beristri lima orang, empat di antaranya menjadi buruh migran di Timur Tengah, yang rajin mengirimkan gaji ke kampung, itu dihajar para penghuni Lapas lainnya. Itu terjadi di malam pertama masuk Lapas, yang membuat Sugeng nyaris koit. Kita tahu karena beritanya merembes keluar tembok tebal. Tak ada yang bisa menjamin hal serupa belum dialami Sugeng di tahanan polisi dan Rutan.
Kemungkinan kedua, kalau tidak sampai dihajar, Herry mungkin mengalami apa yang dikatakan almarhum Anton Medan, saat mengobrol dengan saya waktu masih menjadi wartawan majalah Panji Masyarakat, 1997 lalu. Waktu itu Anton bercerita tentang perpeloncoan di penjara. Tiba pada nasib napi perkosaan, Anton bercerita sambil bergidik. Kata dia, biasanya para napi memaksa si napi pemerkosa untuk buang hajat. (Maaf) Sebagian di antaranya diambil, dicampurkan kepada makanan atau minuman, untuk dinikmati napi pemerkosa itu di bawah ancaman fisik. (Maaf saya pun pening menuliskannya.)
Atau yang ketiga. Para napi lain, jumlahnya tak mungkin dilawan sendirian, akan meminta Herry—atau siapa pun napi perkosaan–menghadap tembok. Lalu mereka akan memaksanya merancap alias onani dengan balsam yang gampang dibeli di warung koperasi Lapas. Bahkan orgasme—yang pasti alangkah susahnya dalam kondisi tertekan begitu—tak menghalangi penyiksaan serupa dilakukan berkali-kali di malam yang sama.
Itu pula yang diakui Rifki, seorang narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta, untuk kasus pembunuhan, sebagaimana dicatat penelitian Aroma dan Chandra. Menurut Rifki, kalau tidak dengan balsam, biasanya dengan minyak gosok yang lebih gampang dicari.
“Tetapi, Mas, biasanya itu berlangsung cuma beberapa bulan saja, kok. Ya, setidaknya dia juga kapoklah dapat hukuman ganda,” kata Rifki dengan nada ‘woles’ saja.
Menurut dia, variasi onani dengan balsam itu kadang bisa diganti, misalnya dengan mengikatkan pemberat pada alat kelamin napi perkosaan, lalu diperintahkan untuk berlari-lari mengelilingi sel. “Kalau dia kecapekan, kita suruh dia tidur di kamar mandi sel.”
Oh ya, kalau Donald Clemmer dalam bukunya, “The Prison Community” meyakini adanya stratifikasi sosial di penjara, napi perkosaan–entah mengapa, menempati dasar piramida social tersebut. Tentu saja, napi pembunuhan menempati posisi atas, meski bukan puncak. Sepengamatan, meski bagi saya alangkah ganjil, napi korupsi menempati puncak piramida hierarki social di penjara. Barangkali karena merekalah yang paling mungkin dimintai bantuan, entah dengan suka rela maupun sedikit paksaan.
Setelah setahun berada di tempat tersebut, lingkungan pun akhirnya terbiasa dan menerima napi setud. Kehidupan akan berjalan ‘normal’ laiknya napi lain. Persoalannya, napi-napi perkosaan umumnya para penghuni penjara yang paranoid terhadap kemungkinan dipindahkan ke penjara lain. Istilah keren di penjara, operan. Mengapa? Karena ‘operan’ berarti mereka memasuki komunitas baru, otomatis pertanyaan baru dari penghuni lama tentang dosa apa yang membuat mereka masuk penjara. Jika diketahui urusannya adalah ‘setud’, bukan tidak mungkin ada yang gatal untuk menghidupkan budaya penindasan terhadap pelaku perkosaan itu.
Imam mushala di Blok Mapenaling kala saya menghuni Lapas Cipinang tersebut, pernah secara terbuka mengemukakan hal itu saat mengobrol usai subuh. Wajahnya tak bisa menutupi kegundahannya terhadap kemungkinan dioper itu. Sayang, justru di bulan keempat saya berada di sana, hal itu terjadi. Biasanya ‘operan’ dilakukan malam hari, dengan kondisi pintu blok dikunci petugas, hingga tak seorang napi pun—kecuali tahanan pendamping (tamping) yang membantu petugas—bisa menyaksikan prosesnya. Saya mendengar kabar, ustadz yang sudah tergolong sepuh itu sampai mencucurkan air mata saat proses operan berlangsung.
Mengapa saya sempat berpikir Herry Wirawan punya kemungkinan mengakhiri hidupnya sendiri?Karena hal itu logis dan rasional. Tekanan, ketakutan, kondisi yang mengungkung dan menekan, bisa membuat seorang napi gelap mata dan memilih cara paling absurd: bunuh diri.
Di Lapas Cipinang, selama saya di sana, setidaknya ada David Tan, napi warga negara Taiwan, nekad menggantung diri dengan tambang plastik di WC blok. Padahal, setiap blok di penjara Indonesia selalu padat sesak oleh penghuni.
David yang punya utang banyak tampaknya frustrasi. Berutang di penjara artinya berjudi dengan nasib. Akan ada banyak brengos dan napi jagoan yang dengan senang hati menagih untuk mengincar komisi. Semacam ‘bounty hunter’, pemburu buronan bayaran di film-film Hollywood. Di penjara, mereka dikenal sebagai “BNN”–Bagian Nagih-nagih, yang bukan tidak mungkin punya kaitan dengan narkoba. Mereka tega kalau sekadar menghajar agar si pengutang membayar dan komisi mereka dapat. David Tan, konon, sering mengalami hal-hal tak menyenangkan itu.
Seorang lainnya, Bong Sukinto, mengikuti jejak David Tan, tiga bulan setelah saya bebas. Keduanya pasti bukan orang-orang yang menemukan penjara sebagai tempat beruzlah, menyepi, lalu menangis setiap malam di Kaki Gusti. [dsy]







