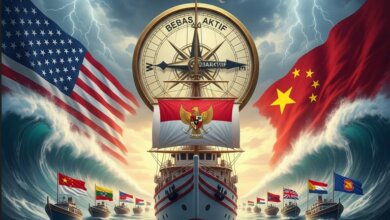Di sinilah figur Menkeu baru akan ditakar. Purbaya berpengalaman di simpul stabilitas sistem keuangan; ia terbiasa berkoordinasi dalam KSSK (BI–OJK–LPS–Kemenkeu), peka pada denyut perbankan dan pasar surat utang, serta dikenal teliti membaca risiko. Tantangan barunya lebih kompleks: menenangkan pasar yang mudah panik, memastikan pembiayaan program prioritas terjangkau, dan mengubah kualitas belanja agar setiap rupiah berbuah produktivitas—bukan sekadar mengisi catatan serapan di akhir tahun.
JERNIH—Besok, Kamis 11 September 2025, sekitar pukul 12.00–16.00 WIB, Jakarta menjadi panggung uji arah fiskal Indonesia. GREAT Institute menggelar GREAT Lecture: “Transformasi Ekonomi Nasional—Pertumbuhan Inklusif Menuju 8 Persen.” Di sana, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Ph.D. dijadwalkan menyampaikan pidato kunci perdananya di hadapan publik kebijakan usai pergantian kursi Menkeu.
Sesi pembuka diisi Dr. Syahganda Nainggolan (ketua Dewan Direktur GREAT Institute). Diskusi panel menghadirkan Dr. H. Mukhamad Misbakhun (ketua Komisi XI DPR RI), Prof. Dr. Perdana Wahyu Santosa (Guru Besar & Dekan FEB Universitas YARSI), dan Herman Saheruddin, Ph.D. (LPS). Selain wartawan, lecture ini digelar untuk undangan terbatas.
Pergantian Menkeu di tengah pasar yang sensitif selalu melahirkan dua rasa sekaligus: cemas dan berharap. Cemas karena keseimbangan rupiah, inflasi, dan defisit bisa goyah oleh sentimen. Berharap karena arah baru kerap membawa energi untuk membenahi simpul-simpul yang lama macet. Penunjukan Purbaya—sebelumnya ketua Dewan Komisioner LPS—menempatkan dua agenda yang kerap berseberangan di satu meja: menjaga disiplin fiskal sambil mempercepat pertumbuhan yang lebih merata. Besok, publik ingin melihat bukan hanya retorika, melainkan peta jalan.
Gambaran ekonomi Indonesia hari ini ibarat pelari yang kuat namun belum meledak. PDB tumbuh di kisaran menengah; konsumsi rumah tangga bertahan, tetapi belum cukup untuk melompat tanpa dorongan investasi dan ekspor. Ketergantungan pada komoditas masih tinggi—ketika harga logam dan batu bara melemah, neraca ikut menyusut. Rasio pajak relatif rendah untuk negara berpenduduk besar; ruang fiskal ketat memaksa pemerintah memilih proyek yang benar-benar produktif. Ketimpangan wilayah menggerus daya beli, terutama ketika ongkos hidup di kota terus merangkak. PR-nya panjang, tetapi arah perbaikannya jelas jika disiplin kebijakan dipegang.
Di balik daftar masalah, peluangnya masih jelas terlihat. Bonus demografi belum habis. Hilirisasi mineral dan ekosistem kendaraan listrik bisa menjadi mesin ekspor baru, asalkan standar lingkungan, alih teknologi, dan kedalaman rantai pasok tidak berhenti di seremoni. Ekonomi digital menurunkan biaya transaksi UMKM, tetapi butuh pembayaran murah, logistik efektif, dan perlindungan konsumen yang jelas. Energi terbarukan serta efisiensi industri menekan biaya produksi sambil mengundang investasi hijau. Pariwisata dan ekonomi kreatif punya ruang memanjang, dengan syarat keamanan, konektivitas, dan tata kelola destinasi ditangani serius. Jalur menuju 6–7 persen terbuka; 8 persen pun tidak mustahil bila keberanian berjalan bersama presisi.
Di sinilah figur Menkeu baru akan ditakar. Purbaya berpengalaman di simpul stabilitas sistem keuangan; ia terbiasa berkoordinasi dalam KSSK (BI–OJK–LPS–Kemenkeu), peka pada denyut perbankan dan pasar surat utang, serta dikenal teliti membaca risiko. Tantangan barunya lebih kompleks: menenangkan pasar yang mudah panik, memastikan pembiayaan program prioritas terjangkau, dan mengubah kualitas belanja agar setiap rupiah berbuah produktivitas—bukan sekadar mengisi catatan serapan di akhir tahun. Publik menunggu sinyal-sinyal itu besok.
Sinyal pertama yang dinanti adalah peta fiskal yang lugas. Angka defisit yang kredibel, strategi pembiayaan yang tidak mencekik, serta jadwal lelang SBN yang seirama dengan kebijakan moneter akan menjadi pertanda bahwa instrumen fiskal dan moneter berjalan dalam satu orkestrasi. Tanpa itu, volatilitas kurs akan memakan ruang kebijakan lain. Sinyal kedua: reformasi pajak yang cerdas. Fokusnya memperluas basis dan meningkatkan kepatuhan berbasis data—bukan sekadar menaikkan tarif—seraya memberi insentif terang bagi investasi padat karya dan padat teknologi. Pajak harus terasa adil, sederhana, dan dapat diprediksi.
Sinyal ketiga: disiplin belanja pada proyek berdaya ungkit tinggi. Kesehatan dasar, ketahanan pangan, pendidikan vokasi, infrastruktur logistik, dan transmisi listrik adalah contoh area yang dampak ekonominya langsung terasa di biaya produksi dan biaya hidup. Belanja sosial yang tepat sasaran—mulai dari gizi anak hingga sanitasi—bukan charity, melainkan investasi produktivitas jangka panjang.
Sinyal keempat: kepastian regulasi untuk hilirisasi dan investasi. Investor bisa menghitung risiko bisnis, tetapi menjauhi ketidakpastian hukum. Penegakan kontrak dan kemudahan perizinan adalah “infrastruktur tak kasat mata” yang tak kalah penting dari jalan dan pelabuhan.
Penting pula komunikasi kebijakan yang konsisten. Pasar bisa menerima kabar kurang menyenangkan, selama arah dan alasannya dijelaskan tanpa berputar. Di titik ini, gaya komunikasi Menkeu berperan setengah kebijakan. Kata-kata yang jernih menahan gejolak sebelum angka-angka bicara. Besok, ketika Purbaya mengambil podium, publik akan menimbang bukan hanya isi, tetapi juga konsistensi pesan dari waktu ke waktu.
Panel GREAT Lecture dirancang untuk menguji klaim “inklusif” secara konkret. Syahganda Nainggolan menempatkan inklusivitas sebagai parameter yang bisa diukur: pendapatan riil rumah tangga, akses kredit UMKM, dan menurunnya jarak ekonomi antarwilayah. Misbakhun membawa perspektif politik anggaran: bagaimana DPR menyeimbangkan hasrat program besar dengan disiplin defisit, termasuk desain insentif yang mendorong investasi namun tetap menjaga keadilan. Perdana Wahyu Santosa diharapkan menyisir produktivitas dari hulu ke hilir: apa yang harus berubah di pabrik, pelabuhan, hingga ruang kelas agar target 8 persen keluar dari slide. Herman Saheruddin mengingatkan batas keamanan sistem keuangan: pertumbuhan tinggi tanpa perbankan yang sehat hanya melahirkan volatilitas.
Di atas panggung itu, beberapa pertanyaan akan menentukan nada diskusi. Apakah disiplin fiskal tetap “sakral” saat program sosial dan infrastruktur menuntut ruang belanja yang lebih lebar? Bagaimana menutup jurang rasio pajak tanpa menggerus daya beli? Seberapa besar APBN diarahkan ke proyek yang mengangkat produktivitas nasional, bukan sekadar memperbanyak acara peresmian? Dan indikator apa yang dipakai pemerintah untuk menyebut pertumbuhan sebagai “inklusif”—di luar headline PDB? Jawaban yang jelas akan memendekkan jarak antara slogan dan implementasi.
Faktor-faktor penopang juga menunggu kepastian. Produktivitas membutuhkan kurikulum vokasi yang menempel ke industri, pembaruan teknologi pabrik, dan kebijakan impor mesin serta bahan baku yang tidak berbelit. Logistik harus diperlakukan sebagai “pajak tak kasat mata” yang wajib dipangkas lewat pelabuhan efisien, integrasi antarmoda, dan kepastian jadwal. Energi—tarif dan keandalannya—menentukan daya saing manufaktur; proyek transmisi dan pembangkit mesti terencana, tak boleh tersandera siklus politik. Semua ini menuntut koordinasi erat pusat-daerah agar biaya transaksi tidak kembali menggunung.
Dari sisi pembiayaan, pilihan terbaik adalah yang paling transparan. Utang jangka panjang dengan biaya rendah lebih aman, tetapi tetap diuji kredibilitas rancangan defisit. Skema kreatif seperti KPBU bisa ditempuh, namun risiko harus dibuka sejak awal—jangan sampai beban publik disembunyikan dalam klausul yang sulit diawasi. Evaluasi proyek mesti tegas, insentif harus berbatas waktu dan berbasis kinerja. Keberanian mengatakan “tidak” pada proyek yang tak layak sama pentingnya dengan langkah cepat mendukung proyek yang benar.
GREAT Lecture besok, dengan format ringkas dan panelis yang representatif, berpeluang menjadi “balai uji” bagi haluan fiskal edisi Purbaya. Jika sinyal-sinyal kunci terjawab—peta fiskal yang lugas, reformasi pajak yang adil, belanja yang berdaya ungkit, kepastian aturan, serta komunikasi yang konsisten—maka target 8% tidak terdengar sebagai mimpi panjang, melainkan rencana kerja yang bisa dipantau publik dari triwulan ke triwulan. Jika tidak, publik akan kembali menggantungkan harapan pada cuaca global—strategi yang jarang berujung pada keadilan.
Indonesia pernah membuktikan diri tangguh ketika badai datang. Modal sosial itu masih ada. Besok, panggungnya jelas, tokohnya lengkap, dan pertanyaannya sederhana: bagaimana membuat pertumbuhan benar-benar terasa—di dompet keluarga pekerja, di neraca pelaku usaha, dan di statistik kemiskinan—tanpa merusak disiplin fiskal? Jawaban yang terang akan menjadi batu pijak pertama. Dari sana, 8 persen bukan lagi angka di spanduk, melainkan alamat yang bisa dituju. [ ]