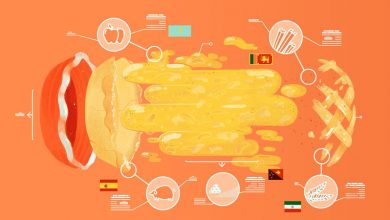Bahkan sekarang, setelah semua yang telah dialami dalam tiga setengah tahun terakhir, ada saat-saat ketika kita dapat merasakan seolah-olah kita sedang mengembara melalui lelucon yang begitu suram dan tidak masuk akal, sehingga hal itu menguji pikiran.
Oleh : Evan Osnos
Ketika jarum jam semakin mendekati saat jam tayang utama, Gedung Putih menyiapkan produksinya yang tidak suci. Saat itu Senin sore, dan Presiden Trump bersiap-siap menyampaikan pidato pertamanya tentang protes besar-besaran yang melanda Amerika.
Setelah sejumlah berita mengecewakan, tentang dirinya yang menghabiskan Jumat malam di bunker, Trump memanggil korps pers ke Rose Garden untuk mendapatkan efek maksimal pemberitaan. Ia tidak peduli bahwa kekacauan telah memberi jalan untuk terjadinya demonstrasi damai di luar Gedung Putih. Pria-wanita, di sepanjang tepian Taman Lafayette yang cerah, berlutut melantunkan puji-pujian. Seorang anak lelaki dan perempuan muda, mengapit ayah mereka, memegang poster protes. Mereka memakai masker bertuliskan slogan suram kekinian: “I Can’t Breathe.”
Sepanjang hari, kota itu mulai memperbaiki luka malam sebelumnya. Seorang pekerja bekerja keras menghapus coret-coretan (graffiti) dari dinding batu sebuah rumah makan steak. Para pekerja memasang kayu lapis di atas jendela-jendela toko perhiasan dan mesin-mesin ATM yang hancur. Slogan-slogan yang ditulis cat semprot—“George Floyd” dan “Fuck the Police!” dan “Bebaskan Rakyat” —menyajikan sejarah singkat tentang sepekan yang menyedihkan di Amerika, yang dimulai pada 25 Mei ketika Floyd meninggal, yang dalam video terlihat lehernya terus ditekan seorang perwira polisi di Minneapolis. Hingga mati.
Biasanya, salah satu fitur paling mencolok dari Gedung Putih adalah keakrabannya. Selama bertahun-tahun, para turis yang berjalan di Pennsylvania Avenue terkejut karena dibiarkan mendekati gedung itu, yang hadir dengan wajah terbuka penuh percaya diri terhadap dunia, berbeda dengan pusat-pusat kekuasaan terpencil di Beijing atau Moskow.
Dalam beberapa bulan terakhir, itu tidaklah benar. Musim panas lalu, pemerintah Trump mulai membangun pagar baru setinggi tiga belas kaki, dua kali lebih tinggi dari yang lama, dilengkapi dengan “anti-climb and intrusion detection technology.” Pemerintah juga menutup Pennsylvania Avenue untuk para pejalan kaki dan menyelubungi bangunan dengan tembok putih yang tinggi. Ketika aksi protes memungkinkan terjadinya kekerasan selama akhir pekan, polisi memperluas wilayah isolasi, menyegel Lafayette Park dan mendorong publik menjauh. Pada hari Senin, pengunjuk rasa kembali ke jalan-jalan terdekat. Menjelang sore, beberapa ratus orang telah berkumpul.
Bagi banyak orang yang bergabung ke dalam kerumunan pemrotes, kematian Floyd adalah percikan terakhir ke lubang besar kemarahan dan keputusasaan. “Mereka semua, mereka semua bersama-sama,” kata Kandyce Baker, seorang wanita berusia 31 tahun yang memegang poster bergambar wajah Floyd. “Saya pikir titik kritis saya dimulai dengan Ahmaud Arbery. Saya seorang pelari yang rajin. Saya punya banyak teman yang rajin berolahraga lari. Saya ikut sembilan maraton, dan itu bisa saja terjadi pada saya. Itu bisa dengan mudah terjadi pada salah satu teman saya,” kata dia menambahkan. (Arbery, yang berusia 25 tahun, ditembak mati pada Februari lalu oleh dua pria, saat sedang jogging di Brunswick, Georgia.).
“Dan kemudian, setelah itu, terjadi juga pada Breonna Taylor dan George Floyd. Sepertinya kita memiliki (kasus) Rodney King setiap hari.”
Baker, yang memiliki gelar master dalam bidang kriminologi, mengatakan kepada saya, “Anda tidak hanya punya polisi yang saling melindungi, tetapi Anda juga punya polisi kulit berwarna yang takut bicara karena kode biru untuk diam. Apakah itu karena takut pembalasan, karena mereka takut kehilangan pekerjaan. . . budaya di Kepolisian begitu beracun.”
Setelah beberapa saat, kerumunan yang terbentuk mulai bergerak ke timur, menuju Gedung Capitol. Beberapa memilih tinggal di belakang, di Gedung Putih, yang kondisinya lebih tenang daripada yang kemudian terjadi selama berjam-jam. Sambil memegangi sebuah tanda kuning bertuliskan “Trump Coward,” Anita, seorang perempuan Virginia dengan rambut pirang panjang, berkata kepada saya, “Saya seorang Republikan terdaftar. Orang ini telah mempermalukan partai politik yang saya pilih. Saya akan mengubah pilihan partai politik setelah ini.”
Dia mengenakan celana capri hitam dan t-shirt putih bergambar bendera Amerika. Sebentar dia sempat menjelaskan, dia telah memuji Trump karena memiliki latar belakang ekonomi yang kuat. Selama lebih dari tiga tahun, ia tetap setia; dia suka membayangkan bahwa Trump adalah orang terbaik untuk masa depan bisnis AS.
“Saya memberinya waktu sebanyak itu. Dan, sebagaimana hari-hari yang telah berlalu, penghinaan dari Presiden ini telah terlalu banyak. Yang dia lakukan kini adalah bersembunyi di rumahnya, di sini.”
Saya bertanya kepada Anita soal keputusan untuk mengubah afiliasi politiknya selama ini. “Kemarin itu,” katanya. Dia telah menonton video kematian Floyd, dan itu membuatnya terguncang. “Salah satu dari kita hanya memiliki secuil kemanusiaan, itu benar-benar menghancurkan hati.” Suaranya pecah. “Setiap departemen kepolisian di negara ini harus berubah. Mereka seharusnya tidak boleh menyentuh kepala atau leher seseorang. Mengapa mereka harus melakukan itu?”
Dia melanjutkan, “Itu membuat Anda bertanya — apa yang telah mereka lakukan di masa lalu yang tidak kita ketahui, yang tidak ada di video? Semua keluhan komunitas kulit hitam, sekarang menjadi hal-hal nyata yang telah terjadi. Realitas dari apa yang telah mereka alami selama bertahun-tahun menjadi begitu nyata.”
Ketika senja berlalu, dan bayang-bayang memanjang, kaskade sandiwara politik mulai terungkap. Kelompok polisi baru datang ke Lafayette Park; beberapa mengenakan seragam hijau zaitun dan helm bergaya Tim Swat, membawa pelontar gas air mata. Presiden akan berbicara, dan manajemen panggung sedang berlangsung. Pukul 6.40, dua puluh menit sebelum jam malam diberlakukan, polisi dengan perisai anti huru-hara menekan kerumunan, mendorongnya kembali ketika beberapa orang memegang tangan mereka. Polisi menembakkan gas air mata dan peluru karet, saat para demonstran, pria dan wanita tersebar. Petugas mengayunkan tongkat ke arah wartawan yang memegang kamera dan mikrofon.
Di Rose Garden, wartawan bisa mendengar granat flash meledak di jalan-jalan. Trump, tampak tegang dan membaca teleprompter, mulai dengan mengangguk ke arah kerusuhan— ia mengatakan bahwa orang Amerika “benar-benar muak dan berontak” oleh kematian Floyd — tetapi kemudian ia memainkan citra tentang kekuatan. Menyatakan dirinya sebagai “Presiden hukum dan ketertiban,”Trump menyebut demonstrasi yang melakukan penjarahan dan kekerasan sebagai “aksi teror domestik.” Dia bersumpah untuk “mendominasi jalan-jalan” dan berjanji “menghadirkan penegakan hukum yang luar biasa sampai kekerasan bisa diatasi.”
“Jika sebuah kota atau negara menolak untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan dan properti penduduk mereka, maka saya akan mengerahkan militer Amerika Serikat, untuk dengan cepat menyelesaikan masalah bagi mereka,” kata Trump.
Disengaja atau tidak, penjajaran adegan Trump dengan adegan di luar, sangat menyebalkan dan menggelikan. CNN memuat pernyataan Presiden di layar, terpisah dengan gambar-gambar polisi yang bergerak maju menerjang kerumunan. Beberapa saat kemudian, sebuah chyron mencatat,”Trump mengatakan bahwa dia adalah ‘sekutu pemrotes damai’ ketika polisi menembakkan gas air mata dan peluru karet ke pemrotes damai di dekat White House.”
Proses produksi ternyata baru saja dimulai. Setelah jalan-jalan di sekitar Lafayette Park dibersihkan, dan gas air mata melayang pergi, Trump berangkat dari Gedung Putih dengan berjalan kaki. Dia ditemani putrinya, Ivanka dan suaminya, Jared Kushner, serta sejumlah pembantu. Mereka menuju ke Gereja Episkopal St. John, sebuah tempat perlindungan kuning kecil yang dikenal sebagai Gereja Presiden, karena selalu menyambut para pemimpin bangsa sejak zaman James Madison. Malam sebelumnya, St. John’s telah dirusak dengan grafiti, dan api membakar ruang bawah tanahnya. Namun, sepanjang Senin sore, para anggota klerus telah berada di depan, menawarkan air dan bantuan kepada para pengunjuk rasa.
Trump berjalan melintasi taman, berjalan melewati monumen-monumen, dengan petugas keamanan yang bergerak cepat di sekelilingnya. Ketika sampai di tempat yang disucikan, dia tidak masuk ke dalam. Sebagai gantinya, dia berbalik ke arah kamera, sehingga anggota rombongannya berkumpul menjadi tablo yang begitu aneh, sehingga butuh beberapa saat bagi mereka untuk memahami apa yang sedang terjadi. Trump mengangkat Alkitab dan berpose untuk kamera, memeluk buku suci itu ke dadanya, memindah-mindahkannya ke satu dan lain tangan, memutarnya ke sana kemari seperti produk di QVC.
Dia tidak meminta waktu untuk berdoa atau membaca tulisan di Kitab Suci. Di kedua sisinya, para pembantunya gelisah; ada wajah muram, wajah basset-hound dari Jaksa Agungnya, William Barr; cheer leader yang tak henti-henti bersorak Mark Meadows; kepala staf dan juru bicaranya, Kayleigh McEnany, yang selalu menyeringai. Selain Ivanka Trump, tidak ada yang memakai masker.
Ketika akhirnya semuanya usai dan ekspedisi Presiden telah kembali ke Gedung Putih, gereja pun ‘berontak’. Dalam sebuah wawancara per telepon dengan CNN, Pendeta Mariann Budde, uskup Episkopal Washington, mengatakan bahwa ia “marah” oleh pemakaian Trump atas St. Yohanes sebagai alat penyokongnya. “Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat di depan mataku malam ini,” katanya. “Apa yang baru saja kita saksikan?”
Mengusir demonstrasi damai dengan gas air mata dan senjata, sekadar agar bisa menggelar ‘operation photo’ adalah “penyalahgunaan simbol suci,”katanya. Seorang pendeta yang akan berkunjung ke sana, disapu dengan gas air mata. “Presiden baru saja menggunakan Alkitab. . . dan salah satu gereja di keuskupan saya tanpa izin, sebagai latar belakang untuk pesan yang bertentangan dengan ajaran Yesus dan segala yang diperjuangkan oleh gereja-gereja kita,” kata dia.
Bahkan sekarang, setelah semua yang telah dialami Amerika dalam tiga setengah tahun terakhir, ada saat-saat ketika kita dapat merasakan seolah-olah kita sedang mengembara melalui lelucon yang begitu suram dan tidak masuk akal, sehingga hal itu menguji pikiran.
Di hari-hari mendatang, negara akan dibiarkan menyaring pelanggaran Presiden dari fantasinya: akankah militer benar-benar menembaki rakyatnya? Akankah beberapa gubernur negara bagian bertindak atas ocehan Trump tentang “mendominasi” jalanan? Akankah virus yang, secara singkat, telah dikalahkan di halaman-halaman depan media massa oleh beragam protes, akan kembali mengaum? Semua pertanyaan ini tetap tidak tertangani pemerintah yang tidak memiliki pengetahuan atau kecanggihan untuk bersaing dengan mereka.
Untuk saat ini, ketika orang-orangnya mengharap kepemimpinan, seorang Presiden tanpa pemahaman pribadi tentang kekuatan atau semangat, menawarkan simulasi kasar terhadap mereka. Dia mengumpulkan piala-piala simbol yang dia tahu memiliki kuasa atas para pengikutnya itu– Alkitab, pistol, dan perisai. Lalu dia melemparkan semua itu bersama, dalam serentetan omong kosong yang keji. [ The New Yorker]
Evan Osnos bergabung sebagai penulis The New Yorker pada 2008, meliput politik dan hubungan luar negeri. Bukunya tentang Cina, “Age of Ambition,” memenangkan National Book Award pada 2014.