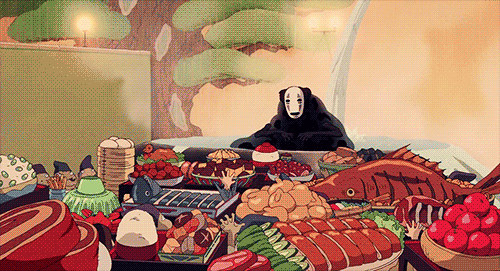Tadinya Setiyardi yang akan meresmikan pemakaian WC di sel kami itu, dengan melakukan ‘modol perdana’. Sayang, dia bilang perutnya lagi nggak mulas. Jadi tanpa terpaksa, akhirnya saya yang melakukan tugas mulia tersebut.
JAKARTA— Sejak awal masuk penjara, saya telah mendengar bahwa hampir semua urusan di sini melibatkan ‘pertukaran’, barter. Penjara, konon adalah tempat paling ‘ekonomis’, dalam arti yang tak sebagaimana kita pakai sehari-hari di kehidupan ‘normal’—kadang normal dan tidak pada akhirnya hanya soal penerimaan.
Arti ‘ekonomis’ yang saya maksud adalah ia memang tempat yang paling membenarkan hukum paling dasar dari ilmu ekonomi, yakni adanya hukum besi dalam hidup, kelangkaan—‘scarcity’, kata guru Pengantar Ilmu Ekonomi Makro saat saya kuliah di Fakultas Ekonomi Unpad, alm Pak Dr Nen Amran. Saya termasuk mahasiswa kesayangan beliau, semata karena saya berani ‘sok pintar’ menulis di koran lokal Pikiran Rakyat sejak awal-awal kuliah tentang persoalan ekonomi. Bahannya, ya tentu saja dari kuliah Pak Nen, atau Pak Suharsono Sagir yang diam-diam saya ikuti dengan menyusup ke kuliah anak-anak Ekonomi Studi Pembangunan sementara saya anak Manajemen. Padahal akar semuanya hanya agar dapat honor, penyambung hidup sebagai ‘anak kost’ gratisan di Masjid UNPAD.
Kelangkaan itulah yang memunculkan adanya harga. Nah, karena ruang, sel, adalah barang langka, maka ia pun berharga. Titik saja, ya?
Saya yakin, karena saya tak pernah dimintai harga, tak pula menawarkan sebuah harga, maka manakala begitu gampangnya saya dan rekan mendapatkan sel sebagai ruang hidup terkecil kami di Lapas—dan itu sempat membuat beberapa teman di Mapenaling terperangah, ada dua hal yang paling mungkin terjadi. Saya dan rekan saya dibantu Yang Maha Kuasa menggerakkan hati semua pihak di Lapas untuk membantu kami berdua. Atau ada orang di luar sana, yang cukup kuat untuk membuat saya dan rekan mudah mendapatkan sel di sini, dan tentu saja ia—atau mereka, itu pun pasti digerakkan hatinya oleh Yang Maha Kuasa untuk membantu, sebagaimana pasti pula Yang Maha Kuasa menggerakkan hati semua pihak yang punya otoritas di dalam untuk juga membantu.
Tetapi sel tipe 5 KB di lantai 2 itu punya kekurangan besar, yakni tak punya peturasan. Ada dua gentong besar yang diisi bergantian oleh penghuni blok, karena sejak awal sel itu ditempati napi yang tergolong ‘brengos’—pemimpin informal yang bukan foreman, biasanya karena ditakuti, yakni Jay dan temannya Opank. Opank, meski bukan penghuni tetapi nyaris setengah dari hidupnya berada di sel KB tersebut. Air di dua gentong plastic besar bekas semacam produk kimia berwarna biru itulah yang dipakai untuk mencuci piring, mandi dan membasuh usai kencing.
Tak adanya WC jelas persoalan besar bagi saya dan Setiyardi. Pikiran kami langsung sejalan: tak elok selalu menggedor tetangga sel hanya untuk buang air besar. Tetapi bagaimana caranya punya WC sendiri? Iseng-iseng kami tanya Jay yang dituakan di sana tentang kemungkinan itu.
“Bisa saja Pak,” kata Jay. Tidak sebagaimana yang lain saat di Mapenaling, para penghuni sel KB selalu menyebut kami berdua ‘Pak’. Hal yang wajar sebenarnya, kami saja selalu sok imut dan merasa belum tua, tampaknya. “Di bawah kamar mandi kan ada saluran pembuangan. Bobok saja, tembus. Bikin WC di atasnya. Beres,” kata dia. Saya tanya, adakah yang bisa mengerjakannya? “Ada Kuro, Pak. Nanti saya minta dia.”

Malamnya, usai apel malam, Jay membawa seseorang ke dalam. Tubuhnya kurus, namun terlihat liat karena ia tak mengenakan pakaian selain celana cingkrang di bawah lutut. Rambutnya terurai tak terawat, tampaknya sudah berapa Lebaran tak bertemu sisir. Yang segera menarik perhatian orang yang pertama melihat, saya yakin wajahnya. Wajah itu tak pernah lepas dari semacam senyum yang agak ganjil, senyum-senyum aneh, nakal, seorang yang dalam hidupnya tampaknya tak pernah punya beban.
“Berapa?” tanya saya dan Setiyardi, untuk memastikan biaya dan upahnya sekalian. Basa-basi kami hanya sekitar tiga menit, itu pun kurang karena Kuro lebih fokus pada rokok yang segera diambilnya begitu datang. Rokok Jay yang tergeletak di tengah ruangan.
Kuro diam, sudut matanya melirik Jay dan Opank.
“Yaa…asal rokok dan makan, Pak,” kata dia.
“Iya berapa? Sebut saja.”
Belum lagi Kuro menjawab, Opank segera berkata sambil tangannya menepuk kepala Kuro.
“Alaaah, lu. Pake harus bayar-bayar segala. Rokok dijamin aman!”
Kuro memegang kepala, menghindari tepukan tangan Opank yang tak berhenti, namun wajahnya tetap saja cengengesan. “Iya…iya…tapi kan memang ada biayanya. Buat semen, buat pasir, buat ngupah orang bawa ke sini, buat dudukan WC-nya, buat salam tempel kalau ada yang tanya…”
Akhirnya keluar juga satu angka dari lisan Kuro. Ia minta sejuta sampai selesai. “Tapi janji ya, rokok lancar..” kata dia, nyaris berbisik.
“Bukan cuma rokok, makanmu kami tanggung. Kami kasih uang capek. Kau pesan sendiri ke kantin Blok Tipe 3, ya,” kata Setiyardi. Tipe 3 adalah blok para napi ‘elit’ Biasanya diisi napi koruptur. Para selebritas yang masuk bui biasanya masuk tipe tersebut. Saat saya di sana, sudah ada Aa Gatot, Labora Sitorus, polisi kaya dari Papua yang didakwa melakukan berbagai kegiatan ekonomi illegal, serta Robert Tantular, terpidana kasus Century, misalnya.
Mulai pagi berikutnya sel kami pun riuh dengan hantaman palu. Entah dari mana Si Kuro dapat palu gada besar yang biasa dipakai petugas PU untuk menghajar beton itu. Suaranya riuh-rendah, membuat hati saya dag dig dug. Jay menutup pintu sel agar suaranya teredam. Tak banyak membantu. Siang-siang, sebelum apel bada Dhuhur, seorang petugas jaga datang memeriksa. Jay menghadapinya, bicara entah apa. Akhirnya petugas itu bisa diyakinkan dan pergi.
Malamnya begitu lagi. Semalaman, bikin kami tak bisa tidur. Tapi tak apalah, demi WC yang benar-benar kami perlukan. Paginya, kecuali Jay dan Opank, beberapa sesama penghuni KB terdengar menggerutu. Namun segera terdiam karena dihardik Opank.
“Lu orang sialan bisanya hanya menggerutu. Pas jadi, kan lu juga yang pastinya ikut berak di sini!”
Siangnya, sekembali dari masjid besar saya mendengar beberapa orang di lorong membicarakan bunyi-bunyian yang datang dari sel kami. Saya diam saja, pura-pura tak mendengar.
“Alah, biar saja Pak. Napi memang bisanya begitu,” kata Jay. Lupa bahwa tak hanya saya di hadapannya, dia pun sama seorang napi.
Malam kedua, bunyi yang ditimbulkan pekerjaan Kuro tak juga berkurang. Esoknya, Jay bilang, semalam sekitar pukul 2 dini hari datang lagi petugas. Jay lagi—karena yang lain tidur, yang menghadapi dan bicara. Untung ada Jay yang sudah lama tinggal dan akrab dengan banyak penjaga.
Tak enak membikin kegaduhan, saya minta Kuro segera menyelesaikan.
“Lu jangan merasa makin lama lu kerja, makin seneng karena makan dan rokok lu terjamin. Bereskan cepat, lu kayaknya dilama-lamain ya?” kata Opank kepada Kuro.
“Kagak..beneran, kagak saya lama-lamain,” Kuro menjawab takut-takut. “Betonnya keras be’eng.”
Tapi bahkan dengan digedor-gedor untuk dipercepat sekali pun, pekerjaan Kuro entah mengapa lama. Dari pertama kali menghajar lantai beton tanggal 18 Mei, baru pada 29 Mei WC itu beres. Perlu 11 hari ia bekerja. Memang ada hari-hari tertentu ia absen. Kata Jay, Kuro diminta mengerjakan ini itu di beberapa tempat. Ia memang terlihat bisa melakukan banyak pekerjaan kasar. Dan gila kerja. Setiap maghrib saat datang untuk mengerjalan WC itu, dia datang dengan tubuh tanpa bajunya yang berlepotan tanah, umumnya lumpur.
“Dia make, Pak, Pasti,” kata Jay. Diiyakan Opank. Maksud mereka memakai narkoba. Saya cuma menggeleng-geleng.
Entah dari mana pastinya Kuro mendapatkan WC jongkok bekas, sekaligus pasir dan semen. Lalu paralon untuk salurannya. Semua bekas, tentu. Hanya tentu saja hanya orang yang bisa keluar-masuk gudang, bengkel dan tempat-tempat sejenis yang bisa mendapatkannya di penjara.
Tadinya Setiyardi yang akan meresmikan pemakaian WC di sel kami itu, dengan melakukan ‘modol perdana’. Sayang, dia bilang perutnya lagi nggak mulas. Jadi tanpa terpaksa, akhirnya saya yang melakukan tugas mulia tersebut. Mengapa dia, karena memang donatur pembangunan WC itu hanya saya dan dia. Dan porsi urunan dia lebih besar. Saya keluar WC itu dengan tepukan tangan meriah tak hanya dari sesama penghuni, tapi juga dari beberapa penghuni sel lain yang datang, solider untuk ikut memeriahkan.
Namun besoknya Setiyardi berkali-kali harus bersyukur. Ia kena diare, berkali-kali harus keluar masuk WC. “Bayangkan, Wan, kalau WC ini belum selesai. Nggak tahu gimana nasib gua,” kata dia.
Dengan adanya WC, kami berdua sepakat untuk menambah gentong air. Penghuni yang lain mengamini. Kuro kembali berjasa, membawa gentong air yang lebih besar. Ia hanya minta Rp 100 ribu untuk gentong besar itu. Itu pun sempat dijitak Opank yang bilang terlalu mahal. Kami diam diam saja, tak ingin sok beradab dengan membela-bela Kuro. Tak sepenuhnya apa yang sudah menjadi adat di sini bisa dan harus kami ubah. Kecuali yang memang tak patut. Misalnya, konon bertahun sebelumnya KB adalah tempat nongkrong para pengisap bong. Konon, namanya juga. “Sejak setahun lalu saya usir-usir mereka yang begitu,” kata Jay. Namun karena Setiyardi punya asma untuk dijadikan alasan, sejak masuknya kami sel KB tak lagi menoleransi orang merokok. Bahkan Jay dan Opank pun selalu keluar manakala ingin merokok.
Dengan bertambahnya gentong, kami tak ingin membebani penghuni blok. Kebiasaan sebelumnya, yakni penghuni blok bergantian mengisi gentong di sel KB pun diubah. Ada dua orang yang kami pekerjakan atas izin foreman, Haji Hasun, orang Madura yang masuk penjara karena menclurit mati. Namanya Yogi dan Ope. Yogi anak muda asal Sukabumi yang masuk Cipinang gara-gara kasus ‘stud’—pemerkosaan. “Yang disebut saya perkosa itu pacar saya, Pak,” kata dia. Dia diadukan orang tua pacarnya yang tak setuju anaknya berpacaran dengan Yogi yang tak jelas pekerjaannya. Sementara Ope masuk karena tawuran. “Kalau tak salah, saya bacok orang pake samurai, deh, Pak,” kata dia. Saya geleng-geleng kepala. Bisa-bisanya membacok orang sampai lupa.
Biasanya mereka mengisi gentong dua kali. Pagi dan sore. Jarak sumber air ke sel kami cukup jauh. Yang paling jauh, tapi kualitas airnya lebih bagus bahkan lebih dari 100 meter, melintas Masjid Jami. Belum lagi harus dibawa naik ke lantai dua. Biasanya kami kasih keduanya harian, usai mengisi, baik pagi atau pun sore. Kadang Rp 10 ribu seorang, kadang Rp 15 ribu, kadang lebih. Bukan suka-suka, tergantung adanya dana. Kalau dihitung-hitung, cukup juga untuk mereka sebulan. Bisa sampai Rp 900 ribu seorang paling pol. Paling nggak Rp 600 ribu mah pasti.
Padahal, pas memberi kedua anak muda itu untuk membantu, foreman bilang. “Bantu ya, jangan pernah minta uang!” Nadanya keras. Tapi ya mana mungkin kami mempekerjakan orang tanpa membayar. Perbudakan sudah resmi hilang sejak Abraham Lincoln memproklamasikan deklarasi anti-perbudakan, 1 Januari 1863!
Namun dua bulan kemudian Yogi kami minta berhenti. Dia ketahuan memakai uangnya—gaji dari kami, untuk menikmati bong malam-malam, bersama para penghuni lorong. Tinggal Ope yang meneruskan pekerjaan itu. Sendirian. Tentu dengan uang terima kasih yang kini lebih banyak buat dirinya.
Banyak gunanya juga menambah gentong. Manakala tiga bulan lebih air ke blok kami berhenti mengalir—akibat permainan tahanan pendamping (tamping) yang mengurus air, kami masih bisa mandi, berwudlu dan lain-lain. Sebagian penghuni blok akhirnya selalu ikut kami saat ada keperluan berwudlu. Tak jarang berwudlu untuk shalat tahajud. Belakangan, mereka membawa sendiri air dalam botol air mineral besar, dan hanya memakai WC di sel kami sebagai tempat berwudlu.
Haji Hasun sang foreman orang baik. Di hari pertama kami masuk blok Tipe 5, ia memberi saya beberapa wirid yang kadang saya amalkan manakala ingat. Ada wiridnya, campuran Bahasa Arab dan Indonesia, yang sering membuat saya berlinang air mata. “Itu wirid tobat,” kata dia. Haji Hasun selalu membuat saya malu hati. Hampir setiap kali ngobrol dia bilang,”Saya senang bisa masuk Cipinang ini, Pak Dermawan, Pak Ardi. Saya bisa kenal banyak orang besar. Ada Pak Saiful (Jamil), Pak Aa Gatot, termasuk Pak Ardi dan Pak Dermawan ini..” Halah!
***
Penjara sebenarnya bisa menjadi tempat untuk menggali pengalaman, belajar dari banyak dan variatifnya orang. Di blok saya ada seorang warga yang dituakan—karena memang juga relatif lebih tua. Namanya Stephanus, sepertinya orang dari wilayah timur Indonesia. Saya agak kaget saat berkenalan di mushala. “Saya Stephanus,” katanya. Dia berbaju koko dengan peci putih yang tampak bagus dan baru.
Namun tak lama. Saya ingat kampung saya, Heuleut, Majalengka, daerah dengan begitu banyak pesantren, meski saya tak pernah masuk satu pun di antaranya. Banyak di antara teman saya di sana yang bernama Paulus, Johannes, bahkan Paus, hanya gara-gara kedua orang tua mereka merasa nama itu gagah.
Tetapi memang Pak Stephanus tidak begitu. “Saya mualaf,” kata dia. “Lima belas tahun lalu.” Pak Stephanus mantan PNS Kepolisian yang masuk Cipinang karena ‘hal kecil’ yang kemudian ternyata besar urusannya: pemalsuan dokumen. Ia kena 20 bulan penjara.
Menurut dia, awal dirinya menjadi Muslim karena telinganya terus diganggu bisikan, yang makin lama kian keras. “Ada yang terus bershalawat di telinga saya,” Shalatullah, salamullah…”kata dia, bercerita di tangga masjid menjelang dhuhur. Sejak itu, menurut dia, hilang keinginannya untuk datang ke ibadat Minggunya.
“Saya lalu masuk Islam,” dia mengaku.
“Dan suara itu hilang?”tanya saya.
“Ya, tapi sesekali datang. Kalau saya malas bershalawat.”
Menurut Pak Stephanus, itu membuatnya membiasakan diri membaca shalawat nabi hingga 15 ribu kali sehari. “Itu makan waktu sekitar 9,5 jam,” kata dia. Stephanus mengaku sering bermimpi kedatangan Nabi Muhammad SAW.
“Sejak di sini, bahkan tak harus dalam mimpi,” kata dia. “Tuh, Nabi sedang tersenyum melihat kita membicarakan Beliau,” kata dia, menunjuk mimbar di Masjid Jami Baitur-Rahman, Lapas Cipinang. [bersambung]