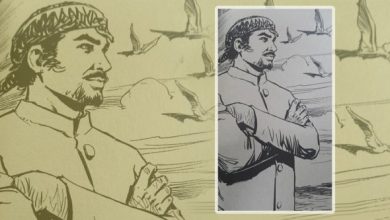UKUR

Dua hari kemudian, 3 Desember 1628, Tumenggung Suro Agul agul meninggalkan Batavia. Ia tak pernah memerintahkan anak buahnya untuk menggali makam dan menguburkan saudara-saudara sebangsa yang mereka bantai itu. Seolah sengaja meninggalkan monumen paling berdarah dan keji, mempertontonkan kekejaman entah untuk maksud apa
Oleh : Darmawan Sepriyossa
Pengantar:
Setelah jatuhnya Kerajaan Majapahit, ratusan tahun kemudian kerajaan-kerajaan taklukan di seluruh Nusantara bangkit memupuk kekuatan. Yang paling mencorong adalah Kerajaan Mataram, pengklaim pewaris kekuasaan Majapahit. Sementara kekuatan asing yakni Portugis, Belanda dan Inggris, mulai pula datang menancapkan kuku kekuasaan mereka. Masing-masing dengan kerakusan dan kekejamannya sendiri. Pada saat itu, di Tanah Sunda muncul kekuatan yang mencoba menolak penjajahan, dipimpin seorang bernama Dipati Ukur.—
Episode-30
Tampaknya kabar tersebut sampai ke telinga Sultan Agung. Pasalnya pada bulan November 1628[1] pasukan bala bantuan yang dipimpin Tumenggung Suro Agul-agul tiba di Batavia. Mereka datang lewat darat.
Mula-mula wadya bala Agul-agul itu berkemah di sebelah timur kota, sedikit mendekat ke Batavia dari arah Jatina Nagara. Lalu sebagian tampak diminta pimpinan mereka untuk merangsek dan berkemah lebih dekat, sekalian untuk mempertontonkan kekuatan. Entahlah apa yang tersirat di kepala orang-orang Kompeni. Bagaimana pun mereka sudah terlalu lelah menghadapi peperangan yang berlangsung terus menerus sejak Agustus itu.
Tampaknya sudah ada hubungan antara pasukan Mandurareja dengan pasukan Suro Agul-agul. Yang paling mungkin, Suro Agul-agul yang mendapat tugas untuk menghukum kegagalan Mandurareja itu memberi kesempatan terakhir kepada Mandurareja untuk menebus kegagalan selama ini. Pasalnya pada 27 November malam hari, pasukan Mandurareja kembali mencoba menyerang dan masuk kota. Tetapi mereka sekali lagi tak mampu menembus pertahanan. Wadya bala Mataram itu kembali dapat dihalau keluar kota.
Besoknya pasukan Adipati Mandurareja dan Upasanta kembali menyerang dengan kekuatan tiga kali lipat, sekitar 300 orang prajurit. Namun tetap saja serangan artileri Meriam yang dipimpin Kapten George mematahkan serangan mereka. Pasukan itu kembali kocar-kacir membawa teman-teman mereka yang cedera.
Aneh sebenarnya, paling tidak dari kacamata berpikir Gubernur Jendral Jan Pieterszoon Coen. Mengapa anggota pasukan yang dibawa Tumenggung Suro Agul-agul yang jumlahnya ribuan itu tidak bergabung bersama menyerang mereka? Apakah sebegitu disiplinnya pasukan Mataram, hingga kalau benar pasukan terakhir yang dikirimkan itu hanya untuk menghukum para kepala pasukan sebelumnya, mereka sama sekali tak tergiur untuk menghajar pihak musuh yang telah membuat kawan-kawannya kehilangan muka, dan bahkan kini terancam hilang nyawa?
Pada 1 Desember 1628, Tumenggung Suro Agul-agul, diiringi sekitar seratus anggota pasukan mendatangi markas pasukan pimpinan Adipati Mandurareja dan Adipati Upasanta di selatan Batavia. Mereka yakin, tak perlu membawa banyak pasukan untuk menghukum kedua adipati yang gagal itu. Kedua adipati itu, dengan rasa hormat dan takut yang begitu kuat kepada Kanjeng Sultan Agung, tak akan melawan. Melawan, sejatinya hanya akan membahayakan keluarga mereka yang ada di Kartasura, yang bisa saja sekalian ditumpas hingga tak tersisa.
Manakala Suro Agul agul turun dari kuda, dirinya segera disambut kedua adipati tersebut. Memang secara umur pun keduanya lebih muda, wajar bila mereka menghargainya.
“Selamat datang Kakanda Tumenggung, salam hormat dari kami berdua,” kata Adipati Mandurareja. Adipati Upasanta–adiknya, mengulang kalimat yang kurang lebih sama, dengan cara yang begitu anggun dan sopan. Dengan hormat pula sambutan itu dibalas Tumenggung Suro Agul agul.
Kedua juniornya itu bahkan sempat menjamunya, yang ia terima pula dengan hormat. Ketiganya makan serba sedikit, hanya untuk saling menghargai.
Selesai makan yang begitu ancin[2] itu, mereka tak segera beranjak. Ketiganya tetap duduk di meja yang kini berganti suguhan dengan beberapa piring berisikan kue-kue basah dan tiga-empat jenis buah-buahan. Ada pisang ambon lumut besar, yang menguarkan harum mengundang selera. Pisang memang selalu ada dalam setiap perjamuan, kecuali Pisang Mas, yang diyakini menjadi pantangan banyak ilmu kanuragan, yang akan melunturkan ilmu yang dipegang banyak prajurit dan perwira. Namun tak ada satu pun yang memetik pisang itu di antara ketiga perwira.
“Adinda adipati berdua pasti telah tahu maksud kakanda datang. Kakanda mohon Adinda berdua sudi memaafkan. Ini benar-benar tugas yang kanda emban dari Kanjeng Sultan,” kata Suro Agul agul, segera setelah mereka bertiga mengisap klembak untuk menghilangkan rasa gurih masakan yang mereka makan.
“Tentu, Kakanda. Apalagi yang Kakanda tunggu? Silakan penuhi tugas Kakanda. Permintaan adinda berdua dengan sangat, mohon agar Kanjeng Sultan memaafkan kami dengan mengampuni seluruh keluarga kami di Mataram. Kami berharap, janganlah mereka dilibatkan dalam kegagalan kami. Biarkan mereka tumbuh untuk pada saatnya berbakti kepada Kanjeng Sultan,” kata Adipati Mandurareja, sekaligus mewakili adiknya.
Suro Agul agul tak bisa menjawab. Ia hanya memeluk keduanya, matanya basah oleh air mata. Bagaimana pun hal yang sama bisa terjadi pada dirinya, kapan pun Kanjeng Sultan menganggapnya gagal menjalankan misi yang diperintahkan kepadanya.
“Sabar Rayi Adipati berdua, ikhlaskan ya…” Hanya itu yang ia katakan.
Setelah berunding sebentar, kedua adipati yang dianggap gagal itu minta mereka dibunuh dengan cara ditusuk keris. Tumenggung Suro Agul agul menyanggupi.
Kedua adipati itu segera keluar tenda mendahului Suro Agul agul. Sekitar enam perwira Suro Agul agul mengiringi mereka, masing-masing dikawal tiga perwira, untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Kedua adipati itu menghampiri para perwira lapangan mereka, mengucapkan beberapa kalimat yang bisa dipastikan menjadi kata-kata perpisahan. Perwira-perwira lapangan tersebut menangis, namun segera dihardik oleh kedua adipati tersebut. Tak lama kemudian keduanya berbalik berjalan menuju Tumenggung Suro Agul agul, diiringi isak tangsi para perwira bawahan mereka. Hanya perlu sekitar semenit sebelum kemudian tangisan itu seolah menjadi koor bersama pasukan yang dipimpin kedua adipati tersebut.
Adipati Mandurareja kembali menyatakan permintaan. Kali ini ia meminta agar dirinya tak harus ditelikung menjelang hukuman mati. Upasanta yang mendengar permintaan kakaknya kemudian turut meminta hal yang sama. Sayang, permintaan keduanya tak dikabulkan.
Sejurus kemudian empat perwira anak buah Suro Agul agul menelikung kedua tangan adipati itu, mengikat erat tangan mereka ke belakang sebelum tubuh keduanya pun masing-masing diikatkan erat-erat ke sebuah tiang. Hanya dalam hitungan detik, bahkan tanpa didului aba-aba apa pun, dua orang perwira bawahan Sang Tumenggung yang berada di samping kedua adipati itu masing-masing segera mengeluarkan golok mereka, menggorok leher kedua adipati tersebut. Prajurit Sunda mengenal cara pembunuhan ini sebagai ‘tugel jangga’. Itulah yang diterima kedua adipati itu sebagai penghargaan atas segala jerih payah dan bakti mereka kepada Kanjeng Sultan.
Jeritan kedua adipati itu melolong memenuhi angkasa Jakatra, mengalahkan tangisan para prajurit bawahan mereka yang terisak-isak menangisi kematian keduanya. Ada satu dua perwira bawahan Mandurareja yang berteriak-teriak histeris menyaksikan itu semua. Ia bahkan melolong mengucapkan kata-kata keji kepada Susuhunan Sultan Agung manakala perwira bawahan Suro Agul-agul memotong leher kedua adipati dan membungkus kepala keduanya untuk dijadikan bukti. Segera perwira itu ditangkap oleh para prajurit Suro Agul agul, dibawa menjauh dari arena penghukuman. Nasibnya tak sulit diterka: ia ikut majikannya yang kini telah perlaya itu, menemani mereka berdua.
Segera setelah pembunuhan resmi itu, Tumenggung memerintahkan wadya bala pasukan Adipati Mandurareja menanggalkan senjata. Perintah yang ganjil sebenarnya. Apalagi Adipati Mandurareja sendiri sudah meminta agar anggota pasukannya tak harus menerima hukuman, karena semua mereka tanggung berdua. Semua prajurit yang tak bisa menahan tangis itu bahkan menyaksikan, Sang Tumenggung pun menyanggupinya. Lalu untuk apa mereka diminta menyerahkan senjata? Apakah akan mereka semua, seluruh prajurit anak buah Mandurareja dan Upasanta itu otomatis dikeluarkan dari dinas keprajuritan Mataram gara-gara gagal merebut Batavia? Apakah memang dari awal pun mereka harus mati, entah itu oleh bedil para Kompeni atau justru tombak dan keris teman sendiri?
Tetapi sebagai prajurit, tak ada yang bisa mereka lakukan kecuali mematuhi perintah tersebut.
“Prajurit, tanggalkan senjata,” kata beberapa perwira pasukan Mandurareja, memberikan perintah dengan suara serak di antara tangis. Mereka bahkan memberikan contoh dengan segera menyerahkan senjata masing-masing. Tak lama, seluruh anggota pasukan Mandurareja sudah menyerahkan senjata, yang terkumpul menggunung aneka rupa. Mulai dari pedang, gobang, keris, tombak, panah, golok, sesuai pasukan masing-masing.
Tiba-tiba Tumenggung Suro Agul-agul meneriakkan aba-aba. Hanya dalam hitungan detik, entah sebelumnya bersembunyi di mana, datanglah pasukan yang langsung mengepung pasukan Mandurareja. Jumlahnya hampir dua kali lipat pasukan yang sudah kehilangan pimpinan itu.
Lalu kekejian pun segera berlangsung. Pasukan yang sudah menanggalkan senjata itu dibantai pasukan senegara mereka sendiri. Jerit tangis mewarnai pembantaian tersebut. Darah berceceran di mana-mana, meruapkan bau anyir yang segera memabukkan, bahkan kepada para pembantai sendiri.
Dua hari kemudian, 3 Desember 1628, Tumenggung Suro Agul agul meninggalkan Batavia. Ia tak pernah memerintahkan anak buahnya untuk menggali makam dan menanam saudara-saudara sebangsa yang mereka bantai itu. Seolah sengaja meninggalkan monumen paling berdarah dan keji, mempertontonkan kekejaman entah untuk maksud apa. Konon, berabad kemudian wilayah eksekusi keji tersebut disebut orang Betawi sebagai Rawa Bangke, yang belakangan nama yang peyoratif itu diubah menjadi Rawa Bunga.
Mayat-mayat
itu kemudian ditemukan patroli Kompeni yang sedang berkeliling mengontrol
wilayah. Dalam catatannya di Dagh Register, Gubernur Jendral Coen
menulis,”Jenazah-jenazah yang tidak dimakamkan, dibiarkan sebagai tontonan
eksekusi kejam. Kami tak dapat mempercayai hal itu, seandainya kami sendiri
tidak melihat jenazah-jenazah tersebut. Orang kami menghitung ada 744 mayat.”[3] [bersambung]
[1] Beberapa sumber—terutama babad, menuliskan bahwa Sultan Agung baru mengirimkan bala bantuan yang dipimpin Tumenggung Suro Agul-agul itu pada bulan Desember. Namun Dagh Register yang ditulis Coen pada tanggal 17 November sudah menyatakan kedatangan pasukan tersebut. Lihat Heukeun jilid 3.
[2] Sedikit, tanpa selera
[3] Dagh Register, Februari 1629, sebagaimana dituliskan Heukeun, jilid 3.